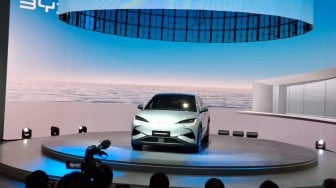Suara.com - Permintaan listrik pasti akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Apalagi elektrifikasi kendaraan merupakan tren dunia saat ini. Kementerian Perindustrian sendiri telah menegaskan tidak akan menunda persiapan elektrifikasi di Indonesia.
Listrik di Indonesia saat ini sebagian besar masih dihasilkan pembangkit berbahan bakar batu bara. Hingga Mei 2020, 63,92% energi primer untuk memproduksi listrik nasional adalah batu bara.
Masalahnya, sumber energi batu bara pasti akan habis tak sampai 50 tahun lagi. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi keniscayaan guna mengurangi ketergantungan pada fossil fuel.
Pemerintah sendiri sudah berkomitmen untuk memangkas ketergantungan sektor kelistrikan nasional pada energi fosil. Seperti termaktub dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), pemerintah menargetkan bauran energi nasional 23% bersumber dari EBT pada tahun 2025, dan akan terus ditingkatkan menjadi 31% pada 2050.
Indonesia sebenarnya kaya sumber energi baru terbarukan, seperti angin, matahari, air, panas bumi, arus laut, dan yang lain. Sayangnya hingga hari ini, sumber daya yang berlimpah ini seperti terabaikan. Apa sebenarnya hambatan pengembangan EBT di Indonesia?
Berikut wawancara eksklusif Rin Hindryati, kontributor Suara.com, dengan pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, baru-baru ini:
Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, hari ini kita mau diskusi soal energi baru terbarukan (EBT). Sepengamatan Mas Fabby, seberapa antusias pemerintah mengembangkan EBT ini?
Kalau dibilang antusias mungkin agak sulit menilai ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Kebijakan Energi Nasional tahun 2014, pemerintah memiliki target energi terbarukan dalam bauran energi primer tahun 2025 itu mencapai 23%.
Bauran energi itu mencakup energi terbarukan untuk pembangkitan tenaga listrik dan juga energi terbarukan untuk bahan bakar cair yang sebagian besar dipakai untuk sektor transportasi.
Baca Juga: Ambisi Elon Musk di Jerman: Tesla Gigafactory Sampai Produksi Vaksin Corona
Jadi, ada targetnya. Dan kalau kita lihat juga target di PP 79 yang diturunkan ke dalam target RPNJM (Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah) 2020-2024, kalau dilihat dari dokumen kebijakan, perencanaan, itu sudah ada. Kalau kita dibilang ambisius, cukup ambisius mungkin. Dibandingkan dengan target sebelumnya yang kurang daripada itu.