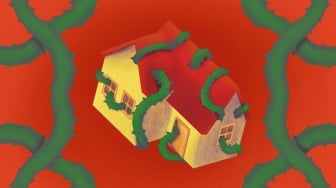Suara.com - Badai pandemi corona Covid-19 telah menimbulkan berbagai dampak ekonomi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, di mana salah satu yang terdampak adalah industri pers atau perusahaan media. Sementara, industri pers sendiri bahkan sejak sebelum pandemi pun sebenarnya sudah berada dalam situasi sulit, terutama dalam hal menjaga keberlanjutan media (media sustainability) karena bisnis yang cenderung tidak menguntungkan.
Sehubungan itu, keberadaan Kelompok Kerja Keberlanjutan Media (Task Force Media Sustainability) yang diresmikan oleh Dewan Pers pada Januari 2020 lalu, menjadi kian penting dalam membuat rumusan-rumusan hingga mengurai persoalan media atau industri pers di era digital ini. Untuk diketahui, kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan SK Dewan Pers Nomor 12/SK-DP/I/2020 ini memiliki masa kerja selama satu tahun. Duduk sebagai koordinatornya adalah Agus Sudibyo, yang juga adalah Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga & Luar Negeri di Depan Pers periode 2019-2022.
Lantas, apa yang sudah bisa disimpulkan dan disampaikan dari telaahan Task Force Media Sustainability tersebut sejauh ini? Kepada Suara.com, Agus Sudibyo, peneliti yang juga mantan wartawan ini menyampaikan beberapa hal penting. Berikut petikan wawancara khusus dengannya:
Bisa dijelaskan sedikit sudah sejauh mana kerja Task Force Media Sustainability saat ini? Apa saja yang sudah bisa disimpulkan sejauh ini?
Sebelum Covid-19 kita sudah membuat rumusan-rumusan tentang bentuk bentuk aspirasi yang kita ajukan ke pemerintah mengenai model kerja sama antara news publisher dan news platform.
Nah, secara umum itu ada dua, yang pertama soal asas similaritas atau asas kesetaraan. Jadi kesetaraan itu menyangkut tiga hal. Jadi, news publisher dan news platform itu kerja samanya ada tiga, yaitu sharing konten, harus diikuti dengan sharing revenue yang adil dan transparan, juga harus diikuti dengan sharing data yang adil dan transparan.
Nah, soal sharing revenue dan sharing data ini belum transparan. Misalnya sebuah media online seperti Suara.com ingin mendapatkan data Google, itu kan data profiling harus beli ke Google. Padahal Google mendapatkan data profiling bisa jadi dengan memanfaatkan kontennya Suara.com. Jadi dalam (hal) sharing konten terjadi, tetapi ketika sharing data itu seakan-akan milik platform sendiri. Padahal platform itu mendapatkan data itu dengan kontribusi konten dari news publisher. Jadi menegakkan prinsip kesetaraan dalam sharing konten, sharing revenue, sharing data.
Kedua, menciptakan yang disebut sebagai equal level playing field, iklim persaingan usaha yang setara. Kesetaraan ini, antara platform dan publisher (dalam) berkompetisi. Dalam kompetisi itu kan harus fair. Kalau Suara.com harus membayar pajak untuk setiap revenue yang didapatkan, maka platform juga harus bayar pajak.
Kalau Suara.com beritanya dianggap melanggar kode etik, itu harus membuat hak jawab, bisa diadukan ke Dewan Pers, bahkan bisa dipidanakan. Platform harus seperti itu juga.
Baca Juga: Kala Wabah Virus Corona, Media Diminta Jadi Penentu Kebenaran informasi
Nah, selama ini platform itu ketika mendapatkan konten dari media online, dia memberlakukan diri sebagai perusahaan media. Tetapi ketika dia harus bertanggung jawab atas konten yang ia sebar, dia berlagak bungkam. 'Kami itu hanya perusahaan teknologi. Kami hanya menyediakan platform. Bagaimana platform digunakan itu bukan tanggung jawab kami.' Dia seakan-akan mengatakan, 'Kami menyediakan platform tapi isi di luar tanggung jawab kami.' Sehingga persoalan hoaks, itu hanya direduksi, hanya persoalan orang yang membikin hoaks dan korban. Padahal persebaran hoaks itu kan (juga) menggunakan platform.
Jadi, platform dalam konteks ini harus bertanggung jawab. Seperti halnya Suara.com, kalau menyebarkan berita yang melanggar Kode Etik (Jurnalistik) kan harus beri hak jawab, harus ke Dewan Pers, bahkan bisa dipidanakan. Nah, terkait dengan kasus penyebaran hoaks, disinformasi, platform itu harus diperlakukan sebagai perusahaan media, bukan hanya (sebagai) perusahaan teknologi.
Jadi kerja samanya harus setara terkait revenue dan data. Dalam kompetisi juga harus fair.
Terkait kerja Task Force sendiri, dalam hal ini regulasi seperti apa yang akan dirumuskan?
Regulasi yang mengatur hak dan kewajiban platform dalam kerja sama dengan publisher tadi. Regulasi terkait dengan pajak, terkait dengan liability atau tanggung jawab terhadap konten, regulasi tentang data. Terkait data itu harusnya milik publisher juga, sejauh dia mendapatkan konten dari publisher.
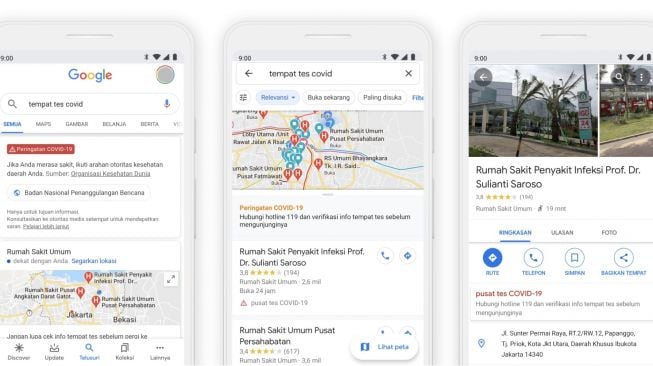
Rumusan-rumusan regulasi itu nantinya akan direkomendasikan oleh Dewan Pers ke pemerintah?
Sebenarnya bukan Dewan Pers. Jadi sebenarnya, di mana-mana untuk isu begini yang maju itu asosiasi, yakni asosiasi perusahaan media dan asosiasi wartawan. Jadi Dewan Pers itu sebenarnya lebih memfasilitasi saja.
Terkait pandemi Covid-19 sendiri, apakah ada pertimbangan khusus untuk situasi seperti saat ini dalam kaitannya dengan keberlangsungan media?
Ya, sudah menjadi komitmen global, Uni Eropa, IFJ (International Federation of Journalists), Pemerintah Kanada, Pemerintah New Zealand, itu diperlukan komitmen negara untuk melindungi ekosistem media. Ekosistem media yang sekarang ini terdampak oleh bisnis ekonomi.
Banyak media yang berada dalam batas akhir kemampuan hidupnya karena revenue yang menurun dan keadaan ekonomi secara lebih luas tidak kondusif. Nah, itu menjadi kesadaran bersama, bukan hanya di Indonesia. Di Inggris, di Eropa, itu negara harus hadir untuk membantu agar pers tetap hidup. Pers yang profesional, bukan pers abal-abal.
Karena tidak ada satu negara pun yang bisa menangani Covid-19 ini tanpa ada peran pers, tanpa ada proses komunikasi massa. Pemerintah menyadari itu. Jadi kalau Presiden mau meresmikan apa dalam kondisi sekarang ini, BNPB mau konferensi pers, siapa yang dicari? Yang dicari wartawan kan. Jadi pemerintah sendiri juga merasakan bahwa mereka sangat membutuhkan pers.
Sementara pers ini sedang terpuruk. Jadi ya, negara harus hadir untuk melindungi pers ini agar tetap hidup.
Belum lagi yang perlu kita pikirkan setelah keadaan normal setelah pandemi ini. Nanti proses demokrasi mau ditopang dengan apa kalau tidak ada pers.
Jadi, menyelamatkan pers profesional hari ini, itu penting. Antara negara bisa menangani pandemi itu dengan baik dan locus penanganan pandemi itu kan komunikasi publik. Tapi menyelamatkan pers sekarang ini juga merupakan investasi jangka panjang. Karena pers yang profesional itu kan dibutuhkan pada saat krisis seperti ini, maupun setelah krisis berlalu.
Apakah menurut Anda, media-media ke depan akan semakin sulit bertahan, pasca pandemi ini yang kemungkinan akan membawa keseimbangan baru?
Ya, kalau kita lihat data SPS, data teman-teman AMSI yang (terkait) penurunan iklan, itu kan mengarah ke sana, (terutama) kalau situasi tidak berubah dan kalau tidak ada intervensi dari negara.
Nah, perlu saya tegaskan, sebenarnya intervensi itu yang kita harapkan dari negara, bukan pemerintah. Sebenarnya ini dua hal berbeda, antara negara dan pemerintah. Jadi kita harus melihat APBN, APBD, itu sebagai dana publik yang harus dialokasikan untuk kepentingan publik juga. Pers yang profesional itu bagian dari kepentingan publik itu.
Jadi wajar sekali kalau APBN dan APBD itu dialokasikan untuk melindungi kehidupan pers. Itu dana publik ya. Jadi pemerintah itu sebenarnya hanya semacam komite, panitia, eksekutif yang diberi wewenang untuk mengelola dana itu. Tapi sebenarnya itu kan bukan dana pemerintah, (melainkan) dana publik.
Ini penting, karena banyak yang mengkritik, 'Wah, pers sekarang merengek-rengek minta pemerintah untuk menolong.' Sebenarnya itu salah. Sebenarnya cara berpikirnya (harusnya bahwa) itu dana publik, (dan) dana publik harus dialokasikan untuk kepentingan publik. Kebebasan pers itu bagian dari kepentingan publik itu.
Apa yang bisa Anda sarankan untuk media-media di Indonesia saat ini? Bagaimana ke depan?
Di luar masalah insentif ekonomi, kita berharap media itu tetap membantu publik untuk menghadapi situasi yang sulit sekarang ini. Tolong sampaikan informasi yang benar, informasi yang bermartabat. Tolong hindari betul kecenderungan clickbait, kecenderungan dramatisasi keadaan korban, taati kode etik.
Dan yang lebih penting adalah menyeimbangkan antara satu fungsi kritik terhadap pemerintah menangani keadaan ini. Kritik itu penting, karena kritik itu energizer bagi pemerintah untuk menangani lebih baik lagi. Tetapi kritik ini harus disampaikan hati-hati betul, jangan berlebihan, karena kalau berlebihan itu bisa membuat ketakutan dan frustrasi yang berlebihan di masyarakat.
Jadi jurnalisme yang kritikal harus diimbangi dengan jurnalisme yang istilahnya itu jurnalisme yang manufacturing hope. Jurnalisme yang menjaga optimisme masyarakat bahwa keadaan ini akan bisa ditangani dengan baik. Itu penting sekali. Jangan sampai masyarakat justru frustrasi, semakin takut ketika membaca media.
Tetapi di saat yang sama, kita juga tahu pemerintah itu harus dikritik terus ini. Kalau tidak dikritik, pemerintah nanti abai.
Jadi menyeimbangkan jurnalisme kritis dengan jurnalisme manufacturing hope itu adalah yang harus dikejar oleh setiap wartawan dan setiap media hari ini. Tentu ini bukan hal yang gampang. Mudah sekali diomongkan, tapi praktiknya sulit memang, (itu) saya akui.
Tetapi kalau tidak mau menghadapi kesulitan, jangan jadi wartawan, kan begitu. Jadi teman-teman pers harus bisa menantang dirinya untuk memikul tanggung jawab yang lebih tinggi.
Itu nggak keren lagi sekarang kan. Mengkritik pemerintah, tahun 1999, 2000-an itu keren. Sekarang, itu bukan sesuatu yang istimewa lagi, setiap pers bisa. Tetapi bagaimana mengkritik, dan menjaga harapan masyarakat bahwa dengan disiplin, dengan solidaritas, dengan empati kita bisa melampaui situasi yang sulit sekarang ini.

Jika butuh bantuan pemerintah untuk "menyelamatkan" media, bantuan seperti apa? Lalu bagaimana dampak atau pengaruhnya terhadap media?
Ya, kan bantuan itu ada beberapa hal, misalnya (di) beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Jepang, itu dana iklan untuk media tidak diutak-atik. Jadi di Indonesia kan dana iklan itu dialokasikan untuk pandemi, dan itu masuk akal. Itu nggak salah pemerintah, kita nggak boleh menyalahkan itu. Tetapi dampaknya (jadi) memukul industri pers.
Nah, kalau (industri pers) terpukul, nanti melahirkan PHK baru kan. Nambah masalah sebenarnya buat pemerintah.
Jadi alokasi iklan pariwara untuk media profesional itu tolong dipertahankan seperti sebelum krisis, tanpa mengalokasikan anggaran baru. Tetapi perusahaan media jangan melakukan PHK atau semacamnya. Jadi dana sosialisasi kebijakan program jangan direduksi, jangan dihilangkan, tetapi secara reciprocal media massa atau perusahaan pers tidak melakukan PHK atau semacamnya.
Bisa juga seperti model Australia, pemerintah atau negara menanggung gaji dan jaminan-jaminan sosial untuk karyawan perusahaan media. Sehingga media tetap bisa berfungsi untuk menyebarkan informasi kepada publik. Jadi pertama alokasi iklan, kedua menanggung gaji dan tunjangan jaminan sosial untuk karyawan media. Jadi itu opsional.
Terus untuk media cetak, (bisa lewat) subsidi harga kertas. Di Eropa itu ada skema memberikan potongan pajak langganan media, baik yang cetak maupun online, khususnya untuk konsumsi muda atau keluarga rumah tangga. Jadi harga langganan media itu dihilangkan instrumen pajaknya. Kemudian ada pemotongan harga listrik untuk perusahaan media.
Khusus terkait media online yang makin menjamur di era digital, bagaimana sebaiknya mengelolanya? Lewat verifikasi Dewan Pers cukupkah? Bagaimana juga dengan keberlangsungannya?
Verifikasi itu penting, tapi saya kira perlu kerja sama antara Dewan Pers dengan asosiasi. Karena Dewan Pers sendiri kayaknya nggak mampu, terlalu lama nanti.
Tapi verifikasi itu penting untuk menjamin bahwa pers online terdaftar, layak untuk beroperasi.
Ada bayangan kira-kira akan bagaimana perkembangan media di Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan? Bagaimana dalam jangka panjang?
Ekosistem industri media itu sangat tergantung pada apakah teman-teman media itu mampu bernegosiasi dengan baik sama platform. Karena hubungannya sekarang timpang, platform sangat dominan sementara publisher selalu banyak kalah.
Jadi negosiasi yang bersifat B to B itu penting, yang di level playing field agar sama, tapi juga mendorong negara agar memberikan keberpihakan terhadap ekosistem pers nasional. Saya kira itu penting. Tapi di saat yang sama media massa konvensional, di Amerika media online ini kan bagian dari media konvensional, harus bisa menciptakan inovasi produk dengan new media.
Jadi kalau hoaks, informasi simpang siur itu sudah bicara di media sosial, maka media konvensional jangan garap itu lagi. Kalau ikut-ikutan garap itu untuk mengejar clickbait, itu namanya kan media massa (jadi) follower media sosial. Kalau itu yang terjadi, nanti yang mainstream itu mereka. Jadi yang disebut new mainstream itu adalah media sosial itu.
Jadi kalau media massa mengikuti media sosial, itu seperti membesarkan musuhnya itu, membesarkan kompetitornya. Karena secara bisnis media sosial itu kadang-kadang menguntungkan media massa lewat mesin pencari. Kalau mengikuti media sosial, mereka yang besar, dan media massa jadi yang alternatif.
Tetapi kalau bisa melakukan diferensiasi produk, produknya lebih baik daripada media sosial, saya yakin akan muncul keseimbangan baru. Media baru, media sosial dan sebagainya jalan, dengan media lama tetap dibaca oleh orang karena memberikan sesuatu yang berbeda, memberikan informasi yang lebih baik.
Jadi yang terjadi tidak total disruption, tapi akan mencapai keseimbangan baru di mana media lama akan hidup berdampingan dengan media baru. Karena mereka sebenarnya lapak-lapak yang berbeda dagangannya.
Sekarang di Eropa Utara sudah terjadi, media cetak sudah nggak turun lagi, sekarang sudah landai kurvanya. Kenapa itu terjadi, karena diferensiasi dan distansiasi itu. Di situ kita harus percaya pada good journalism itu. Itu klise, tapi penting.