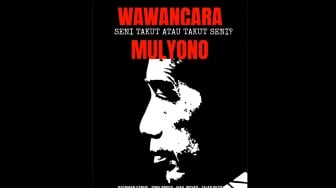Suara.com - Meski era reformasi di Indonesia sudah berjalan lebih dari 21 tahun, ancaman atau kekerasan terhadap jurnalis ternyata masih menjadi salah satu "penyakit" yang seakan susah dicarikan obatnya. Tidak saja dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di berbagai pelosok Nusantara, pada momen atau peristiwa besar yang menjadi sorotan jutaan orang pun, jurnalis yang notabene adalah penyampai informasi bagi kepentingan publik masih kerap menjadi korban.
Dalam momentum rangkaian aksi unjuk rasa di berbagai kota sepanjang akhir September 2019 lalu saja misalnya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat setidaknya ada 10 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Sebagaimana sempat diutarakan dalam pertemuan di LBH Pers beberapa waktu lalu, empat di antara kasus itu dialami jurnalis Jakarta dari aparat saat meliput aksi di depan Gedung DPR, sementara enam lainnya terjadi di Makassar dan Jayapura.
Faktor apa sebenarnya yang menyebabkan kasus-kasus seperti ini masih saja terjadi, serta bagaimana upaya yang mesti dilakukan dalam mengatasinya? Lebih jauh, bagaimana seharusnya posisi pemerintah dalam hal ini? Mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, belum lama ini Suara.com berbincang dengan Gilang Parahita, akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku salah seorang yang concern terhadap persoalan ini. Berikut petikan wawancara dengannya:
Bagaimana Anda melihat masih maraknya kasus kekerasan terhadap jurnalis sejauh ini? Bagaimana polanya?
Baca Juga: Eksekutor dan Otak Pembunuh 2 Jurnalis di Labuhanbatu Terancam Hukuman Mati
Sebetulnya pola ancaman kekerasan terhadap jurnalis ini tidak banyak berubah, ya. Secara tradisional tetap yang menjadi pelaku utama itu adalah aparat; birokrasi, militer, maupun kepolisian. Begitu. Namun dari segi bentuk, kami melihat bahwa jurnalis (kini juga) kerap mengalami kekerasan melalui teknologi online, entah dia mengalami doxing, bullying, secara online; atau bahkan institusi medianya itu mengalami sejenis hacking begitu.
Nah, kalau melihat bahwa bentuk kekerasan itu berubah, atau bergeser atau berkembang, hal ini menunjukkan aktornya itu sendiri semakin beragam, tidak hanya negara melainkan juga aktor non-negara. Bisa itu masyarakat biasa ataupun warga yang tergabung dalam ormas yang menggunakan identitas agama tertentu.
Kita menemukan itu dari segi persepsi jurnalis, begitu ya. Real-nya memang, data-data sudah dikumpulkan oleh teman-teman AJI, dan itu cocok bahwa pelaku kekerasan itu secara tradisional masih dari negara. Walaupun tidak menutup kemungkinan jika memperhitungkan bentuk-bentuk kekerasan online, maka pelaku non-negara ini juga makin banyak begitu.
![Aksi Jurnalis Surabaya tolak kekerasan yang terjadi di beberapa wilayah oleh aparat kepada peliput aksi damonstrasi di beberapa kota. [Suara.com/Dimas Angga P]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/09/25/75336-aksi-jurnalis-surabaya-tolak-kekerasan.jpg)
Faktor apa menurut Anda yang menyebabkan jurnalis masih kerap menjadi korban kekerasan oleh aparat?
Sebenarnya faktor utamanya adalah (bahwa) profesi jurnalis ini kurang dihormati oleh aktor-aktor negara, sehingga masyarakat kita menirunya. Meskipun secara internal jurnalis itu merasa terhormat dengan profesinya, sebab mereka patuh terhadap prinsip-prinsip profesionalisme jurnalisme, namun negara itu masih meremehkan hal-hal itu.
Baca Juga: William Aditya Sarana: Tugas Kami Mengawasi Anggaran, Sesederhana Itu
Buktinya adalah saya menemukan Sustainable Development Goals (SDGs) yang sudah diadopsi oleh pemerintah Indonesia dan sudah dikeluarkan juga Peraturan Presiden terkait SDGs di Indonesia tahun 2017, nyatanya belum menguatkan sisi pilar hukum dan HAM dan kelembagaan terkait hukum dan HAM. Hal itu menunjukkan bahwa persoalan HAM, apalagi persoalan kekerasan terhadap jurnalis, itu masih belum didukung oleh negara, begitu. SDGs-nya secara formalnya iya, sudah diakui oleh negara kita, tetapi pilar-pilarnya ternyata tidak secara total dijalankan, terutama pilar hukum dan HAM.
Nah, kita menginginkan bahwa negara itu harus konsisten terhadap pernyataan politiknya melindungi HAM, dan kemudian menempatkan keselamatan terhadap jurnalis ini, perlindungan anti kekerasan terhadap jurnalis ini ada (menjadi) prioritas setiap kelembagaan pemerintah. Artinya, di level pusat sampai level daerah, mereka harus punya aware, bagaimana menghadapi jurnalis tanpa menggunakan pendekatan yang berindikasi kekerasan apa pun bentuknya.
Jadi, terkesan pemerintah masih tidak menghormati profesi jurnalis? Apa ini karena faktor jurnalis yang terlalu mengkritisi pemerintah sehingga pemerintah tidak suka dan memandang tidak hormat terhadap jurnalis, atau seperti apa?
Tugas jurnalis itu memang untuk mengkritisi. Jadi kalau pemerintah merasa risih dengan itu, artinya pemerintah masih belum mengakui adanya kebebasan pers dan independensi pers. Pers di era reformasi itu punya peran sangat berbeda dibandingkan pers era Orde Baru. Di era reformasi, pers memang harus memerankan fungsi check and balances terhadap tugas-tugas pemerintah. Dari situlah sebetulnya warga masyarakat itu bisa terinformasi dengan baik, termasuk soal program-program pemerintah baik kelebihannya maupun kekurangannya. Tanpa adanya pers yang baik, maka bagaimana mungkin kita bisa memilih, katakanlah calon bupati, calon wali kota, gubernur hingga presiden, dengan pertimbangan pertimbangan yang rasional, begitu.
Bagaimana harusnya sikap aparat dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis, juga langkah perusahaan pers dan jurnalis itu sendiri, diungkap Gilang Parahita di laman berikutnya...