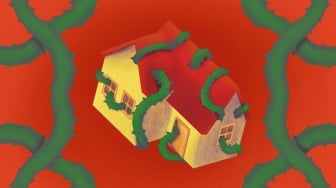Suara.com - Bulan Agustus ini, Republik Indonesia (RI) kembali berada di momentum refleksi kemerdekaannya, tepatnya dengan memperingati proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 untuk yang ke-74 kalinya. Sebagaimana biasa, momen HUT RI kali ini pun di berbagai tempat, dalam maupun luar negeri, telah dan masih akan diisi dengan berbagai kegiatan, baik seremonial hingga yang bersifat hiburan.
Namun yang kerap jadi pertanyaan mungkin, apakah makna peringatan Hari Kemerdekaan saban tahun ini sudah memberi sesuatu secara filosofis kepada segenap elemen bangsa, baik rakyat maupun pejabatnya? Lebih jauh lagi, apakah masyarakat Indonesia benar-benar bersyukur telah puluhan tahun hidup sebagai bangsa yang merdeka, dan apa kaitannya dengan Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai ideologi?
Mencoba mendapatkan pandangan mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut, Suara.com baru-baru ini menanyai Syaiful Arif, Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila (PSPP) yang juga adalah mantan Tenaga Ahli Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Penulis buku Islam, Pancasila dan Deradikalisasi (Elexmedia, 2018) dan sejumlah buku lainnya itu pun secara gamblang menuturkan pendapatnya, termasuk kritikan, salah satunya bahwa ada "dosa" terbesar bangsa ini karena belum merumuskan bangunan pengetahuan dari ideologi Pancasila.
Berikut petikan wawancara khusus Suara.com dengan Syaiful Arif:
Apa sebenarnya makna kemerdekaan RI pada era kekinian? Apakah cuma seremonial belaka, ataukah ada hal filosofis yang seharusnya bisa diresapi oleh rakyat Indonesia?
Terima kasih. Peringatan Kemerdekaan itu kan ungkapan rasa syukur kita atas nikmat kemerdekaan yang diperoleh bangsa ini sejak 17 Agustus 1945. Sebagai ungkapan rasa syukur, ya harus disertai dengan kesadaran, pemahaman dan kehendak untuk berbuat baik. Kebaikan yang harus kita lakukan, ya menjadi warga negara yang baik. Seperti apa? Seperti digariskan oleh nilai-nilai di dalam dasar negara, Pancasila.
Seremonial? Itulah problemnya. Lembaga kenegaraan kita, juga lembaga pendidikan tidak serius menggunakan momen ini sebagai proses penguatan kesadaran berbangsa. Kita hanya merayakan "Agustusan" ini seperti perayaan hari-hari besar lainnya: minus refleksi, minim edukasi.
Apa saja tantangan besar secara politik, ekonomi, maupun sosial-budaya pada saat ini, tepatnya ketika HUT ke-74 Kemerdekaan RI?
Ya, saya kira kita harus optimis ya. Pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebagai pemerintahan yang bekerja, saya kira sudah berbuat maksimal. Hanya saja memang perlu lebih dioptimalkan, terutama di soal pembangunan karakter bangsa (nation and character building). Ini yang luput dari periode pertama Pak Jokowi. Akibatnya, radikalisme menguat, intoleransi merebak. Kecintaan pada nilai-nilai kebangsaan memudar, penolakan terhadap Pancasila menanjak. Setelah Republik berusia 74 ini, semangat untuk merawat keindonesiaan harus menjadi prioritas kita.
Baca Juga: Beka Ulung Hapsara: Razia Buku oleh Ormas Itu Tindak Pidana, Melanggar HAM
![Ribuan warga mengarak peti jenazah berbentuk sapi dalam iring-iringan prosesi kremasi jenazah tokoh Puri (kerajaan) Denpasar Ida Anak Agung Ayu Oka Pemecutan di Denpasar, Bali, Rabu (14/11). [ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2018/11/14/13101-upacara-ngaben.jpg)
Kalau secara ideologi, bagaimana konsepsi Pancasila setelah 74 tahun RI berdiri? Apakah banyak distorsi?
Apakah Pancasila sudah kita rumuskan menjadi ideologi? Saya kira belum. Dan inilah "dosa" terbesar bangsa ini: kita belum merumuskan bangunan pengetahuan dari ideologi Pancasila. Mengapa? Kompleks persoalannya. Tapi salah satu sebabnya ialah kita tidak terbiasa menempatkan Pancasila sebagai diskursus ilmiah, wacana intelektual. Pancasila lebih sering kita bicarakan sebagai dasar negara yang legalistik, atau nilai-nilai normatif yang kosong konsepsi. Padahal Pancasila itu kan ideologi politik. Sebagai ideologi, ia adalah pergulatan pemikiran.
Apa yang bisa dijadikan sebagai hal kebaruan dari Pancasila di era kekinian? Terutama kalau dihadapkan dengan problem sikap serta aksi intoleran yang semakin marak?
Saat ini, kita harus memperbarui cara baca kita terhadap Pancasila. Akibat "pemurnian Pancasila" yang dilakukan Orde Baru, ideologi kita ini telah lama bersifat bebas nilai. Tidak ada preskripsi ideologis yang khas, dilengkapi oleh kandungan intelektual yang mendalam. Sila-sila Pancasila kita baca, pinjam istilah Sutan Takdir Alisjahbana, "secara bercerai-berai". Setiap sila terpisah dari sila-sila lainnya, menjadi urutan kalimat yang hanya dihapal secara numerik.
Kini, kita harus lepas dari cara baca yang bebas nilai itu, dengan membaca Pancasila sebagai kesatuan nilai integral yang "saling mengandaikan dan mengunci". Dalam hal ini, pandangan pemikir Pancasila, Prof. Notonagoro, penting kita pakai. Yakni membaca Pancasila secara piramidal. Hanya saja Notonagoro menggunakan piramida terbalik, di mana sila keadilan sosial menjadi pucuk piramid yang mengkhususkan nilai-nilai umum di atasnya. Ketuhanan dalam piramida terbalik ini justru berada di lantai, bukan di mahkota.
Nah, Bung Hatta membaca secara piramidal juga tetapi dengan posisi ketuhanan di pucuk hirarki. "Di bawah terang nilai ketuhanan, sila-sila di bawahnya mendapatkan dimensi religius dan etik", demikian ungkap karib Bung Karno ini. Dengan "piramida ketuhanan" ini, maka Pancasila adalah dasar negara, ideologi dan pandangan hidup yang religius, teologis. Inilah cara baca yang penting kita kembangkan, di tengah menguatnya penolakan terhadap Pancasila atas nama Tuhan. Lho, gimana menolak Pancasila karena Tuhan, wong di dalam Pancasila (justru sebenarnya) Tuhan dinomorsatukan?
Oleh karenanya, saya punya pandangan, kelompok yang menuduh Pancasila sebagai ideologi sekular, sebenarnya telah menerapkan sekularisasi atas Pancasila. Mereka yang sekular, karena faktanya, Pancasila adalah ideologi ketuhanan!
Ke depan, pemahaman Pancasila sebagai ideologi ketuhanan yang mencerminkan nilai-nilai tauhid dan maqashid al-syar'i inilah yang wajib kita kembangkan untuk mengikis kesalahpahaman umat.
Soal konsep Pancasila-nya Bung Karno, hingga era Soeharto dan sekarang, juga tentang "sosialisme" sebagai inti dari Pancasila, baca di laman berikutnya!