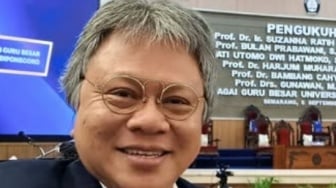Suara.com - Wacana pemindahan Ibu Kota RI kembali menghangat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui pemindahan ibu kota ke luar Jawa. Hal itu diputuskan dalam rapat terbatas terkait Pemindahan Ibu Kota pada 29 April 2019 di Kantor Kepresidenan, Jakarta.
Sebagian pihak menilai hal ini hanyalah utopia belaka. Namun, pendapat itu ditampik oleh Pakar Perencanaan Wilayah Universitas Gadjah Mada (UGM) Lutfi Mutaali. Ia menilai pemindahan ibu kota bukan angan-angan belaka, melainkan hal itu sudah menjadi impian lama, bahkan sudah sempat dilontarkan oleh Presiden pertama RI Soekarno.
Meski banyak perdebatan, Lutfi menilai sudah saatnya impian Proklamator RI itu diwujudkan. Baru-baru ini, Suara.com berkesempatan berbincang lebih lanjut, untuk mengetahui pandangan Lutfi mengenai wacana tersebut. Berikut petikan wawancaranya:
Seberapa mendesak pemindahan Ibu Kota Indonesia perlu dilakukan?
Kalau ditanya seberapa mendesak, itu tergantung perspektifnya, terutama perspektif politik. Orang bisa mengatakan tidak mendesak; orang juga bisa mengatakan sangat mendesak. Itu sangat debatable.
Bagi saya, ini merupakan bagian dari sejarah yang sangat lama sekali. Keinginan untuk pindah itu kan bukan keinginan saat ini saja, tapi sejak zaman Soekarno. Sejarah panjang ini kemudian bertemu dengan fakta tentang terkonsentrasinya pembangunan di wilayah Pulau Jawa, khususnya Jabodetabek, baik secara demografis maupun secara ekonomi.
Saya mengatakan, ini sudah waktunya. Karena pemindahan ibu kota ini cuma masalah politik saja. Secara faktual, orang memerlukan hal itu untuk penyegaran, mewujudkan cita-cita lama, mewujudkan amanat konstitusi, dan sebagainya. Kalau saya pribadi menilai, kebutuhan ini sudah sangat mendesak sekali.
Kenapa harus dilakukan perpindahan ibu kota?
Ada pertimbangan daerah asal yaitu Jakarta, dan daerah tujuan pemindahan ibu kota. Dalam konsep interaksi wilayah, ada daya dorong dari daerah asal dan daya tarik dari daerah tujuan.
Baca Juga: Sutrisna Wibawa: Media Sosial untuk Terapkan Kepemimpinan Partisipatif
Daya dorong utama berasal dari kepentingan negara, yaitu mewujudkan amanat konstitusi untuk melakukan proses keseimbangan dan keadilan pembangunan bagi seluruh rakyat dan wilayah di Indonesia. Karena fakta ketimpangan wilayah dan sosial di Indonesia sudah berlangsung lama dan sistemik, bahkan akut. Dari zaman kemerdekaan sampai sekarang, keadaan tidak bertambah merata, namun semakin timpang. Konsentrasi ekonomi "kue pembangunan" di Jawa 52 persen dan Sumatera 28 persen. Bahkan, seperlima PDB terkonsentrasi di Jabodetabek. Ini melukai rasa keadilan Indonesia. (Maka) Jalan ekstrem harus ditempuh, salah satunya adalah melakukan "revolusi spasial" dengan jalan memindah ibu kota.
Dorongan lainnya adalah untuk menjaga integrasi Nusantara, yang dibuktikan dengan sistem konektivitas antar-seluruh wilayah Nusantara. Faktanya, sekarang hampir 60-70 persen orientasi pergerakan orang dan barang mengarah ke Pulau Jawa. Bisa dicek data penerbangan dan bongkar-muat pelabuhan. Sistem integrasi regional yang lemah, semakin mendorong wilayah maju semakin maju, (sedangkan) wilayah tertinggal semakin tertinggal. Harus ada keberanian untuk melakukan restrukturisasi.
Dalam sistem negara kepulauan seperti Indonesia, model konsentrasi sistem pelayanan pemerintahan telah mengakibatkan banyaknya inefisiensi sosial ekonomi, karena semua penjuru Nusantara harus menuju ke satu tempat. Orang mau ke mana-mana harus ke Jakarta dulu. Oleh karena itu, diperlukan pembuatan pusat-pusat pertumbuhan baru di seluruh penjuru Nusantara, baik dalam dimensi ekonomi seperti Kawasan Andalan dan Kawasan Ekonomi Khusus, maupun pelayanan pemerintahan. Semuanya dilakukan dalam kerangka mendistribusikan hasil-hasil pembangunan secara lebih merata dan berkeadilan.
Daya dorong dari daerah asal, yaitu Jakarta, bukanlah menjadi pertimbangan penting. Degradasi lingkungan dan sistem wilayah Jakarta sudah teramat parah. Mustahil (dengan) memindahkan ibu kota ke tempat lain akan mengurangi beban Jakarta dan menjadi solusi. Dengan memindah atau tanpa memindah ibu kota, Jakarta akan tetap seperti sekarang ini. Bahkan lebih parah, karena beban dorongan pinggiran semakin kuat dengan adanya Kota Meikarta dan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Ibaratnya, Jakarta (tetap) akan tergencet dari semua arah.
Jadi, keliru mengaitkan pemindahan ibu kota ini dengan kondisi Jakarta. Ingat, sumbangan fungsi pemerintahan dalam beban dan mobilitas penduduk tidak sebesar fungsi ekonomi. Jakarta akan menghebat dan terus bertambah hebat secara ekonomi. Jakarta akan sampai ke titik jenuh, di mana kemacetan dan banjir akan terus bertambah dan menjadi beban ekonomi yang tidak mampu lagi ditanggung oleh pasar. Jika kondisi ini tercapai, maka pasar akan mencari keseimbangan. Ibu kota baru beserta pusat pertumbuhan lain akan menjadi alternatif yang menarik. Dengan kata lain, pemindahan ibu kota akan menjadi embrio lahirnya pusat-pusat pertumbuhan baru yang menjadi daya tarik bagi bekerjanya sistem ekonomi spasial yang lebih berimbang di Indonesia.
Dalam bayangan Anda, akan bagaimana kondisi Jakarta pasca-pemindahan Ibu Kota RI?
Sebenarnya kalau terkait Jakarta itu sendiri, pendapat saya (perubahannya) tidak terlalu signifikan. Artinya, pindahnya ibu kota itu tidak terlalu mempengaruhi kondisi dan beban Jakarta.
Kalaupun mungkin punya pengaruh, itu di angka 10-20 persen. Beban Jakarta itu kan bisa kita lihat dari beban mobilitas penduduknya. Kalau kita melakukan survei, mungkin bisa dicek di data BPS tentang pola perjalanan dari pinggiran Jakarta ke Jakarta. Orang yang melakukan perjalanan untuk kepentingan pelayanan publik dan pemerintahan itu mungkin cuma 10-20 persen. Lebih dari 80 persen bermobilitas karena faktor ekonomi. Artinya, dia bekerja di perusahaan, di pabrik, di pusat-pusat perbelanjaan, dan sebagainya.
Artinya, kalau dari segi mobilitas penduduk itu, gampangnya, beban yang dikurangi Jakarta dengan memindah itu tidak terlalu signifikan. Macet pasti (masih terjadi), banjir juga pasti. Enggak punya pengaruh yang terlalu besar. Makanya, memindah Ibu Kota (RI) ini kan sebenarnya pertimbangan nasional, bukan pertimbangan lokal dari Jakarta.
Kedua, kita bisa lihat mobilitas orang dari luaran. Dari daerah luar itu kan hampir pola pergerakannya ke Jakarta. Saya tidak punya data, tapi saya bisa memprediksi, orang yang naik pesawat ke Jakarta itu 30-40 persen terkait dengan pelayanan publik di pusat pemerintahan. Apakah di kehutanan, di dinas pendidikan, dan sebagainya. Contoh di Yogyakarta, mungkin 40-50 persen orang yang saya temui orientasinya ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah atau saking terkonsentrasinya kegiatan di Jakarta. Banyak anggota DPRD di daerah justru menyelenggarakan kegiatan di Jakarta.
Dalam konteks inilah yang mau kita sebar. Sehingga kalau ibu kota negara pindah di manapun, paling tidak beban itu akan berkurang. Beban terhadap Jakarta dan mobilitas penduduk dan kegiatan pelayanan publik itu bisa dikurangi. Untuk Jakarta (sendiri) efeknya tidak terlalu besar. Makanya, ada banyak ahli juga yang mengatakan itu nggak menyelesaikan (masalah) Jakarta. Saya bilang, memindah ibu kota (memang) bukan karena urusan Jakarta. Urusan Jakarta dengan pemindahan itu kecil. Ini urusan negara, bukan urusan Jakarta.
![Suasana kemacetan di sepanjang Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (27/7). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2015/07/27/o_19r7kqhok15r415c91bm5m8m93sa.jpg)
Pemindahan ibu kota ini akan berdampak negatif terhadap ekonomi Jakarta atau tidak?
Kalau saya bilang, Jakarta akan tetap seperti ini. Makanya saya bilang, tidak terlalu terpengaruh secara signifikan. Apalagi kalau misalnya terjadi pusat pemerintahan (baru), gedung-gedung pusat pemerintahan di Jakarta kan bukan berarti kosong. Pasti nanti diganti peruntukan. Kalau untuk peruntukan bisnis, tambah lagi kan (value) Jakarta jadi kota bisnis.
Beberapa gedung yang memiliki nilai strategis, lokasi yang luar biasa, itu kalau ditawarkan ke swasta banyak yang mau. Dan kalau terjadi perubahan fungsi kantor-kantor itu jadi pusat bisnis, justru akan mempercepat Jakarta menjadi kota bisnis secara ekonomi. Jadi Jakarta akan tetap seperti ini. Bahkan growth-nya bisa tinggi, dengan mengkhususkan daerahnya itu sebagai pusat bisnis sekelas Singapura.
Perlukah memisahkan ibu kota pemerintahan dan ibu kota ekonomi?
Di mana pun, tidak ada fungsi kota yang tunggal. Semua menyatu dan saling terkait, sampai keduanya menjadi dominan. Terpisah atau jadi satu, dua-duanya dapat dilakukan.
Secara prinsipil, "ibu kota ekonomi" itu mengikuti sistem dan mekanisme pasar atau konsentrasi penduduk, dan menjadi pusat pertumbuhan yang memiliki multiplier effect yang sangat besar. Jadi, based on location. Sedangkan "ibu kota pemerintahan" memiliki sifat footloose location. Artinya dapat berlokasi di mana saja, asal mampu memberikan pelayanan publik terbaik.
Menurut saya, dalam skala nasional pengaruh pemindahan ibu kota terhadap growth ekonomi nasional itu tidak akan terjadi. Apalagi kita berharap ada pusat pertumbuhan ekonomi baru, kemudian ekonomi bisa meningkat karena mindahin ibu kota; itu hampir enggak mungkin terjadi. Karena memang fungsinya beda. Pusat ekonomi dan pemerintahan pasti (fungsinya) beda.
Tapi pada skala lokal, misal di Kalimantan, apalagi provinsinya, kabupatennya, growth-nya akan sangat besar. Jadi nanti akan menimbulkan beberapa provinsi baru yang growth-nya tinggi; bukan agregasi nasional. Kalau nasional kecil. Tapi dengan memindah pusat pemerintahan, misal di Kalimantan, bisa menimbulkan pertumbuhan ekonomi di situ. Dan kalau dia punya multiplier yang besar bagi sekitarnya, itu besar sekali efeknya. Artinya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baru di luar Jakarta itu bisa terjadi.
Bagaimana caranya agar pusat ekonomi itu bisa tumbuh di ibu kota yang baru?
Ini bisa dilakukan apabila pusat pemerintahan di-backup oleh kegiatan-kegiatan yang orientasinya pada human capital, bukan kegiatan-kegiatan yang resource-based kaya tambang, perkebunan, hutan. Kalau hutan dan tambang, kan harus berlokasi di situ karena sumber dayanya di situ.
Kita bisa mengembangkan sebuah ibu kota negara yang di-backup belakangnya dengan industri hi-tech, semacam Silicon Valley di Amerika. Itu bisa enggak dilakukan? Sangat bisa. Karena ibu kota pemerintahan dan industri hi-tech itu tipenya sama-sama footloose. Modalnya (untuk mewujudkan) cuma satu: yaitu keberanian dan kebijakan pemerintah.
Desain Silicon Valley ini bisa dikonsentrasikan di hinterland-nya. Bagi saya itu akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kita belajar dari India. India itu menciptakan pusat ekonomi baru dengan wilayah yang basis ekonominya itu di industri hi-tech, teknologi informasi. Dan kita tahu peran industri hi-tech terhadap pertumbuhan ekonomi besar sekali.
Kalau memang pemerintah ada keberanian, jangan hanya mendesain pusat pemerintahan, jangan hanya memindah kantor-kantor di satu tempat, pegawainya di situ. Tidak hanya itu. Step berikutnya adalah menyiapkan daerah belakangnya, semacam Silicon Valley. Di Kalimantan enggak masalah. Kalau Anda ciptakan di situ, orang akan pergi ke situ. Sama dengan di India, orang Amerika balik ke India. Tapi itu perlu effort yang lebih besar.
Ini sebenarnya ketemu dengan rencana Presiden Jokowi kalau dia menang (Pemilu). Kalau dia menang, di pemerintahan berikutnya kan terjadi perubahan orientasi (pembangunan) dari infrastruktur ke sumber daya manusia (SDM). Yang dipaparkan capres kan gitu. Artinya, lima tahun ke depan itu semacam program besar untuk menciptakan SDM yang nanti bisa bersaing di level global.
Bayangan saya, pemindahan ibu kota ini kan butuh waktu yang lama. Dalam lima tahun, paling dapatnya cuma kajian dan konsensus politik. Jadi kayanya, lima tahun ini belum sampai kepada pembangunan fisik. Lima tahun ini capaian yang paling bagus kalau terjadi konsensus bahwa semua pihak di DPR itu menyepakati, kemudian dibuat UU. Kita enggak mau kan pindah ibu kota tanpa punya basis legal yang kuat? Nanti kalau presidennya ganti, nanti ibu kotanya ganti lagi. Jadi, step lima tahun itu, bayangan saya, (baru tahap) konsensus politik beserta kajian kelaikan.
Sambil itu, lima tahun (ke depan) ini adalah lima tahun SDM. Sehingga lima tahun berikutnya itu sudah operasional memindahkan, membangun infrastruktur, termasuk SDM yang cukup kuat untuk menciptakan daerah belakang --atau hinterland ibu kota-- itu (jadi) semacam Silicon Valley.
Lebih jauh, Lutfi Mutaali pun membeberkan proses, perkiraan waktu, juga contoh pemindahan Ibu Kota yang pernah dilakukan negara lain. Simak di laman berikutnya..!
Kontributor : Sri Handayani
Butuh waktu berapa lama kira-kira untuk proses pindah ibu kota? Langkah-langkahnya apa saja?
Kalau menurut Bappenas kan butuh waktu 20-30 tahun. Artinya, butuh waktu lama. Step (menurut) saya, bayangan saya, konsensus politik dulu. Enggak mungkin kita melakukan kegiatan besar tanpa konsensus politik. Belajar dari membuat UU, itu kan tidak mudah. Lama prosesnya. Tahap paling krusial dan sulit itu kan menyepakati perundang-undangan. Kalau ibu kota dipindah, itu kan UU-nya berubah. Mungkin pertimbangan orang tentang sejarah dan sebagainya mungkin jadi pertimbangan.
Menurut saya, paling aman, lima tahun itu perjuangan yang paling bagus adalah kalau sampai terjadi konsensus politik. (Hingga) Dikeluarkanlah UU yang namanya UU Pemindahan Ibu Kota. Sambil itu, dilakukan kajian lebih detail. Sampai sekarang kan belum bisa nunjuk (kota) A, B, C. Kita harusnya setelah ini sudah masuk level makro-meso. Level detailnya bagaimana? Kalau istilah teknisnya, DED. Jadi lima tahun itu sampai menyiapkan DED-nya. Desainnya dan lokasinya sudah jelas, budget-nya seperti apa, termasuk bagaimana budget itu dikeluarkan. Kalau kita mau melibatkan swasta dan sebagainya, desainnya seperti apa. Bayangan saya lima tahun pertama sampai di situ.
Baru lima tahun kedua kita bisa operasional. Yang jadi masalah berikutnya itu (adalah) tentang siapa yang bisa merealisasikan ide UU yang sudah diterbitkan. Kalau orang bangun infrastruktur, itu enggak terlalu lama. Katakanlah menyiapkan pembangunan fisik itu lima tahun kedua, lima tahun ketiga itu baru orang pindah, pegawai pindah dan sebagainya. Jadi kira-kira, lima belas tahun lah baru terealisasi, baru berjalan.
Lantas, selama 15 tahun itu potensi gejolaknya seperti apa?
Pasti ada lah. Salah satu kelemahan di Indonesia, kan itu, inkonsistensi di dalam pelaksanaan kebijakan. Makanya kan harus dikunci dengan UU. (Bahkan) UU saja kadang bisa diubah kok. Itu pasti punya pengaruh besar (terhadap gejolak yang muncul).
Makanya, kadang kan ada yang menganggap itu utopis. Itu mimpi kayanya. Bagi saya sih enggak mimpi. Itu real kok. Cuma, dibutuhkan pemerintah yang kuat dan berani. Misal di parlemen itu kuat, bisa menjaga 15 tahun itu konsisten terus. Di Malaysia itu kan (berhasil) karena Mahathir. Dia bisa memindahkan Putrajaya itu karena pemerintahannya kuat tak tertandingi. Enggak ada oposisi yang memprotes, makanya mulus-mulus saja.
Kalau ini nanti dimanfaatkan untuk kepentingan politik, dimain-mainin, ini kan sudah terasa. Saya lihat suara partai yang tidak setuju, yang di luar pemerintahan itu kan kaya enggak setuju. Itulah kendala yang paling berat; bukan kendala teknis.
Bagaimana agar dalam 15 tahun nanti proses pemindahan ibu kota tetap berjalan? (Soalnya) Presiden Jokowi kalaupun menang kan tinggal satu periode lagi?
Pertama, ya, memang diperlukan konsensus politik nasional. Bahkan saya pernah menulis, kalau ngeyel terus, kalau perlu referendum misalnya. Artinya (itu nanti) kan kehendak rakyat. Kalau rakyat menghendaki untuk dipindah, DPR itu enggak boleh (menolak).
Pertama konsensus politik, kemudian konsistensi kebijakan, penyiapan SDM, dan pembiayaan. Yang biasanya krusial kan masalah budgeting. Budget-nya itu mau APBN full atau dikerjasamakan. Waktu sosialisasi kajian Bappenas itu kan selain aspek-aspek pembiayaan. Titik krusialnya biasanya di situ.
Kalau seperti yang ditulis media (bahwa biayanya) Rp 400 triliun, itu kan sebenarnya tidak terlalu besar. Katakanlah kalau orang bangun itu Rp 10 triliun tahun pertama, kedua, ketiga (dan seterusnya). Dalam komposisi APBN kita yang Rp 2.500 triliun lebih, itu kan tidak terlalu besar. Enggak sekali keluar lah (biayanya). Tapi itu tadi, dibutuhkan dukungan.
Skema pembiayaannya sebaiknya seperti apa?
Biasanya, fungsi pemerintahan itu jarang ada swasta mau. Contoh di Indonesia, kalau pindah ibu kota kabupaten atau provinsi, itu 100 persen (dari) APBN atau APBD. Karena untuk swasta tidak menguntungkan. Makanya saya bilang, mungkinkah bisa diset sebagai ibu kota, tapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, supaya menarik minat swasta?
Caranya, jangan hanya mendesain pusat pemerintahan, tapi (juga) pusat ekonomi, misal di hinterland-nya. Misal kita punya 400 ribu hektare, nanti ada yang disediakan untuk swasta. Nanti swasta ikut berperan dalam mengembangkan infrastruktur, desain kawasan industri hi-tech-nya. Bayangan saya seperti itu, untuk menarik budget dari sektor government ya harus dengan daya tarik.
Desain yang memungkinkan dikerjasamakan dengan pihak swasta, misal membangun permukiman pegawai. Bayangan saya, ya, mendesain sub-sub kota. Kalau permukiman kan pasti diikuti fasilitas bisnis, sekolah, dan lain-lain. Desain di luar gedung pemerintahan itu bisa melibatkan swasta pembiayaannya, karena pembiayaan perumahan pegawai itu kan juga tidak kecil. Tidak hanya perumahan lho, (ada) sistem drainase, listrik, dan lain-lain. Jadi, pembiayaan juga bagian yang harus dipikirkan, terutama bagaimana melibatkan pihak non-government. Bukan pada core pembangunan fasilitas pemerintahan, tapi hilirnya, akibat multiplier dari itu.
Terus, model pemindahannya bagaimana?
Setidaknya ada dua jenis model pemindahan yang dapat kita pilih. Pertama, memindah fungsi pemerintahan, ibu kota tetap. Kedua, memindah ibu kota sekaligus memindahkan fungsi pemerintahan. Ibu kota memiliki makna politis, sedangkan pemerintahan lebih fungsional.
UU Pembentukan Negara menyampaikan bahwa Ibu Kota Negara RI berada di Jakarta. Presiden berkedudukan di Ibu Kota Negara. Jika menggunakan model pertama, ibu kota negara dan simbol politik kepresidenan masih di Jakarta, sedangkan fungsi pemerintahan, seperti kementerian, dapat disebar atau didesentralisasikan ke daerah-daerah di seluruh penjuru Nusantara. Saya menyebutnya dengan desentralisasi fungsional.
Ada dua pilihan desentralisasi fungsional. Pertama, desentralisasi fungsional terpusat, yaitu memindahkan fungsi pemerintahan pada satu daerah tertentu. Kedua, desentralisasi fungsional tersebar, yaitu memindahkan fungsi pemerintahan secara tersebar sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan bisa dipindah ke Yogyakarta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bisa di Kalimantan Timur, dan sebagainya. Ini perlu dikaji lebih lanjut tentang perbandingan plus-minus antara desentralisasi fungsional tersebar atau tersentral.
![Obyek wisata upacara pergantian penjagaan Istana Kepresidenan, Jakarta [suara.com/Erick Tanjung]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2016/10/16/o_1av5rtn2p7v118hv16tu1no11pq3a.jpg)
Plus-minus dua model itu apa?
Jika menggunakan model pertama, tidak diperlukan adanya perubahan perundang-undangan karena posisi Presiden masih di Jakarta. Dalam era global dan IT yang sangat maju, jarak geografi tidak menjadi masalah dalam koordinasi pemerintahan. Kalaupun perlu bertemu, yang bertemu cukup menterinya atau Presidennya yang mobile. Kalau sekarang, sebagian besar perjalanan dinas dilakukan menuju Jakarta, dan terkadang untuk urusan yang sepele yang dilakukan oleh setingkat SPPD.
Jika menggunakan model kedua, yang dipindah adalah ibu kota. Untuk efisiensi sebaiknya juga diikuti dengan memindahkan fungsi pemerintahan secara bersamaan pada satu lokasi tertentu. Wacana yang berkembang sampai saat ini tampaknya adalah pilihan kedua, di mana sedang dikaji kelaikan calon Ibu Kota Negara. Bahkan sudah banyak yang mengasumsikan tentang lokasi ibukota yang baru (itu) di wilayah A, B, C, dan yang lain.
Model ini, selain membutuhkan biaya yang sangat besar karena (harus) menyediakan infrastruktur pembangunan ibu kota baru , juga harus dilakukan perubahan UU tentang letak ibu kota negara. Hal ini biasanya akan terkendala pada nilai sakral dan kekhawatiran kehilangan sejarah perjuangan bangsa. Sebagai contoh, Naskah Proklamasi (kan) dibacakan di Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.
Tidak menutup kemungkinan terjadi deadlock dalam rencana pemindahan ini. Maka, bisa dilakukan referendum, tentu saja dengan pilihan-pilihan yang tepat. Sebagai sebuah opsi pilihan, maka hendaknya wacana perdebatan tidak selalu harus difokuskan pada pilihan kedua, tapi mewacanakan dan memperdebatkan pilihan pertama juga tidak kalah menarik.
Selain itu, bagi saya, pilihan pertama cenderung bersifat pilihan moderat dan mengakomodasikan banyak pilihan, dengan beban pembiayaan yang tidak terlalu besar. Semua pilihan ada kelebihan dan kekurangannya, dan kita harus berani terbuka untuk membandingkan keduanya.
Contoh pemindahan ibu kota di negara lain bagaimana?
Kita contohkan tiga negara yang melakukan pemindahan ibu kota, yaitu Malaysia, Brasil, dan Australia. Dengan alasan efisiensi pelayanan, Malaysia memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada 1995, sehingga terpisah jelas antara pusat ekonomi di Kuala Lumpur dengan pusat pemerintahan di Putrajaya.
Kesemrawutan kota Rio de Janeiro dan posisi geografis yang tidak strategis, memotivasi Brasil memindahkan seluruh fungsi pemerintahan ke Kota Brazilia pada 1960. Itu terbukti berhasil, sehingga kota lama Rio de Janeiro berkembang menjadi tujuan wisata internasional.
Sedangkan Australia, pada 1927 melakukan pemindahan dari Kota Melbourne yang relatif sempit dan kepadatan tinggi ke kota Canberra sebagai pusat pemerintahan. Hal itu salah satunya berhasil mengatasi permasalahan di Kota Melbourne (kota asal) hingga mendapat predikat (salah satu) "The World's Most Liveable Cities". Dari tiga kasus ini, semuanya menggunakan model kedua, yaitu memindah ibu kota sekaligus memindahkan fungsi (pemerintahan), sebagaimana wacana yang berkembang saat ini.
Namun harus diingat, ketiga kasus negara tersebut kesemuanya adalah negara benua atau daratan, dan bukan seperti Indonesia sebagai negara kepulauan. Tidak ada kasus yang serupa dengan konfigurasi kepulauan seperti Indonesia.
Ada negara yang pernah gagal?
Kayanya saya belum membaca ya. Karena gagal atau tidak itu kan ada indikator di dalam proses melakukan penilaian. Saya rasa, semua orang memindah itu punya kisah sukses semua. Maksudnya, tidak ada yang cerita memindah ibu kota, karena ada masalah terus balik lagi. Memang tidak ada cerita itu. Paling ada yang sukses jadi pusat pertumbuhan ekonomi, ada yang begitu-begitu saja. Antara sukses dan standar.
Indonesia pernah punya pengalaman memindahkan Ibu Kota ke Yogyakarta pada 1946. Apa pelajaran yang bisa dipetik?
Kalau menurut saya itu (terkait) masalah keamanan saja. Di zamannya itu yang penting aman, penerimaan orang, efisiensi biaya, tidak terlalu jauh. Itu masalah keamanan dan ekonomi saja pertimbangannya. Oh, di sana aman, kita jangan jauh-jauh. Kan dulu alat transportasi tidak seperti sekarang. Dulu ya, (lebih terkait) keamanan dan aksesibilitas.
Sejarah itu memberikan (pelajaran), kalau dulu itu kan ibu kota politik. (Bahwa) Ibu kota itu sebetulnya politik, bukan pemerintahan. Pemerintahan ya, iya, tapi tidak sampai berimplikasi pada pemindahan kantor-kantor. Kalau sekarang konteksnya kantor juga ikut pindah, fungsi-fungsi pemerintahannya itu. Kompleksitas dulu dengan sekarang sudah sangat berbeda. Di Yogyakarta itu, misal Sultan-nya (bilang), "Silakan di sini." Perlu juga ada seperti itu. "Saya lindungi, kalau enggak punya duit saya bantu."
Lantas, di manakah sebenarnya lokasi baru ibu kota RI yang terbaik menurut pakar perencanaan wilayah ini? Simak kriteria, analisis, hingga calon lokasi paling pas menurutnya di laman berikut.
Kontributor : Sri Handayani
Soal lokasi, apa saja kriteria untuk menentukan lokasi baru Ibu Kota Negara?
Untuk menentukan lokasi yang tepat, maka langkah paling dasar yang harus dilakukan adalah menyusun atau menetapkan kriteria atau indikator lokasi ibu kota. Berbeda dengan wacana sebelumnya, sebagai geograf pengembangan wilayah, saya menggunakan perspektif geografi dengan pisau analisis geografis. Pisau analisis yang kita gunakan adalah analisis geopolitik, geostrategis, geoekonomi, dan geoekologi. Lokasi calon ibu kota negara terpilih harus memenuhi kriteria kelaikan tersebut. Kriteria pertama dan kedua berada pada tingkat makro yang sifatnya lebih political decision, sedangkan kriteria ketiga dan keempat digunakan pada tingkat meso dan mikro yang bersifat technical decision.
Kriteria geopolitik terdiri dari komponen perwujudan cita-cita politik bangsa akan pentingnya NKRI dan Wawasan Nusantara (integrasi bangsa), stabilitas politik dan Hankamnas, mendorong keseimbangan pembangunan, mengurangi ketimpangan antar-wilayah, realisasi kebijakan pembangunan dan pinggiran, (serta) menjamin rasa keadilan sosial dan spasial.
Kriteria geostrategis terdiri dari nilai efisiensi lokasi (aksesibilitas dan konektivitas). Jarak terpendek, pemusatan (titik berat) arus mobilitas, keterbukaan wilayah posisi terhadap sistem kemaritiman (jalur laut), responsif terhadap perubahan sistem transportasi global dan strategi pertahanan dan keamanan.
Kriteria geoekonomi, terdiri atas unsur kemampuan menjawab tumbuhnya pusat pertumbuhan baru, meningkatkan nilai daya saing ekonomi (efisiensi lokasi dan sistem logistik produksi), konektivitas terhadap pusat-pusat ekonomi dunia (jalur perdagangan), mengurangi kesenjangan ekonomi antar-wilayah (pemerataan), integrasi ekonomi nasional.
Kriteria geoekologi berhubungan dengan unsur daya dukung lingkungan, kemampuan sumber daya lahan dan sumber daya air, ketersediaan ruang (budidaya), bukan kawasan lindung, keamanan dari ancaman bencana, tekanan penduduk, dan risiko kerusakan lingkungan.
Setelah ditentukan kriteria-kriteria di atas, kita masuk tahap analisis. Dalam kajian dan teori lokasi, terdapat dua tingkatan analisis yang dapat digunakan untuk menilai kesesuaian lokasi, yaitu situation and site selection. Analisis situation bersifat lingkungan makro, mencakup analisis lingkungan Indonesia. Site selection bersifat analisis meso atau mikro. Analisis meso dapat dilakukan sampai level kabupaten, sedangkan analisis mikro terkait dengan tinjauan kelaikan, baik yang sifatnya teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan, serta pembiayaan dan kelembagaan. Selanjutnya, apa yang kita sampaikan dalam diskusi ini lebih pada analisis makro dan meso dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
Jadi, di mana lokasi yang memenuhi kriteria tersebut?
Pada analisis tingkat makro, khususnya tinjauan geopolitik dan geostrategis, saya telah mengeluarkan Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera dari lokasi calon ibu kota baru. Demikian pula dengan Pulau Papua dan gugusan Kepulauan Maluku serta gugusan Pulau Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.
Selain faktor geostrategis dan geoekonomi rendah, juga dipertimbangkan risiko geoekologi, khususnya kerentanan kebencanaan yang tinggi. Karena faktor geoekologi ini pula yang menyebabkan sebagian besar wilayah di Pulau Sulawesi sisi timur tidak menarik, meskipun secara geostrategis memiliki daya tarik yang besar.
Dalam pandangan geomaritim, koridor laut di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi paling strategis, sehingga wilayah-wilayah yang berhadapan dengan koridor laut ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) ini memiliki potensi tinggi sebagai calon ibu kota. Wilayah-wilayah ini merupakan pintu gerbang aliran logistik bagi daerah-daerah di pedalaman Kalimantan dan Sulawesi.
Pada jalur ini juga terdapat kota-kota besar seperti Balikpapan, Samarinda, Palu, Makassar, dan Banjarmasin, selain juga keberadaan beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Aktivasi jalur ALKI melalui peletakan calon ibu kota ini diharapkan juga dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan geoekonomi kawasan tersebut, termasuk pengembangan KEK dan Jalur Kawasan Perbatasan di bagian hinterland.
Pada analisis situation ini, Pulau Kalimantan dan sebagian Sulawesi sisi barat memiliki potensi besar untuk diadu atau dibandingkan keunggulan dan kelemahannya pada tingkat meso, bahkan sampai site selection.
Untuk kriteria geopolitik lokal, hampir semua provinsi menginginkan dirinya untuk menjadi lokasi terpilih. Jadi tidak ada persoalan. Pertimbangan geostrategis menempatkan provinsi Kalimantan Barat memiliki nilai terendah, karena posisi geografinya yang kurang strategis.
Meskipun memiliki potensi geoekonomi besar dan jalur laut perdagangan yang cukup strategis, namun untuk kriteria ibu kota sebagai pusat pelayanan yang termudah daya jangkau dan aksesibilitas, menyebabkan kami harus mengeluarkan Kalimantan Barat. Demikian pula posisi Kalimantan Utara yang nilai geostrategis dan geoekonominya terendah, juga dieliminasi.
Bagaimana dengan wilayah bagian barat Sulawesi, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah? Meskipun nilai geostrategisnya lumayan tinggi, sisi kelemahan utama terletak pada aspek geoekologi, terkait dengan morfologi wilayah (perbukitan-pegunungan). Ketersediaan ruang, dengan jalur kerawanan bencana yang tinggi, terlebih dari sisi geoekonomi daya tariknya lebih rendah dibanding provinsi di Kalimantan.
Ingat, bandul pemberat perekonomian dan demografis Indonesia utamanya masih di Pulau Jawa. Kedekatan dan akses yang baik dengan Pulau Jawa menjadi pertimbangan yang tidak bisa diabaikan. Hasil analisis gravitasi yang kita lakukan menunjukkan bahwa kekuatan daya tarik ekonomi dan demografi Jawa tidak mampu dilawan. Secara mekanisme pasar, patok pemberat Indonesia ada di Jawa. Hanya keputusan politik yang mampu memindahkan semua orientasi dari Pulau Jawa.
Akhirnya, pertandingan akhir adalah pilihan atas tiga provinsi di Kalimantan yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Tinjauan geopolitik tiga wilayah (ini) relatif lebih seimbang. Ketiganya menginginkan dijadikan calon ibu kota.
Yang menarik dicermati adalah daya terima masyarakat dan peluang munculnya potensi konflik, di mana hal ini dapat dilihat dari sistem keterbukaan dan heterogenitas yang terdapat di tiga provinsi ini. Kalimantan Timur memiliki keunggulan tertinggi pada sistem masyarakat yang heterogen dan daya terima yang tinggi tentang berbagi terhadap komunitas lain. Berikutnya Kalimantan Selatan, dan terakhir yang terendah adalah Kalimantan Tengah.
Berita tentang berbagai macam syarat dan permintaan khusus yang diajukan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah menjadi indikasi persoalan sosial yang rumit ke depannya. Keunggulan utama Kalimantan Tengah adalah posisi yang paling strategis, posisi centrum geografis, jarak terdekat dari seluruh penjuru tanah air, dengan suplai sumber daya lahan yang luas.
Namun, kelemahan utama Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya, adalah posisi geografis yang berada di tengah daratan dan tidak memiliki akses pantai sehingga tergolong wilayah "tertutup". (Ini) Karena tidak memiliki akses langsung dengan laut dan jalur maritim yang sangat vital bagi perkembangan wilayah.

Sebenarnya Kalimantan Tengah dapat mengajukan wilayah kabupatennya yang memiliki pantai, namun kesemuanya terkendala kriteria geoekologi khususnya kersediaan dan kemampuan lahan yang rendah. Sebagian (adalah) area gambut yang dilindungi, dan jika dikembangkan menjadi perkotaan membutuhkan rekayasa dan biaya yang teramat tinggi.
Secara geoekonomi, lokasi ibu kota di bagian dalam tidak menguntungkan dan tidak strategis, mengingat jalur logistik terbesar ada di jalur laut. Selain itu juga berlawanan dengan fakta wilayah kepulauan Indonesia dan kehendak politik untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Meskipun memiliki modal sejarah yang kuat, karena pernah disebut oleh Presiden Soekarno sebagai calon ibu kota, tampaknya Kalimantan Tengah memiliki nilai kompetitif lebih rendah dibandingkan dengan dua kompetitor lainnya, yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Lalu, pilih mana antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur? Dan di mana tepatnya?
Karena wilayahnya yang relatif terbuka, menyebabkan masyarakat di dua wilayah ini relatif lebih terbuka dan heterogen dibandingkan Kalimantan Tengah. Selain itu, ada sejarah panjang tentang hubungannya dengan wilayah luar dengan daya terima yang cukup besar, di samping konflik sosial juga relatif rendah. Untuk menilai di antara keduanya, analisisnya harus diturunkan pada skala meso yaitu kabupaten, karena tidak semua kabupaten ini dianggap cukup mampu menyediakan lahan yang diperlukan untuk calon ibu kota.
Penilai utamanya adalah posisi geostrategis dan geoekonomi, mengingat kondisi geopolitik dan geoekologinya relatif sama. Pertimbangan geostrategis dan geoekonomi berpusat pada posisi wilayah terhadap Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang merupakan poros dan koridor yang menghubungkan pusat ekonomi Indonesia (Jawa) dengan wilayah-wilayah lain di Nusantara, bahkan ke laut internasional. Dengan demikian, saya akan keluarkan kabupaten-kabupaten di dua provinsi tersebut yang tidak berhadapan dengan jalur laut ALKI II.
Konsekuensinya, pilihan kian menyempit pada kabupaten-kabupaten tertentu, yaitu Kabupaten Kota Baru (Kalimantan Selatan) dan Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Balikpapan dan Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur). Dan di antara tiga kabupaten tersebut, jika ditimbang dengan empat kriteria geografis, maka pilihannya adalah Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Jadi, alternatifnya tiga tempat itu?
Belum. Ini masih kajian makro. Tahap selanjutnya adalah kajian yang lebih detail pada tingkat site selection, termasuk tingkat kelayakan detail teknik, sosial, ekonomi, lingkungan, pembiayaan, dan seterusnya.
Selain empat perspektif yang telah dikemukakan sebelumnya (geopolitik, geostra, geoekonomi dan geoekologi), pada kajian tingkat kedetailan seperti ini sangat banyak sekali instrumen dan metode dalam ilmu geografi yang dapat digunakan. Di antaranya analisis geologi, geomorfologi, kebencanaan, sumber daya lahan, kemampuan dan kesesuaian lahan, hidrologi, sumber daya air, demografi, geografi ekonomi, perkotaan, penginderaan jauh, perpetaan, sistem informasi geografis, dan tentu saja aspek manajerial terkait dengan perencanaan pengembangan wilayah.
Kalau Anda menanyakan where, di mana, panggillah seorang geograf karena ia lahir untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Saya membatasi diri pada tinjauan geografis terhadap rencana, sehingga tidak memperbincangkan peluang implementasi dan aspek pembiayaan yang banyak diperbincangkan di media.
Bagaimana menjawab kekhawatiran bahwa pemindahan Ibu Kota RI ke Kalimantan akan merusak lingkungan di sana?
Kalau orang menulis "nanti akan merusak Kalimantan", Kalimantan itu kan sebenarnya sudah rusak. Kalimantan itu kalau Anda lihat di citra satelit, itu sudah bukaan semua. Sudah open space. Statusnya hutan, tapi sebenarnya sudah enggak ada hutannya.
Jadi menurut saya, pasti punya risiko lah. Namanya juga membangun kota baru, pasti ada risikonya. Karena built-up area makin banyak, resapan makin berkurang. Kemudian kalau daerah sudah sangat berkurang (resapannya), banjir (berpotensi datang) biasanya.
Tapi ini kan daerah baru yang harusnya bisa diset lingkungannya lebih bagus. Karena menata sesuatu yang sudah berkembang seperti Jakarta, dengan menata daerah baru, itu kan mestinya lebih bisa terencana, lebih bagus. Harapan saya, desain ibu kota ini bisa mengalahkan Putrajaya di Malaysia.
Desainlah yang (penuh) green building, betul-betul yang green dan nyaman. Apalagi kalau tadi ekspektasi saya, di belakangnya itu hinterland-nya adalah yang smart city, hi-tech, itu harus kompatibel. Jadi benar-benar smart and green.
Dampaknya bisa diantisipasi lah untuk sebuah kawasan baru, dibandingkan dengan eksploitasi sumber daya alam yang luar biasa besar. Sangat bisa di-manage. Perubahan yang paling tampak, kalau bangun perumahan atau apa pun, itu berkurangnya resapan. Kebetulan, curah hujan di Kalimantan, apalagi di Khatulistiwa, itu curah hujannya cukup. Dan saya kira, (dengan) rekayasa sipil bisa lah. Buat saya enggak masalah.
***
Lutfi --atau yang bernama lengkap Dr. Lutfi Muta'ali S.Si, MSP-- saat ini menjabat atau bertugas di Fakultas Geografi UGM. Lelaki kelahiran Bojonegoro, 4 April 1969, ini dikenal memiliki bidang spesialisasi antara lain dalam Perencanaan Pengembangan Wilayah, Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan, hingga Ekonomi Wilayah.
Alumnus S1 UGM yang menyelesaikan S2 di ITB, ini meraih gelar doktornya di Universitas Padjadjaran (Unpad) pada 2005 di bidang ilmu Ekonomi Pembangunan, dengan judul disertasi "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dinamika Peran Sektor Pertanian dan Hubungannya Dengan Pembangunan Wilayah di Indonesia (1973-2003)". Hingga saat ini, ia tercatat menjadi anggota di Ikatan Geografiwan Indonesia (IGI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), serta di Urban and Regional Development Institute (URDI).
Selain sederet penelitian yang sudah dijalani, baik sebagai anggota maupun Ketua Tim, juga tulisan hasil kajian di berbagai jurnal dan majalah, Lutfi Mutaali tercatat sudah menulis setidaknya belasan buku. Beberapa di antaranya berjudul Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah (2012), Pengembangan Wilayah Berbasis Pengurangan Resiko Bencana (2013), Pengembangan Wilayah Tertinggal (2014), Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI (2014), hingga Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi (2016), yang kesemuanya diterbitkan UGM.
Kontributor : Sri Handayani