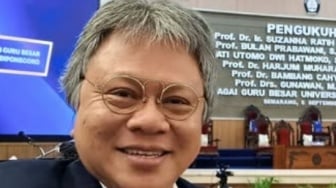Butuh waktu berapa lama kira-kira untuk proses pindah ibu kota? Langkah-langkahnya apa saja?
Kalau menurut Bappenas kan butuh waktu 20-30 tahun. Artinya, butuh waktu lama. Step (menurut) saya, bayangan saya, konsensus politik dulu. Enggak mungkin kita melakukan kegiatan besar tanpa konsensus politik. Belajar dari membuat UU, itu kan tidak mudah. Lama prosesnya. Tahap paling krusial dan sulit itu kan menyepakati perundang-undangan. Kalau ibu kota dipindah, itu kan UU-nya berubah. Mungkin pertimbangan orang tentang sejarah dan sebagainya mungkin jadi pertimbangan.
Menurut saya, paling aman, lima tahun itu perjuangan yang paling bagus adalah kalau sampai terjadi konsensus politik. (Hingga) Dikeluarkanlah UU yang namanya UU Pemindahan Ibu Kota. Sambil itu, dilakukan kajian lebih detail. Sampai sekarang kan belum bisa nunjuk (kota) A, B, C. Kita harusnya setelah ini sudah masuk level makro-meso. Level detailnya bagaimana? Kalau istilah teknisnya, DED. Jadi lima tahun itu sampai menyiapkan DED-nya. Desainnya dan lokasinya sudah jelas, budget-nya seperti apa, termasuk bagaimana budget itu dikeluarkan. Kalau kita mau melibatkan swasta dan sebagainya, desainnya seperti apa. Bayangan saya lima tahun pertama sampai di situ.
Baru lima tahun kedua kita bisa operasional. Yang jadi masalah berikutnya itu (adalah) tentang siapa yang bisa merealisasikan ide UU yang sudah diterbitkan. Kalau orang bangun infrastruktur, itu enggak terlalu lama. Katakanlah menyiapkan pembangunan fisik itu lima tahun kedua, lima tahun ketiga itu baru orang pindah, pegawai pindah dan sebagainya. Jadi kira-kira, lima belas tahun lah baru terealisasi, baru berjalan.
Lantas, selama 15 tahun itu potensi gejolaknya seperti apa?
Pasti ada lah. Salah satu kelemahan di Indonesia, kan itu, inkonsistensi di dalam pelaksanaan kebijakan. Makanya kan harus dikunci dengan UU. (Bahkan) UU saja kadang bisa diubah kok. Itu pasti punya pengaruh besar (terhadap gejolak yang muncul).
Makanya, kadang kan ada yang menganggap itu utopis. Itu mimpi kayanya. Bagi saya sih enggak mimpi. Itu real kok. Cuma, dibutuhkan pemerintah yang kuat dan berani. Misal di parlemen itu kuat, bisa menjaga 15 tahun itu konsisten terus. Di Malaysia itu kan (berhasil) karena Mahathir. Dia bisa memindahkan Putrajaya itu karena pemerintahannya kuat tak tertandingi. Enggak ada oposisi yang memprotes, makanya mulus-mulus saja.
Kalau ini nanti dimanfaatkan untuk kepentingan politik, dimain-mainin, ini kan sudah terasa. Saya lihat suara partai yang tidak setuju, yang di luar pemerintahan itu kan kaya enggak setuju. Itulah kendala yang paling berat; bukan kendala teknis.
Bagaimana agar dalam 15 tahun nanti proses pemindahan ibu kota tetap berjalan? (Soalnya) Presiden Jokowi kalaupun menang kan tinggal satu periode lagi?
Baca Juga: Sutrisna Wibawa: Media Sosial untuk Terapkan Kepemimpinan Partisipatif
Pertama, ya, memang diperlukan konsensus politik nasional. Bahkan saya pernah menulis, kalau ngeyel terus, kalau perlu referendum misalnya. Artinya (itu nanti) kan kehendak rakyat. Kalau rakyat menghendaki untuk dipindah, DPR itu enggak boleh (menolak).
Pertama konsensus politik, kemudian konsistensi kebijakan, penyiapan SDM, dan pembiayaan. Yang biasanya krusial kan masalah budgeting. Budget-nya itu mau APBN full atau dikerjasamakan. Waktu sosialisasi kajian Bappenas itu kan selain aspek-aspek pembiayaan. Titik krusialnya biasanya di situ.
Kalau seperti yang ditulis media (bahwa biayanya) Rp 400 triliun, itu kan sebenarnya tidak terlalu besar. Katakanlah kalau orang bangun itu Rp 10 triliun tahun pertama, kedua, ketiga (dan seterusnya). Dalam komposisi APBN kita yang Rp 2.500 triliun lebih, itu kan tidak terlalu besar. Enggak sekali keluar lah (biayanya). Tapi itu tadi, dibutuhkan dukungan.
Skema pembiayaannya sebaiknya seperti apa?
Biasanya, fungsi pemerintahan itu jarang ada swasta mau. Contoh di Indonesia, kalau pindah ibu kota kabupaten atau provinsi, itu 100 persen (dari) APBN atau APBD. Karena untuk swasta tidak menguntungkan. Makanya saya bilang, mungkinkah bisa diset sebagai ibu kota, tapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, supaya menarik minat swasta?
Caranya, jangan hanya mendesain pusat pemerintahan, tapi (juga) pusat ekonomi, misal di hinterland-nya. Misal kita punya 400 ribu hektare, nanti ada yang disediakan untuk swasta. Nanti swasta ikut berperan dalam mengembangkan infrastruktur, desain kawasan industri hi-tech-nya. Bayangan saya seperti itu, untuk menarik budget dari sektor government ya harus dengan daya tarik.
Desain yang memungkinkan dikerjasamakan dengan pihak swasta, misal membangun permukiman pegawai. Bayangan saya, ya, mendesain sub-sub kota. Kalau permukiman kan pasti diikuti fasilitas bisnis, sekolah, dan lain-lain. Desain di luar gedung pemerintahan itu bisa melibatkan swasta pembiayaannya, karena pembiayaan perumahan pegawai itu kan juga tidak kecil. Tidak hanya perumahan lho, (ada) sistem drainase, listrik, dan lain-lain. Jadi, pembiayaan juga bagian yang harus dipikirkan, terutama bagaimana melibatkan pihak non-government. Bukan pada core pembangunan fasilitas pemerintahan, tapi hilirnya, akibat multiplier dari itu.
Terus, model pemindahannya bagaimana?
Setidaknya ada dua jenis model pemindahan yang dapat kita pilih. Pertama, memindah fungsi pemerintahan, ibu kota tetap. Kedua, memindah ibu kota sekaligus memindahkan fungsi pemerintahan. Ibu kota memiliki makna politis, sedangkan pemerintahan lebih fungsional.
UU Pembentukan Negara menyampaikan bahwa Ibu Kota Negara RI berada di Jakarta. Presiden berkedudukan di Ibu Kota Negara. Jika menggunakan model pertama, ibu kota negara dan simbol politik kepresidenan masih di Jakarta, sedangkan fungsi pemerintahan, seperti kementerian, dapat disebar atau didesentralisasikan ke daerah-daerah di seluruh penjuru Nusantara. Saya menyebutnya dengan desentralisasi fungsional.
Ada dua pilihan desentralisasi fungsional. Pertama, desentralisasi fungsional terpusat, yaitu memindahkan fungsi pemerintahan pada satu daerah tertentu. Kedua, desentralisasi fungsional tersebar, yaitu memindahkan fungsi pemerintahan secara tersebar sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan bisa dipindah ke Yogyakarta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bisa di Kalimantan Timur, dan sebagainya. Ini perlu dikaji lebih lanjut tentang perbandingan plus-minus antara desentralisasi fungsional tersebar atau tersentral.
![Obyek wisata upacara pergantian penjagaan Istana Kepresidenan, Jakarta [suara.com/Erick Tanjung]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2016/10/16/o_1av5rtn2p7v118hv16tu1no11pq3a.jpg)
Plus-minus dua model itu apa?
Jika menggunakan model pertama, tidak diperlukan adanya perubahan perundang-undangan karena posisi Presiden masih di Jakarta. Dalam era global dan IT yang sangat maju, jarak geografi tidak menjadi masalah dalam koordinasi pemerintahan. Kalaupun perlu bertemu, yang bertemu cukup menterinya atau Presidennya yang mobile. Kalau sekarang, sebagian besar perjalanan dinas dilakukan menuju Jakarta, dan terkadang untuk urusan yang sepele yang dilakukan oleh setingkat SPPD.
Jika menggunakan model kedua, yang dipindah adalah ibu kota. Untuk efisiensi sebaiknya juga diikuti dengan memindahkan fungsi pemerintahan secara bersamaan pada satu lokasi tertentu. Wacana yang berkembang sampai saat ini tampaknya adalah pilihan kedua, di mana sedang dikaji kelaikan calon Ibu Kota Negara. Bahkan sudah banyak yang mengasumsikan tentang lokasi ibukota yang baru (itu) di wilayah A, B, C, dan yang lain.
Model ini, selain membutuhkan biaya yang sangat besar karena (harus) menyediakan infrastruktur pembangunan ibu kota baru , juga harus dilakukan perubahan UU tentang letak ibu kota negara. Hal ini biasanya akan terkendala pada nilai sakral dan kekhawatiran kehilangan sejarah perjuangan bangsa. Sebagai contoh, Naskah Proklamasi (kan) dibacakan di Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.
Tidak menutup kemungkinan terjadi deadlock dalam rencana pemindahan ini. Maka, bisa dilakukan referendum, tentu saja dengan pilihan-pilihan yang tepat. Sebagai sebuah opsi pilihan, maka hendaknya wacana perdebatan tidak selalu harus difokuskan pada pilihan kedua, tapi mewacanakan dan memperdebatkan pilihan pertama juga tidak kalah menarik.
Selain itu, bagi saya, pilihan pertama cenderung bersifat pilihan moderat dan mengakomodasikan banyak pilihan, dengan beban pembiayaan yang tidak terlalu besar. Semua pilihan ada kelebihan dan kekurangannya, dan kita harus berani terbuka untuk membandingkan keduanya.
Contoh pemindahan ibu kota di negara lain bagaimana?
Kita contohkan tiga negara yang melakukan pemindahan ibu kota, yaitu Malaysia, Brasil, dan Australia. Dengan alasan efisiensi pelayanan, Malaysia memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada 1995, sehingga terpisah jelas antara pusat ekonomi di Kuala Lumpur dengan pusat pemerintahan di Putrajaya.
Kesemrawutan kota Rio de Janeiro dan posisi geografis yang tidak strategis, memotivasi Brasil memindahkan seluruh fungsi pemerintahan ke Kota Brazilia pada 1960. Itu terbukti berhasil, sehingga kota lama Rio de Janeiro berkembang menjadi tujuan wisata internasional.
Sedangkan Australia, pada 1927 melakukan pemindahan dari Kota Melbourne yang relatif sempit dan kepadatan tinggi ke kota Canberra sebagai pusat pemerintahan. Hal itu salah satunya berhasil mengatasi permasalahan di Kota Melbourne (kota asal) hingga mendapat predikat (salah satu) "The World's Most Liveable Cities". Dari tiga kasus ini, semuanya menggunakan model kedua, yaitu memindah ibu kota sekaligus memindahkan fungsi (pemerintahan), sebagaimana wacana yang berkembang saat ini.
Namun harus diingat, ketiga kasus negara tersebut kesemuanya adalah negara benua atau daratan, dan bukan seperti Indonesia sebagai negara kepulauan. Tidak ada kasus yang serupa dengan konfigurasi kepulauan seperti Indonesia.
Ada negara yang pernah gagal?
Kayanya saya belum membaca ya. Karena gagal atau tidak itu kan ada indikator di dalam proses melakukan penilaian. Saya rasa, semua orang memindah itu punya kisah sukses semua. Maksudnya, tidak ada yang cerita memindah ibu kota, karena ada masalah terus balik lagi. Memang tidak ada cerita itu. Paling ada yang sukses jadi pusat pertumbuhan ekonomi, ada yang begitu-begitu saja. Antara sukses dan standar.
Indonesia pernah punya pengalaman memindahkan Ibu Kota ke Yogyakarta pada 1946. Apa pelajaran yang bisa dipetik?
Kalau menurut saya itu (terkait) masalah keamanan saja. Di zamannya itu yang penting aman, penerimaan orang, efisiensi biaya, tidak terlalu jauh. Itu masalah keamanan dan ekonomi saja pertimbangannya. Oh, di sana aman, kita jangan jauh-jauh. Kan dulu alat transportasi tidak seperti sekarang. Dulu ya, (lebih terkait) keamanan dan aksesibilitas.
Sejarah itu memberikan (pelajaran), kalau dulu itu kan ibu kota politik. (Bahwa) Ibu kota itu sebetulnya politik, bukan pemerintahan. Pemerintahan ya, iya, tapi tidak sampai berimplikasi pada pemindahan kantor-kantor. Kalau sekarang konteksnya kantor juga ikut pindah, fungsi-fungsi pemerintahannya itu. Kompleksitas dulu dengan sekarang sudah sangat berbeda. Di Yogyakarta itu, misal Sultan-nya (bilang), "Silakan di sini." Perlu juga ada seperti itu. "Saya lindungi, kalau enggak punya duit saya bantu."
Lantas, di manakah sebenarnya lokasi baru ibu kota RI yang terbaik menurut pakar perencanaan wilayah ini? Simak kriteria, analisis, hingga calon lokasi paling pas menurutnya di laman berikut.
Kontributor : Sri Handayani