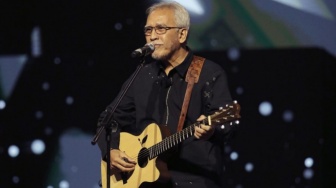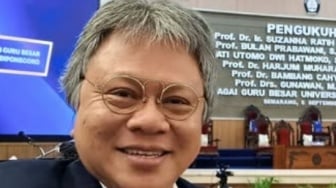Suara.com - Jelang Pilpres 2019, kabar bohong atau hoaks makin sering muncul dan meresahkan warga. Tidak sedikit masyarakat yang nyaris tak bisa membedakan antara kebenaran dan kebohongan, lantaran kini perbedaan keduanya begitu samar, dan itu termasuk diakui oleh Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Prof. Dr. Henri Subiakto.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pun selama ini selalu dijadikan payung untuk berlindung dari serangan hoaks. Namun nyatanya, satu-satunya aturan yang mengatur mengenai aktivitas di dunia maya itu seringkali tak mampu membendung hoaks-hoaks yang bermunculan.
Prof. Henri Subiakto, dalam perbincangannya dengan Suara.com pada Jumat (29/3/2019), mengakui bahwa keberadaan UU ITE sama sekali tidak tepat dijadikan sebagai payung penangkal hoaks. Sebab menurutnya, berbagai pasal yang tertuang dalam peraturan perundangan itu memang tidak secara khusus diarahkan untuk menangkal hoaks.
Dari beberapa pasal yang ada dalam UU ITE, hanya ada satu pasal yang membahas soal hoaks yakni pasal 28 ayat 1. Namun, pasal itu pun tidak secara jelas mendefinisikan hoaks dan ancaman yang menjerat pelaku penyebarnya.
Baca Juga: Darmaningtyas dan PR Dunia Pendidikan untuk Dua Calon Presiden
Berikut hasil wawancara lengkap Suara.com dengan Henri Subiakto mengenai gejolak hoaks yang disebutnya hampir mirip dengan kasus di Pilpres Amerika Serikat, hingga ketidaksiapan UU di Indonesia dalam menangkal hoaks yang merebak.
Gambaran hoaks di dunia sudah mewabah seperti apa?
Hoaks itu, kalau tadi ada pertanyaan apakah politik itu bisa tanpa hoaks, saya katakan agak sulit, bahkan mungkin itu sesuatu yang utopia. Politik itu selalu ada tiga level. Level pertama level ideal; cita-cita banyak orang, banyak membicarakan teori ataupun filsafat. Ini biasanya di level ideal adalah orang-orang kampus atau aktivis, yang termasuk wartawan, yang memimpikan politik tanpoa hoaks.
Level kedua adalah level normatif, (terkait) aturan hukumnya seperti apa. Apakah mampu menghilangkan hoaks atau tidak itu level normatif. Yang ketiga level praktis. Nah, level praktis ini persoalan bagaimana mencapai kekuasaan, mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan. Pernyataan yang praktisnya justru sudah menjadi bagian political game, permainan politik di berbagai negara di era digital, di era post-truth tadi. Nah ini persoalannya. Dan kalau kita mau searching, banyak hoaks tidak hanya di Indonesia, tapi hampir di setiap negara yang sedang ada Pilpres atau Pemilu. Itu hoaksnya banyak sekali dan ada tren yang hampir mirip-mirip.
Nah, kalau sudah seperti itu, karena apa? Dunia kan trennya bebas. Ada kebebasan, ada katakanlah, negara tidak seperti zaman otoriter. Kalau Indonesia otoriter, bisa tanpa hoaks. Tapi kalau negara Indonesia masih demokrasi, ada kebebasan, maka hoaks besar kemungkinan akan sulit sekali ditiadakan.
Baca Juga: Johan Budi: Teror KPK dari Kaki Patah, Penembakan Misterius, sampai Santet
Karena apa? Ini juga sempat tadi kita sampaikan, karena hoaks itu jauh lebih aman dibandingkan "Operasi Subuh", dibandingkan money politics, dan lebih murah.
Ini kenyataan yang tak bisa dihindari, tapi harus dipikirkan bersama, ketika keyakinan benar dan salah sudah kabur batasnya. Bagaimana (dengan itu)?
Pertama tadi, mengenai post-truth tadi, kebenaran itu dianggap sesuatu yang belum tentu benar kalau belum sesuai dengan apa yang kita sukai. Masyarakat sudah mengalami atau terhinggap penyakit bahwa kebenaran hanya sesuai dengan kesukaannya. Seorang profesor, walaupun dia profesor, dia guru besar, walaupun sudah keliling dunia, dia bisa dianggap tidak benar ketika tidak disukai apa yang dia sampaikan. Seorang ustadz dan seorang kiai sama saja, tiba-tiba dia jadi (dinilai) munafik ketika dia tidak disukai. Itu post-truth.
Dalam konteks seperti ini, memang sekarang yang bermain itu apa yang sekarang kita sebut bermain di media sosial. Media sosial-lah tempat untuk berperang opini, berperang hoaks, berperang informasi. Ada buku namanya "LikeWar: The Weaponization of Social Media" yang ditulis oleh Peter Singer. Peter Singer ini sangat terkenal sekali. Di Indonesia seharusnya terkenal karena bukunya sempat di-quote, yaitu berjudul Ghost Fleet yang mengatakan Indonesia akan musnah pada 2030.
Peter Singer mengatakan bahwa sosial media memang tempat perang. Kalau bisa menang perang di sosial media, maka bisa menang di dunia fisik di negara. Maka, itu yang terjadi di berbagai negara.
![Staf Ahli Menkominfo, Prof Henri Subiakto, bersama Imam Wahyudi dari Dewan Pers dan Rustika Herlambang dari Indonesia Indicator, dalam talkshow Politik Tanpa Hoax di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (29/3/2019). [Suara.com/Muhaimin A Untung]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/04/01/11160-staf-ahli-menkominfo-henri-subiakto-dalam-talkshow-politik-tanpa-hoax.jpg)
Dengan adanya post-truth itu, meskipun ada data sekalipun, kalau kita tak suka, ya, akan susah mengungkapnya?
Ada beberapa survei yang dianggap bahwa survei itu bohong. Jadi survei itu kalau dianggap menguntungkan akan dipercaya, tapi tak percaya dari data yang sama pada survei yang sama. Jadi misalnya, ini capresnya, naik dia senang. Oh ini partainya akan hilang, dia nggak senang. Walaupun ini sudah satu survei. Jadi semua tergantung pada apa yang dia sukai.
Ketika hoaks ini menyebar, ada di mana-mana, kemudian ada penegakan hukum. Karena kita juga mencoba sebagai negara, karena negara itu mencoba kalau ada pelanggaran hukum, ya, dicoba ditegakkan. (Lalu) Muncul hoaks baru. Hoaks barunya apa? (Bahwa) Penegakan hukum itu merupakan bentuk kriminalisasi. Itu merupakan kezaliman yang baru yang terjadi. Sehingga sekarang hoaks itu sulit. Mau ditangani, muncul hoaks kriminalisasi atau penzaliman; mau tidak ditangani juga, ini mau jadi apa negara ini.
Ketika kemudian politik hoaks jitu untuk Pilpres, Pileg belum tentu. Praktik-praktik itu (apakah) sekarang masih ada?
Secara pengalaman, Donald Trump itu dianggap sebagai biang hoaks, sampai dikatakan persoalan post-truth mulai mengemuka setelah fenomena Donald Trump. Tapi Donald Trump berhasil jadi Presiden, Jair Bolsonaro di Brazil juga berhasil jadi Presiden. Artinya memang, ada orang yang memanfaatkan hoaks dan itu berhasil, berhasil dalam artian sukses mendapatkan kekuasaan. Kalau kita lihat dari beberapa negara, termasuk Indonesia, hoaks itu yang diserang adalah mayoritas. Yang ditakut-takuti segala macam "awas hilang azan" (misalnya) pasti mayoritas, bukan awas hilang lonceng gereja. Polanya sama dengan di luar negeri.
Ada beberapa contoh di luar negeri. Misal (orang) Amerika tahu bahwa mayoritas kulit putih Amerika tidak suka dengan imigran. Dulu Amerika punya Ku Klux Klan yang rasisme, anti-kulit hitam dan sebagainya. Sekarang yang dibuat oleh Trump adalah menakut-nakuti kulit putih, bahwa kulit putih nanti akan kehilangan pekerjaan, kulit putih akan kedatangan imigran dari Timur Tengah dan terjadi Islamisasi. Jadi yang ditakut-takuti selalu mayoritas. Ini contohnya. Hoaks-hoaks ini membuat mereka semakin takut dengan imigran.
Nah, kita juga yang dibuat hoaks (soal) imigran, tapi imigrannya TKA yang berada di negara lain dan mengancam mayoritas. Kalau ada antek asing dan sebagainya, di Amerika (tahun) 2016 sudah ada istilah traitor, ada pengkhianat di antara kita. Ini antek asing juga, yang kena Obama. Traitor berikutnya, Hillary Clinton. Bahkan ada pola-pola kalau isunya PKI, pulpen, surat suara. Nah, ini (soal) surat suara juga pernah terjadi di Amerika Serikat pada 2016 di Ohio, bahwa surat suaranya sudah tercoblos Hillary ada (sebanyak) 10 ribu, dan yang menyebarkan namanya Christian Times, bukan New York Times. Kenapa? Kalau New York Times belum tentu dipercaya dan tidak mudah mengelabui.
Mengenai penggunaan microphone, sudah pernah terjadi. Jadi sudah pernah terjadi... kalau di Indonesia pulpen dan microphone kan. Itu sudah pernah terjadi. Jadi hoaks itu ada yang copy-paste, dalam mempelajari dan mempergunakan hoaks. Dan ini kita memang kalau cerdas, kita akan lihat bagaimana di beberapa negara.
Di Brazil juga sama, mayoritas di sana yaitu Katolik, ditakut-takuti. Kalau mayoritas ditakut-takuti, ya sama, (soal) agama akan hilang, pelajaran agama hilang, azan nggak boleh. Nanti lama-lama sunat juga (disebut) nggak boleh.
UU ITE senjata ampuh tidak, untuk melawan hoaks?
Pertama, kalau ada yang mengatakan UU ITE alat untuk melawan hoaks, itu salah, karena UU ITE muncul di 2008, di era pemerintahan sebelumnya. Dan UU ITE itu dikatakan tidak mampu. Saya sebagai ketua (tim) revisi dari pemerintah. Kalau DPR ada Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, yang dari pemerintah saya ketuanya. Ini saya sering sekali dilibatkan sebagai saksi ahli, seringkali nggak bisa untuk mengurusi hoaks. Tidak mampu.
Tidak mampu kenapa? Apakah di pasalnya, atau lainnya?
Ini persepsi masyarakat saja. Ada yang menganggap UU ITE bisa menegakkan hukum dan menghilangkan hoaks. Itu persepsi masyarakat. Ketika persepsi itu muncul dan kuat, kasihan penegak hukum, karena ketika diurus, dilakukan pengusutan, nah lepas.
Jadi salah (kalau) kita mengharapkan UU ITE sebagai payung?
Dalam UU ITE, yang bicara tentang hoaks cuma satu pasal, yaitu pasal 28 ayat 1. Itu pun dikatakan kabar bohong yang merugikan konsumen. Mana ada hoaks merugikan konsumen? Sehingga (pasal) 28 ayat 1 tidak bisa dipakai. Akhirnya yang terjadi adalah penegak hukum menggunakan bukan UU ITE, tapi UU Nomor 1 Tahun 1946 yaitu UU tentang (Peraturan Hukum) Pidana. (Di situ) Ada pasal 14 yang menyatakan bahwa hoaks itu kabar bohong yang dibuat secara sengaja untuk memunculkan atau menerbitkan keonaran. Jadi hanya yang menerbitkan keonaran itu dalam UU Nomor 1 Tahun 1946. Kalau di UU ITE hanya penghinaan. Kalau penghinaan atau pencemaran nama baik, itu bisa masuk. Tapi kalau penghinaan pada Presiden atau hoaks yang menuduhkan seseorang itu, katakanlah Presiden, nah itu polisi nggak bisa melakukan penegakan hukum. Harus Presidennya datang, lapor, mengadu. Mana ada Presiden datang, melapor, mengadu (untuk itu)? Kalau hanya datang, lapor dan mengadu, waktunya habis hanya untuk itu.
Saat SBY dulu jadi Presiden, melaporkannya melalui pengacara. Masalahnya Pak Jokowi tidak mengangkat pengacara pribadinya, sehingga akhirnya tidak bisa. Itu satu. Yang kedua, banyak yang namanya hoaks tidak menyerang pribadi, tapi menyerang sistem. Misalnya tadi, (bahwa) sudah ada kertas suara dicoblos. Mau siapa yang harus menuntut? Maka itu tidak bisa pakai UU ITE, bisa jadi pakai UU Nomor 1 Tahun 1946. Tapi banyak juga di UU itu tidak bisa, kalau dia tidak memunculkan keonaran, tapi hanya merusak cara berpikir.
Batasan keonaran itu apa?
Menerbitkan keonaran berarti bahwa peristiwa bisa memunculkan kerusuhan atau keonaran. Nah ini, kalau kita pakai sebagai undang-undang hukum materiil, sangat sulit, karena harus tunggu ada kerusuhan beneran. Tapi kalau hukum formil, cukup berpotensi bisa. Persoalannya, banyak ahli hukum mengatakan ini hukum materiil harus tunggu kerusuhan. Jadi sebenarnya saya katakan, (soal) hoaks itu jauh dari aman, karena sulit digunakan pasal pidana.
![Henri Subiakto dan Imam Wahyudi (Dewan Pers) dalam acara talkshow Politik Tanpa Hoax di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (29/3/2019). [Suara.com/Muhaimin A Untung]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/04/01/68772-staf-ahli-menkominfo-henri-subiakto-dalam-talkshow-politik-tanpa-hoax.jpg)
Jadi kita nggak punya payungnya untuk menangkal hoaks?
Boleh dikatakan (jika) dari Dewan Pers menegakkan demokrasi, sekarang di Mahkamah Konstitusi aturan hukum yang mencoba menghilangkan kebebasan itu sudah nggak ada. Jadi kesulitan. Cuma masih ada, kalau misalnya dia menyebarkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras atau golongan, itu masih ada, masih bisa. Atau penghinaan terhadap seseorang masih bisa. Tapi kalau yang sudah terkait menyerang sistem dan sebagainya, tidak terkait keonaran, itu agak sulit. Ini yang saya katakan (bahwa) seharusnya negara ini darurat. Makanya sampai ada wacana UU Terorisme mau dipakai, sebenarnya itu kebingungan saja.
Hoaks yang tersebar di Whatsapp cukup banyak, bukan hanya di media sosial Twitter, Facebook atau Instagram. Itu bagaimana?
Memang trennya, termasuk di Brazil itu di WhatsApp. Hoaks yang disebar di Brazil itu di WhatsApp. Bawaslu tidak bisa masuk ke WhatsApp, dan mesinnya juga nggak bisa masuk ke WhatsApp karena lebih privat. Tapi sekarang kita kerjasama terus dengan WhatsApp. Kenapa hanya membatasi forward sampai 5 (misalnya). Dulu nggak tertulis kalau itu diforward, sekarang ada tulisannya.
Ke depan, akan kita coba seperti yang di Brazil, walaupun lewat pengadilan, mereka bisa menghapus akun-akun yang secara teknologi dia kelihatan suka share yang sama.
Kalau WhatsApp dihapus, kan tinggal beli nomor baru?
Kalau nomor baru sudah ada mekanismenya, sudah tidak mudah lagi, selain KTP dan sebagainya. Ini masih dalam proses. Tapi nantinya kalau ada pelanggar pidana menggunakan nomor baru, suatu hari nanti, ini masih dibuat regulasinya, bisa hanya diblokir nomornya, bisa yang diblokir NIK (Nomor Identitas Kependudukan)-nya, sehingga nggak bisa dipakai lagi kalau dia ganti nomor baru dengan NIK yang sama. Jadi ini wacana yang sedang kita kembangkan di kementerian (Kominfo).
Saya mau kembangkan sedikit mengenai literasi. Literasi yang perlu kita sampaikan ke publik. Tadi (dikatakan) banyak yang masih mendukung atau menyebarkan hoaks. Mereka (yang) menyebarkan hoaks itu akan kesulitan di masa depan, karena mereka akan sama saja dengan menunjukkan karakternya yang buruk sebagai pro kebohongan. Itu ditunjukkan dalam reputasi dirinya. Kalau mau jadi pegawai negeri, itu tidak hanya diperlukan surat kelakuan baik, tapi akan dilihat medsosnya. Bahkan ketika nanti kita bisa bekerjasama dengan para pemilik big data, itu tidak hanya itu, tapi semua perilaku digital kita bisa ketauan. Jadi kalau misalnya alim, tapi masih suka bukain bokep, itu ketahuan. Karena teknologi itu mencatat semua perilaku kita. Dia boleh dikatakan membantu Malaikat Rakib dan Atid, perilaku kita ada di situ semua. One day, pelaku kejahatan, pelaku penyebar hoaks (akan) ketahuan kok, dan akan merugikan dirinya sendiri.
***
Prof. Dr. Henri Subiakto, SH, MA, bisa dikatakan merupakan Staf Ahli Menteri terlama dalam sejarah Kemenkominfo. Sebagaimana diinfokan di laman daring Kominfo sendiri, Henri sudah mengabdikan diri menjadi "penasihat menteri" sejak era Menteri M Nuh (2007-2009), Tifatul Sembiring (2009-2014), hingga Rudiantara (sejak 2014).
Sebelum menjabat Staf Ahli Menkominfo di Bidang Hukum, alumnus UGM, UII, UI dan Unair ini menjadi Staf Ahli Menkominfo di Bidang Komunikasi & Media Massa. Sebagai Staf Ahli Bidang Hukum Menkominfo, Henri Subiakto khususnya bertugas memberikan asistensi bidang hukum kepada Menteri Rudiantara, antara lain termasuk dalam penyusunan berbagai RUU maupun revisi undang-undang terkait.