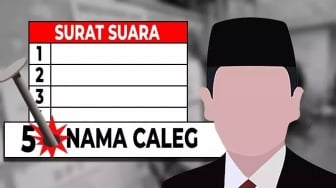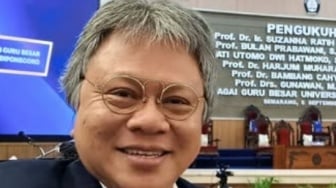Suara.com - Politik uang atau money politics masih menjadi masalah besar dalam perkembangan demokrasi di Indonesia --sama halnya dengan di berbagai negara lainnya. Terutama di momen-momen seputar agenda pemilihan umum seperti Pilkada, juga Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang kebetulan segera digelar tahun 2019 depan, masalah ini pun kembali mencuat.
Sehubungan dengan itu, Suara.com sempat berbincang banyak dengan Burhanuddin Muhtadi, seorang peneliti yang juga menjabat Direktur Eksekutif di lembaga Indikator Politik Indonesia. Dia juga sebagai Dosen Tetap Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah.
Berikut petikan wawancara yang dilakukan beberapa waktu lalu di kantornya:
Bisa dijelaskan disertasi Anda soal politik uang dalam Pemilu dan broker politik?
Jadi, disertasi saya awalnya muncul dalam konferensi atau workshop ilmiah di Bali. Saya dilibatkan dalam proyek besar (tentang) money politics (Money Politics: Patronage and Clientelism in Southeast Asia). Ada beberapa peneliti besar dunia seperti Edward Aspinall yang sedang melakukan perumusan proposal terkait penelitian tentang politik uang di empat negara, di Indonesia, Filipina, Malaysia dan Thailand, di Bali tahun 2011.
Jadi ide tentang disertasi saya muncul dari workshop itu, sebelum saya resmi menjadi mahasiswa doktoral di Australian National University (ANU). Saya resmi menjadi mahasiswa Phd itu tahun 2013, jadi dua tahun sebelumnya saya pernah dilibatkan dalam proyek itu. Nah, idenya kira-kira, karena saya fokus di Indonesia, idenya muncul karena keprihatinan. Karena sebagai negara demokrasi baru, proses politik di Indonesia itu diganggu oleh patronase politik elektoral bernama money politics. Jadi, pemilih atau pejabat publik itu tidak bisa all out untuk merepresentasikan kepentingan publik, karena dia merasa sudah membeli pemilih. Jadi pemilih tidak dianggap, tidak punya mandat demokratik untuk menuntut hak kepada pejabat publik yang terpilih dalam proses pemilu, karena mandat demokratik itu sudah ditukar dengan uang.
Nah, dalam studi tentang political clientelism, ini yang disebut dengan perverse accountability, pertanggungjawabannya tertukar. Kalau dalam demokrasi, pemilih seharusnya berhak untuk menuntut kepada politisi, karena pemilih ini sudah memberikan suara. Tetapi dalam politik demokrasi yang dikuasai oleh politik uang, bukan pemilih yang punya hak menuntut pertanggung jawaban, tetapi justru politisi yang menuntut balik kepada pemilih agar memilihnya karena mereka sudah menerima uang.
Jadi ada argumen normatif yang membuat concern saya selain politik uang, faktor yang selama ini turut dibicarakan secara masif, bahwa politik itu mahal, karena proses kampanye yang menyebabkan salah satunya politik uang itu sendiri secara masif. Tetapi sering kali kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa data yang tersedia itu bersifat anecdotal. Jadi masing-masing lembaga atau peneliti tidak mempunyai alat ukur yang jelas yang bisa diperbandingkan dengan negara lain. Ketika bicara soal seberapa besar politik uang, itu kita sering kali berbeda-beda, tidak bisa dibandingkan dengan negara lain.
Nah, saya punya ambisi untuk meneliti tentang politik uang dengan menempatkan Indonesia dengan perspektif komparatif. Kalau kita bicara perspektif komparatif, studi tentang politik uang itu sudah established di negara-negara Amerika Latin, Afrika, termasuk beberapa negara Asia yang lain. Sedangkan penelitian di Indonesia itu masih kosong. Kebanyakan peneliti kita jago kandang. Jadi pada titik itu project disertasi saya dimulai. Petualangan menempuh studi doktoral, tapi di saat yang sama mengelola lembaga riset, satu Lembaga Survei Indonesia dan kedua adalah Indikator Politik Indonesia. Saya punya kemewahan untuk melihat klaim yang mengatakan politik uang (itu) besar.
Pertanyaan paling awal yang saya ajukan adalah: seberapa banyak politik uang di Indonesia dengan alat ukur studi komparatif? Yang kedua, sejauh mana efektivitasnya kalau betul politik uang itu masif? Dari situ saya temukan, di Indonesia itu sangat besar. (Sebanyak) 33% responden yang terpilih dalam post election survey pasca Pemilu Legislatif 2014, itu mengaku pernah ditawari uang atau barang sebagai ganti suara mereka. 33% itu artinya kalau kita kaitkan dengan jumlah pemilih yang terdaftar tahun 2014 sebesar 108 juta, itu kurang lebih sekitar 62 juta pemilih yang pernah ditawari uang pada Pemilu Legislatif 2014. Dan kalau saya masukkan ke dalam perspektif komparatif dengan alat ukur yang kurang lebih sama yang dipakai lembaga asosiasi survei di Amerika Latin atau Lapop -- Lapop itu juga salah satu asosiasi lembaga survei di Amerika Latin-- atau Afro Barometer --itu lembaga survei yang melakukan riset di banyak negara Afrika-- atau Asian Barometer di Asia, itu Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar sedunia (politik uang). Hanya kalah dengan Uganda dan Benin, (itu) Afrika keduanya.
Nah, pertanyaannya kemudian adalah: apa yang menyebabkan pemilih, yang satu mudah ditarget obyek pakai politik uang, sementara ada segmen pemilih yang lain yang tidak ditarget tidak memakai politik uang? Apa yang menjelaskan determinan politik uang, secara individual assessment-nya, secara individual? Itu pertanyaan kunci. Mengapa ada pemilih yang rentan ditarget politik uang, dan mengapa ada beberapa pemilih yang tidak rentan politik uang? Kan bagaimana pun, meskipun 33% besar, tetapi ada dua pertiga yang lain yang tidak ditawari politik uang.
Pada titik itu, setelah kita analisis dengan berbagai macam teori, kita uji dalam survei, hasilnya mengagetkan. Ternyata kedekatan terhadap partai, itu menjadi pretiktor pemilih rentan menjadi sasaran tembak politik uang. Jadi, party ID. Ketika seseorang punya kedekatan terhadap partai, punya hubungan psikologis, party attachment, maka kemungkinan pemilih yang punya kedekatan dengan partai yang disasar politik uang. Itu temuan dengan memakai berbagai referensi dan dari berbagai macam variabel yang kita uji dan sifatnya robust.
Nah, ini saja sudah mengagetkan. Karena di negara barat, literatur tentang party dan dempkrasi itu justru sebaliknya. Di negara barat, party ID, kedekatan pemilih terhadap partai, itu membantu mengurangi ongkos politik, karena orang yang dekat dengan partai umumnya bersifat sukarela untuk membantu partai atau kandidat yang didukungnya. Di Indonesia mengapa sebaliknya, semakin dekat dengan partai, semakin mata duitan? Nah ini kan secara tidak langsung menunjukkan ada kontribusi secara ilmiah, party ID bukan seperti ditemukan di negara-negara yang sudah established demokrasinya. Justru (di sini) orang yang mempunyai kedekatan dengan partai, justru kemungkinan menjadi money grabber.
Data dari survei pemilih, itu ternyata sekilas inline atau paralel dengan temuan saya di survei kandidat dan survei broker. Jadi saya juga melakukan survei di kalangan kandidat di tingkat lokal dengan survei broker, cara pemilihannya dengan historical data yang dipunya. Terutama kita mengandalkan data dari survei dapil (daerah pemilihan). Jadi untuk menentukan ke mana saya harus melakukan survei kandidat dan survei broker, saya memakai historical data. Jadi saya survei dapil yang kami punya jelang Pileg 2014, satu dari Indikator Politik Indonesia dan satu lagi dari SMRC, kita gabung.
Kemudian karena temuannya adalah satu politik uang dan satu lagi adalah party ID, jadi kita bikin 4 sub-kuadran. Jadi, survei dapil itu kita gabung berdasarkan provinsi, misalnya di Jawa Tengah ada 10 dapil dan Jawa Barat ada 11 dapil, kita gabung. Seluruh Indonesia kita punya data 73 dapil. Dan kita temukan satu representasi provinsi, gabungan dari survei dapil tadi di masing-masing provinsi yang party ID-nya tinggi dan money politics tinggi. Mana itu arah yang presentasi party ID tinggi dan money politics tinggi? Itu adalah Jawa Tengah.
Yang kedua adalah party ID relatif rendah, tetapi money politics tinggi. Nah, itu ada di Jawa Timur. Kemudian ada juga sub-kuadran party ID relatif tinggi, tetapi money politics-nya tidak terlalu tinggi, agak rendah. Itu Sulawesi Utara. Dan terakhir, party ID rendah, politik uang rendah, itu adalah representasi daerah Sumatera Barat. Dari empat provinsi ini, kemudian jadi sub-national case study saya. Di situ saya bikin survei broker dan bikin survei kandidat.
Nah, bagaimana cara mencari data broker, padahal kita nggak punya populasi broker? Caranya adalah mewawancarai caleg terpilih di empat provinsi ini. Dari situ ketahuan caleg-caleg terpilih. Jadi saya mewawancarai secara random caleg terpilih di empat provinsi tadi, tingkat DPRD provinsi dan tingkat DPRD kabupaten/kota. Setelah saya wawancarai secara random ratusan anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi, saya tanya mereka di akhir wawancara. Saya minta mereka me-list daftar tim sukses yang membantu mereka. Ada yang sampai ribuan itu untuk satu caleg. Makanya kita bikin rata-rata tim sukses tiap provinsi berapa, tim sukses tiap partai berapa, dari data itu.
Setelah tersedia informasi berapa tim sukses yang mereka punya, kemudian saya random lagi, dari situ saya dapatkan 900 broker yang terpilih secara random. Kemudian ditanya lagi. Data survei broker maupun survei kandidat terpilih dapil DPRD I dan II di empat provinsi tadi, sekilas menyimpulkan hal yang sama dengan apa yang saya temukan di survei pemilih. Kalau kita bicara perspektif kandidat maupun perspektif broker, itu umumnya mereka mengaku menarget basis mereka sendiri atau pemilih loyal mereka sendiri, orang yang mereka anggap punya kedekatan dengan partai mereka. Jadi, sekilas saya temukan ada yang paralel antara survei pemilih, survei kandidat dan survei broker, bahwa orang yang punya kedekatan terhadap partai cenderung ditarget untuk menerima uang.
Nah, kemudian puzzle-nya muncul, kalau benar bahwa orang yang dekat dengan partai lebih besar peluangnya menerima politik uang, sebagaimana temuan survei pemilih maupun klaim dari para broker maupun politisi tingkat lokal. Pertanyaannya, berapa banyak pemilih yang memiliki kedekatan dengan partai? Saya temukan yang punya kedekatan terhadap partai sebelum dan sesudah pemilu tahun 2014 itu kurang lebih hanya sekitar 14,9%. Sekilas kecil. Pertanyaannya, apa cukup caleg dari sebuah partai itu menang dengan hanya mengandalkan orang yang dekat dengan partai itu sendiri saja? Kan mereka mengklaim itu simpatisan mereka.
Tapi kemudian misteri itu terpecahkan ketika saya menggunakan pendekatan etnografi. Selama setahun lebih saya jalan ke empat provinsi itu, saya wawancara bukan hanya tingkat lokal, namun saya wawancara puluhan politisi tingkat nasional, baik caleg gagal maupun caleg sukses tingkat nasional. Ketika saya wawancara mereka secara mendalam, buka lagi rekaman wawancara, ternyata pengertiannya tentang pemilih loyal itu tidak 100% sama dengan apa yang dipahami oleh konsep tentang party ID di literartur barat. Jadi kalau di barat, party ID itu merujuk kedekatan terhadap partai. Tapi ketika saya wawancara kepada mereka, itu mereka mendefinisikan party ID secara luas, termasuk kedekatan secara personal.
Dari situ kemudian saya menemukan tafsir atas data statistik yang saya miliki. Setelah saya lihat, saya investigasi betul bahwa dari sisi relatif pemilih yang dekat dengan partai cenderung ditawari uang, tapi secara absolut pemilih swing yang lebih banyak mendapatkan uang. Jadi, 43% dari 14,9% yang dekat sama partai ditawari uang, dibanding 22% dari 85% yang nggak punya kedekatan sama partai yang ditawari uang. Kan 43% secara relatif lebih besar dibanding 22%, tetapi 43% dari 15% tentu lebih sedikit secara absolut dibanding dari 85%.
Nah, di situ saya punya hipotesis awal, bahwa pada dasarnya caleg maupun broker tadi punya klaim untuk menarget pemilih yang dekat dengan partai yang mereka sebut dengan pemilih basis, pemilih loyal, tetapi karena dalam sistem proporsional terbuka, suara pemilih yang dekat dengan partai itu diperebutkan bukan hanya oleh satu caleg, tetapi bahkan caleg dalam satu partai, akibatnya mereka memperluas makna tentang party ID.
Apa lagi yang bisa disimpulkan Buhanuddin Muhtadi? Simak penjelasan lebih lanjut di laman berikutnya...
Jadi definisi pemilih basis dalam konteks Indonesia itu berbeda dengan literatur di Barat, karena sistem kita proporsional terbuka. Nggak mungkin mengandalkan mereka yang dekat dengan partai saja, karena secara jumlah kecil. Kedua, jumlah yang kecil itu diperebutkan oleh caleg dalam satu partai. Jadi, logika sistem proporsional terbuka itu memaksa persaingan tidak hanya bersifat inter party competition, tapi intra party competition.
Nah, karena pertarungan dalam satu partai, maka caleg tidak lagi mengandalkan struktur partai, tetapi mereka memperluas, karena beradu kuat caleg dalam satu partai. Kemudian mulai muncullah konsep individual success team campaign. Jadi tim sukses itu tidak lagi masing-masing partai, tapi setiap caleg punya tim sukses sendiri. Terus kemudian kalaupun ada pemilih dekat dengan partai, dalam teori saya, saya menyebutnya dengan istilah personal loyalis model. Itu pemilih yang dekat tadi dipersonalisasi untuk kepentingan caleg. Jadi misalnya, saya boleh dekat dengan PDIP, PKB, PPP, tetapi kedekatan itu dipersonalisasi, tidak lagi kedekatan partai, tetapi kedekatan caleg dari partai yang bersangkutan.
Jadi kira-kira puzzle-nya sudah ketemu dan itu menjawab pertanyaan kunci, Indonesia itu dalam literatur politik uang yang sudah established dalam studi politik distributif, apakah mengikuti jalur core voters model dan swing voters model? Ada dua debat nih di literatur. Menurut core voters model, itu politisi dari partai cenderung menarget pemilih yang dekat sama partai, karena yang mereka tuju adalah mobilisasi untuk memilih dia. Jadi daripada menyasar swing, meski mereka kasih uang untuk memilih, lebih baik pemilih pasif partai mereka yang dicirikan dengan terhadap partai mereka yang akan disasar, sehingga mereka akan datang ke TPS.
Sebaliknya, ada literatur lain yang disebut dengan swing voters model. Ngapain menarget pemilih yang secara ideologis sudah dekat dengan partai, toh mereka juga pasti memilih, lebih baik menarget pemilih yang tidak punya kedekatan dengan partai mana pun, pemilih swing.
Nah, Indonesia itu menurut temuan saya tidak kedua-duanya. Mengapa? Karena secara relatif sepertinya pemilih yang dekat dengan partai yang disasar, tapi secara absolut pemilih swing yang paling banyak terima uang. Nah, saya mengajukan teori yang disebut dengan personal loyalist model. Apa itu? Karena sistem proporsional terbuka, maka caleg itu akan mempersonalisasi pemilih yang dekat dengan partai, mereka tidak lagi bergantung dengan partai, mereka akan mengandalkan jaringan personal. Personal network ini bisa timses, bisa karena famili, bisa karena kedekatan etnik, kesamaan agama, bisa juga karena jaringan sosial.
Jadi kedekatan caleg tadi, mencari indentifikasi sosial yang kemudian diaksentuasikan oleh timses mereka. Termasuk dalam sistem proporsional terbuka, caleg dalam satu partai, mereka sudah mulai melihat-lihat siapa lawan internal mereka. Mereka cukup bermodalkan asalkan pemilih itu memiih dirinya, memilih caleg secara personal, maka cukup mengantarkan ke Senayan (DPR). Teori personal loyalist model ini mengandaikan tidak seperti yang diasumsikan oleh teori core voters model atau swing voters model. Itu bukan dua-duanya.
Nah, di bagian akhir disertasi saya, setelah tahu petanya, berapa banyak, kemudian determinan politik uang apa saja, kemudian pertanyaan berikutnya adalah seberapa efektif politik uang. Kok ada 33% pemilih yang mengaku ditawari uang? Jika banyak yang mengaku ditawari uang, pertanyaannya adalah seberapa efektif uang tersebut mempengaruhi pemilihan mereka.
Dalam survei pemilih saya punya pertanyaannya, kemudian setelah kita kuantifikasi, efek politik uang terhadap pilihan kurang lebih 10,2% dari total pemilih. Jadi banyak pemilih yang ambil duitnya, pemilihannya soal lain. Dan ini nggak memuaskan saya. Kalau betul bahwa banyak pemilih yang ambil duitnya dan pilihannya sesuai hati nurani mereka, pertanyaannya apakah politisi sebodoh itu, mengguyur pemilih dengan uang yang tak terhingga dengan strategi politik uang? Apakah mereka tidak tahu bahwa politik uang itu efeknya tidak terlalu besar? Kan politisi itu makhluk yang rasional, jadi tidak mungkin mereka melakukan sesuatu tanpa ada kalkulasi rasional.
Kemudian lagi-lagi sistem proporsional terbuka menjelaskan motivasi di balik masifnya politik uang di Indonesia. Jadi 10,2%, efek politik uang terhadap pilihan itu terlihat kecil. Tetapi dalam konteks sistem proporsional terbuka, 10,2% ini lebih dari cukup buat caleg untuk lolos ke Senayan. Apa alasannya? Saya kumpulkan data dari KPU, saya lihat data dari KPU, kemudian saya kumpulkan apa yang disebut dengan istilah winning margin. Winning margin itu adalah selisih antara caleg yang terbawah yang lolos dengan caleg tertinggi tetapi tidak lolos. Selisihnya berapa, kemudian saya persentasekan. Nah itu memang variatif tiap partai, antara 1,6% sampai 2,4% untuk winning margin tadi. Tetapi kalau saya rata-rata setiap partai, caleg yang lolos dari 10 partai ke Senayan yang kemarin, rata-rata untuk lolos 1,6%. Jadi, kecil sekali bagi seorang caleg untuk mengalahkan teman separtainya menuju Senayan.
Jadi, 10,2 % terlihat kecil untuk efek politik uang, tetapi karena untuk lolos hanya butuh 1,6 persen, jadi 10,2% itu besar sekali untuk caleg melakukan operasi politik uang. Makanya kemudian saya kasih sub-judulnya adalah "personal network and winning margin".
Temuan Anda, Jawa Tengah adalah provinsi yang party ID-nya tinggi dan politik uang tinggi. Apa sebab dan faktornya?
Teorinya itu yang saya jelaskan di atas tadi. Jadi untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, semuanya itu adalah kedekatan terhadap partai yang menjelaskan dan sistem proporsional terbuka yang membuat caleg dalam satu partai baku bunuh untuk mengalahkan teman separtainya agar lolos ke Senayan. Dan itu bukan hanya Jateng.
Bagaimana cara-cara kerja broker untuk pembelian suara pemilih?
Secara umum seperti tadi saya bilang, personal loyalist model yang menjelaskan bagaimana mekanisme politik uang itu didistribusikan. Jadi pertama adalah caleg melakukan proses rekrutmen timses. Timses itu dimulai dari keluarga terdekat. Jadi sistemnya itu kayak struktur piramida, yang paling atas adalah keluarga. Keluarga ini direkrut oleh caleg, karena dianggap lebih loyal dan tidak mata duitan. Umumnya jejaring kinship atau famili ini diartikan luas. Dan keluarga ini semacam manager campaign-nya di tingkat paling atas. Kemudian, di bawahnya mulai dibikin struktur timses di tingkat dapil, terus di bawahnya lagi ada koordinator kabupaten, karena tiap dapil umumnya terdiri dari kabupaten/kota. Kemudian dibikin koordinator keematan di masing-masing kota/kabupaten, di bawahnya lagi ada koordinator desa/kelurahan, koordinator RT, lalu koordinator TPS.
Pertanyaannya, bagaimana rekrutmen timses jika jumlah keluarganya terbatas? Jumlah keluarga yang terbatas itu hanya ada di level atas. Ketika sudah masuk pada tingkat grass root broker atau timses lapangan, makin jauh itu, jarak antara broker akar rumput dengan calegnya, karena dia mengandalkan struktur yang dia bentuk untuk mencari timses tadi. Timses keluarga, kemudian jaringan pertemanan, jaringan suku, jaringan agama, jaringan masjid, jaringan gereja, itu kan semuanya merujuk pada teori personal network, dan itu beyond partai politik.
Jadi struktur timses tadi itu lagi-lagi mengandalkan jaringan sosial personal yang dimiliki oeh si caleg, dalam beberapa kasus, extended broker yang di bawah, karena jaraknya jauh di bawah, ikatan personalnya dengan caleg makin jauh. Makanya muncul dengan istilah problem agency last, semakin ke bawah semakin susah dikontrol jaringan broker di tingkat bawah. Yang bisa dikontrol adalah orang-orang terdekat yang ada di atas. Nah, lagi-lagi itu menjelaskan kelebihan dan kelemahan teori personal loyalist model, karena di tingkat bawah mau tidak mau caleg dihadapkan pada kebutuhan menguatkan armada di tingkat broker, sedangkan armada yang tersedia dekat dengan dirinya tidak banyak.
Nah, pada titik itu ada agency last yang melakukan misalnya dia terima uang, barang yang seharusnya dia distribusikan ke pemilih tetapi diambil broker di tingkat grass root. Itulah yang menjelaskan kenapa politik uang itu banyak bocor ke swing voters, karena awalnya mau menarget pemilih yang dekat dengan caleg, tetapi secara absolut banyak swing voters yang menerima politik uang. Tapi lagi-lagi, meskipun bocor di sana-sini, politisi tetap insist melakukan praktik politik uang, dan mereka mengakui itu dalam banyak wawancara dengan saya.
Kalau ada 600.000 amplop yang dibagi, kebanyakan politisi merasa kalau dapat sepertiga suara sudah bagus, dua pertiganya dianggap uang sedekah. Ada spekulatif. Tetapi sepertiga dari 600.000 itu sudah lebih dari cukup untuk lolos ke Senayan. Apalagi kalau di Jawa uang yang diberikan rata-rata itu kecil, Rp 20 ribu sampai Rp 30 ribu. Kalau di luar Jawa yang jauh atau geografisnya susah, itu harga pemilih untuk bisa menerima politik uangnya semakin tinggi. Tetapi operasinya kira-kira begitu. Jadi, saya bedakan satu proses rekrutmen broker oleh caleg, kemudian proses rekrutmen pemilih oleh broker, ada dua tingkat di situ.
Nah, proses retrutmen pemilih oleh timses, itu lagi-lagi pakai jaringan personal. Jadi timses kalau sudah di-assign untuk membantu caleg, dia akan memprioritaskan keluarganya dulu, karena paling mudah dipengaruhi. Setelah keluarga intinya, dia masuk ke keluarga besarnya. Tapi rata-rata timses itu kan diberi tugas untuk mencari pemilih yang banyak dan luas, yang tidak bisa ditutupi dengan anggota keluarganya sendiri. Nah, lagi-lagi di situ, semakin luas target suara yang diberikan, semakin besar bocornya. Karena kalau sudah melampaui dari keluarga besarnya, melampaui dari jaringan sosial timses, besar juga rent seeking-nya. Pemilih melakukan rent seeking juga, dia terima duitnya, memilih urusan lain. Secara umum praktek rent seeking itu terjadi beberapa lapis, pertama hubungan rent seeking terjadi antara caleg dengan broker, broker pun ada broker tingkat inti, dan broker grass root, kemudian antara broker dengan pemilih.
Beberapa caleg yang saya wawancarai yang kebetulan sukses, rata-rata menyimpulkan kesuksesan atau kegagalan caleg 2014 itu pada titik seberapa tepat memilih broker, dan yang kedua seberapa kontrol itu dijalankan caleg kepada broker. Semakin tepat pilihan terhadap broker, semakin besar peluang si caleg untuk menang. Tepat-tidaknya pemilihan broker didasarkan pada kedekatan broker dengan si caleg. Jadi kalau misalnya pemilihan brokernya tidak tepat, maka banyak uang yang mubazir, terbuang percuma, semakin kecil juga peluangnya untuk menang.
Tetapi sehebat-hebatnya caleg melakukan operasi politik uang, mereka juga mengakui cara semacam ini memiliki kelemahan yaitu tadi, semakin luas ambisi untuk menarget pemilih di luar personal network yang mereka punya, maka semakin besar uangnya. Makanya politisi yang pintar, mereka meng-assign brokernya tidak lebih dari 20 orang. Jadi satu broker diminta untuk mencari sampai 20 orang saja. Jadi nggak dikasih target yang terlalu ambisius, karena kalau dikasih target yang terlalu ambisius, bocornya semakin besar. Jadi 1-20 orang, itu broker paling mengandalkan keluarganya. Jadi semakin kecil target broker untuk menarget pemilih, maka semakin besar armada broker yang medeka butuhkan.
Jadi kalau hanya 20 maksimal target yang diberikan kepada setiap broker, berarti si calegnya butuh ratusan hingga ribuan broker untuk memastikan politik uangnya betuk-betul terdistribusi di lapangan.
Berapa besar sebenarnya biaya jadi caleg, dan bagaimana pandangannya untuk Pemilu 2019 nanti? Burhanuddin Muhtadi bicara lebih banyak di laman berikutnya...
Lantas, untuk seorang caleg, rata-rata menghabiskan berapa biaya untuk kampanye?
Saya sendiri tidak menanyakan itu secara khusus. Kalau saya tanya si caleg, mereka umumnya tidak mau mengatakan secara terbuka. Karenanya, saya tanyanya bukan kepada caleg, tetapi kepada pemilih dan broker, berapa uang yang didistribusikan oleh timses. Kemudian saya tanya juga kepada pemilih, berapa uang yang mereka terima.
Nah, menurut pengakuan paling pesimis, untuk politik uang saja dari rata-rata gambaran dari broker tadi, itu kurang lebih Rp 6,7 miliar untuk politik uang saja. Itu di Jawa. Itu untuk politik uang saja, belum tentu berhasil juga. Itu rata-rata pesimis ya, mungkin angka aktualnya lebih besar daripada itu untuk satu caleg. Jadi kalau misalnya Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu (per amplop), jadi estimasinya segitu. Ada di Bab 6 disertasi saya.
Bagaimana menurut Anda untuk Pileg 2019 nanti?
Saya terus terang kecewa kenapa revisi UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 itu tidak menganulir sistem proporsional terbuka. Jadi kemarin perdebatan lebih banyak perdebatan di DPR persoalan Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold 20% atau 25% suara. Hampir semua partai tidak ada yang memperdebatkan perlu-tidaknya DPR untuk mengevaluasi sistem proporsional terbuka. Seperti kita duga, akhirnya sistem proporsional terbuka tetap dilanjutkan untuk 2019.
Waktu pembahasan UU tersebut, terus terang disertasi saya belum selesai, tetapi pas sudah selesai saya kirim ke beberapa elite partai dan pemerintah. Motivasi saya adalah, tolong dievaluasi sistem proporsional terbuka, kenapa tidak memikirkan sistem proporsional tertutup. Alasan saya, salah satu sebab yang mengakibatkan poitik uang tinggi adalah salah satunya karena kita memakai sistem proporsional terbuka, dan itu paralel dengan party ID. Party ID kita kalau kita bandingkan dari data 1999 sampai sekarang, secara sistematik turun signifikan, dan itu bersamaan dengan sistem proporsional terbuka yang diintrodusir oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi nasi sudah jadi bubur, semua partai tidak tertarik dengan usulan saya. Dan mereka merasa, terutama ketua umum atau elitenya, kalau proporsional terbuka diterapkan, tanggung jawab kemenangan ada di tangan masing-masing caleg. Jadi yang menjelaskan mengapa elite partai enggan untuk menerima usulan saya untuk mengganti sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup adalah setidaknya 2009, 2014, kampanye itu ada di tingkat caleg. Jadi elite partai tidak perlu mengeluarkan ongkos besar, karena caleglah yang bertanggung jawab untuk hidup mati karier politik mereka masing-masing. Dan karena sudah disahkan, tunggu saja, saya tidak tahu persis apa yang akan terjadi di 2019. Saya harus melakukan survei lagi untuk mengecek seberapa besar politik uang di 2019 nanti.
Idealnya adalah post election survey. Jadi setelah pemilu, baru saya melakukan survei. Waktu yang saya idealkan untuk turun adalah kurang lebih seminggu setelah Pemilu, karena memori pemilih masih fresh. Teorinya itu masih besar, tapi seberapa besar, harus diriset lagi. Tetapi yang saya dengar dari pembicaraan dengan banyak (di) elite partai, sekarang ada satu fenomena yang harus diuji, di mana caleg yang direkrut untuk berkompetisi 2019 itu banyak yang mengalami demotivasi, karena sudah habis-habisan di 2014. Banyak yang kapok, trauma. Saya ingat waktu wawancara dengan anggota DPR yang terpilih 2014, beberapa di antaranya meneteskan air mata, betapa kerasnya pertarungan di 2014 kemarin. Padahal mereka menang. Tapi ingat betapa situasi yang terjadi di 2014 membuat traumatik, bukan hanya mereka yang kalah, bahkan yang menang pun merasakan betapa kerasnya pertarungan di tingkat bawah. Seorang anggota DPR incumbent yang gagal di 2014, mengibaratkan Pemilu 2014 sebagai perang saudara di Suriah, karena sesama caleg dalam satu partai saling bunuh, dan alat bunuhnya adalah uang.
Kemudian ada juga caleg mantan pimpinan MPR yang kalah oleh caleg lokal, karena caleg lokalnya punya kekuatan politik uang yang besar dan bahasa-bahasa atau idiom yang dipakai untuk politik uang luar biasa, ada istilah golput 9golongan pemerima uang tunai), ada NPWP (no piro wani piro), ada istilah sentuhan terakhir (finishing touch), ada istilah bom, jadi hal-hal yang menggambarkan betapa brutalnya pertarungan di 2014, yang mengedepankan uang sebagai panglima. Dan itu membuat sebagian caleg trauma dan sebagian lagi enggan untuk maju di 2019. Tapi lagi-lagi, ini kan data anecdotal, jadi perlu diuji lagi. Teorinya sih, seharusnya politik uang tetap tinggi. Tapi politik uang tinggi itu ada dua sisi, satu adalah sisi supply-nya atau calegnya, yang kedua adalah demand-nya atau pemilihnya.
Pengalaman di Timor Leste, kita juga melakukan exit poll di Pemilu 2017 di Timor Leste, itu demand-nya tinggi kaya di Indonesia. Pemilihnya menunggu politik uang itu. Mereka menganggap politik uang itu wajar di sana, tetapi supply-nya terbatas. Makanya di Timor Leste dalam temuan kita, pemilih yang menerima uang di Pileg itu cuma 4%, (sementara) kita 33%. Tetapi demand-nya di Timor Leste tinggi, kenapa yang menerima mengaku cuma 4%. Oh, ternyata penjelasannya sistem propersional tertutup. Jadi tidak indentif buat caleg yang melakukan kampanye secara individual, mereka kampanyenya untuk partai. Karena partai yang maju, otomatis ideologi dan multiplatform yang lebih penting. Jadi demand tinggi seperti di Indonesia, tapi supply-nya terbatas. Di Indonesia demand tinggi, supply tinggi, itu yang menyebabkan politik uang masif.
Jadi menurut Anda, yang lebih tepat sistem proporsional tertutup?
Tentu ada plus-minus. Kita perlu banyak masukan dari ahli politik. Ada ahli politik yang mengatakan kalau sistem proporsional tertutup, politik uang akan terjadi di tingkat elite dan sulit untuk dikontrol. Ada benarnya juga argumen tersebut. Tapi yang menjadi motivasi saya bukan hanya sekadar politik uang terjadi secara masif di tingkat pemilih, tetapi yang paling urgen adalah sistem proporsional terbuka membuka kemungkinan lahirnya politik yang berbiaya mahal, saat yang sama menurunkan kedekatan pemilih terhadap partai, jadi party ID turun. Ketika party ID drop, partai tidak termotivasi untuk membangun ideologisasi atau kelembagaan partai. Jadi mereka tidak lagi berbicara tentang ideologi berpartai mereka masing-masing, karena yang bertarung caleg mereka masing-masing. Dan implikasinya jangka panjang. Kalau uang yang menentukan caleg untuk lolos, bukan ideologi partai, maka caleg yang punya kekuatan modal yang menang. Dan kalau mereka yang menang, akibatnya caleg-caleg yang punya kompetensi namun tidak memiliki akses terhadap ongkos politik, tidak punya kekuatan finansial untuk kampanye, maka akan gagal.
Jadi kita menunjukkan ada hal yang paralel: sistem proporsional terbuka diterapkan, party ID turun, kualitas anggota DPR turun. Itu ada hubungan korelasi yang menunjukkan antar variabel. Sejak proporsional terbuka diperkenalkan, politik dinasti makin menguat, caleg-caleg kompeten gagal. Orang seperti Ferry Mursidan Baldan yang disebut sebagai UU berjalan kalah, ketika sistem proporsional terbuka dijalankan ketika dia maju melalui Golkar. Yuddy Krisnandi kalah dari caleg partai lain. Sony Keraf mantan menteri era Megawati kalah di dapil saya. Tingkat absensi anggota DPR drop. Jadi efeknya itu berantai. Itu yang membuat saya berpandangan (bahwa) sistem proporsional tertutup lebih tepat tuk menyelesaikan berbagai persoalan itu, terutama politik uang yang besar. Tapi usulan saya tidak populer, bahkan di kalangan konsultan politik, karena secara bisnis merugikan. Karena kliennya terbatas hanya pada partai. Tetapi efek jangka panjangnya, karena kita ingin memperbaiki sistemnya.
Soal lembaga survei, sebenarnya sejauh mana bisa independen?
Sebenarnya kita sudah uji, tidak ada dampaknya secara signifikan untuk mempengaruhi perilaku pemilih. Untuk menguji seberapa besar lembaga survei mempengaruhi di tingkat massa, itu kan ada dua teori. Satu underdog effect, pemilih cenderung memilih calon dari partai yang dianggap kalah atau yang dikesankan sering kali dianggap nomor buncit dalam survei. Orang bersimpati pada orang yang berada di bawah. Kedua, orang cenderung memilih yang dipersepsikan lembaga survei menang. Itu dua teori yang tidak tunggal. Jadi yang mengatakan lembaga survei punya efek, itu menurut saya asbun, asal bunyi itu. Ini eranya data, jadi nggak boleh asal mangap itu.
Underdog effect itu harus sistematif. Lembaga survei kan nggak hanya satu, dan berbeda-beda temuannya. Jadi, argumen lembaga survei berpengaruh pada pemilih mudah sekali untuk kita bantah.
Kedua, pemilih sebagian tidak tahu lembaga survei. Itu hanya fenomena sosmed saja yang membesar-besarkan efek lembaga survei. Kalau lembaga survei itu punya efek besar, menurut saya partai politik bikin lembaga survei saja. Tetapi hasil survei berpengaruh untuk di tingkat elite. Di tingkat elite itu satu, pengaruh lembaga survei yang kredibel untuk mempengaruhi pilihan atau nominasi calon, entah itu pilpres, pilkada. Bagi sebagian besar parpol, survei yang bisa diandalkan bisa menjadi alat pandu mereka untuk menentukan nominasi. Misalnya untuk pilkada, mana calon yang berpotensi menang. Tapi pengaruhnya di tingkat nominasi dan tingkat elite. Ketiga, mempengaruhi di tingkat elite pengusaha, karena elite pengusaha ini kan ingin membantu partai atau calo yang potensial menang. Pengusaha pasti akan memberikan bantuan kepada semua partai dan calon, tetapi seberapa besar porsi bantuannya ditentukan oleh seberapa besar peluang calon atau partai yang bersangkutan menang. Apa alat ukurnya untuk menentukan itu? Ya, survei.
Adakah lembaga survei dan hasil survei yang bisa dibeli atau disewa?
Saya susah untuk mengomentari lembaga survei lain, tetapi menurut saya fenomena semacam itu dengan mudah kita bisa menilainya. Jadi kepercayaan publik terhadap lembaga survei turun adalah ada supply and demand. Supply-nya adalah ada lembaga survei yang abal-abal yang tidak terdaftar di asosiasi, sehingga tidak bisa diricek, tidak bisa diaudit metodologinya. Dan surveinya itu kebetulan tersedia. Ada beberapa lembaga survei yang track record-nya meragukan, tapi tetap saja lembaga survei itu mendapatkan publikasi luas dari media. Media juga tidak mengkritisi metodologinya, prosedur ilmiahnya, dan seterusnya. Tetapi supply-nya juga ditentukan oleh demand. Jadi demand-nya ada. Ada politisi yang suka atau ingin di-entertain oleh angin surga, oleh angka-angka yang dimasak lembaga survei yang meragukan tadi. Jadi ada titik temu di situ. Jadi ini tugas bersama untuk meminimalisir lembaga survei abal-abal. Karena sebenarnya, lembaga survei punya misi suci, seperti halnya media, yaitu sebagai pilar demokrasi. Lembaga survei itu seharusnya mampu menyerap aspirasi publik, termasuk kalau bicara pacuan kuda elektabilitas, memotret opini publik secara benar sesuai metodologi ilmiah. Dan karenanya, agar memudahkan misi suci itu terlaksana, maka lembaga survei harus bergabung dengan asosiasi, supaya bisa dikontrol, karena ada lembaga etik dari kampus seperti Persepi. Kalau ada lembaga survei di luar Persepi, itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Sekarang saja Persepi sudah memecat 6 lembaga survei yang jadi anggotanya, karena dianggap melakukan pelanggaran etik keras.
Di Persepi, independensi ada dua level, yang satu independensi akademik, siapa pun kliennya tidak bisa mengintervensi. Satu lagi independensi finansial. Persepi mempersilakan bekerjasama dengan pihak ketiga, tapi pihak ketiga itu tidak bisa mendikte metode dan kesimpulan survei. Sama seperti pers, media, ada pagar api antara redaksi dan iklan. Banyak orang yang berpersepsi bahwa hasil survei didikte oleh sponsornya. Nggak begitu. Sebab kliennya juga ingin hasil survei yang objektif. Karena kalau tak objektif, justru merugikan kliennya. Kecuali kliennya agak "sakit", dia pingin di-entertain.