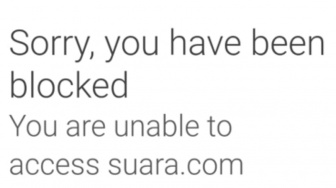Burhanuddin Muhtadi : Politik Uang karena Ada Supply dan Demand

Dalam wawancara ini, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan beberapa temuan mengapa politik uang bisa begitu masif di Indonesia.
Lantas, untuk seorang caleg, rata-rata menghabiskan berapa biaya untuk kampanye?
Saya sendiri tidak menanyakan itu secara khusus. Kalau saya tanya si caleg, mereka umumnya tidak mau mengatakan secara terbuka. Karenanya, saya tanyanya bukan kepada caleg, tetapi kepada pemilih dan broker, berapa uang yang didistribusikan oleh timses. Kemudian saya tanya juga kepada pemilih, berapa uang yang mereka terima.
Nah, menurut pengakuan paling pesimis, untuk politik uang saja dari rata-rata gambaran dari broker tadi, itu kurang lebih Rp 6,7 miliar untuk politik uang saja. Itu di Jawa. Itu untuk politik uang saja, belum tentu berhasil juga. Itu rata-rata pesimis ya, mungkin angka aktualnya lebih besar daripada itu untuk satu caleg. Jadi kalau misalnya Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu (per amplop), jadi estimasinya segitu. Ada di Bab 6 disertasi saya.
Bagaimana menurut Anda untuk Pileg 2019 nanti?
Baca Juga: Politik Gentong Babi dalam Pemilu dan Korupsi Politik yang Mengakar
Saya terus terang kecewa kenapa revisi UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 itu tidak menganulir sistem proporsional terbuka. Jadi kemarin perdebatan lebih banyak perdebatan di DPR persoalan Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold 20% atau 25% suara. Hampir semua partai tidak ada yang memperdebatkan perlu-tidaknya DPR untuk mengevaluasi sistem proporsional terbuka. Seperti kita duga, akhirnya sistem proporsional terbuka tetap dilanjutkan untuk 2019.
Waktu pembahasan UU tersebut, terus terang disertasi saya belum selesai, tetapi pas sudah selesai saya kirim ke beberapa elite partai dan pemerintah. Motivasi saya adalah, tolong dievaluasi sistem proporsional terbuka, kenapa tidak memikirkan sistem proporsional tertutup. Alasan saya, salah satu sebab yang mengakibatkan poitik uang tinggi adalah salah satunya karena kita memakai sistem proporsional terbuka, dan itu paralel dengan party ID. Party ID kita kalau kita bandingkan dari data 1999 sampai sekarang, secara sistematik turun signifikan, dan itu bersamaan dengan sistem proporsional terbuka yang diintrodusir oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi nasi sudah jadi bubur, semua partai tidak tertarik dengan usulan saya. Dan mereka merasa, terutama ketua umum atau elitenya, kalau proporsional terbuka diterapkan, tanggung jawab kemenangan ada di tangan masing-masing caleg. Jadi yang menjelaskan mengapa elite partai enggan untuk menerima usulan saya untuk mengganti sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup adalah setidaknya 2009, 2014, kampanye itu ada di tingkat caleg. Jadi elite partai tidak perlu mengeluarkan ongkos besar, karena caleglah yang bertanggung jawab untuk hidup mati karier politik mereka masing-masing. Dan karena sudah disahkan, tunggu saja, saya tidak tahu persis apa yang akan terjadi di 2019. Saya harus melakukan survei lagi untuk mengecek seberapa besar politik uang di 2019 nanti.
Idealnya adalah post election survey. Jadi setelah pemilu, baru saya melakukan survei. Waktu yang saya idealkan untuk turun adalah kurang lebih seminggu setelah Pemilu, karena memori pemilih masih fresh. Teorinya itu masih besar, tapi seberapa besar, harus diriset lagi. Tetapi yang saya dengar dari pembicaraan dengan banyak (di) elite partai, sekarang ada satu fenomena yang harus diuji, di mana caleg yang direkrut untuk berkompetisi 2019 itu banyak yang mengalami demotivasi, karena sudah habis-habisan di 2014. Banyak yang kapok, trauma. Saya ingat waktu wawancara dengan anggota DPR yang terpilih 2014, beberapa di antaranya meneteskan air mata, betapa kerasnya pertarungan di 2014 kemarin. Padahal mereka menang. Tapi ingat betapa situasi yang terjadi di 2014 membuat traumatik, bukan hanya mereka yang kalah, bahkan yang menang pun merasakan betapa kerasnya pertarungan di tingkat bawah. Seorang anggota DPR incumbent yang gagal di 2014, mengibaratkan Pemilu 2014 sebagai perang saudara di Suriah, karena sesama caleg dalam satu partai saling bunuh, dan alat bunuhnya adalah uang.
Kemudian ada juga caleg mantan pimpinan MPR yang kalah oleh caleg lokal, karena caleg lokalnya punya kekuatan politik uang yang besar dan bahasa-bahasa atau idiom yang dipakai untuk politik uang luar biasa, ada istilah golput 9golongan pemerima uang tunai), ada NPWP (no piro wani piro), ada istilah sentuhan terakhir (finishing touch), ada istilah bom, jadi hal-hal yang menggambarkan betapa brutalnya pertarungan di 2014, yang mengedepankan uang sebagai panglima. Dan itu membuat sebagian caleg trauma dan sebagian lagi enggan untuk maju di 2019. Tapi lagi-lagi, ini kan data anecdotal, jadi perlu diuji lagi. Teorinya sih, seharusnya politik uang tetap tinggi. Tapi politik uang tinggi itu ada dua sisi, satu adalah sisi supply-nya atau calegnya, yang kedua adalah demand-nya atau pemilihnya.
Pengalaman di Timor Leste, kita juga melakukan exit poll di Pemilu 2017 di Timor Leste, itu demand-nya tinggi kaya di Indonesia. Pemilihnya menunggu politik uang itu. Mereka menganggap politik uang itu wajar di sana, tetapi supply-nya terbatas. Makanya di Timor Leste dalam temuan kita, pemilih yang menerima uang di Pileg itu cuma 4%, (sementara) kita 33%. Tetapi demand-nya di Timor Leste tinggi, kenapa yang menerima mengaku cuma 4%. Oh, ternyata penjelasannya sistem propersional tertutup. Jadi tidak indentif buat caleg yang melakukan kampanye secara individual, mereka kampanyenya untuk partai. Karena partai yang maju, otomatis ideologi dan multiplatform yang lebih penting. Jadi demand tinggi seperti di Indonesia, tapi supply-nya terbatas. Di Indonesia demand tinggi, supply tinggi, itu yang menyebabkan politik uang masif.
Baca Juga: Ini Kisi-kisi Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Tahap 1
Jadi menurut Anda, yang lebih tepat sistem proporsional tertutup?
Tentu ada plus-minus. Kita perlu banyak masukan dari ahli politik. Ada ahli politik yang mengatakan kalau sistem proporsional tertutup, politik uang akan terjadi di tingkat elite dan sulit untuk dikontrol. Ada benarnya juga argumen tersebut. Tapi yang menjadi motivasi saya bukan hanya sekadar politik uang terjadi secara masif di tingkat pemilih, tetapi yang paling urgen adalah sistem proporsional terbuka membuka kemungkinan lahirnya politik yang berbiaya mahal, saat yang sama menurunkan kedekatan pemilih terhadap partai, jadi party ID turun. Ketika party ID drop, partai tidak termotivasi untuk membangun ideologisasi atau kelembagaan partai. Jadi mereka tidak lagi berbicara tentang ideologi berpartai mereka masing-masing, karena yang bertarung caleg mereka masing-masing. Dan implikasinya jangka panjang. Kalau uang yang menentukan caleg untuk lolos, bukan ideologi partai, maka caleg yang punya kekuatan modal yang menang. Dan kalau mereka yang menang, akibatnya caleg-caleg yang punya kompetensi namun tidak memiliki akses terhadap ongkos politik, tidak punya kekuatan finansial untuk kampanye, maka akan gagal.
Jadi kita menunjukkan ada hal yang paralel: sistem proporsional terbuka diterapkan, party ID turun, kualitas anggota DPR turun. Itu ada hubungan korelasi yang menunjukkan antar variabel. Sejak proporsional terbuka diperkenalkan, politik dinasti makin menguat, caleg-caleg kompeten gagal. Orang seperti Ferry Mursidan Baldan yang disebut sebagai UU berjalan kalah, ketika sistem proporsional terbuka dijalankan ketika dia maju melalui Golkar. Yuddy Krisnandi kalah dari caleg partai lain. Sony Keraf mantan menteri era Megawati kalah di dapil saya. Tingkat absensi anggota DPR drop. Jadi efeknya itu berantai. Itu yang membuat saya berpandangan (bahwa) sistem proporsional tertutup lebih tepat tuk menyelesaikan berbagai persoalan itu, terutama politik uang yang besar. Tapi usulan saya tidak populer, bahkan di kalangan konsultan politik, karena secara bisnis merugikan. Karena kliennya terbatas hanya pada partai. Tetapi efek jangka panjangnya, karena kita ingin memperbaiki sistemnya.
Soal lembaga survei, sebenarnya sejauh mana bisa independen?
Sebenarnya kita sudah uji, tidak ada dampaknya secara signifikan untuk mempengaruhi perilaku pemilih. Untuk menguji seberapa besar lembaga survei mempengaruhi di tingkat massa, itu kan ada dua teori. Satu underdog effect, pemilih cenderung memilih calon dari partai yang dianggap kalah atau yang dikesankan sering kali dianggap nomor buncit dalam survei. Orang bersimpati pada orang yang berada di bawah. Kedua, orang cenderung memilih yang dipersepsikan lembaga survei menang. Itu dua teori yang tidak tunggal. Jadi yang mengatakan lembaga survei punya efek, itu menurut saya asbun, asal bunyi itu. Ini eranya data, jadi nggak boleh asal mangap itu.
Underdog effect itu harus sistematif. Lembaga survei kan nggak hanya satu, dan berbeda-beda temuannya. Jadi, argumen lembaga survei berpengaruh pada pemilih mudah sekali untuk kita bantah.
Kedua, pemilih sebagian tidak tahu lembaga survei. Itu hanya fenomena sosmed saja yang membesar-besarkan efek lembaga survei. Kalau lembaga survei itu punya efek besar, menurut saya partai politik bikin lembaga survei saja. Tetapi hasil survei berpengaruh untuk di tingkat elite. Di tingkat elite itu satu, pengaruh lembaga survei yang kredibel untuk mempengaruhi pilihan atau nominasi calon, entah itu pilpres, pilkada. Bagi sebagian besar parpol, survei yang bisa diandalkan bisa menjadi alat pandu mereka untuk menentukan nominasi. Misalnya untuk pilkada, mana calon yang berpotensi menang. Tapi pengaruhnya di tingkat nominasi dan tingkat elite. Ketiga, mempengaruhi di tingkat elite pengusaha, karena elite pengusaha ini kan ingin membantu partai atau calo yang potensial menang. Pengusaha pasti akan memberikan bantuan kepada semua partai dan calon, tetapi seberapa besar porsi bantuannya ditentukan oleh seberapa besar peluang calon atau partai yang bersangkutan menang. Apa alat ukurnya untuk menentukan itu? Ya, survei.
Adakah lembaga survei dan hasil survei yang bisa dibeli atau disewa?
Saya susah untuk mengomentari lembaga survei lain, tetapi menurut saya fenomena semacam itu dengan mudah kita bisa menilainya. Jadi kepercayaan publik terhadap lembaga survei turun adalah ada supply and demand. Supply-nya adalah ada lembaga survei yang abal-abal yang tidak terdaftar di asosiasi, sehingga tidak bisa diricek, tidak bisa diaudit metodologinya. Dan surveinya itu kebetulan tersedia. Ada beberapa lembaga survei yang track record-nya meragukan, tapi tetap saja lembaga survei itu mendapatkan publikasi luas dari media. Media juga tidak mengkritisi metodologinya, prosedur ilmiahnya, dan seterusnya. Tetapi supply-nya juga ditentukan oleh demand. Jadi demand-nya ada. Ada politisi yang suka atau ingin di-entertain oleh angin surga, oleh angka-angka yang dimasak lembaga survei yang meragukan tadi. Jadi ada titik temu di situ. Jadi ini tugas bersama untuk meminimalisir lembaga survei abal-abal. Karena sebenarnya, lembaga survei punya misi suci, seperti halnya media, yaitu sebagai pilar demokrasi. Lembaga survei itu seharusnya mampu menyerap aspirasi publik, termasuk kalau bicara pacuan kuda elektabilitas, memotret opini publik secara benar sesuai metodologi ilmiah. Dan karenanya, agar memudahkan misi suci itu terlaksana, maka lembaga survei harus bergabung dengan asosiasi, supaya bisa dikontrol, karena ada lembaga etik dari kampus seperti Persepi. Kalau ada lembaga survei di luar Persepi, itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Sekarang saja Persepi sudah memecat 6 lembaga survei yang jadi anggotanya, karena dianggap melakukan pelanggaran etik keras.
Di Persepi, independensi ada dua level, yang satu independensi akademik, siapa pun kliennya tidak bisa mengintervensi. Satu lagi independensi finansial. Persepi mempersilakan bekerjasama dengan pihak ketiga, tapi pihak ketiga itu tidak bisa mendikte metode dan kesimpulan survei. Sama seperti pers, media, ada pagar api antara redaksi dan iklan. Banyak orang yang berpersepsi bahwa hasil survei didikte oleh sponsornya. Nggak begitu. Sebab kliennya juga ingin hasil survei yang objektif. Karena kalau tak objektif, justru merugikan kliennya. Kecuali kliennya agak "sakit", dia pingin di-entertain.