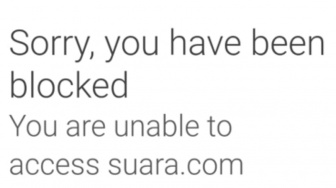Burhanuddin Muhtadi : Politik Uang karena Ada Supply dan Demand

Dalam wawancara ini, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan beberapa temuan mengapa politik uang bisa begitu masif di Indonesia.
Jadi definisi pemilih basis dalam konteks Indonesia itu berbeda dengan literatur di Barat, karena sistem kita proporsional terbuka. Nggak mungkin mengandalkan mereka yang dekat dengan partai saja, karena secara jumlah kecil. Kedua, jumlah yang kecil itu diperebutkan oleh caleg dalam satu partai. Jadi, logika sistem proporsional terbuka itu memaksa persaingan tidak hanya bersifat inter party competition, tapi intra party competition.
Nah, karena pertarungan dalam satu partai, maka caleg tidak lagi mengandalkan struktur partai, tetapi mereka memperluas, karena beradu kuat caleg dalam satu partai. Kemudian mulai muncullah konsep individual success team campaign. Jadi tim sukses itu tidak lagi masing-masing partai, tapi setiap caleg punya tim sukses sendiri. Terus kemudian kalaupun ada pemilih dekat dengan partai, dalam teori saya, saya menyebutnya dengan istilah personal loyalis model. Itu pemilih yang dekat tadi dipersonalisasi untuk kepentingan caleg. Jadi misalnya, saya boleh dekat dengan PDIP, PKB, PPP, tetapi kedekatan itu dipersonalisasi, tidak lagi kedekatan partai, tetapi kedekatan caleg dari partai yang bersangkutan.
Jadi kira-kira puzzle-nya sudah ketemu dan itu menjawab pertanyaan kunci, Indonesia itu dalam literatur politik uang yang sudah established dalam studi politik distributif, apakah mengikuti jalur core voters model dan swing voters model? Ada dua debat nih di literatur. Menurut core voters model, itu politisi dari partai cenderung menarget pemilih yang dekat sama partai, karena yang mereka tuju adalah mobilisasi untuk memilih dia. Jadi daripada menyasar swing, meski mereka kasih uang untuk memilih, lebih baik pemilih pasif partai mereka yang dicirikan dengan terhadap partai mereka yang akan disasar, sehingga mereka akan datang ke TPS.
Sebaliknya, ada literatur lain yang disebut dengan swing voters model. Ngapain menarget pemilih yang secara ideologis sudah dekat dengan partai, toh mereka juga pasti memilih, lebih baik menarget pemilih yang tidak punya kedekatan dengan partai mana pun, pemilih swing.
Baca Juga: Politik Gentong Babi dalam Pemilu dan Korupsi Politik yang Mengakar
Nah, Indonesia itu menurut temuan saya tidak kedua-duanya. Mengapa? Karena secara relatif sepertinya pemilih yang dekat dengan partai yang disasar, tapi secara absolut pemilih swing yang paling banyak terima uang. Nah, saya mengajukan teori yang disebut dengan personal loyalist model. Apa itu? Karena sistem proporsional terbuka, maka caleg itu akan mempersonalisasi pemilih yang dekat dengan partai, mereka tidak lagi bergantung dengan partai, mereka akan mengandalkan jaringan personal. Personal network ini bisa timses, bisa karena famili, bisa karena kedekatan etnik, kesamaan agama, bisa juga karena jaringan sosial.
Jadi kedekatan caleg tadi, mencari indentifikasi sosial yang kemudian diaksentuasikan oleh timses mereka. Termasuk dalam sistem proporsional terbuka, caleg dalam satu partai, mereka sudah mulai melihat-lihat siapa lawan internal mereka. Mereka cukup bermodalkan asalkan pemilih itu memiih dirinya, memilih caleg secara personal, maka cukup mengantarkan ke Senayan (DPR). Teori personal loyalist model ini mengandaikan tidak seperti yang diasumsikan oleh teori core voters model atau swing voters model. Itu bukan dua-duanya.
Nah, di bagian akhir disertasi saya, setelah tahu petanya, berapa banyak, kemudian determinan politik uang apa saja, kemudian pertanyaan berikutnya adalah seberapa efektif politik uang. Kok ada 33% pemilih yang mengaku ditawari uang? Jika banyak yang mengaku ditawari uang, pertanyaannya adalah seberapa efektif uang tersebut mempengaruhi pemilihan mereka.
Dalam survei pemilih saya punya pertanyaannya, kemudian setelah kita kuantifikasi, efek politik uang terhadap pilihan kurang lebih 10,2% dari total pemilih. Jadi banyak pemilih yang ambil duitnya, pemilihannya soal lain. Dan ini nggak memuaskan saya. Kalau betul bahwa banyak pemilih yang ambil duitnya dan pilihannya sesuai hati nurani mereka, pertanyaannya apakah politisi sebodoh itu, mengguyur pemilih dengan uang yang tak terhingga dengan strategi politik uang? Apakah mereka tidak tahu bahwa politik uang itu efeknya tidak terlalu besar? Kan politisi itu makhluk yang rasional, jadi tidak mungkin mereka melakukan sesuatu tanpa ada kalkulasi rasional.
Kemudian lagi-lagi sistem proporsional terbuka menjelaskan motivasi di balik masifnya politik uang di Indonesia. Jadi 10,2%, efek politik uang terhadap pilihan itu terlihat kecil. Tetapi dalam konteks sistem proporsional terbuka, 10,2% ini lebih dari cukup buat caleg untuk lolos ke Senayan. Apa alasannya? Saya kumpulkan data dari KPU, saya lihat data dari KPU, kemudian saya kumpulkan apa yang disebut dengan istilah winning margin. Winning margin itu adalah selisih antara caleg yang terbawah yang lolos dengan caleg tertinggi tetapi tidak lolos. Selisihnya berapa, kemudian saya persentasekan. Nah itu memang variatif tiap partai, antara 1,6% sampai 2,4% untuk winning margin tadi. Tetapi kalau saya rata-rata setiap partai, caleg yang lolos dari 10 partai ke Senayan yang kemarin, rata-rata untuk lolos 1,6%. Jadi, kecil sekali bagi seorang caleg untuk mengalahkan teman separtainya menuju Senayan.
Baca Juga: Ini Kisi-kisi Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Tahap 1
Jadi, 10,2 % terlihat kecil untuk efek politik uang, tetapi karena untuk lolos hanya butuh 1,6 persen, jadi 10,2% itu besar sekali untuk caleg melakukan operasi politik uang. Makanya kemudian saya kasih sub-judulnya adalah "personal network and winning margin".
Temuan Anda, Jawa Tengah adalah provinsi yang party ID-nya tinggi dan politik uang tinggi. Apa sebab dan faktornya?
Teorinya itu yang saya jelaskan di atas tadi. Jadi untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, semuanya itu adalah kedekatan terhadap partai yang menjelaskan dan sistem proporsional terbuka yang membuat caleg dalam satu partai baku bunuh untuk mengalahkan teman separtainya agar lolos ke Senayan. Dan itu bukan hanya Jateng.
Bagaimana cara-cara kerja broker untuk pembelian suara pemilih?
Secara umum seperti tadi saya bilang, personal loyalist model yang menjelaskan bagaimana mekanisme politik uang itu didistribusikan. Jadi pertama adalah caleg melakukan proses rekrutmen timses. Timses itu dimulai dari keluarga terdekat. Jadi sistemnya itu kayak struktur piramida, yang paling atas adalah keluarga. Keluarga ini direkrut oleh caleg, karena dianggap lebih loyal dan tidak mata duitan. Umumnya jejaring kinship atau famili ini diartikan luas. Dan keluarga ini semacam manager campaign-nya di tingkat paling atas. Kemudian, di bawahnya mulai dibikin struktur timses di tingkat dapil, terus di bawahnya lagi ada koordinator kabupaten, karena tiap dapil umumnya terdiri dari kabupaten/kota. Kemudian dibikin koordinator keematan di masing-masing kota/kabupaten, di bawahnya lagi ada koordinator desa/kelurahan, koordinator RT, lalu koordinator TPS.
Pertanyaannya, bagaimana rekrutmen timses jika jumlah keluarganya terbatas? Jumlah keluarga yang terbatas itu hanya ada di level atas. Ketika sudah masuk pada tingkat grass root broker atau timses lapangan, makin jauh itu, jarak antara broker akar rumput dengan calegnya, karena dia mengandalkan struktur yang dia bentuk untuk mencari timses tadi. Timses keluarga, kemudian jaringan pertemanan, jaringan suku, jaringan agama, jaringan masjid, jaringan gereja, itu kan semuanya merujuk pada teori personal network, dan itu beyond partai politik.
Jadi struktur timses tadi itu lagi-lagi mengandalkan jaringan sosial personal yang dimiliki oeh si caleg, dalam beberapa kasus, extended broker yang di bawah, karena jaraknya jauh di bawah, ikatan personalnya dengan caleg makin jauh. Makanya muncul dengan istilah problem agency last, semakin ke bawah semakin susah dikontrol jaringan broker di tingkat bawah. Yang bisa dikontrol adalah orang-orang terdekat yang ada di atas. Nah, lagi-lagi itu menjelaskan kelebihan dan kelemahan teori personal loyalist model, karena di tingkat bawah mau tidak mau caleg dihadapkan pada kebutuhan menguatkan armada di tingkat broker, sedangkan armada yang tersedia dekat dengan dirinya tidak banyak.
Nah, pada titik itu ada agency last yang melakukan misalnya dia terima uang, barang yang seharusnya dia distribusikan ke pemilih tetapi diambil broker di tingkat grass root. Itulah yang menjelaskan kenapa politik uang itu banyak bocor ke swing voters, karena awalnya mau menarget pemilih yang dekat dengan caleg, tetapi secara absolut banyak swing voters yang menerima politik uang. Tapi lagi-lagi, meskipun bocor di sana-sini, politisi tetap insist melakukan praktik politik uang, dan mereka mengakui itu dalam banyak wawancara dengan saya.
Kalau ada 600.000 amplop yang dibagi, kebanyakan politisi merasa kalau dapat sepertiga suara sudah bagus, dua pertiganya dianggap uang sedekah. Ada spekulatif. Tetapi sepertiga dari 600.000 itu sudah lebih dari cukup untuk lolos ke Senayan. Apalagi kalau di Jawa uang yang diberikan rata-rata itu kecil, Rp 20 ribu sampai Rp 30 ribu. Kalau di luar Jawa yang jauh atau geografisnya susah, itu harga pemilih untuk bisa menerima politik uangnya semakin tinggi. Tetapi operasinya kira-kira begitu. Jadi, saya bedakan satu proses rekrutmen broker oleh caleg, kemudian proses rekrutmen pemilih oleh broker, ada dua tingkat di situ.
Nah, proses retrutmen pemilih oleh timses, itu lagi-lagi pakai jaringan personal. Jadi timses kalau sudah di-assign untuk membantu caleg, dia akan memprioritaskan keluarganya dulu, karena paling mudah dipengaruhi. Setelah keluarga intinya, dia masuk ke keluarga besarnya. Tapi rata-rata timses itu kan diberi tugas untuk mencari pemilih yang banyak dan luas, yang tidak bisa ditutupi dengan anggota keluarganya sendiri. Nah, lagi-lagi di situ, semakin luas target suara yang diberikan, semakin besar bocornya. Karena kalau sudah melampaui dari keluarga besarnya, melampaui dari jaringan sosial timses, besar juga rent seeking-nya. Pemilih melakukan rent seeking juga, dia terima duitnya, memilih urusan lain. Secara umum praktek rent seeking itu terjadi beberapa lapis, pertama hubungan rent seeking terjadi antara caleg dengan broker, broker pun ada broker tingkat inti, dan broker grass root, kemudian antara broker dengan pemilih.
Beberapa caleg yang saya wawancarai yang kebetulan sukses, rata-rata menyimpulkan kesuksesan atau kegagalan caleg 2014 itu pada titik seberapa tepat memilih broker, dan yang kedua seberapa kontrol itu dijalankan caleg kepada broker. Semakin tepat pilihan terhadap broker, semakin besar peluang si caleg untuk menang. Tepat-tidaknya pemilihan broker didasarkan pada kedekatan broker dengan si caleg. Jadi kalau misalnya pemilihan brokernya tidak tepat, maka banyak uang yang mubazir, terbuang percuma, semakin kecil juga peluangnya untuk menang.
Tetapi sehebat-hebatnya caleg melakukan operasi politik uang, mereka juga mengakui cara semacam ini memiliki kelemahan yaitu tadi, semakin luas ambisi untuk menarget pemilih di luar personal network yang mereka punya, maka semakin besar uangnya. Makanya politisi yang pintar, mereka meng-assign brokernya tidak lebih dari 20 orang. Jadi satu broker diminta untuk mencari sampai 20 orang saja. Jadi nggak dikasih target yang terlalu ambisius, karena kalau dikasih target yang terlalu ambisius, bocornya semakin besar. Jadi 1-20 orang, itu broker paling mengandalkan keluarganya. Jadi semakin kecil target broker untuk menarget pemilih, maka semakin besar armada broker yang medeka butuhkan.
Jadi kalau hanya 20 maksimal target yang diberikan kepada setiap broker, berarti si calegnya butuh ratusan hingga ribuan broker untuk memastikan politik uangnya betuk-betul terdistribusi di lapangan.
Berapa besar sebenarnya biaya jadi caleg, dan bagaimana pandangannya untuk Pemilu 2019 nanti? Burhanuddin Muhtadi bicara lebih banyak di laman berikutnya...