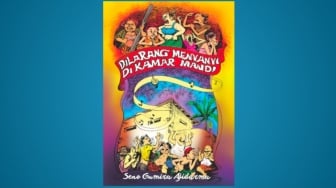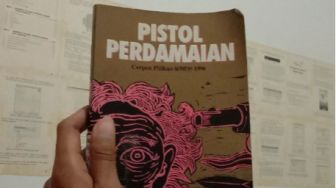Suara.com - Anak Proklamator Kemerdekaan Indonesia Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri dituduh menistakan agama lantaran membuat dan membacakan puisi berjudul ‘Ibu Indonesia’. Sampai sekarang laporan itu belum dicabut dari Markas Besar Kepolisian Indonesia (Mabes Polri) dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).
Dalam puisinya itu, Sukma menyindir azan dan berbagai simbol Islam, dan membandingkan dengan kidung. Kelompok berlatar Islam menilai, Sukma menistakan Agama.
Namun kelompok pro kebebasan berekspresi menilai puisi Sukmawati bagian dari kebebasan mengungkapkan pendapat. Sehingga tidak bisa dianggap melanggar hukum dengan alasan penistaan agama.
Lalu bagaimana dari sudut pandang sastra? Rektor Institut Kesenian Jakarta yang juga sastrawan, Seno Gumira Ajidarma berkomentar. Menurut dia, puisi Sukma sudah jadi korban komoditas politik.
Suara.com berbincang dengan lelaki gondrong itu di ruangan kerjanya di Rektorat IKJ Lantai 2, Jakarta Pusat pekan lalu. Mengenakan kaos lengan panjang warna hitam, dia bercerita dengan santai mulai dari puisi ‘Ibu Indonesia’ sampai kesusasteraan Indonesia.
Pertanyaan mendasar, apakah ‘Ibu Indonesia’ bisa disebut sebagai puisi? Jika ya, apakah laporan penistaan agama itu sudah mengkriminalisasi sastra?
Berikut wawancara lengkap suara.com dengan Seno:
Apakah Anda sudah membaca habis puisi ‘Ibu Indonesia’ Sukmawati? Menurut Anda, apakah kata, larik, bait, bunyi, dan makna dalam tulisan itu bisa dikategorikan sebagai puisi?
Ya, sebetulnya gini ya. Ada format puisi, tadi itu, larik, bait, bunyi, dan makna. Tapi kalau formatnya seperti itu, apakah pasti puisi? Ya belum tentu.
Puisi itu pasti puitik, dan puitik itu tidak bisa lahir dari sebuah rumus. Itu jawabannya.
Jadi bisa dikatakan puisi Sukmawati belum tentu pasti puisi ya?
Jawabannya itu saja, karena sastra itu urusannya bukan itu. Bukan ini sastra apa bukan. Capek deh, sibuk amat sih sastra apa bukan gitu. Terus kalau bukan, apakah dosa? Ya kalau belum bisa bikin, boleh saja toh?
Atau orang bilang ini bukan puisi, tapi sampah. Ya suka-suka lah.
Tapi kalau dari segi teknis, format, bentuk, ya puisi itu ada begitunya, format, larik, dan bait. Tetapi itu puisi konvensional. Kalau puisi modern, puisi kontemporer kadang-kadang kertas putih saja, itu puisi. Jadi diskusi sia-sia, sastra apa bukan.
Sukmawati mengklaim tulisannya adalah puisi, lantas, bagaimana cara memperlakukan puisi itu dengan segala kontroversinya? Apakah seharusnya harus dikritik memakai kritik sastra, alih-alih dilaporkan ke polisi?
Dibaca dengar terbuka, ya dibaca, baca saja.
Dibaca dengan terbuka, karena puisi itu kan ungkapan jiwa. Ya kalau jiwa orang tertutup nggak akan baca puisi dengan indah.
Dibaca dengan kritis, apa sih kritis? Mampu menjelaskan. Kalau belum mampu menjelaskan, dia belum mampu membaca puisi. Kalau belum mampu ya jangan bersikap seperti bisa menilai, apalagi menghakimi.
Kalau belum bisa membaca dengan kritis, berarti jangan menghakimi?
Ya, makanya saya belum memeriksa (puisi Sukmawati). Tapi, pokoknya puisi yang manapun tidak bisa dibaca dengan jiwa yang tertutup, harus terbuka.
Setelah itu kalau sudah terbuka, baca dengan kritis, kritis itu bukan mencari kejelekan, kritis adalah kemampuan menjelaskan. Kalau belum mampu, bisa dinilai sendiri, seberapa haknya menilai.
Apakah Anda sudah baca pusi Sukmawati itu?
Sebagian saja, ya yang dipermasalahkan itu. Dan itu jawaban Gus Mus sudah benar. Itu kesan, kesan ya boleh-boleh saja, dan tidak menilai isi ya boleh-boleh aja. Tapi menilai isi pun itu tidak harus dianggap menghina.
Jadi kita itu kalau jiwa tertutup, maka pengetahuan ikut tertutup. Kalau jiwa terbuka, pengetahuan bisa melihat masalah dengan jelas, dengan terang, dengan cahaya terang. Jadi kalau niatnya sudah jelek gitu ya, ya sudah tamat di situ sebetulnya. Sudah tidak perlu ditanggapi.
Apakah suatu produk sastra bisa dinilai, terlepas dari lingkup kesusasteraannya seperti yang terjadi pada karya Sukmawati, yang justru ditafsirkan sepihak oleh kelompok-kelompok politik?
Kalau yang namanya politis, itu artinya dia sudah berterus terang tentang sesuatu yang bertujuan. Jadi dia itu nggak usah lihat puisi. Kartun, drama, sandiwara, iklan, apapun lah, pokoknya bisa dipakai sebagai komoditas politik. Apapun bisa mengenalkan siapa saya, siapa kami, itu yang disebut politik identitas.
Makanya yang ngomong seperti itu tidak perlu lulus S1 sastra.
Apakah Anda menilai pelaporan puisi Sukmawati itu sebagai kriminalisasi karya sastra?
Saya lebih suka bilang politisasi.
Publik justru mudah terprovokasi ketika puisi Sukmawati itu tersebar di Medsos di olah-olah oleh kelompok tertentu, bagaimana menurut Anda?
Yang disebut orang awam, ya begitu. Awam adalah orang-orang yang jika tidak diberi tuntunan akan tersesat dan akan tetap tersesat ketika diberi tuntunan yang keliru.
Ini adalah masalah pendidikan. Mereka kan nggak sekolah perguruan tinggi, ya dari SD.
Kalau pantun itu kebudayaan kita, dari SD harus dikenalkan, pantun itu apa. Pantun itu juga bisa untuk mengkritik, bisa untuk mengungkap, itu sarana dialog. Jadi ya kalau pantun balas pantun dong.
Apakah bisa orang-orang itu bikin pantun juga, yang katakan lah membalas Sukma gitu, nggak bisa. Kalau nggak bisa kenapa kenapa menilai?
Saya tidak mengatakan itu bagus ya, tapi ya proporsional lah. Ini nggak proporsional, baca puisi kok ke pengadilan. Kalau puisi dibalas puisi, itu lebh produktif.
Tapi yang paling penting dari saya, yang pertama adalah ilmu dasar pendidikan umum, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi. Kalau sejak TK kita sudah dibiasakan untuk menerima pendapat orang lain, merasa kaya dengan perbedaan, maka ini semua bisa mengundang kritik, tapi kritik yang sehat, yang produktif, ya kan.
Misalnya, ini memang seperti puisi, tapi belum puitis, misalnya begitu, itu kan sehat. Atau orang menjelaskan ini jenis puisi kritik sosial, boleh dong.
Jadi terbuka, dialog itu proporsional. Menghina agama itu apanya? Gus Mus saja sudah membela seperti itu, itu yang Kyai. Mungkin dia ngomong suara, serak, bukan isi, itu jelas kan. Kritis sekali sebetulnya, cuma menjelaskan.
Apakah Anda bisa ceritakan sejarah sastra dalam agama, baik pada tradisi Abrahamik maupun non-Abrahamik? Apa selalu selaras, ataukah sastra bisa mengkritik penerapan agama oleh penganutnya?
Saya bukan ahli sastra. Saya tidak tahu, tapi saya kira ada. Rendra itu mengkritik juga, tetapi dia tidak mengkritik agama, dia mengkritik ahli agama yang tidak peduli keadilan sosial.
Siapa yang mengkritik agama? Kecuali Nietzsche. Dan yang dikritik bukan agama toh, yang dikritik adalah bagaimana agama diperlakukan. Agama itu spiritual, tapi jadi politik di sini, untuk “kamu agama itu, lain dengan agama saya, itu kan politis”.
Jadi puisi Sukwa bisa ‘dibantai’, tapi secara kritis secara sastra. Itu menarik, ketimbang menuduh menghina agama.
Bisa Anda cerita soal Darmogandul, Gatoloco, cerpen Ki Panji Kusmin, yang sama-sama dinilai mengkritik agama, dan diklaim melecehkan Islam di Indonesia?
Saya tidak ahli soal itu, tetapi yang saja baca reaksi atau tanggapan terhadap Islam yang mulai mendominasi tradisi spiritual rakyat setempat, orang Jawa lah gitu. Ya nggak apa-apa.
Apakah puisi Sukma sama posisinya dengan kesemua karya sastra itu dalam konteksnya?
Oh tidak, beda sekali.
Jadi itu masalah kekuasaan sebetulnya, mungkin merasa begitu, bisa. Tapi saya kira tidak terbandingkan ya. Dia mungkin merasa gitu, mungkin ada miripnya juga ya.
Tapi saya kira perlu lebih banyak argumen untuk membandingkannya. Tapi saya kira kritik sosial lah itu, ketimbang kritik agama. Kritik sosial iya. Artinya kenapa sih orang merasa dirinya paling benar. Bukan kritik agama.
Yang bisa kritik agama ya orang agama sendiri, Gus Dus, bisa itu. Kalau bukan orang agama kayak saya ini apa haknya kritik agama? Paham agama juga tidak. Beragama nggak cukup ya, harus mengerti ilmu agama.
Itu disebut politik identitas, mencari korban-korban untuk memunculkan dirinya. Jadi bukan soal puisi, bukan soal kartun, bukan soal drama, film, bukan, soal dia sendiri.
Bagaimana Anda menilai kesadaran kesusateraan publik maupun kaum elite di Indonesia?
Katakan lah sudah berkembang, gitu aja. Buktinya, dulu nggak ada klub buku, sekarang banyak. Klub buku yang isinya diskusi buku, kemudian buku atau membaca itu bagian dari lifestyle kan, orang bawa buku itu senang.
Kalau belum baca buku apa malu? Buku sudah jadi fashion, itu perkembangan bagus. Bergaya kalau pakai buku, bergaya baca, itu perkembangan. Perkara apa buku yang diomongin, cuma lucu doang itu soal lain.
Kan di situ dulu, dari itu orang akan jenuh dengan hiburan dan akan mencari yang lebih bermakna. Dan sekarang diskusi intelektual dan masalah kritik sosial sudah jauh lebih bagus.
Buktinya, penerbitan dulu kan cuma ada Gramedia, Sinar Harapan, Gunung Agung, Tiga, Grafiti. Sekarang terbitan indie jumlahnya beratus-ratus, ditiap kota berpuluh-puluh, perkembangan bagus.
Jadi tak perlu dikhawatirkan buku digital?
Sama sekali tidak. Loh di digital isinya apa? Semua buku yang ada didigital. Malah gratis, kan nggak usah tebang pohon. Buku kan lertasnya dari pohon, kulit kayu, bagus.
Bagaimana perkembangan kebudayaan di tanah air sekarang menurut Anda? Apakah dalam perubahan budaya selalu ada perlawanan?
Kebudayaan semua. Pajak juga kebudayaan, ekonomi juga kebudayaan, perang juga kebudayaan. Ya dia akan tumbuh dengan rumus seperti itu.
Misalnya aku anggap dangdut murahan, dia akan melawan. Pejabat dangdut, semua dangdut, melawan. Nggak selalu makin lama, makin naik, nggak gitu. Tapi selalu ada, apa istilahnya itu ya, ada suatu griliya semiotik. Ini lawan ini, ini lawan itu.
Jadi sekarang ini orang yang nggak ngerti sastra mau menggulingkan kuasa sastra dengan ancaman-ancaman? Ya nggak bisa.
Ya itu perlawanan orang-orang yang nggak tahu, kalau sastra kan nggak ngerti dia, kan ditertawai orang. Demo saja.
Biografi Seno Gumira Ajidarma
Seno Gumira Ajidarma lahir di Boston, Amerika Serikat, 19 Juni 1958. Dia adalah penulis dari generasi baru di sastra Indonesia. Beberapa buku karyanya adalah ‘Atas Nama Malam, Wisanggeni’, ‘Sepotong Senja untuk Pacarku’, ‘Biola tak Berdawai’, ‘Kitab Omong Kosong’, ‘Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi’, dan ‘Negeri Senja’.
Seno menyelesaikan gelar sarjananya di Fakultas Film & Televisi, Institut Kesenian Jakarta, lalu Magister Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia, dan gelar Doktor Ilmu Sastra di kampus yang sama.
Sekarang Seno menjadi Rektor di Institut Kesenian Jakarta sejak 2016 dan tetap menjadi dosen di Fakultas Film dan Televisi.