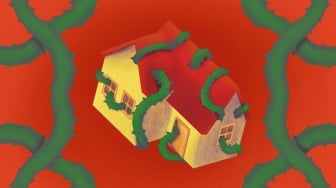Suara.com - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi orang yang ke-97 yang berurusan dengan delik penodaan agama. Ke-96 orang lainnya menjadi terlapor penodaan agama di kurun waktu 1965 sampai 2017.
Pekan lalu organisasi yang fokus memperhatikan masalah hak asasi manusia, demokrasi dan keberagaman, Setara Institut membebeberkan kajian ilmiah tentang persoalan itu. Mereka menemukan banyak masalah di penerapan kasus penodaan agama, terlepas dari kasus yang menjerat Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu.
Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dengan menganalisa dokumen, mengolah data skunder, dan berdiskusi dengan beberapa ahli dan peneliti.
Seretan nama yang dituduh menista agama di antaranya, Lia Eden, Abdul Rahman, eks Pimpinan Gafatar Ahmad Musadeq, Hans Bague Jassin, Arswendo Atmowiloto, Sumardin Tapaya, Yusman Roy, sampai Pimpinan Sekte Kiamat Mangapin Sibuea. Nama-nama itu yang heboh di media, sama dengan Ahok. Mereka dilaporkan 3 kelompok dan 148 perorangan.
Konteks kasus penodaan agama yang terjadi selama ini palimg banyak dilatar belakangi polemik pemahaman keagamaan, polemik kebebasan berpendapat dan berekspresi dan polemik gerakan keagamaan baru atau aliran kepercayaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, ini dia pangkal masalahnya. UU ini telah diturunkan ke UU Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan UU pasal Informasi dan Transaksi Elektronik 28 ayat 2. Ini juga yang menyebabkan dari 97 kasus penodaan agama selama 1965 sampai 2017, 9 kasus terjadi sebelum era reformasi (1998) dan sesudah reformasi sebanyak 88 kasus penodaan agama.
Sekilas delik penodaan agama bertujuan mulia, namun harus dilihat dari sudut pandang yang jernih dan rasional, begitu kata Ismail Hasani. Ismail Hasani adalah pendiri Setara Institut dan memimpin riset ‘Rezem Penodaan Agama 1965-2017’. Pakar hukum itu sejak awal reformasi banyak berkutat di isu toleransi, terorisme dan kebebasan berkeyakinan. Dia pernah meneliti soal gerakan organisasi radikal di Indonesia, bahkan hingga kini.
Suara.com berbincang dengan Ismail di ruang kerjanya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pekan lalu. Dia banyak menganalisa delik penodaan agama lebih banyak dipakai untuk kepentingan ‘jahat’ seseorang. Alih-alih bertujuan menjaga kesucian dan toleransi beragama, delik penodaan agama dipakai untuk kepentingan politik, bahkan pihak swasta untuk menjatuhkan lawan bisnisnya.
Paling hangat, delik penodaan agama menjerat Ahok. Kasus ini banyak turunannya. Mulai dari demo ‘bela Islam’ ormas yang berkali-kali, sampai pemerintah niat membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai merongrong Pancasila.

Namun yang pasti, yang paling menakutkan di balik kasus Ahok dan demo itu adalah semakin tumbuhnya organisasi radikal di Indonesia. Kata Ismai, Presiden Joko Widodo pantas untuk waspada melihat dituasi saat ini.
Lalu, apa buktinya Indonesia lagi rawan organisasi radikal? Bagaimana cara mencegahnya?
Simak wawancara suara.com dengan Ismail Hasani berikut ini:
Setara Institut mencatat hampir 100 ‘korban’ delik penodaan agama sejak 1965 sampai 2017. Bagaimana membaca situasi itu?
Sebanyak 88 kasus penodaan agama terjadi setelah reformasi, sementara 9 kasus terjadi pada reformasi. Artinya pertama, bahwa dalam catatan kami dalam 10 tahun terakhir ada desain politik penyeragaman atas nama agama dan moralitas. Orang-orang diseragamkan atasnama agama dan moral itu. Isu penodaan agama dijadikan sebagai alat penundukan.
Transisi politik dalam teori selalu melahirkan dua kecenderungan. Pertama, kembalinya kekuatan lama ke panggung politik baru. Kedua, kokohnya kekuatan politik baru dengan mengusung nilai-nilai baru. Tapi khusus di Indonesia, munculnya kekuatan ketiga.
Preseden ini tidak terjadi di berbagai negara yang mengalami proses transisi demokrasi. Kekuatan ketiga ini memanfaatkan instrument demokrasi, tetapi untuk mempromosikan nilai-nilai yang antidemokrasi. Kekuatan ketiga itu bisa ada di tubuh parlemen, partai politik, ormas dan sebagainya.

Artinya 10 tahun kemarin adalah masa penguatan kelompok intoleran…
Betul, dalam 10 tahun terakhir kelompok ini lah yang menguasai ruang publik terkait kebebasan beragama dan berekspresi. Karena itu dengan mudah orang dikriminalisasi seseorang dengan tuduhan penodaan agama.
Lalu kenapa kasus ini meningkat? Karena kekuatan ketiga ini kesulitan mencari kapital politik baru sebagai alat untuk memperluas konstituennya. Makanya kelompok yang digarap oleh kelompok ini menggunakan instrument agama dengan menjadikan berbagai isu yang berhubungan dengan agama dan bisa menyulut. Sehingga ini sama dengan menggunakan umat sebagai alat politik.
Karena itu buat saya, kriminalisi penodaan agama dan aliran kepercayaan, persoalan menunggu giliran saja.
Di masa lalu (orde baru) orientasi politik Indonesia koeksistensi, kerukunan, kedamaian, ketertiban. Atasnama kerukunan represi dijalankan, memang tidak juga suasananya. Sebaliknya saat ini di mana orang bisa merasakan kebebasan berpendapat dan sebagainya, tapi orang dengan mudah menggunakan demokrasi untuk menundukan pihak yang dia tidak kehendaki keberadaannya.
Soal peristiwa yang diikuti dengan tekanan massa dan tidak diikuti tekanan massa. Sejatinya dalam UU PNPS itu, di pasal hukum acara, ketika ada orang yang diduga melakukan penodaan harus diperingari sebelumnya. Tapi dengan tekanan massa, langkah ini hampir tidak dilalui.

Kelompok pro hak asasi manusia mengkritik putusan penjara 2 tahun terhadap Ahok. Bagaimana publik seharusnya membaca putusan itu dengan pikiran jernih tanpa politis, terutama memahami soal pasal penodaan agama?
Saya harus mengatakan, putusan pengadilan terhadap Ahok akan memberikan preseden buruk bagi Indonesia. Ini terlepas dari Pilkada. Karena itu bukan hanya Ahok, tapi semua orang berpotensi mengalami hal yang sama. Karakter dari delik penodaan agama yang multitafsir dan bias rentan dipolitisasi untuk tujuan politik. Pasal ini digunakan sebagai alat pendudukan.
Institusi peradilan bisa menerapkan pasal ini lebih ketat dan berhati-hati. Pasal ini tidak serta merta begitu saja dibawa ke proses yudisial atau peradilan. Untuk jangka panjang, delik penodaan agama ini harus ditarik dari pembahasan Rancangan RUU KUHP.
Mahkamah Konstitusi sebenarnya menilai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama ini bermasalah. Tapi karena belum ada undang-undang baru yang menggantikannya, maka masih dinilai konstitusional. Pemerintah harus mengambil langkah untuk membuat UU baru. Tapi sampai hari ini langkah itu belum dilakukan.
Apakah kebanyakan kasus ini dilatarbelakangi politik?
Tidak, sebagian besar kasus sepele, dan dilatarbelakangi adanya konflik dan polemik. UU ini tidak steril dalam proses delik yang bisa diverifikasi sebagai melanggar. Yang paling penting bukan hanya dengan isu agama tapi tantangan ke depan, mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat dan jug keagamaan.
Kontestasi antar kelompok keagamaan juga bisa menggunakan alasan dalil penodaan beragama.
Apa yang perlu dipahami masyarakat tentang pasal penodaan ini?
Pertama, delik penodaan agama ini telah efektif menjadi alat penundukan bagi pihak-pihak yang berkonflik baik dalam konteks ketegangan berpolitik, atau juga konflik personal.
Dalam riset kami, semua latarnya konflik, kecuali 21 kasus yang diselesaikan di luar pengadilan, ternyata alat penundukan itu tidak efektif.
Jadi bisa dibayangkan delik penodaan agama ini bisa dipakai juga untuk kepentingan bisnis. Ini keluar dari genus sejarah-sejarah tentang penodaan agama yang seharusnya untuk melindungi kesucian agama.
Sekalipun dalam konteks hak asasi manusia, penodaan agama tidak dikenal. Dalam HAM, yang harus dibela adalah personal manusia, bukan agama itu sendiri.
Kedua, tafsir konteks ini kerumunan massa jadi legitimasi pembenar institusi penegak hukum. Sehingga persoalan selain ada pada delik penodaan agama itu sendiri, juga ada pada institusi peradilan.

Organisasi keagamaan subur sejak era reformasi. Bagaimana pergerakan mereka saai ini? Apakah ada penurunan aktivitas atau ada tren penaikan?
Aksi-aksi kemarin sudah bisa dijadikan indikator. Misal di Aksi 212, mereka bukan hanya anggota FPI saja, tapi masyarakat muslim, NU dan Muhammadiyah. Itu aksi betulan, bahkan yang mengadukan Ahok saja seorang Muhammadiyah. Mereka ikut demo karena merasa rentan dan diprovokasi identitasnya.
Pertanyaan penting, mengapa aksi itu bisa besar? Karena dalam 10 tahun terakhir, kelompok ini bekerja sangat efektif memberikan pengaruh dan pandangan keagamaan yang ‘berbeda’. Mereka berkembang sangat pesat. Ditambah, riset kami tahun 2010 mengklaim anggota FPI sebanyak 5 juta.
Kemampuan organisasi ini mempenetrasi kepada masyarakat dan memberikan jawab aktual yang dibutuhkan masyarakat.
FPI hadir di gang kecil dan hadir di tengah persoalan masyarakat. Jadi jangan kaget kalau mereka mendapatkan tempat di hati masyarakat. Apalagi yang digoreng adalah isu keagamaan. Jadi jawabannya, kelompok itu semakin membesar.
Ketegangan berdasarkan isu agama menjadi medium recovery kelompok intoleran dan radikal, pada kasus tertentu itu menjadi recovery kelompok teroris. Seperti pada aksi 212 ada Jamaah Anshorus Syariah yang ikut aksi.
(Catatan: Jamaah Ansharusy Syariah atau JAS adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Organisasi ini merupakan pecahan dari JAT. JAS didirikan tahun 2014 di Bekasi. Pendirian JAS dilatarbelakangi karena merespon kondisi perbedaan pendapat yang terjadi pada anggota JAT dalam menyikapi fenomena klaim Khilafah Islamiyah oleh ISIS. Amir JAT, Abu Bakar Baasyir telah memutuskan bahwa seluruh anggota JAT yang menolak klaim Khilafah (ISIS) itu harus keluar dari Jamaah dan tidak lagi berada dalam ikatan JAT)
Mengapa ini digunakan medium recovery? Karena orang radikal itu selalu butuh tempaan. Mundur ke belakang, tahun 1999 kelompok ini berkembang cepat karena ada konflik Ambon dan Poso. Radikalisasinya tumbuh melihat saling adu antar kelompok keagamaan.