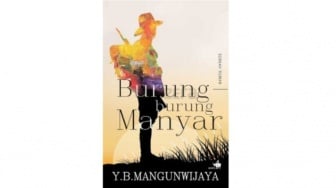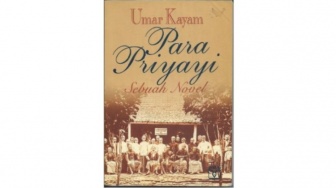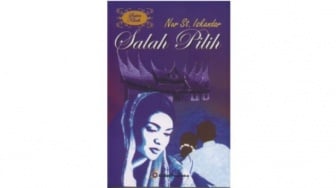Suara.com - Aku Ingin
aku ingin mencintaimu dengan sederhana
dengan kata yang tak pernah diucapkan
kayu kepada api yang menjadikannya abu.
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana
dengan isyarat yang tak sempat disampaikan
awan kepada hujan yang menjadikannya tiada
Itu adalah salah satu puisi yang sangat terkenal ciptaan Sapardi Djoko Damono. Puisi itu mendunia dan sering dijadikan lirik untuk musikalisasi puisi. Lirik dalam puisi itu sering dijadikan bait undangan pernikahan karena dinilai romantis.
Sapardi memang besar karena sajak-sajaknya yang bermakna dan romantis. Sejak 1987, puisinya sering diambil untuk dijadikan lirik musik. Karya pertamanya yang dijadikan musikalisasi puisi adalah “Aku Ingin”.
“Puisi ini jadi beberapa menit, cuma 15 menitan,” kata Sapardi.
Bahkan tahun 1991, lirik puisi “Aku Ingin” diaransemen ulang oleh musisi Dwiki untuk kepentingan proyek soundtrack album film ‘Cinta dalam Sepotong Roti’ 1991.
Di tengah usianya yang ke- 76 tahun, sang pujangga masih aktif di dunia kesusatraan. Dia masih aktif menulis berbagai buku, seperti novel dan puisi. Terakhir, Sapardi menerbitkan buku ‘Bilang Begini, Maksudnya Begitu’, ‘Hujan Bulan Juni’, dan ‘Trilogi Soekram’. Empat buku lainnya, segera terbit tahun ini.
Suara.com menemui Guru Besar Institut Kesenian Jakarta itu di Taman Ismail Marzuki, Cikini pekan lalu. Dia masih terlihat bugar dan teliti melihat setiap kalimat di kertas. Terbukti beberapa kali Sapardi mengoreksi hasil tulisan mahasiswanya di kampus.
Sapardi, salah satu sastrawan Indonesia yang mendunia, namun lelaki yang piawai bicara banyak bahasa asing itu tetap rendah hati dan apa adanya. Bahkan sastrawan yang banyak menterjemahkan karya sastra asing itu merahasiakan jumlah bahasa yang dia kuasai.
“Rahasia, waktu sekolah saya belajar 4 bahasa. Setelah itu terus belajar. Sekarang lagi terjemahkan buku sastra dari Rusia,” kata Sapardi.
Sapardi baru saja memperoleh penghargaan bergengsi Habibie Award 2016 di bidang kebudayaan karena dedikasinya dengan dunia kesusastraan Indonesia. Karya Sapardi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Hindi, Jepang, Cina, Prancis, Inggis, dan lainnya.
Dalam perbincangan dengan suara.com, Sapardi banyak mengupas soal pendidikan sastra masa kini. Dia juga menganalisa dunia sastra saat ini di tengah era digital dan media sosial.
Berikut wawancara lengkapnya:
Sebagai sastrawan, Anda mendapatkan penghargaa Habibie Award 2016. Apa hubungan puisi dengan teknologi?
Taufiq Ismail dulu juga dapat, bukan saya saja. Kadang sejarawan juga dapat. Tahun 1996 lalu, saat Habibie menjadi Menteri Riset dan Teknologi, saya sempat katakana kalau sastra itu sebenarnya juga teknologi, yaitu teknologi sastra. Saya pernah baca kalau aksara itu hasil dari teknologi. Mulai dari tulisan menjadi gambar, lalu diproses menjadi teknologi layar sentuh, itu adalah teknologi seni.
Saat ini sastra sangat tergantung dengan teknologi karena menulis berdasarkan teknologi yang kita kembangkan. Dulu menulis dengan pensil, lalu berkembang pembuatan komputer, dengan itu sekarang ini kita menulis. Jadi sastra saat ini tergantung dengan teknologi.
Bahkan bisa saja nanti puisi dikembangkan dalam bentuk gambar dia atau juga gambar bergerak. Dasarnya aksara atau huruf-huruf itu kan gambar. Jadi kalau ingin mengembangkan cyber sastra juga bisa, asalkan bisa menguasai teknologi secanggih-canggihnya.
Saat ini kalau tidak menguasi teknologi dan litrasi modern, tidak akan bisa. Sastrawan modern harus akrab dengan teknologi. Kalau tidak, karyanya tidak ada yang baca.
Apakah ada sisi negatif dari perkembangan teknologi untuk sastra?
Nggak ada. Kalau ada sisi negatifnya, ngapain ciptakan teknologi? Teknologi mempermudah penciptaan karya kesusastraan. Maka harus terus dikembangkan. Jadi dulu kita kirim surat, sekarang dengan menelepon. Jadi ini alat.
Tapi minat baca buku jadi kurang. Sebab orang lebih suka menghabiskan waktu dengan ponsel pintarnya…
Gundul mu! Di toko buku, berapa ratus buku tiap bulan terbit? Kalau tidak ada yang baca, ngapain dijual sebanyak itu. Mengapa begitu banyak penerbit di Indonesia? Bahkan toko buku tiap bulan menerbitkan 50 judul buku. Siapa yang mau baca itu? Berapa penjualan buku.
Cek saja Gramedia, ada berapa ratus judul yang keluar tiap pekan? Ini tidak pernah ada dalam sejarah sastra di Indonesia sebelumnya. Nah kalau nyatanya begitu, yang baca buku itu siapa? Memang setan?
Buku-buku yang terbit makin laku saat diunggah di media sosial. Mereka yang melihat akan beli karena mendapat tanggapan positif.
Jadi minat baca mana yang turun? Anda bayangkan anak-anak sekarang baca buku Harry Potter yang tebalnya sampai ribuan halaman hanya dibaca dalam sehari. Kenyataan gitu.
Saat ini kalau kita berpegang keyakinan kalau sastra itu adalah buku, itu salah. Sastra bukan buku saat ini, bagaimana kalau And abaca sajak Rendra di komputer, apa itu bukan sastra? Jika nulis sajak di blog, apa itu bukan sastra? Saat Sastra tidak mengenal medium saat ini.
Jadi buku dan teknologi saling jalan. Buku dihidupkan dengan intenet, internet dihidupkan dengan buku. Sebab internet nggak akan ada isinya kalau tidak ada buku. Buku tidak akan laku kalau nggak ada internet.
Kalau kita tetap berpikir sastra adalah buku, maka anak-anak di Pupua sana tidak akan mengenal tulisan. Mereka lebih baik diberikan komputer dan akses internet agar bisa baca berbagai hal. Kalau hanya mengirim buku, maka jumlah dan akses akan terbatas.
Sekarang penyair modern membuat karya karena membaca di internet. Mereka belajar buku-buku orang asing dari internet, jadi lebih pintar.
Medium kesusastraan tidak dibatasi, namun apakah penulis blog atau juga di media sosial bisa disebut sebagai penulis sastra?
Jadi penyebutan penulis harus menulis buku, ketinggalan sekali. Penulis tidak harus menulis menjadi buku. Kan jadi e-book bisa, audio pun bisa. Jaman dulu, sastra juga bukan buku. Dongeng pun sastra.
Apakah syarat yang harus dipenuhi agar sebuah tulisan bisa dikatakan sastra?
Sejak zaman Plato, sudah ada sastra. Kata dia, sastra adalah hasil peniruan atau gambaran dari kenyataan. Karya sastra harus merupakan peneladanan alam semesta dan sekaligus model kenyataan. Dan masih banyak yang mendefenisikan sastra, jadi tidak ada syarat baku, bebas saja. Asal jelas apa yang dia sampaikan. Misalnya sajak, cerita, atau juga novel. Semua orang punya pandangan sendiri.