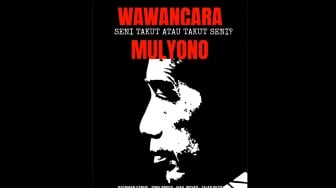Suara.com - Sepanjang tahun 2015 sampai, Minggu (11/10/2015) kemarin ada 137 pesawat yang kecelakaan di berbagai negara di dunia. Pesawat itu mulai dari jenis Boeing, Airbus, bahkan Cessna.
Khusus di Indonesia ada 6 pesawat kecelakaan pesawat. Keenam pesawat itu adalah Trigana Air jenis DHC-6-300 Twin Otter (11 Januari 2015), Deraya Air Taxi jenis British Aerospace ATP-F (LFD) (4 Maret 2015), Hercules C-130B milik TNI AU (30 Juni 2015), Trigana Air jenis ATR 42-300 (16 Agustus 2015), Cardig Air jenis Boeing 737-3Q8BDSF (28 Agustus 2015), dan Aviastar jenis DHC-6 Twin Otter 300 (2 Oktober 2015). Berdasarkan data situs Aviation Safety, dari 6 pesawat, 4 di antaranya kecelakaan di Papua.
Pengamat penerbangan dan investigator swasta khusus kasus-kasus kecelakaan pesawat, Gerry Soejatman tidak kaget dengan banyaknya kecelakaan pesawat di Indonesia timur, seperti di Papua. Medan yang sulit dan infrastuktur terbatas di sana, seharusnya membuat pemerintah memaklumi kecelakaan itu.
"Dengan menteri (Menteri Perhubungan Ignatius Jonan) yang sekarang, maskapai nggak boleh salah. Kalau salah, dihukum," kata Gerry.
Saat ini peringkat Indonesia versi Federation Aviation Administration (FAA) di kategori 2 atau a Failure. Ini disebabkan regulator Indonesia tidak memenuhi standar pengawasan keselamatan penerbangan yang ditetapkan International Civil Aviation Organization (ICAO). FAA menyebut sistem penerbangan di Indonesia kacau. Makanya seluruh sistem penerbangan di Indonesia perlu diperbaiki.
FAA menemukan kekurangan terkait dengan regulasi untuk menjembatani masalah pengawasan dan pengecekan berkala dalam peraturan kelaikan udara di Kemenhub. FAA juga menyoroti masalah sumber daya manusia seperti kebutuhan inspektor pesawat khusus. Selama ini inspektor untuk melakukan pengawasan terhadap jenis pesawat tertentu hanya terdiri dari dua orang. Itu pun disuplai dari maskapai lokal.
Gerry mengatakan peraturan penerbangan di Indonesia ‘amburadul’. Menurutnya, Kementerian Perhubungan terlalu mudah menutup sebuah maskapai penerbangan. Padahal alasannya tidak ada sangkut pautnya dengan alasan keamanan penerbangan.
Salah satunya keinginan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang akan membekukan 8 maskapai penerbangan karena belum memenuhi ketentuan pemenuhan kepemilikan pesawat. Ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang penerbangan.
"Itu undang-undang dagelan menurut saya," kata Gerry.
Peraturan penerbangan Indonesia mana saja yang ‘amburadul’? Apakah solusi yang bisa dilakukan agar penerbangan di Indonesia timur minim insiden kecelakaan?
Berikut analisa Gerry Soejatman dalam wawancara suara.com pekan lalu di Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta:
Indonesia disorot Federation Aviation Administration (FAA) karena sistem penerbangan di Indonesia buruk. Anda melihat ada masalah apa dengan penerbangan di Indonesia?
Dari sisi keselamatan penerbangan, tugas pemerintah itu gampang. Pemerintah membuat peraturan apa? Lalu diikuti tidak peraturan itu? Kita punya kendala, banyak laporan maskapai penerbangan tertutup, laporan penerbangan tidak jalan. Makanya tahun 2007 kita kena oleh FAA.
Pada 16 April 2007, FAA menurunkan peringkat Indonesia ke kategori 2 atau a Failure. Karena regulator Indonesia tidak memenuhi standar pengawasan keselamatan penerbangan yang ditetapkan International Civil Aviation Organization (ICAO). (ICAO: badan khusus PBB yang menangani permasalahan penerbangan sipil antar negara)
Seharusnya, kalau ada maskapai pekerbangan yang melaporkan safety report, Kementerian Perhubungan harus terbuka untuk berdiskusi, mendengarkan cerita, dan dicari pencegahannya. Semenjak menterinya Ignatius Jonan (Kementerian Perhubungan), maskapai tidak berani laporkan safety report. Sebenarnya ini persoalan mindset. Karena tugas regulator itu bukan sebagai polisi. Regulator ini tugasnya kayak panti sosial, maskapai punya masalah apa? Kasih tahu peraturannya. Tapi kalau maskapai penerbangan tidak ingin ikuti peraturannya, tendang dan selesai (tutup).
Tapi sebelum sampai ke tahap itu (penutupan) harus dibina dulu. Tapi sekarang ini regulator kayak polisi, main hukum saja. Maka budaya safety ini tidak bisa ditanamkan kalau seperti itu. Kalau saat ini maskapai mengaku ada salah, langsung ditindak. Itu tidak akan membuat maskapai sadar dan membentuk budaya safety.
Dengan menteri yang sekarang, maskapai nggak boleh salah. Kalau salah, dihukum.
Bukankah itu dilakukan lantaran agar maskapai itu menjadi aman untuk terbang?
Bicara soal penerbangan, bukan bicara soal "tidak akan ada musibah penerbangan". Maskapai yang bagus pun akan kena musibah. Kalau nggak mau ada musibah, tutup saja semua maskapai penerbangan. Setiap ingin 'bermain' di dunia penerbangan, pasti ada risiko itu.
AirAsia itu kurang baik apa? Masih tetap kecelakaan. Garuda Indonesia sering sekali tergelincir. Padahal AirAsia dan Garuda yang terbaik di antara penerbangan lainnya.
Kalau laporan minor (tidak baik) maskapai turun tahun ini, saya tidak terkejut. Makapai nggak berani melapor. Saat ini kalau ada kecelakaan, pemerintah pasti akan mencari siapa yang salah. Sikap seperti itu yang harus diubah. Laporan safety dari maskapai itu banyak dilakukan sejak 2010 sampai 2013. Tapi saat ini sudah tidak banyak. Tahun 2014 sudah mulai kendur.
Indonesia juga disorot banyak maskapainya yang tidak memenuji standar keamanan…
Defenisi tidak memenuhi standar dari mana? Maskapai kita sudah diakui oleh Eropa. Garuda, AirAsia. Maskapai kita 10 tahun terakhir ini sudah lebih bagus. Tapi memang masih ada yang bandel, tapi mereka itu bisa dicari. Hampir semua maskapai penerbangan di Indonesia memenuhi standar keamanan. Paling hanya 2-3 buah maskapai yang tidak standar.
Tapi yang perlu di lihat, daerah operasi mereka ini ada di mana? Sebut lah di wilayah timur, wajar kalau disebut tidak aman. Medannya itu yang tidak aman. Ngeri banget terbang di pedalaman.
Tapi masyarakat di sana berhak mendapatkan transportasi penerbangan. Pemerintah tidak bisa melarang maskapai di sana tidak beroperasi dengan alasan tidak layak terbang. Medannya saja ekstrim. Apakah mau pemerintah memotong puncak bukit untuk dijadikan bandara? Kebanyakan bandara di Papua dan kawasan timur itu ada di lembah.
Coba pasang ILS (Instrument Landing Syatem) di bandara di Wamena, mantul itu sinyalnya karena ada di lembah dan di antara gunung. ILS adalah alat bantu pendaratan instrumen (non visual) yang digunakan untuk membantu penerbang dalam melakukan prosedur pendekatan dan pendaratan pesawat di suatu bandara.
ILS ini ada 3 sistem, yaitu Localizer (LOC) yang memberikan sinyal pemandu azimuth mengenai kelurusan pesawat terhadap garis tengah landasan pacu, atau membantu pesawat terbang agar tepat di centerline landasan pada saat mendarat. Localizer beroperasi pada daerah frekuensi 108 MHz hingga 111,975 MHz. Glide Slope (GS) yang memberikan sinyal pemandu sudut luncur pendaratan (3 derajat) , atau membantu pesawat terbang agar tepat di touchdown pada saat mendarat. Glide Slope sering juga disebut Glide Path (GP) dan bekerja pada frekuensi UHF antara 328,6 MHz hingga 335,4 MHz. Dan Marker Beacon yang menginformasikan sisa jarak pesawat terhadap titik pendaratan. Marker beroperasi pada frekuensi 75 Hz.
Sekarang saja barang-barang sudah menumpuk di Papua karena jarang ada penerbangan. Sebab Airlines yang mengangkut barang di Papua harus mempunyai izin sebagai airlines kargo. Mana ada yang bisa. Itu menyebabkan harga barang di Papua naik 2 kali lipat.
Infrastuktur penerbangan di Indonesia timur tidak memadai?
Jangankan di timur, di Kalimantan saja sering tak ada listrik.
Kita harus sadar, jika kita hanyalah manusia. Dan Indonesia bukan hanya Pulau Jawa. Jangan membuat aturan yang terpusat pada Jawa. Lihat lah di luar medannya seperti apa? Itu di Kalimantan saja, ada listrik nggak? Bahan bakar tersedia nggak? Kalau ada pesawat jatuh, ini dianggap salah penerbangan.
Jadi berhentilah melihat siapa yang salah. Tapi apa yang kurang dan yang perlu diperbaiki.
Di Papua, medannya saja sudah susah. Solusinya, Kementerian Perhubungan jangan berpikir sebagai orang Jakarta dan Jawa. Di sana berbeda apa yang dibutuhkan di Jawa. Misal ILS itu tidak bisa dipasang di bandara di kawasan pegunungan seperti Papua. Karena akan memantul ke dinding sinyalnya. Itu bukan solusi tepat. Kalau memang ILS itu harus dipasang, maka bukit seluas 5000 hektar di sana harus dipangkas untuk dijadikan bandara.
Wajar tidak bandara mengeluarkan puluhan triliun hanya untuk bandara yang dikunjungi ratusan orang? Nggak masuk akal itu. Bandara perintis, butuh ILS atau tidak? Selama ini aman-aman aja. Jadi jangan main tutup pesawat kalau pesawat kecelakaan.
Contoh kasus di Amerika Serikat, di Alaska. Dulu hitungannya, kemarian penerbangan di sana setiap 4 hari ada 1 orang yang mati. Saat ini 1 orang mati perbulan. Mereka duduk bersama dan berdiskusi. Mungkin nggak pesawat besar masuk situ. Mereka harus bawa barang-barang ke Alaska.
Kondisi di Alaska dan bagian timur Indonesia, terutama Papua ini sama. Kalau tidak ada pesawat terbang ke sana (Papua dan Alaska), makan ada banyak mausia yang mati kelaparan dan kedinginan. Di Alaska, penerbangan dengan medan sulit dan maskapai tahu kalau risikonya mati.
Yang penting ikuti prosedur keselamatan, tapi kalau tetap kecelakaan, siapa yang salah? Nah di Indonesia harus menerima itu, jika penerbangan di Papua itu sulit. Semestinya khusus di Papua itu, pesawat jangan sampai dilarang terbang. Mau makan apa daerah-daerah di sana?