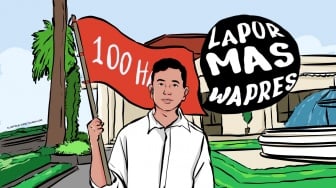Dalam pemindahan ibukota ke Kalimantan, paling tidak terdapat 20.000 masyarakat adat yang akan berhadap-hadapan nasib terhadap proyek pembangunan yang ada.
Megaproyek pemindahan ibukota melibatkan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Proyek ini juga akan menggandeng investor asing.
Proyek tahap awal mencakup pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR)/ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan perumahan buat Aparatur Sipil Negara (ASN) tahap awal, serta pembangunan infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk. Ada juga proyek infrastruktur lain seperti jalan tol, jalan non-tol, dan infrastruktur pendukung.
Dari proyek-proyek tersebut, amat banyak permasalahan sosial yang berpotensi muncul; kesenjangan sosial, konflik sosial, tergusurnya identitas lokal, dan berbagai persoalan lainnya. Terlebih masih terdapat 54 desa tertinggal di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tempat di mana ibu kota akan berdiri.
Ketidakseimbangan hak dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat lokal dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seringkali mendorong proses pemiskinan masyarakat komunal lokal (masyarakat adat). Risiko lainnya adalah beban sosial tanpa kompensasi yang harus ditanggung oleh masyarakat tersebut.
Situasi tersebut akan membuat masyarakat adat semakin terasing di tanahnya sendiri. Selama ini pun, konflik sosial yang terjadi melibatkan masyarakat adat dengan perusahaan ekstraktif sudah banyak terjadi. Masyarakat adat semakin rentan kehilangan pengetahuan tradisional seiring dengan hilangnya hak mereka atas tanah dan hak kelola.
Selama pemerintah terus menerbitkan kebijakan yang meminggirkan komunitas lokal, maka stigma Pulau Kalimantan sebagai daerah yang tertinggal akan terus hidup.
Artikel ini sebelumnya tayang di The Conversation.

Baca Juga: Sah! RUU IKN Jadi Undang-undang No. 3 Tahun 2022 Tentang IKN