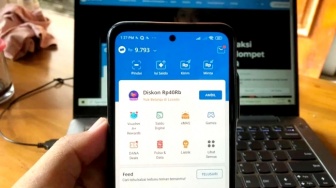Suara.com - Pemilihan presiden dalam dua dekade terakhir terbukti meningkatkan emosi masyarakat seiring dengan polarisasi yang semakin tajam antara kubu Joko Widodo (Jokowi) dan lawannya, Prabowo Subianto.
Tahun ini dengan semakin meluasnya penggunaan telepon seluler dan media sosial, masyarakat terpapar beragam informasi, palsu maupun valid, yang memicu perasaan cemas, amarah, dan takut.
Ini mendorong individu-individu untuk bereaksi dalam beragam cara, dari berceloteh di media sosial hingga terlibat dalam kerusuhan dan menyulut bom molotov dalam demonstrasi anarkistis di Jakarta pekan ini.
The Conversation Indonesia melakukan tanya jawab dengan Berry Juliandi, peneliti neurosains dari Institut Pertanian Bogor untuk mengetahui mengapa aksi kerusuhan ini bisa terjadi dari aspek bagaimana otak manusia bekerja ketika menerima (dis)informasi.
Dengan memahami cara kerja otak, kita akan lebih menyadari jika tindakan kita didorong oleh emosi yang tidak teregulasi dengan baik.
Apa yang terjadi dengan otak manusia ketika menerima informasi, baik yang benar atau palsu?
Ketika manusia menerima stimuli informasi otak kita memiliki dua cara untuk memproses informasi tersebut.
Cara pertama, terjadi secara cepat dan didorong oleh naluri bertahan hidup, diatur oleh bagian otak yang disebut otak kuno. Sementara cara kedua, terjadi secara lebih lambat dan menggunakan logika, diatur oleh bagian otak yang disebut otak baru.
Otak kuno mengatur fungsi hewani seperti nafas, nafsu makan, dan rasa takut. Otak kuno ini dimiliki oleh semua hewan bertulang belakang. Bagian dari otak kuno yang mengatur bermacam-macam nafsu (seperti nafsu berahi, amarah, dan makan) disebut hipotalamus. Sementara bagian dari otak kuno yang mengatur rasa takut disebut amigdala.
Otak baru atau neocortex membentuk otak besar atau cerebrum yang mengatur rasionalitas, kognisi, penglihatan–hal-hal yang membantu manusia mengambil keputusan yang didasari logika. Otak baru berkembang pesat di hewan mamalia golongan primata, yaitu monyet, kera dan manusia.