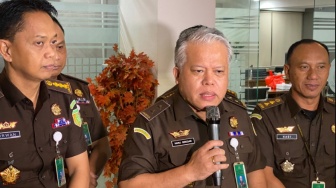Suara.com - Rencana pemberian izin bagi perguruan tinggi mengelola tambang masih menuai penolakan. Perguruan tinggi disangsikan kemampuan dan kapasitasnya mengelola bisnis pertambangan.
Dalam diskusi virtual yang digelar Perkumpulan Bakul Pemimpi, Sabtu (8/2/2025), ahli pertambangan dan para akademisi menelaah sejumlah tantangan dan risiko yang akan dihadapi perguruan tinggi bila dipaksa terjun ke bisnis tambang.
Akademisi sekaligus pakar pertambangan Zulfatun Mahmudah dalam presentasinya menegaskan, dipastikan kampus akan buntung bila nekat mengelola tambang.
Dia mengungkapkan tiga alasan, Antara lain menyangkut kemampuan finansial, kapasitas operasional penambangan termasuk tantangan sosial dan lingkungan, hingga kehancuran reputasi kampus itu sendiri. Menurutnya, sektor pertambangan membutuhkan modal awal yang sangat besar. Meliputi jaminan reklamasi yang harus disetor dalam waktu 30 hari setelah dokumen rencana reklamasi diserahkan.
Pendanaan berikutnya untuk eksplorasi yang mencakup pemetaan lokasi, penentuan kualitas dan deposit batu bara, serta analisis dampak lingkungan yang juga membutuhkan dana besar.
Jika dua tahapan itu terpenuhi, tidak serta merta bisa segera menambang lalu meraup untung. Perusahaan tambang harus mengeluarkan biaya lagi untuk konstruksi yaitu pembangunan fasilitas pengolahan seperti crusher dan coal processing plant, pembuatan jalur pengangkutan (hauling road) yang bisa sangat mahal jika lokasi tambang jauh dari jalur distribusi. Biaya kontruksi ini termasuk pembangunan perkantoran dan perumahan karyawan karena tambang biasanya berada di daerah terpencil.
“Bisa dibayangkan, modal awal sebelum menambang sudah sangat mahal. ini belum menambang. Sebagai gambaran, PT Kaltim Prima Coal menghabiskan 570 juta USD dalam tahap konstruksi awalnya, atau sekitar 10 triliun rupiah dengan kurs saat ini,” kata Zulfatun.
Biaya besar berikutnya adalah untuk operasional dan keselamatan tambang. Walaupun katanya menghasilkan untung, perusahaan tambang harus mengeluarkan lagi biaya pajak, royalti. Sedangkan royalti ekspor lebih tinggi dibanding domestik. Ini belum termasuk sharing profit ke pusat dan daerah, bahkan wajib mengalokasikan duit untuk CSR dan tanggung jawab sosial.
Zulfatun mengatakan, hanya dua pilihan pendanaan. Melibatkan pihak ketiga, berarti memberi hak konsesi ke investor dan kampus menerima fee namun hilang kendali penuh atas tambang. Atau kampus harus mencari pinjaman, yang berarti harus ada aset sebagai
jaminan.
Baca Juga: Baleg DPR Sebut Pemerintah Sudah Setuju Kampus Bisa Kelola Tambang
“Pilihan pertama, berarti kampus menjadi broker. Atau pilihan kedua, ada risiko break-even point (BEP) dalam industri tambang sangat panjang, dan ada risiko kerugian akibat fluktuasi harga batu bara,” katanya.