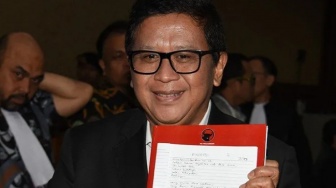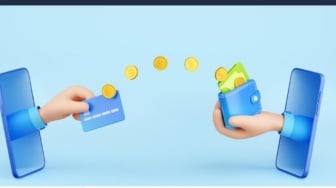Suara.com - Diawali oleh Sri Lanka, lalu dua tahun kemudian, rangkaian peristiwa yang sama terjadi di Bangladesh. Seolah sudah belajar dari negara-negara tetangganya, Indonesia mampu terhindar dari bencana politik belum lama ini. Namun, kini, Maladewa juga menghadapi masalah dan hampir terjerumus ke dalam krisis ekonomi. Ini bisa jadi akan menjadi krisis politik besar berikutnya di Asia.
Konteks krisis ini mungkin berbeda satu sama lain. Faktanya, di India, tepatnya di New Delhi, kita melihat protes massa semacam ini untuk pertama kalinya. Namun, protes itu sebagian besar terbatas pada petani. Gerakan itu tidak meluas menjadi gerakan multi-pemangku kepentingan, meskipun berlangsung selama berbulan-bulan. Memang, para pengunjuk rasa tidak dapat menjadikannya protes massa "oleh rakyat."
Apa yang terjadi di Sri Lanka pada 2022 lalu merupakan hal yang berbeda. Protes yang terjadi pada saat itu merupakan gerakan yang dipimpin pemuda tanpa politik partai, setidaknya selama tiga bulan pertama.

Tujuannya adalah perubahan rezim, atau perubahan sistem, dan setelah Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri, mayoritas pengunjuk rasa mengundurkan diri sehingga memungkinkan transisi kekuasaan yang lancar. Namun, beberapa tetap bertahan, memprotes, bahkan saat rezim transisi berkuasa. Mereka juga bersiap untuk mundur, ketika pasukan pemerintah menyerang mereka.
Meskipun tujuan protes ini bervariasi dari satu kelompok ke kelompok lain, tujuan utamanya adalah untuk mengeluarkan keluarga penguasa dari sistem, meskipun itu tidak terjadi dalam jangka panjang. Pada bulan Agustus 2022, para pengunjuk rasa menyadari bahwa tugas mereka telah selesai, dan membiarkan proses transisi demokrasi berjalan dengan sendirinya. Mereka mengemasi tas dan pulang.
Di Bangladesh, rutinitas yang hampir sama terjadi hingga batas tertentu. Tidak berlangsung selama berbulan-bulan seperti di Sri Lanka, protes ini hanya butuh beberapa minggu saja. Mahasiswa yang frustrasi memimpin protes, yang dipicu oleh keputusan untuk menerapkan kembali sistem kuota yang kontroversial. Namun karena tanggapan yang agresif dan brutal oleh pasukan keamanan, protes berubah menjadi gerakan protes besar-besaran terhadap pemerintah, yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina.
Ia melarikan diri dari negara itu. Namun protes terus berlanjut, berbeda dengan apa yang terjadi di Sri Lanka. Akibatnya, hingga saat ini, hukum dan ketertiban belum sepenuhnya ditegakkan di negara tersebut untuk membuka jalan bagi pemilihan umum dalam waktu kurang dari dua bulan. Pemerintah sementara belum menentukan cara-cara untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil.
![Para pengunjuk rasa memblokir persimpangan Shahbagh selama unjuk rasa di Dhaka, Bangladesh, Minggu (4/8/2024). [Munir UZ ZAMAN / AFP]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/08/05/31161-unjuk-rasa-di-bangladesh-kerusuhan-di-bangladesh.jpg)
Dua minggu lalu, perkembangan serupa terlihat di negara demokrasi lain yang sedang berkembang pesat di Asia yaitu negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia. Protes kali ini menentang gerak-gerik meragukan dari Presiden Joko Widodo yang akan lengser untuk menjadikan dirinya sebagai penguasa bayangan di balik layar. Presiden Joko Widodo telah berhasil mengangkat putra sulungnya Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden untuk pemerintahan berikutnya di bawah Prabowo Subianto, mulai bulan Oktober. Ia juga menginginkan putra lainnya, Kaesang Pangarep menjadi Gubernur Jakarta.
Jokowi meminta DPR untuk mengesahkan undang-undang dalam waktu 24 jam untuk membatalkan keputusan pengadilan konstitusi yang menghalangi putranya untuk mencapai jabatan tinggi. Menantu Jokowi telah mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara, yang memastikan posisi yang kuat bagi keluarganya. Pada titik ini, pemuda Indonesia memutuskan bahwa apa yang terjadi sudah cukup. Maka, mereka turun ke jalan. Protes yang dimulai dalam waktu 24 jam dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru negeri. Pemerintah, yang merasakan panasnya, dan juga meniru apa yang terjadi di Bangladesh, mencabut undang-undang yang kontroversial itu dan mengalah pada para pengunjuk rasa. Ketegangan di negara itu pun kembali mereda.
Satu pertanyaan pokok ketika menganalisis gerakan massa ini adalah: siapa sebenarnya yang berada di balik protes besar-besaran ini?