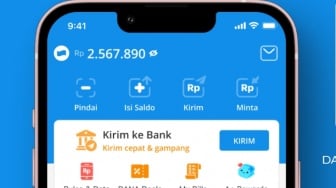Suara.com - Permintaan maaf negara kepada Sukarno dan keluarganya terkait Gerakan 30 September 1965 (G30S), menurut sejarawan, dapat membuka jendela dialog dan meluruskan fakta sejarah masa lalu yang terbentuk selama beberapa dekade di bawah Orde Baru - yang menyebut Sukarno diduga melindungi PKI bahkan disebut terlibat dalam G30S.
Namun, mantan aktivis 66 yang mendesak Sukarno mundur dari jabatannya tidak setuju dengan wacana permintaan maaf tersebut karena, menurutnya, merupakan fakta sejarah bahwa saat itu Sukarno ragu-ragu dan pasif dalam merespon peristiwa G30S.
Usul agar pemerintah meminta maaf kepada keluarga Sukarno diusulkan oleh PDI Perjuangan.
Mereka beralasan, Ketetapan MPRS XXXIII tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Sukarno, salah satu poinnya, menyebut Sukarno menguntungkan kelompok yang melakukan G30S.
Saat memberikan keterangan perihal penganugerahan gelar pahlawan nasional, Senin (07/11), Presiden Joko Widodo menegaskan kembali, Sukarno merupakan pahlawan nasional dan Ketetapan MPRS XXXIII tahun 1967 telah dinyatakan tidak berlaku melalui Ketetapan MPR Nomor 1 tahun 2003.
Membuka jendela dialog dan meluruskan sejarah masa lalu
Sejarawan dari Universitas Nasional, Jakarta, Andi Achdian mengatakan negara layak menyampaikan permintaan maaf atas perlakuan buruk yang dilakukan Suharto dan rezimnya Orde Baru, kepada Sukarno dan keluarganya.
“Permintaan maaf itu sebagai jendela untuk membuka wacana sejarah yang sudah terbentuk selama beberapa dekade di bawah Orde Baru,” kata Achdian, Rabu (09/11).
“Itu sebagai pintu masuk untuk membuka dialog tentang apa yang terjadi di tahun 60-an dan pelanggaran HAM yang terjadi saat itu.
“Melalui maaf itu juga akan membebaskan kita dari trauma dan meluruskan sejarah masa lalu tentang G30S,” ujarnya.
Baca Juga: Apa Maksud Presiden Jokowi Sebut Soekarno Tidak Pernah Berkhianat? Babak Baru Sejarah G30S/PKI
Salah satu perlakuan buruk terhadap Sukarno, menurut Achdian, adalah pengambilalihan kekuasaan secara tidak resmi melalui Ketetapan MPRS XXIII tahun 1967 lalu kemudian menjadikannya sebagai tahanan politik.
Dalam kepemimpinan Rezim Orde Baru, Achdian mengatakan, pemerintah membangun narasi sejarah secara resmi yang mendelegitimasi posisi Sukarno sebagai pendiri bangsa dan pahlawan nasional.
Sukarno tidak pernah tampil sebagai satu pribadi mandiri yang berjasa bagi Indonesia, ujar Achdian.
“Karena sejarah yang dibentuk itu dengan kebohongan. Rezim Orde Baru membangun narasi sejarah melalui propaganda yang menyesatkan hingga sampai sekarang kontroversi itu tetap ada,” katanya.
Salah satu propagandanya, Achdian mencontohkan, pada 1 Oktober 1965, Sukarno memutuskan batal ke Istana Merdeka karena dikepung pasukan militer.
Lalu, Sukarno kemudian mengamankan diri di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
“Namun posisi Sukarno di Halim itu menjadi tuduhan bahwa ia merestui G30S, jadi itu sebenarnya kerangkanya. Padahal itu adalah prosedur pengamanan presiden bahwa Halim itu tempat aman,” katanya.
“Tidak mungkin seorang presiden mengkudeta dirinya sendiri, secara logika tidak masuk akal.”
“Posisi Sukarno sebenarnya tidak ingin terjadi pertumpahan darah sehingga dia enggan membubarkan PKI. Itu yang menyebabkan muncul narasi, Sukarno bagian dari G30S, padahal itu sama sekali tidak berdasarkan fakta, hanya tuduhan,” katanya.
PDI Perjuangan minta negara minta maaf
PDI Perjuangan meminta negara melalui pemerintah menyampaikan permohonan maaf kepada Sukarno yang dituding tidak setia kepada NKRI dan mendapat perlakuan tak adil dalam sisa akhir hidupnya.
Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, permintaah maaf merupakan bagian dari tanggung jawab moral dalam berbangsa dan bernegara serta mengajarkan generasi selanjutnya untuk terus menghormati jasa para pahlawan, terutama pendiri bangsa.
Di tambah, katanya, segala tuduhan kepada Sukarno dalam G30S tidak pernah terbukti hingga sekarang.
Salah satu perlakuan tidak adil yang diterima Sukarno adalah melalui Ketetapan MPRS Nomor 30 tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.
Pada Pasal 3 TAP MPRS tersebut, secara tegas melarang Sukarno untuk melakukan aktivitas politik apa pun sampai dengan pelaksanaan pemilu selanjutnya.
Sukarno juga dituduh membuat kebijakan yang dianggap berpihak pada tokoh-tokoh PKI, yang tertuang dalam bab pertimbangan TAP MPRS tersebut.
Pada 2017 lalu di acara peringatan wafat Bung Karno di Gedung MPR, putri Sukarno yang juga Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri menceritakan momen yang dialami saat ayahnya dilengserkan dan dituding mendukung serta melindungi pemberontakan terhadap negara.
"Karena memang politik, ada sebuah proses de-Sukarnoisasi. Apa yang berbau Bung Karno harus ditenggelamkan. Foto saja mesti diturunkan, kalau tidak, tidak bisa makan," kata Mega dikutip dari Detik.com.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan kembali bahwa Sukarno merupakan pahlawan nasional dan Ketetapan MPRS XXXIII tahun 1967 telah dinyatakan tidak berlaku melalui Ketetapan MPR Nomor 1 tahun 2003.
“Perlu kami tegaskan bahwa ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor XXXIII sebagai kelompok ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi, dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut,” katanya saat memberikan keterangan perihal penganugerahan gelar pahlawan nasional, Senin (07/11).
“Baik karena bersifat final, telah dicabut, maupun telah dilaksanakan. Di tahun 1986 Pemerintah telah menganugerahkan pahlawan proklamator kepada Sukarno. Dan tahun 2012, pemerintah juga telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Sukarno,” kata Jokowi.
Berdasarkan keputusan tersebut, tambah Jokowi, Sukarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia, dan tidak menghinanati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan.
“Hal ini merupakan bukti pengakuan dan penghormatan negara atas kesetiaan dan jasa-jasa Bung Karno terhadap bangsa dan negara baik sebagai pejuang dan proklamator kemerdekaan, maupun sebagai kepala negara di saat bangsa Indonesia sedang berjuang membangun persatuan dan kedaulatan negara,” katanya.
Aktivis 66: 'Ini peran Sukarno'
Mantan aktivis 66 yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Ridwan Saidi, mengatakan tidak tepat jika negara menyampaikan permintaan maaf kepada Sukarno dan keluarganya.
“Urusannya apa negara harus minta maaf? Negara yang memiliki adalah rakyat,” kata Ridwan.
Ia pun tidak setuju jika TAP MPR XXXIII dihapuskan karena merupakan fakta sejarah bahwa saat itu Sukarno sebagai pemimpin negara tidak mampu bersikap atas pembunuhan berdarah para jenderal dan dugaan keterlibatan PKI.
“Tidak bisa dong menghapus begitu saja dan apanya yang dihapus? Itu fakta, fakta bahwa Presiden Sukarno tidak bersikap. Ia pasif, diam, dan ragu-ragu untuk bertindak. Kan tidak bisa, negara sedang dalam bahaya,” kata Ridwan.
Ia juga menambahkan, pada tahun 2003 tidak ada sidang MPR dan pembahasan untuk mencabut ketetapan MPRS sebelumnya.
“Tahun 2003 itu presidennya Ibu Megawati. Sidang MPR baru tahun 2004 dan itu tidak membahas TAP-TAP MPRS, tidak membahas. Jadi harus ditertibkan dulu pernyataan bahwa MPR tahun 2003 mencabut, setahu saya, sidang MPR pun tidak ada,” ujarnya.
Ridwan mengatakan, TAP MPRS XXXIII merupakan hasil dari tuntutan dari dirinya dan rekan aktivis Angkatan 66 atas sikap Sukarno yang tidak bersikap atas pembunuhan jenderal dan dugaan keterlibatan PKI.
“[TAP MPRS itu] tuntutan kami, pergerakan KAMI waktu itu, bahkan sampai minta Sukarno diadili, Cuma Pak Suharto yang tidak mau. Jadi aneh menghapus itu,” katanya yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Batalion Soeprapto Arief Rahman Hakim.
Ridwan juga menyebut perlakuan rezim Orde Baru terhadap Sukarno masuk dalam kategori normal. Menurutnya, Sukarno tidak diadili dan ditahan, berbeda ketika Sukarno menahan para pemimpin Masyumi.
Pada 30 September 1965 malam, terjadi peristiwa berdarah dimana enam jenderal dan seorang perwira menengah tewas dibunuh dan dibuang di Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Peristiwa itu memicu tragedi berdarah, yaitu pembantaian massal orang-orang yang dicurigai sebagai anggota atau simpatisan PKI.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM pada 23 Juli 2012 lalu menyatakan, peristiwa brutal yang diduga menewaskan lebih dari 500.000 orang yang dituduh PKI itu merupakan pelanggaran HAM berat.
Bagaimanapun, peristiwa penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal dan perwira itu, disebut sebagian analis, menjadi awal melemahnya kekuasaan Sukarno.
Dia kemudian 'digantikan' oleh Suharto melalui apa yang disebut sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 dan 'diresmikan' dalam Sidang Istimewa MPRS tahun 1967. Sebagian pengamat menyebutnya sebagai 'kudeta merangkak'.
Di bawah rezim Orde Baru, sosok, peran, dan terutama sebagian ajaran-ajaran presiden pertama Indonesia itu diyakini disembunyikan atau dihilangkan secara sistematis.
Anak-anaknya bahkan sempat dihalang-halangi untuk terjun ke politik praktis.
Berakhirnya kekuasaan Presiden Suharto, melalui peristiwa politik Reformasi 1998, menjadi pintu masuk untuk memberikan tempat kepada narasi seputar Sukarno - dengan segala kelebihan dan kelemahannya - yang sebelumnya dibatasi.