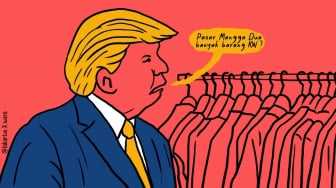Artinya otoritas ini pada akhirnya takubahnya dengan lembaga pemerintah (eksekutif) lainnya, padahal salah satu mandat utamanya adalah memastikan kepatuhan kementerian/lembaga yang lain terhadap UU PDP, sekaligus memberikan sanksi jika institusi pemerintah tersebut melakukan pelanggaran.
Pertanyaan besarnya, kata Wahyudi, apakah mungkin satu institusi pemerintah memberikan sanksi pada institusi pemerintah yang lain? Belum lagi UU PDP juga seperti memberikan cek kosong pada Presiden, tidak secara detail mengatur perihal kedudukan dan struktur kelembagaan otoritas ini, sehingga ‘kekuatan’ dari otoritas yang dibentuk akan sangat tergantung pada ‘niat baik’ Presiden yang akan merumuskannya.
Wahyudi menyebutkan kondisi tersebut makin problematis dengan ‘ketidaksetaraan’ rumusan sanksi yang dapat diterapkan terhadap sektor publik dan sektor privat, ketika melakukan pelanggaran. Bila melakukan pelanggaran, sektor publik hanya mungkin dikenakan sanksi administrasi (Pasal 57 ayat (2)), sedangkan sektor privat selain dapat dikenakan sanksi administrasi, juga dapat diancam denda administrasi sampai dengan 2 persen dari total pendapatan tahunan (Pasal 57 ayat (3)), bahkan dapat dikenakan hukuman pidana denda mengacu pada Pasal 67, 68, 69, 70.
Dengan rumusan demikian, kata dia, meski disebutkan undang-undang ini berlaku mengikat bagi sektor publik dan privat, dalam kapasitas yang sama sebagai pengendali/pemroses data, namun dalam penerapannya, akan lebih bertaji pada korporasi, tumpul terhadap badan publik.
Risiko over-criminalisation juga mengemuka dari berlakunya undang-undang ini, khususnya akibat kelenturan rumusan Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (2), yang pada intinya mengancam pidana terhadap seseorang (individu atau korporasi), yang mengungkapkan data pribadi bukan miliknya secara melawan hukum.
Dalam hukum PDP, kata Wahyudi, pemrosesan data pribadi, termasuk pengungkapan, sepanjang tidak memenuhi dasar hukum pemrosesan (persetujuan/konsen, kewajiban hukum, kewajiban kontrak, kepentingan publik, kepentingan vital, dan kepentingan yang sah), maka dapat dikatakan telah melawan hukum.
Ketidakjelasan batasan frasa ‘melawan hukum’ dalam pasal tersebut akan berdampak karet dan multi-tafsir dalam
penerapannya, yang berisiko disalahgunakan, untuk tujuan mengkriminalkan orang lain.
Lebih jauh, dikatakan Wahyudi, selain ragam catatan permasalahan di atas, tantangan besar implementasi UU PDP adalah pada penyiapan dan pembentukan berbagai regulasi pelaksana, mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, peraturan lembaga, hingga berbagai panduan teknis lainnya. Detail dan kedalaman dari berbagai peraturan teknis yang dirumuskan, akan sangat menentukan dapat berlaku tidaknya undang-undang ini.
Besarnya tantangan ini misalnya sebagai akibat terbatasnya tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki oleh Lembaga Pengawas Perlindungan Data, yang merupakan bagian dari institusi eksekutif, sehingga tidak dilengkapi dengan wewenang penyelesaian sengketa melalui mekanisme ajudikasi non-litigasi, dan kewenangan mengeluarkan putusan mediasi terkait ganti kerugian.
Baca Juga: Menkominfo: Pengesahan UU PDP Tandai Era Baru Tata Kelola Data Pribadi di Indonesia
Belum lagi problem batasan waktu (timeline) dalam pemenuhan hak subjek data oleh pengendali data, yang diatur secara rigid dan berlaku untuk semua sektor (keseluruhannya dirumuskan 3x24 jam). Ketentuan tersebut tentunya akan menjadi kendala bagi pengendali data dari beragam sektor, dengan corak dan model bisnis yang berbeda-beda,
termasuk juga sektor publik, untuk dapat memastikan kepatuhan pada UU PDP.