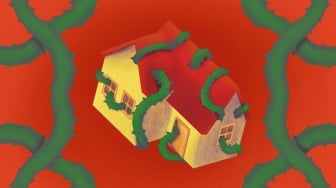Suara.com - Velmariri Bambari adalah ibu rumah tangga dan satu-satunya pendamping korban kasus kekerasan seksual di Lembah Bada, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dia berjuang mendobrak hukum adat demi memenjarakan pelaku kejahatan seksual sekaligus mencari keadilan bagi para korban.
Peringatan: Artikel mengandung materi tentang kejahatan seksual yang dapat membuat Anda merasa tidak nyaman.
Dengan kruk yang setia menopang tubuhnya untuk berjalan, Velmariri Bambariri begitu gesit menemui para Majelis Adat di kampungnya. Ini tugas yang sulit, tetapi harus dilakukannya.
Velma, demikian dia biasa disapa, berupaya membujuk para anggota Majelis Adat untuk menghapus denda 'cuci kampung' yang dijatuhkan pada keluarga korban kekerasan seksual, menurut hukum adat.
Sanksi adat 'cuci kampung' dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang dianggap telah mengotori nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi masyarakat setempat.
Kekerasan seksual, di wilayah ini kerap kali dilihat sebagai perbuatan zina, sehingga baik pelaku maupun korban kejahatan seksual dijatuhi sanksi adat yang sama.
"Sudah menjadi korban, anak-anak ini harus didenda," kata Velma, yang tahun ini berusia 42 tahun.
Langkah Velma terhitung berani. Seorang diri, perempuan yang mengaku taat pada adat ini "mendobrak" aturan-aturan yang sejak kecil menjadi nilai penting dalam hidupnya.
Baca juga:
Baca Juga: Tak Hanya Pemerkosaan, Ini Bentuk Lain Kejahatan Seksual Pada Anak
- Dilecehkan saat usia dini, korban kekerasan seksual di Indonesia menderita puluhan tahun
- Remaja 14 tahun diperkosa dan dijadikan budak seks di Bandung, 'darurat kekerasan seksual pada anak' yang terus berulang
- Korban revenge porn: 'Saya berkali-kali mencoba bunuh diri'
"Tiga belas tahun! Ya, saya segera ke Polsek," raut wajah Velma memerah karena marah setelah menerima panggilan telepon tersebut.
Dia bergegas mengeluarkan sepeda motor dan memacunya ke Polsek Lore Selatan, yang terletak tak jauh dari rumahnya di Desa Gintu, Lembah Bada, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Kruk digenggamnya dengan erat selama motor melaju.
Sesampainya di Polsek, Velma menghampiri korban dugaan kekerasan seksual yang duduk meringkuk di kursi plastik yang disediakan.
Ibu dan bibi korban, yang menemani pelaporan itu, terisak dan menangis histeris. Kejadian tersebut baru dilaporkan beberapa jam yang lalu.
"Pak, boleh kami ke belakang?" tanya Velma kepada petugas yang mencatatkan laporan itu.
Di halaman belakang Polsek Lore Selatan, remaja 13 tahun itu mendekap erat Velma, sambil terisak tanpa henti. Sementara Velma membisikkan kata-kata untuk menguatkan koban.
Ini adalah kasus kesembilan yang akan ditangani Velma dan perkara kekerasan seksual ketiga yang terjadi pada tahun ini di Lore Selatan.
Kasusnya kini ditangani oleh Polres Poso, dan korban untuk sementara tinggal di lokasi rahasia demi keselamatannya.
Sang ibu, sebut Velma, mengatakan bahwa pelaku terus mengirim pesan singkat bernada ancaman kepada korban.
Hingga Juli 2022, terdapat 26 kasus kekerasan seksual di Kabupaten Poso tahun ini, menurut situs Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Velma mendampingi dua di antaranya, yang terjadi di Lore Selatan.
Kedua korban yang didampingi Velma itu masih anak-anak. "Satu di antaranya anak difabel berusia 15 tahun," kata Velma.
Ini membuat dia sangat marah. Nalarnya tak mampu lagi mendeskripsikan kejahatan yang dilakukan pelaku yang berusia 60 tahun.
Telepon pertama dari polisi
Sekarang, bila ada kasus kekerasan seksual dilaporkan ke Polsek Lore Selatan, Velma menjadi orang pertama yang akan ditelepon polisi untuk mendampingi korban, kata dia.
Ini terjadi sejak 2018, ketika Velma memperkenalkan diri sebagai aktivis perlindungan perempuan di desanya.
Empat tahun sebelumnya, pada 2014, Velma bergabung dengan Institut Mosintuwu, sebuah organisasi nirlaba di Poso.
Selain menggelar pelatihan perlindungan anak dan perempuan - yang diikuti Velma selama tiga tahun - organisasi ini juga berfokus pada upaya perdamaian dan keadilan pada saat konflik dan pascakonflik di wilayah Kabupaten Poso dan sekitarnya.
Sebuah kejadian menggugah nuraninya sebelum dia bergabung dengan Instistut Mosintuwu. Di desanya, terjadi peristiwa pemerkosaan.
"Anak itu diperkosa, lalu putus sekolah, para pelaku dikenakan sanksi adat tapi tidak dipidanakan," jelas Velma.
Velma yang kala itu mengaku tidak bisa berbuat apa-apa, merasa tidak berdaya.
"Saya tidak punya pegangan [bekal pengetahuan] kala itu," katanya.
Setelah menempuh pelatihan, Velma memberanikan datang ke Polsek Lore Selatan untuk pertama kali dalam hidupnya pada 2018.
Polisi meneleponnya untuk mendampingi korban kekerasan seksual yang tengah melapor.
Di kantor polisi, Velma mengaku terkejut mendengar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan polisi kepada korban saat pemeriksaan.
"Saya hidup dalam masyarakat adat, pertanyaan tentang itu [perkosaan] adalah tabu bagi saya yang juga seorang ibu.
"Apalagi ditanyakan kepada korban yang masih anak-anak," kata Velma. "Korban pemerkosaan itu baru berusia 15 tahun."
Tak hanya mendampingi korban ketika proses penyusunan berita acara pemeriksaan oleh polisi, Velma juga hadir hingga hakim memutuskan pelaku bersalah di pengadilan.
Tidak berhenti di situ, hingga kini Velma juga masih mendampingi para korban yang kasus hukumnya telah diputus pengadilan.
Mengawal proses pemulihan
Pagi di Desa Gintu begitu ramai. Para tetangga memasang musik kencang hingga suaranya sampai ke rumah Velma.
Dapur Velma berselimut asap yang berasal dari tungku kayu bekas memasak air dan ubi yang masih membara.
Ubi rebus dan kopi dengan sedikit gula adalah sarapannya setiap hari bersama suami dan anak-anaknya.
Setelah suaminya pamit bekerja sebagai pengolah sawah, Velma mempersiapkan diri untuk pergi ke desa tetangga. Dia hendak menemui korban ketiga yang ia dampingi kasusnya dua tahun lalu.
Velma ingin memastikan bahwa proses pemulihan berjalan dan korban bisa bangkit dari keterpurukan.
Korban diperkosa pada 2020 lalu. Kala itu, korban diajak pergi oleh kerabat sang ayah. Pelaku mengaku disuruh ayah korban untuk menjemputnya.
"Anak ini langsung percaya dan mereka pergi," kata ayah korban kepada Silvano Hajid, wartawan BBC News Indonesia.
Sang ayah gelisah karena anaknya belum pulang hingga pukul 21.00 WITA. Namun, kegelisahan itu berubah menjadi rasa patah hati yang teramat dalam.
"Pelaku kabur, korban ditinggalkan begitu saja di sawah dalam keadaan pendarahan," jelas Velma.
Korban harus berjalan sambal menahan sakit hingga jalan utama, lanjutnya.
"Dari situ, korban berteriak meminta tolong dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat," kata Velma, sesuai keterangan korban dalam laporannya kepada polisi.
Malam itu, sang ayah langsung dikabari untuk datang ke puskesmas. Dari situ, anaknya harus dibawa ke rumah sakit di Tentena, kota terdekat dari Lembah Bada.
Hanya ada satu akses jalan ke Tentena, menembus deretan bukit dengan mobil selama sekitar tiga jam.
"Saya harus mencari pinjaman uang untuk ongkos transportasi ke Tentena," kata sang ayah.
Dia akhirnya meminjam uang sekitar Rp2 juta untuk biaya transportasi anaknya berobat ke Tentena dan lebih jauh lagi, Kota Poso.
Utang itu baru bisa dilunasi setahun setelah peristiwa yang mematahkan hatinya itu.
Velma ditelepon polisi untuk mendampingi kasus ini pada pukul 04.00 WITA. Paginya, dia langsung berangkat ke Tentena.
"Setiap sepuluh menit korban kesakitan. Apalagi ketika mau buang air kecil," ungkap Velma.
Kini, dua tahun setelah kejadian, korban masih memulihkan diri.
Velma mengatakan, dia lega karena korban mulai bisa fokus di sekolah. Bahkan nilai mata pelajaran matematika korban adalah yang terbaik di sekolah.
Hukum pidana, bukan hukum adat
Peran Velma sebagai aktivis perlindungan anak dan perempuan begitu besar dampaknya bagi sistem adat di Lembah Bada.
Selain mendampingi korban kekerasan seksual yang kebanyakan anak-anak, Velma juga menemui Majelis Adat dari 14 desa di Lembah Bada.
Setiap desa memiliki majelis adat dan aturan yang berbeda tentang kekerasan seksual.
"Satu majelis adat yang saya temui menjelaskan bahwa yang didenda adalah orangtuanya. Tapi hidup anak masih bergantung pada orang tua.
"Itu tidak baik untuk tumbuh kembang anak, dia akan selamanya merasa bersalah," ungkap Velma.
Maka dia pun melobi para Majelis Adat, terutama di desa tempat tinggal korban, agar korban dibebaskan dari denda 'cuci kampung'.
Dia mencoba memberi pengertian kepada Majelis Adat, bahwa keluarga juga sejatinya merupakan korban dalam kasus kekerasan seksual.
Selain beban psikis, keluarga juga harus mengeluarkan uang untuk biaya perawatan korban, ongkos transportasi ketika persidangan, dan biaya pemulihan psikis korban.
Semua itu tidak diatur oleh adat.
Hukum adat sejatinya juga berlaku bagi pelaku kejahatan seksual. Pelaku bisa dikenakan sanksi berupa tiga ekor kerbau dan selebihnya dalam bentuk uang yang diberikan kepada korban.
Namun dalam beberapa kasus terdahulu, pelaku justru mengulang perbuatannya kepada korban yang sama ketika masih mencicil pembayaran denda kepada korban.
"Fenomena yang terjadi di sini, pelaku menganggap denda bisa dibayarkan oleh sanak saudaranya, sehingga dia meremehkan denda adat itu," kata Velma, yang menilai hukum adat tidak cukup untuk membuat jera pelaku.
Maka, Velma memulai jalan yang teramat terjal, untuk meyakinkan para Majelis Adat agar pelaku kejahatan seksual tidak lagi dihukum secara adat, melainkan hukum positif.
"Dari 14 desa di Lembah Bada, sekitar delapan desa sudah paham untuk menindak para pelaku kekerasan seksual," ungkap Velma.
Wakil Ketua Majelis Adat Desa Gintu, Salber Pole mengungkap, di desanya kini sudah tidak ada lagi denda 'cuci kampung' untuk korban.
"Kepada korban akan diberikan petuah, karena korban belum mengetahui bagaimana liku hidup ini, dia tidak akan diberikan sanksi adat," jelas Salber.
Baca juga:
- Poso yang tidak Anda ketahui: Kesaksian agen perdamaian Poso, Lian Gogali
- Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati, diganjar hukuman mati, 'harta dan aset dirampas'
- Cegah pelecehan seksual, penumpang angkot di Jakarta akan dipisahkan, tetapi bagaimana penerapannya?
Majelis Adat juga menyerahkan sepenuhnya urusan hukum kepada pihak yang berwenang. Bila pelaku sudah dipidanakan, hukum adat tidak akan dikenakan lagi.
"Hukum adat itu menjunjung tinggi harkat, martabat dan hak asasi seseorang. Pelaku sudah menjalani hukumannya tidak akan disanksi lagi," kata Salber.
Bagi Velma, untuk sementara keputusan itu sudah cukup adil.
Pelaku 'berlindung di balik hukum adat'
Ada potensi pelaku kejahatan seksual memiliki impunitas dalam hukum adat, menurut Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Siti Aminah Tardi.
"Adat tidak menjadikan pelaku mendapat penghukuman lewat hukum positif," kata Siti.
"Pelaku bisa berlindung di balik hukum adat untuk menghindari hukum pidana."
Terlebih, kata Siti, sejumlah penelitian di Indonesia menemukan bahwa kebanyakan struktur hukum adat di Indonesia bersifat patriarki.
"Belum ada perwakilan atau kepentingan perempuan. Pengenaan sanksi lebih berbasis kepada ganti kerugian yang nilainya jadi berapa ekor kambing, kuda, lembu atau kerbau," imbuh dia.
Seseorang yang memiliki kekuatan ekonomi, kata Siti, bisa saja dengan mudah membayar sanksi adat.
"Denda itu tidak memperhitungkan trauma psikis yang dialami korban bertahun-tahun."
Tetapi, tambah Siti, hukum adat berpotensi berubah karena sifatnya yang dinamis.
Usaha Velma menjadi contoh bagaimana hukum adat dapat berubah menjadi lebih berpihak kepada korban.
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang memiliki aturan lebih lengkap soal pemenuhan hak korban, disebut Velma sebagai kabar yang baik.
"Ini angin segar bagi saya sebagai pendamping, juga baik bagi korban," kata Velma.
Meski begitu, pekerjaannya sebagai satu-satunya aktivis perlindungan perempuan dan anak di Lembah Bada masih jauh dari selesai.
Dia berharap, lebih banyak perempuan mengambil peranan seperti dirinya.
"Semua perempuan dan ibu bisa seperti saya. Apalagi jika mereka 'normal'. Maksud saya, normal pikiran dan tidak difabel seperti saya, yang memakai tongkat untuk berjalan."