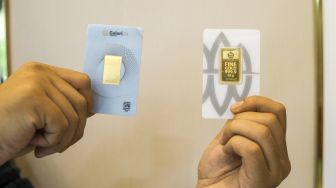Suara.com - Meskipun secara resmi melarang perbudakan, negara-negara Arab di kawasan Teluk meremehkan warisan penindasan dan rasisme yang dihadapi minoritas. Namun, beberapa negara mengambil tindakan untuk mengatasi sejarah itu.
Praktik perbudakan modern masih tersebar luas di negara-negara Arab di kawasan Teluk, di mana jutaan pekerja migran dipaksa bekerja di bawah kondisi yang memprihatinkan dengan sedikit atau tanpa upah.
Sistem "kafala", misalnya, sebuah praktik yang masih umum di sebagian besar negara di kawasan itu, memungkinkan majikan untuk mempekerjakan pekerja tidak terampil yang berasal seperti dari Afrika dan Asia Selatan.
Sebagai "imbalannya", pekerja menyerahkan paspor sehingga tidak mungkin untuk meninggalkan negara atau berganti pekerjaan tanpa izin dari majikan mereka.
Baca Juga: Polri Selidiki Kasus Dugaan Perbudakan Terkait Penemuan Karangkeng di Rumah Bupati Langkat
Sebelumnya, perbudakan tradisional, di mana orang diculik dan dijual sebagai budak, masih legal dan dipraktikkan di sebagian besar wilayah Teluk hingga akhir 1970-an.
Tidak seperti perbudakan modern, di mana beberapa negara Arab seperti Qatar secara perlahan mulai mengambil langkah untuk mengatasinya, sejarah perbudakan lama sebagian besar masih belum diakui dan merupakan masalah yang tabu.
Berurusan dengan rasisme setiap hari
"Kami biasanya bergaul dengan baik, orang kulit hitam, Arab, dan Baluch, tetapi segera setelah perkelahian pecah, hinaan rasial yang mengerikan diteriakkan dengan keras," kata Yassar Khalaf, seorang pelaut berkulit hitam berusia 27 tahun dari Bahrain, yang secara teratur melakukan perjalanan si wilayah Teluk.
"Sangat mudah bagi orang untuk tidak menghormati kami," kata Maddah G., seorang pria kulit hitam dari Irak yang tidak mau menyebutkan nama lengkapnya.
Baca Juga: Mencari Benang Kusut Perbudakan ABK di Jateng dan Pengaruh Pandemi Covid-19
"Orang-orang memanggil kami Abeed (Bahasa Arab untuk budak). Ini sangat umum sehingga mereka bahkan tidak merasa bahwa itu bisa menghina," katanya kepada DW.
Lahir dan dibesarkan di komunitas kulit hitam di dekat pelabuhan selatan Basra, Maddah adalah salah satu dari sekitar 1 juta warga keturunan Afrika yang tinggal di wilayah Teluk.
Namun, "tidak semua orang Afrika yang tinggal di wilayah itu dibawa ke sini sebagai budak," kata Hesham Al-Awadi, seorang profesor sejarah dan ilmu politik di American University of Kuwait.
"Beberapa dari mereka datang secara sukarela karena berbagai alasan seperti ziarah atau perdagangan dan kemudian tinggal secara permanen."
"Kelompok lain dari populasi Afrika di Teluk adalah hasil perkawinan antara pelaut dengan penduduk setempat," tambahnya.
Maddah G. tidak tahu persis dari mana nenek moyangnya berasal, seperti banyak orang kulit hitam lainnya di kawasan Teluk.
Namun, "Apakah kakek-neneknya adalah budak atau bukan, hal itu tidak relevan," katanya, "Setidaknya bagi mereka yang terus menyebut orang kulit hitam Abeed di abad ke-21."
Bagian yang tidak banyak diketahui dari sejarah Teluk Perdagangan budak di Teluk sudah ada selama berabad-abad, tetapi baru betul-betul berkempang sejak tahun 1800-an.
Memiliki budak adalah tanda status, terbatas pada sekelompok kecil elit kaya, kata sejarawan Matthew S. Hopper dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2015, "Slaves of One Master."
Budak tidak hanya dari Afrika, tapi juga datang dari berbagai tempat di Timur Tengah, Kaukasus, dan anak benua India, tulis Hopper.
Perbudakan berubah pada paruh kedua abad ke-19, ketika permintaan global yang meningkat pesat akan buah kurma dan mutiara alami di kawasan itu, sehingga menciptakan kebutuhan mendesak akan tenaga kerja.
Pedagang Arab mulai menculik orang-orang dari bagian timur laut benua Afrika dan menjual mereka di pasar budak di Teluk.
Setelah resesi global tahun 1930-an, pasar mutiara dan kurma runtuh. Banyak budak yang bekerja di perkebunan kelapa sawit atau industri mutiara dibebaskan oleh pemilik yang tidak mampu lagi menopang mereka, menurut Hopper.
Butuh beberapa dekade sampai semua negara Arab di kawasan Teluk secara resmi melarang memiliki, dan memperdagangkan budak.
Irak telah secara resmi menghapus perbudakan pada awal 1920-an. Dan negara-negara seperti Qatar dan Arab Saudi mengikuti langkah tersebut masing-masing pada tahun 1952 dan 1962.
Oman, yang pernah menjadi salah satu pasar budak terbesar di kawasan itu, menjadi salah satu negara yang terakhir melarang praktik perbudakan pada tahun 1970.
Topik tabu
Meskipun telah secara resmi melarang perbudakan tradisional selama beberapa dekade, masyarakat Teluk masih belum bisa secara terbuka tentang masa lalu mereka sebagai pedagang budak.
Abdulrahman Alebrahim, seorang peneliti independen sejarah Teluk modern, percaya undang-undang yang diberlakukan dengan dalih persatuan nasional menjadikannya topik ini sebagai hal yang dapat memicu perpecahan sosial.
"[Undang-undang ini] secara signifikan telah mencegah orang - sejarawan lokal, khususnya - untuk mendiskusikan masalah sensitif yang dianggap tabu secara sosial," katanya kepada DW.
"Bahkan ketika topik ini dibahas secara akademis dan dalam kerangka keadilan dan kesetaraan sosial, itu sangat tidak disukai."
"Ini ada hubungannya dengan cara kami menjelaskan identitas nasional kami di sini, di Teluk. Kami terutama menekankan homogenitas di antara masyarakat kami, pada kesamaan yang kami miliki,” katanya kepada DW.
"Kami tidak merayakan heterogenitas kami dalam wacana sehari-hari kami."
Maddah G. tidak dapat membayangkan bahwa ada sesorang di komunitasnya akan bersedia berbicara tentang asal-usul Afrika mereka dan fakta bahwa banyak orang Afrika dibawa ke sini sebagai budak.
"Selama tidak ada yang malu akan kakek-nenek mereka dulu memiliki budak, tidak bisa diharapkan bahwa orang Arab Hitam nyaman dengan masa lalu mereka sendiri," katanya.
Perubahan lambat sedang berlangsung
Namun, beberapa negara di kawasan Teluk telah mengambil langkah awal untuk mengakui warisan perbudakan.
Qatar membuka Bin Jelmood House, museum pertama yang berfokus pada perbudakan di dunia Arab, di Doha pada tahun 2015.
Museum ini secara eksplisit menunjukkan tentang peran Qatar dalam perdagangan budak yang dan menyoroti kehidupan berat para korbannya.
"Perkembangan begitu cepat di Qatar, kami ingin melihat bagaimana keadaan berubah, bagaimana Qatar dipengaruhi oleh perbudakan dan bagaimana budak diintegrasikan ke dalam masyarakat," Hafiz Abdullah, manajer museum, mengatakan kepada kantor berita Reuters.
Museum secara eksplisit menghubungkan perdagangan budak di masa lalu dengan perdagangan manusia dan kerja paksa saat ini.
"Kisah perbudakan tidak berakhir pada tahun 1952," kata Abdullah.
"Orang-orang perlu fokus pada eksploitasi manusia hari ini dan bagaimana kita bisa mengubahnya."
"Di media sosial, orang-orang semakin membahas perbudakan di Teluk, akar sosial, dan etnisnya dengan referensi khusus untuk populasi kulit hitam lokal,” kata Alebrahim, seraya menambahkan, "Dalam beberapa tahun terakhir, lingkungan akademisi dan generasi baru akademisi Teluk lebih tertarik pada sejarah perbudakan."
Langkah lain untuk pengakuan datang tahun lalu, ketika Al-Awadi menerbitkan "The History of Slaves in the Gulf," salah satu publikasi Arab pertama tentang topik tersebut.
"Selama bertahun-tahun, ketika menceritakan sejarah Teluk, kami berfokus pada orang-orang perkotaan, orang terkenal, orang kaya, penguasa, dan elit," kata Al-Awadi. "[Ini telah terjadi] dengan mengorbankan terkadang membungkam, melewatkan, mengabaikan, meminggirkan perempuan, orang miskin, budak, orang-orang yang tidak memiliki suara. "Buku ini bisa menjadi awal budaya baru,” tambahnya. (ha/yf)