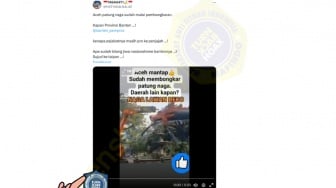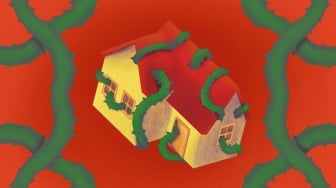Suara.com - 'Desa PKI', begitu julukan sebuah desa di Aceh Tengah ini. Bukan tanpa alasan disebut demikian, sebab desa tersebut menjadi saksi bisu pembantaian 1965. Mulai dari arak-arakan massa membawa potongan kepala petinggi PKI, sampai teka-teki siapa yang membakar sebuah masjid dua bulan jelang G30S 1965.
Pada 1 Oktober 1965, salah satu pimpinan lokal PKI dieksekusi. Mayatnya 'dibuang' lalu kepalanya sengaja diarak keliling kota Takengon menuju lapangan.
Pemandangan mengerikan tersebut disaksikan sebagian warga kota Takengon saat gelombang pembantaian terhadap orang-orang komunis tengah berlangsung masif.
Aksi brutal itu hanyalah salah satu dari sejumlah kasus kekerasan di wilayah itu dengan korban orang-orang komunis serta mereka yang dikaitkan dengan PKI.
Berdasarkan penelitian sejarawan Australia, Jess Melvin, jumlah korban tewas di Aceh Tengah terbilang paling tinggi jika dibandingkan beberapa wilayah lainnya di Aceh.
Baca juga:
- Kesaksian 'Algojo 1965' di Aceh, lubang pembantaian, dan korban yang dilupakan — 'Saya masih simpan parang untuk potong leher'
- 'Tembak dan kuburkan saya, supaya anak-anak bisa berziarah' — Thaib Adamy dan pembunuhan massal 1965 di Aceh
- Soeharto 'koordinir' operasi pembantaian 1965-1966, sebut dokumen
Dokumen internal militer Aceh, seperti terekam dalam penelitian sejarawan Australia, Jess Melvin (dan diterbitkan dalam buku The Army and The Indonesian Genocide-Mechanics of Mass Murder, 2018 — akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada Januari 2022), menyebut setidaknya ada 500 orang dibantai di dataran tinggi itu.
(Petikan wawancara dengan Jess Melvin dapat dibaca pada bagian bawah artikel ini).
Namun sebuah penelitian independen yang sedang berlangsung, memperkirakan operasi pembersihan orang-orang komunis itu mengakibatkan 2.500 mati terbunuh.
Trauma akibat kekerasan dan stigma anti Tuhan, membuat sebagian besar keluarga penyintas 1965 di Aceh Tengah lebih memilih menutup rapat-rapat masa lalunya.
Namun demikian, sejumlah warga Takengon menawarkan semacam jalan keluar dari luka-luka masa lalu itu dengan caranya masing-masing.
Bagaimana nasib keluarga pimpinan PKI yang potongan kepalanya diarak?
Kembali ke peristiwa arak-arakan membawa potongan kepala pimpinan PKI itu tadi.
Lebih dari 55 tahun kemudian, tindakan sadis itu masih menghantui masyarakat di sana.
Tapi, bagaimana nasib keluarga korban yang kepalanya diarak itu? Tidak banyak yang tahu.
Selama puluhan tahun keluarganya memilih mengubur dalam-dalam episode gelap dalam hidup mereka.
Namun pada awal Oktober 2021 lalu, melalui sumber BBC News Indonesia di Takengon, salah seorang cucu sang korban menyatakan bersedia untuk bersaksi. Pria ini berusia 30an tahun.
Siang itu kami bertemu di sebuah hotel di Kota Takengon. Kami semula mengira dia bersedia mengungkap jati dirinya, namun pada detik-detik terakhir dia meminta identitasnya disamarkan.
"Saya harus melindungi keluarga, ibu saya masih sakit," kata Budi — bukan nama sebenarnya — menjelaskan alasannya.
Alasannya lainnya, Budi khawatir kesaksiannya ini akan memancing tudingan seolah-olah dirinya "membela" PKI.
"Padahal saya mau ungkap sebuah kebiadaban masa lalu," katanya.
Dia tidak siap menghadapi bombardir stigma "PKI" diarahkan kepadanya.
"Saya punya anak dan istri," ujarnya. Akhirnya kami sepakat untuk menyamarkan identitasnya.
Baca juga:
- Peristiwa G30S 1965, penumpasan PKI, dan hari-hari sesudahnya
- Soeharto 'koordinir' operasi pembantaian 1965-1966, sebut dokumen
- Dokumen rahasia Amerika: AS mengetahui skala pembantaian tragedi 1965
'Kakek saya disembelih, dan kepalanya diarak di Takengon'
Cerita pun mengalir dari mulut Budi. "Kakek saya pengurus PKI dan serikat buruh di Aceh Tengah," ungkapnya membuka kisah. Dia tinggal di Kota Takengon.
Tidak lama setelah G30S 1965, kakeknya ditangkap bersama ratusan orang-orang tertuduh komunis lainnya.
Setelah sempat dipenjara, sang kakek dan tahanan lainnya dinaikkan ke dalam truk menuju kawasan perbukitan di pinggiran kota. Di sisinya ada jurang nan dalam.
Masyarakat Takengon dan sekitarnya menyebut kawasan yang kadang-kadang diselimuti kabut itu sebagai bur Lintang — bur artinya gunung atau bukit dalam bahasa Gayo.
Di sanalah orang-orang yang kepalanya ditutup karung itu antre untuk disembelih atau ditembak. Tapi, "kakek saya lari, dia loncat" bersama dua orang lainnya.
Sempat bersembunyi di hutan dan perkebunan kopi, dia memutuskan kembali ke rumah karena kelaparan. Di dalam rumah, neneknya dan anggota keluarga lainnya diinterogasi aparat.
Baca juga:
- 'Saya selalu berdoa, kapan bertemu ibu', kisah Francisca Fanggidaej dan tujuh anaknya 'terpisah' 38 tahun sejak 1965
- Perempuan dan propaganda terhadap Gerwani, 'Stigma belum hilang sekalipun mereka sudah tidak memberi label lagi'
- Tionghoa Indonesia dalam pusaran peristiwa 65 - Pengalaman, kenangan dan optimisme generasi muda
"Nenek saya diikat di batang kopi," ungkapnya. Singkat cerita, sang kakek akhirnya tertangkap dan dieksekusi di rumahnya. "Ditembak dulu lalu dipenggal [kepalanya]."
Tanpa kepala, jenazah kakeknya dibuang ke bawah jembatan. "Lalu, kepala kakek saya diarak di sekitar Takengon," ujar Budi dengan kalimat datar.
Arak-arakan itu kemudian berakhir di sebuah lapangan luas di pusat kota yang dipadati massa antikomunis.
"Ini semacam 'pesta' bahwa pimpinan PKI itu sudah mati," ungkapnya, mengutip cerita ibu dan ayahnya.
'Nenek saya alami gangguan mental, ibu saya memendam sendiri deritanya'
Sampai usia remaja, Budi tidak pernah mendapatkan informasi utuh tentang pembunuhan keji atas kakeknya. Juga apa yang melatari mengapa neneknya mengalami gangguan mental.
Orang tuanya selalu menutup rapat-rapat tragedi itu. "Mungkin mereka tidak berani, ditutupi, karena dulu stigma [PKI] kuat sekali," jelasnya.
Budi kemudian teringat, ketika masih bocah, dia pernah menanyakan ihwal kebenaran desas-desus 'arak-arakan menenteng kepala kakeknya' kepada orang tuanya, tapi dia tak mendapatkan jawaban memuaskan.
Rupanya, ibunya lebih memilih memendam ingatan pedihnya untuk dirinya sendiri.
Seiring pengetahuannya yang terus bertambah, Budi kemudian berusaha meyakinkan ibunya supaya mau bercerita.
"Tak usah lagi disembunyikan, ibu," kata Budi, mengulang lagi percakapan dengan ibunya.
Dia merasa yakin bahwa dengan berbagi cerita itu akan membantu meringankan beban masa lalu ibunya.
Baca juga:
- Ribuan buku peristiwa 1965: Mengubah kesedihan menjadi kekuatan
- Kisah para eksil 1965: Mereka yang 'dibui tanpa jeruji'
- Menunggu puluhan tahun untuk tetap menjadi WNI
Akhirnya,"dia mau cerita," kata Budi.
Menjelang kami wawancarai, Budi mengaku mengorek informasi terlebih dulu kepada ibu dan ayahnya — keduanya berusia 80an tahun — tentang tragedi itu.
"Semoga dengan kesaksian saya ini, membuat beban ibu saya berkurang," katanya.
'Yang mengerikan, anak-anak kecil pun dibantai'
Peristiwa sadis yang dialami keluarga Budi bukanlah contoh satu-satunya di Aceh Tengah.
Sebuah penelitian independen mengungkapkan ada sebuah kasus kekerasan 1965 yang korbannya adalah anak-anak.
"Dan, yang lebih mengerikan, yang mati dibunuh, bukan hanya orang tua, ada anak-anak yang dibantai," ungkap Mustawalad, warga Takengon, yang meneliti kekerasan 1965 di Aceh Tengah.
Informasi ini didapatkan Mustawalad dengan mewawancarai beberapa orang yang menyebut dirinya sebagai pelaku dan sejumlah saksi mata.
Dia kemudian menyebut sebuah kampung di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah.
"Kenapa mereka dibantai? Apakah bapaknya salat? Salat! Kenapa dibantai? Ya, karena PKI!" Mustawalad mengulang percakapannya dengan seseorang yang mengaku sebagai pelaku.
Pembantaian terhadap anak-anak yang orang tuanya dicap komunis itu sempat membuat Mustawalad dihantui mimpi buruk.
"Apa hubungan anak kecil yang masih sekolah dasar dengan [pilihan] politik orang tua mereka?" katanya saat ditemui BBC News Indonesia di Takengon, Oktober lalu.
Baca juga:
- G30S: Cucu-cucu 'Pahlawan Revolusi' dan 'elite PKI' bicara soal sejarah dan harapan 'tak mau warisi konflik untuk membenci'
- Penari asal Kupang yang dituding PKI: Diperkosa, katong diperlakukan seperti anjing, 'Biar Tuhan yang mengadili'
- Kisah anak algojo PKI di Blitar selatan yang mendampingi penyintas kasus 1965: 'Saya minta maaf'
"Kebodohan apa yang telah mereka lakukan? Saya tidak habis pikir," tambah Mustawalad, yang pernah aktif di organisasi Kontras di Jakarta dan Banda Aceh.
Kejadian kekerasan ini kemudian memotivasi dirinya untuk meneliti berbagai peristiwa kekerasan 1965 di tanah kelahirannya.
Sejak 2006, Mustawalad melakukan penelitian secara independen. Dia mewawancarai korban dan keluarganya, para pelaku, saksi mata serta mendatangi lokasi pembantaian di Aceh Tengah.
Bersama Mustawalad, kami kemudian mendatangi salah-satu lokasi pembantaian, yaitu di Bur Lintang. Jaraknya sekitar 21km dari Takengon.
Ini adalah kawasan pegunungan yang memiliki tebing curam dan dalam.
"Ini salah-satu lokasi di mana sebagian besar korban dibantai," ungkapnya. Di Aceh Tengah ada sekitar 13 lokasi pembantaian.
Baca juga:
- Cucu eksil: Peristiwa 1965, sejarah yang tak boleh dilupakan
- Cerita para eksil 1965: 'Identitas dicabut, seolah nyawa dicabut'
- Menunggu puluhan tahun di Praha untuk paspor Indonesia
"Dari riset awal, kami menemukan sekitar 2.500 korban. Bandingkan saja dengan jumlah penduduk Aceh Tengah yang hanya 25.000 pada saat itu," katanya.
Mustawalad juga pernah menulis bahwa banyak warga yang ditangkap dan dibantai karena hanya mendapat informasi yang tidak jelas.
"Informasi ini lebih banyak berdasarkan fitnah," tulisnya di Majalah Pantau, awal Februari 2008.
"Biasanya pelapor mempunyai dendam pribadi terhadap korban... Tak ada verifikasi, yang dituduh dapat langsung di-PKI-kan dan selanjutnya dibantai," lanjutnya.
Mustawalad pernah mewawancarai Ibrahim Kadir, penyair asal Gayo, Aceh Tengah, yang sempat ditahan dan terancam dieksekusi.
Belakangan terungkap Kadir ditangkap "karena informasi yang salah". Kadir bukanlah anggota PKI, tetapi PNI.
Dalam risetnya, dia juga menemukan bahwa pembantaian orang-orang yang dituduh PKI di Gayo juga dilatari dendam politik masa lalu.
Ada sejumlah eks-pasukan DII/TII membalas dendam dengan ikut membantai orang-orang yang dicap PKI.
"Rasakan ini pembalasan kami, gara-gara kamu [korban PKI] menjadi milisi, susah sekali kami," ungkap Mustawalad, menirukan suara pelaku pembantaian.
Selama pemberontakan DI/TII di Aceh, PKI mendukung sikap Jakarta yang mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan.
Baca juga:
- Korban 1965: 'Saya bertemu algojo yang menembak mati ayah saya'
- 'Saya dituduh anggota Gerwani yang mencukil mata jenderal'
- Jumat pagi bersama 'algojo pemburu' PKI
Mengunjungi Desa Nosar yang pernah dicap desa 'PKI'
Salah-satu lokasi penelitian Mustawalad adalah Kampung Mude, Desa Nosar, di pinggir Danau Air Laut Tawar, Takengon.
Pada 1965, sedikitnya 60 orang warga dari desa ini dibunuh karena dituduh komunis.
Siang itu, pada pekan ketiga Oktober 2021, ketika langit berwarna alumunium, saya dan videografer BBC News Indonesia, Anindita Pradana, mengunjungi desa nan tenang itu.
Di salah satu sudut kampung itu berdiri sebuah masjid kuno. Di sanalah, kami bertemu Syahbandar, 52 tahun, salah seorang yang 'dituakan'.
Syahbandar mengatakan, tuduhan 'desa PKI' itu sangat melukai warga, karena seolah-olah mereka dianggap antiTuhan.
"Itu tidak benar," katanya berulang-ulang. Dia kemudian mengungkapkan beberapa orang warga Desa Nosar yang dibunuh itu adalah "orang-orang pintar".
"Ada isu (mereka yang ditangkap) adalah anti-Tuhan. Itu harus kami bantah, karena mereka yang tertumpas dan kena tangkap adalah tokoh-tokoh (intelektual dan agama)," ujarnya.
Akan halnya ada sekitar 60 orang warga desa itu dibunuh, menurutnya, karena mereka tidak lari. Termasuk seorang imam di kampung itu
"Mereka tidak lari, karena mereka pikir mereka tidak bersalah dan ini adalah negara hukum," kata Syahbandar.
Dia juga menggarisbawahi bahwa kebanyakan warga Nosar yang dibunuh pada 1965 "tidak tinggal di desa, tapi di kota."
Demi membersihkan desa itu dari stigma PKI, Syahbandar bahkan menemui seseorang ulama berinisial TB yang disebutnya ikut terlibat pembantaian atas orang-orang yang dicap komunis di Aceh Tengah.
Baca juga:
- Malam jahanam di hutan jati Jeglong
- Mengungkap kebenaran, menggelar rekonsiliasi
- 'Dosa turunan' dicap PKI, keluarga penyintas 65 masih mengalami diskriminasi: 'Jangan bedakan kami'
"Dia menyesal, menangis dan bilang 'kenapa kita bodoh', sehingga banyak jatuh korban," ungkapnya.
Di akhir wawancara, Syahbandar mengharapkan peristiwa kekerasan 1965 tidak terulang kembali.
Dia lalu mengutip kata-kata bijak Gayo, yaitu 'agih si belem, genap si nge munge'.
"Sudah cukup, jangan terulang lagi," Syahbandar kemudian menerjemahkannya kepada kami.
Untuk menghilangkan residu konflik 1965 di antara warga desa, mereka pun memiliki cara sendiri, yaitu, menggelar upacara adat.
Siapa yang membakar 'masjid Bebesan' di Takengon pada Juli 1965?
Ingatan kolektif masyarakat di Aceh Tengah terhadap kekerasan 1965, tidak terlepas pula dari keberadaan sebuah masjid di Takengon.
Masjid Raya Quba di Kecamatan Bebesan dilalap api pada 21 Juli 1965, dua bulan sebelum G30S 1965.
Berbagai laporan menyebut pria yang dituduh membakar masjid adalah anggota atau simpatisan PKI. Namanya Islah.
"Islah adalah anak tiri Tengku Abdul Jalil, ulama berpengaruh di Gayo," tulis Mustawalad di Majalah Pantau, 2008. "Tapi Islah dituduh PKI."
Keterangan polisi saat itu menyebut Islah sebagai pelaku pembakaran, walau masyarakat menyangsikannya, ujarnya.
Islah kemudian dieksekusi oleh tentara di dekat Takengon. Mayatnya kemudian dibiarkan di jalanan dalam kondisi memprihatinkan.
"Ususnya terburai dimakan anjing," ungkap Mustawalad mengutip seorang saksi yang berada di lokasi.
Belakangan ketika pecah G30S 1965, peristiwa kebakaran masjid itu menjadi peletup kemarahan warga di Aceh Tengah terhadap siapapun yang dikaitkan dengan PKI.
Di masa Orde Baru, narasi dominan bahwa pelaku pembakaran masjid adalah anggota PKI bernama Islah, terus dipelihara.
Di Takengon, BBC News Indonesia melihat sendiri ada lukisan tentang kebakaran masjid itu yang disebut pelakunya adalah anggota PKI.
Namun kepada sumber BBC Indonesia, salah satu anak tertuduh, mengatakan ayahnya tidak pernah membakar masjid itu.
Beberapa saksi mata juga disebutnya membantah tuduhan itu. Saat masjid terbakar, Islah sedang bersama istrinya.
"Pria itu bahkan berupaya memadamkannya," ungkap sumber BBC News Indonesia.
Kisah tiga orang warga Takengon dan ikhtiar mereka menyembuhkan 'luka 1965'
Lahir dan tumbuh besar di Kota Takengon, Aceh Tengah, tiga orang ini relatif tidak berjarak dengan para keluarga korban 1965 di wilayah itu.
Bahkan ada di antara mereka, anggota keluarganya ditangkap dan dipenjara karena dituduh anggota PKI atau tersangkut G30S 1965.
Dalam cara pandang yang tidak selalu sama, mereka kemudian masing-masing menawarkan 'jalan keluar' — sesuai latar profesinya atau keahliannya — bagi para korban.
Selama liputan tiga hari di Takengon, kami menemui Sri Wahyuni (kelahiran 1978), Win Wan Nur (1976) dan Nanda Winar Sagita (1994).
Berikut petikannya:
'Saya menulis cerpen, hutang saya buat paman saya yang dicap PKI' — Sri Wahyuni, pengacara
Salah-seorang pamannya, yang berlatar atase penerjun di TNI AU, pernah dipenjara di Nusa Kambangan karena dianggap terlibat G30S 1965.
Setelah G30S 1965, pamannya memimpin operasi penangkapan Ketua CC PKI Aidit. Namun operasi ini gagal.
"Dan karena kegagalan itu, paman saya dituduh melindungi Aidit," ungkap Sri. Dia kemudian dijebloskan ke penjara Nusakambangan.
Setelah dibebaskan, sang paman mengalami trauma dan terstigma dicap anggota PKI dan anti Tuhan. "Padahal dia sangat religius," katanya.
Di sinilah, Sri Wahyuni melibatkan diri untuk mengetahui lebih banyak perihal pamannya itu. "Saya mewawancarainya dan mencatat."
Di saat bersamaan, Sri mewawancarai pamannya yang lain. Pada 1965, dia membantu tentara 'mengantar' tahanan ke algojo untuk dieksekusi.
Kepada Sri, pamannya ini sempat menangis dan menyesal atas keterlibatannya itu. Selanjutnya dia menolak tugas itu.
"Saya melihat kesedihan wajah paman-paman saya," katanya. "1965 merupakan masa paling mengerikan."
Di sinilah, Sri memutuskan untuk menulis tentang pengalamannya tersebut. "Tapi menulis tentang tema PKI itu sangat berat."
Dia tidak mau tulisannya nanti akan menimbulkan "masalah baru", karena menurutnya stigma terhadap penyintas itu belum hilang.
"Karena masih ada kampanye yang terus menerus, seolah-olah PKI masih ada... Sehingga untuk bicara komunisme, masih sesuatu yang mengerikan," jelasnya.
Dalam konteks seperti itu, dibutuhkan pendekatan yang tidak frontal, seperti melalui pengenalan sejarah, misalnya. "Mungkin di forum ilmiah atau menulis buku."
Sri Wahyuni memilih menulis fiksi sebagai healing (menyembuhkan) dirinya sendiri, karena "saya seperti menerima kesedihan paman saya."
"Utang saya kepada paman saya adalah menuliskannya. Bisa jadi nama baik paman saya dipulihkan, sehingga orang tahu paman saya tidak ateis," kata Sri Wahyuni.
'Saya menulis, agar orang tahu ketidakadilan yang dialami penyintas 1965' — Win Wan Nur, jurnalis dan penulis
Win Wan Nur memilih mengungkapkan tragedi 1965 di kota kelahirannnya itu dengan menulis sebuah novel.
Lima tahun lalu, dia meluncurkan novel berjudul Romansa Gayo dan Bordeaux.
Walaupun berkisah tentang percintaan, Win mengaku menyisipkan 'percakapan' tentang tragedi G30S di beberapa halaman novelnya.
Kesadarannya untuk memasukkan potongan kisah 1965 dilatari apa yang disebutnya "ketidakadilan" yang dialami para penyintas 1965.
"Setelah saya melihat bagaimana kehidupan mereka, bagaimana mereka mencoba bertahan hidup dengan keadaan itu, saya pikir orang perlu tahu," katanya saat kami temui di Takengon, pekan ketika Oktober 2021 lalu.
Pilihannya menulis novel, karena Win Wan Nur meyakini para pembaca akan dapat memasuki jalan ceritanya.
"Bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang hidup dengan orang tua yang dituduh PKI, hidup dengan stigma, itu dapat tergambarkan," paparnya.
"Kalau saya menuliskannya dalam bentuk laporan seperti itu, nanti saya dikesankan seolah membela mereka, dan pro ke ideologi itu [komunisme]," jelas Win Wan Nur. "Ini akan timbulkan gejolak."
Terlepas dari pilihannya untuk menuliskannya dalam bentuk novel, dia sampai pada satu titik bahwa diperlukan "pemahaman situasi" di mana para penyintas itu hidup.
Dia menekankan hal ini karena belum hadirnya negara untuk mendampingi para korban 1965 di Gayo.
Saat ini diperlukan cara yang tepat agar para korban itu justru tidak makin tersudut jika caranya tidak tepat.
"Kita tidak bisa melakukan pendekatan seragam untuk setiap kelompok masyarakat," ujarnya.
"Karena banyak korban [1965], tiap orang pasti punya kenangan personal. Entah kerabat melalui perkawinan, entah sepupu... Semua orang di Gayo pernah merasakannya," jelas Win Wan Nur.
Karena itulah, menurutnya, kalau ada upaya untuk mengungkap kekerasan 1965, selalu orang luar yang melakukannya.
"Kalau diangkat, bagaimana lukanya lagi, bagaimana sakitnya lagi," katanya.
'Saya tidak ajak murid-murid memihak PKI dan membenci militer' — Nanda Winar Sagita, guru sejarah di SMAN di Takengon
Nanda Winar Sagita terus mencari tahu tentang kekerasan 1965 di Aceh Tengah setelah membaca buku pledoi salah-seorang pimpinan PKI di Aceh, Thaib Adamy, Atjeh Mendakwa.
Dari sanalah, Nanda melakukan riset kecil-kecilan dengan membaca dan bertanya langsung keluarga korban.
"Kebanyakan yang menjadi korban itu orang-orang yang tidak tahu apa-apa," katanya saat ditemui BBC News Indonesia di Takengon, Oktober lalu.
"Mereka menjadi korban keadaan dari politik dan konflik yang terjadi 'di atas', di kalangan elit politik," tambahnya.
Di sisi lain, Nanda mendapati buku-buku sejarah seputar 1965 masih didominasi versi tertentu peninggalan Orde Baru. Dan sebagian besar murid-muridnya masih berpijak dari buku-buku seperti itu.
"Di sana memang berat sebelah, PKI selalu distigma sebagai penjahat, paling bersalah," ujarnya. Diakuinya PKI juga terlibat dalam peristiwa pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat pada 1965.
Menurutnya, salah-satu cara untuk memberikan perspektif lebih segar tentang peristiwa 1965 di Aceh Tengah adalah melalui anak didiknya di sekolah.
"Karena siswa-siswa ini masih mudah dibentuk pola pikirnya," katanya.
Tentu saja, Nanda menekankan bahwa dirinya tidak mengajarkan kepada mereka untuk berpihak kepada PKI atau membenci militer.
"Tetapi mereka harus berdiri di tengah. Bagaimana memandang kasus itu secara netral. Bagaimana memandang kasus G30S secara obyektif," jelasnya.
Dari cara pandang sepeeri itu, Nanda menggarisbawahi bahwa dirinya juga berusaha memberikan materi sejarah yang semangatnya tidak mewariskan dendam dan konflik baru.
"Kami hanya mencoba kepada mereka bagaimana caranya bisa bersikap lebih progresif dalam memandang suatu kasus," katanya.
"Jangan hanya terpaku pada stigma-stigma di masyarakat terus kita takut untuk membuka diri. Terus kita ikut-ikutan sesuatu yang sebenarnya sejak awal sudah keliru," tandasnya.
Wawancara Jess Melvin, sejarawan dari Australia:
'PKI memiliki banyak musuh di Aceh, tapi tanpa ada pengumuman militer, tak mungkin ada pembantaian'
Peneliti dari Australia, Dr Jess Melvin meneliti pembantaian orang-orang yang dituduh anggota dan simpatisan PKI di Aceh hampir 10 tahun.
Dia meneliti 3.000 halaman dokumen arsip militer di Aceh dan meneliti catatan, rekaman, dan hasil wawancara 70 orang yang selamat, eksekutor, dan saksi mata dalam aksi kekerasan 1965 di Aceh.
Dari penelitian itulah, dia kemudian menyusun disertasi yang diujikan di Universitas Melbourne pada 2014.
"3.000 halaman dokumen itu," kata Jess Melvin, "membuktikan keterlibatan militer Indonesia dalam pembunuhan massal 1965-1966."
Kesimpulan penelitiannya juga menunjukkan sebuah koordinasi tingkat tinggi dan terpusat yang bisa ditelusuri rantai komandonya hingga ke Suharto di Jakarta.
Hasil penelitiannya itu kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul The Army and The Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder (2018).
Buku ini sedang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Komunitas Bambu dan bukunya akan diterbitkan dalam waktu dekat.
Saya mewawancarai Jess Melvin melalui sambungan zoom pada Selasa, 9 November 2021, dan berikut petikannya:
Apa bukti bahwa pembantaian 1965 di Aceh merupakan perintah dari pimpinan militer di Jakarta?
Ada pengumuman militer Indonesia, pada pagi 1 Oktober 1965, yang menyatakan militer harus siap. Malam harinya, sudah ada perintah langsung dari militer, bahwa PKI harus ditumpas.
Untuk melakukan itu, militer memakai rantai komando yang sudah disiapkan sebelumnya.
Pada pagi 1 Oktober 1965, militer mampu menerapkan darurat militer yang sudah mulai di Sumatera, dan mereka memakai semua struktur itu.
Mulai 1 Oktober 1965 sudah ada koordinasi dan melakukan pembunuhan massal.
Anda mengatakan kekerasan 1965 di Aceh sebagai yang pertama di Indonesia?
Ini semua sangat kompleks. Kalau kita melihat bukti militer, ya. Kita punya tanggal spesifik untuk tanggal 9 Oktober di Aceh Barat, itu korban pertama. Ada nama, ada tempat, dan alasan kenapa dibunuh. Ini ditulis oleh militer sendiri.
Tapi apakah itu yang pertama, kita tidak tahu. Pasti ada pembunuhan di tempat lain.
Namun kalau berdasarkan catatan militer sendiri, itu pembunuhan pertama dimulai di Aceh.
Saya tidak berpikir militer memiliki rencana untuk memulai pembunuhan massal di Aceh. Mereka keluarkan pengumuman itu secara nasional, tapi Aceh paling siap untuk bergerak, dan untuk memulai prosesnya.
Aceh dikatakan paling siap karena struktur komando memang membuat mereka siap. Atau ada faktor lain, misalnya, pimpinan tentara di Sumatera termasuk golongan anti komunis?
Ada beberapa alasan. Misalnya, kalau di Aceh, baru saja berakhir pemberontakan Darul Islam (DI/TII). Jadi militer sudah kuat di Aceh.
Di wilayah Sumatera, militer juga kuat. Itu menjadi contoh bagi negara, untuk menjalankan rezim militer di Indonesia.
Mana yang lebih dulu, fatwa ulama di Aceh yang 'menghalalkan' membunuh orang-orang PKI, atau keputusan militer di Jakarta untuk melakukan pembasmian sampai ke akar-akarnya?
Kalau pengumuman militer untuk menghancurkan dan bunuh orang PKI itu keluar 1 Oktober 1965. Itu sudah dari awal.
Pada 4 Oktober 1965, militer sudah menyuruh masyarakat ikut dalam kampanye untuk membantu membunuh. Jadi sejak awal Oktober 1965.
Kalau masalah fatwa ulama di Aceh, itu baru terjadi pada Desember 1965. Jadi dua bulan setelah pembunuhan dimulai.
Malah fatwa itu keluar waktu pembunuhan massal sudah selesai di Aceh.
Dan itu terjadi dalam konteks, ketika Panglima Antar Daerah Sumatera Letnan Jenderal Ahmad Mokoginta datang ke Banda Aceh untuk bilang 'kita sudah membunuh PKI, sekarang kita sudah bisa membuat yang lain'.
Dia membuat pengumuman di depan Masjid Raya di Banda Aceh, dan di situ dia mengajak ulama ikut dia. Fatwa itu dikeluarkan di situ.
Jadi, itu menjadi alasan kenapa itu 'sah', kenapa mereka tidak bersalah, ikut dalam kampanye militer.
Dan ulama dipakai sebagai alat oleh militer pada waktu itu. Kita juga perlu ingat, hal ini baru setelah terjadi pemberontakan Darul Islam di Aceh.
Jadi para pemimpin Islam juga harus cari perhatian kepada militer saat itu. Mereka dianggap musuh sebelumnya. Tapi sekarang mereka saling mendekat dan bersama-sama.
Apakah dari temuan Anda di lapangan, ada bukti bahwa pembunuhan terhadap orang-orang yang dicap PKI di Aceh, juga spontanitas masyarakat?
Bagaimana itu spontanitas masyarakat? Dari 1 Oktober 1965, sudah ada perintah militer untuk menghancurkan dan membunuh semua anggota PKI.
Dan mulai 4 Oktober 1965, masyarakat sudah disuruh untuk ikut.
Jadi pembunuhan itu terjadi dalam konteks masyarakat 'harus ikut' atau mereka akan dituduh sebagai PKI.
Itu yang dibuat oleh Pangdam I/Iskandar Muda, Brigadir Jenderal TNI Ishak Juarsa, yang keliling daerah, dan membuat itu menjadi sangat jelas.
Dan, kalau ada masyarakat Aceh yang bersemangat untuk ikut menumpas PKI, itu pasti ada.
PKI itu juga banyak musuh di Aceh. Tapi kalau itu akan terjadi tanpa ada pengumuman dari militer, saya rasa itu tidak mungkin.
Apakah selama riset, Anda juga menemukan bukti seperti apa detil peranan militer, apakah sampai ke hal teknis, misalnya menyediakan truk untuk mengangkut tahanan PKI?
Untuk proses memfasilitasi pembunuhan, ya kita dapat bukti itu. Misalnya ada surat berisi nama-nama orang yang diambil dari penjara militer dan dibawah untuk dibunuh. Semua itu ada.
Kita juga dapat dokumen dari Aceh Utara, yang menjelaskan berapa senjata yang dipegang oleh Hansip dan Hanra di pos penjagaan untuk membunuh PKI. Semua ada di situ, dan sangat detil.
Itu bukti dokumen internal TNI yang Anda temukan?
Ya. Ini kampanye nasional. Dan ini perlu organisasi yang sangat kuat untuk menjalankan seperti ini.
Jadi kita ada catatan dari semua rapat-rapat yang ada. Kita tahu apa yang mereka putuskan di situ. Dan bagaimana pembunuhan itu dilakukan.
Sampai militer merekam berapa orang yang dibunuh di jalan-jalan waktu itu. Ada peta yang mereka buat. Mereka sangat tahu apa yang terjadi waktu itu. Mereka rekam semua.
Dan peta itu tertera dalam buku Anda, 'peta kematian'?
Ya, di setiap kabupaten, mereka mencatat berapa orang yang dibunuh di jalan-jalan.
Selain itu, kita mendapatkan bukti bahwa proses pembunuhan berjalan sistematis dengan wawancara orang-orang yang ikut dalam proses itu.
Apakah penelitian Anda juga menemukan metode eksekusi yang terjadi di Aceh pada tahun-tahun itu? Apakah setiap kota sama, atau ada kekhususan setiap daerah?
Ada pola besar yang bisa kita lihat di seluruh Aceh, dan ada pula pola khusus di kabupaten tertentu.
Jadi, kalau pola besar, yang kita lihat, pembunuhan itu dimulai dengan demonstrasi. Lalu militer keluar, memberi perintah agar orang-orang harus bergabung.
Setelahnya, mereka mendatangi ke kantor dan rumah pimpinan PKI, menggelar demonstrasi di sana.
Kemudian, apabila mereka menangkap anggota PKI di lokasi, rata-rata mereka dibunuh di situ juga.
Mayatnya ditemukan di sana. Itu pembunuhan di tempat umum. Itu terjadi di seluruh Aceh.
Selanjutnya, banyak orang-orang PKI yang berada di dalam penjara. Ada keputusan baru untuk membawa mereka ke tempat pembunuhan.
Nah, mereka biasanya dibawah naik truk militer ke tempat itu.
Nah, di setiap kabupaten, ada pola yang sedikit berbeda, misalnya di Banda Aceh. Kita tahu itu militer yang menembak langsung para tahanannnya. Ini yang terjadi pada pimpinan PKI Thaib Adamy yang ditembak di Lhoknga.
Di Takengon, militer juga ikut langsung dalam pembantaian. Mereka yang memotong leher atau menembak korban.
Tapi juga ada tempat di mana mereka menggunakan 'orang-orang politik' seperti di Aceh Barat. Mereka menggunakan 'orang pemerintah' untuk ikut dalam proses pembunuhan.
Di Lhokseumawe, ada kasus mereka merekrut warga sipil untuk melakukannya. Mereka diancam untuk ikut dalam proses pembunuhan.
Tapi, kalau mau melihat pola besar, ini semua dalam konteks militer yang melakukan rencana untuk menghanccurkan dan menumpas sampai habis PKI di Aceh.
Dalam penelitian Anda, apakah Anda juga menemukan sebagian besar orang yang dibunuh, adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa atau hanya ikut-ikutan, dan bahkan tidak berafiliasi dengan PKI?
Ya, ini memang modus operandi militer Indonesia, yang sama dengan konflik di Aceh kemarin.
Tapi kalau tahun 1965, yang bisa kita lihat, targetnya itu golongan komunis di Indonesia.
Jadi, mereka membunuh kader, pemimpin politik PKI. Habis itu juga ada pemimpin organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI. Misalnya Gerwani, Pemuda Rakyat, dll. Mereka juga diserang.
Habis itu ada keluarga mereka, istri, ada anak-anak yang juga dibunuh pada waktu itu.
Terus orang yang mungkin satu kampung sama orang PKI juga diserang, dan dituduh PKI.
Sampai juga ada orang yang kerjsama dengan mereka, kawan dan rekannya dan juga komunitas Tionghoa diserang seluruhnya.
Padahal, hanya sebagian dari komunitas Tionghoa itu pro-komunis. Tapi semuanya diserang pada waktu itu.
Jadi, itu kelompok yang jauh lebih besar daripada anggota PKI saja, sengaja diserang, seperti itu biar habis dibunuh.
Apakah penelitian Anda juga berhasil mengungkap berapa jumlah orang yang dibunuh di Aceh?
Kita tidak tahu dengan pasti berapa orang yang dibunuh di Aceh. Tapi kita tahu dari catatan militer sendiri yang dibunuh di tempat umum, itu 2.000 orang.
Nah, menurut Panglima Antar Daerah Sumatera, Letjen Ahmad Mokoginta, ada 6.000 orang yang dibunuh di Aceh.
Dari riset saya di beberapa kabupaten, kemungkinan rata-rata 10.000 orang dibunuh.
Tapi kalau ingin melakukan riset lebih mendalam, harus pergi ke setiap daerah, ke setiap kabupaten. Kalau itu tidak dilakukan, kita tidak akan tahu angkanya. Dan riset seperti itu belum dibuat.
Tulisan ini merupakan bagian dari liputan khusus Pembantaian massal 1965 di Aceh — Kisah Algojo, korban terlupakan dan upaya penyembuhan di situs BBC News Indonesia.
Anda juga bisa menyimak kisah ini di Siaran Radio Dunia Pagi Ini BBC Indonesia dan siniar kami di Spotify.
Produksi visual oleh Anindita Pradana. Grafis oleh tim jurnalis visual East Asia BBC News.