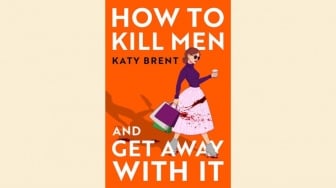Suara.com - Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dipandang sebagai suatu langkah yang progresif oleh sejumlah pihak di tengah keresahan akan tingginya kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi.
Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan aturan ini merupakan respons atas kegelisahan di lingkungan kampus atas meningkatnya kasus kekerasan.
"Kita juga mengalami pandemi kekerasan seksual [kalau dilihat] dari data apa pun," kata Nadiem melalui dialog virtual pada Jumat (12/11).
Namun, aturan tersebut ternyata menuai perdebatan di media sosial. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah mencabut atau merevisi Permendikbud tersebut karena keberatan dengan frasa terkait persetujuan korban atau yang juga dikenal dengan istilah consent.
Baca Juga: Permendikbudristek PPKS Penting Hadir di Kampus Agar Tak Ada Kekerasan Seksual
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera juga menyatakan melalui akun Twitter-nya, bahwa frasa "tanpa persetujuan korban" dia maknai sebagai "pelegalan kebebasan seks".
Pendapat serupa juga disampaikan oleh salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah yang menyatakan bahwa peraturan ini "mengandung unsur legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan".
https://twitter.com/muhammadiyah/status/1458795372264898565?s=20
Seberapa urgen situasi kekerasan seksual di kampus?
Merujuk pada survei yang dilakukan Kementerian Pendidikan pada 2020, sebanyak 77% dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Namun, 63% di antaranya tidak melaporkan kejadian itu karena khawatir terhadap stigma negatif.
Selain itu, data Komisi Nasional Perempuan menunjukkan terdapat 27% aduan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi, berdasarkan laporan yang dirilis pada Oktober 2020.
Baca Juga: Permen Anti Kekerasan Seksual di Kampus Jadi Polemik, Nadiem Ungkit Nasib 3 Anaknya
Menurut Menteri Nadiem, kasus kekerasan seksual yang sejauh ini terungkap di kampus hanya lah "puncak gunung es" dari puluhan ribu, bahkan ratusan ribu kasus yang sebenarnya terjadi.
Sementara itu, pihak universitas kerap kali kebingungan menangani laporan kekerasan seksual karena sebelumnya tidak ada aturan dan panduan yang jelas terkait itu.
"Ini memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas," kata Nadiem.
Lewat peraturan tersebut, maka kampus wajib membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
'Kampus belum jadi ruang yang aman'
Seorang mahasiswi berinisial H, yang enggan disebutkan namanya, berpendapat penerbitan Permendikbud ini bagaikan titik terang dan memberi kepastian hukum atas penanganan kekerasan seksual di kampus.
Mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat ini pernah merasakan sulitnya menuntut keadilan teman-temannya yang mengalami kekerasan seksual di kampus.
Pelaku dari kekerasan seksual tersebut juga merupakan mahasiswa di fakultas yang sama dengan dia, dan dikenal sebagai sosok yang berprestasi.
"Awalnya kami takut melaporkan ini karena khawatir pelaku akan dibela, tapi ternyata Kepala Prodi kami terbuka dan membela korban," kata dia.
Namun, begitu isu ini diangkat ke tingkat fakultas dan universitas, mereka sempat berhadapan dengan pihak-pihak yang meragukan kesaksian korban.
"Bahkan laporan kami diprosesnya sampai berbulan-bulan," tutur H.
Baca juga:
- Dugaan pelecehan seksual di universitas: Peraturan Menteri soal pencegahan kekerasan seksual 'rawan digembosi'
- Korban dugaan pemerkosaan Kapolsek Parigi 'sering menangis histeris', mampukah sanksi tegas Kapolri ditegakkan?
- Kasus dugaan pelecehan di KPI disebut bagian dari 'fenomena gunung es' di lembaga negara
Menurut pengakuan H, bahkan ada salah satu pihak yang meminta agar korban menempuh jalur damai. Namun, mereka menolak.
Sampai saat ini, dia mengatakan belum ada penyelesaian yang tuntas atas kasus tersebut.
"Pelakunya memang digantung oleh fakultas, enggak dilulusin, ijazahnya enggak keluar, tapi dia masih bisa kerja dimana-mana," tutur H.
Situasi ini juga membuat H merasa bahwa kampusnya bukan ruang yang aman.
"Saya takut sih, andai saya yang menjadi korban mau ngadu ke siapa? Siapa yang menindak? Saya pun enggak powerful untuk menindak dia [pelaku].
"Apalagi melihat dia [pelaku] masih bisa hidup tenang dan bahagia, sanksi sosial itu enggak cukup. Enggak adil aja rasanya," ujar H.
Dia berharap penerbitan Permendikbud ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan ruang yang lebih aman di kampus.
"Setidaknya jadi ada seruan untuk universitas agar concern ke isu ini," kata dia.
H juga menyayangkan penolakan terhadap Permendikbud itu, sebab kasus kekerasan seksual bukan lagi hal yang jarang dia dengar, tidak hanya di kampusnya sendiri juga dari berbagai universitas lain di Indonesia.
https://twitter.com/tunggalp/status/1457935226621988867?s=20
Mengapa MUI menolak konsep 'consent'?
Salah satu poin keberatan MUI, menurut Wakil Ketua Komisi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan MUI Pusat, Wido Supraha, ada pada Pasal 5 dari Permendikbud 30/2021.
Dalam pasal itu, kekerasan seksual didefinisikan mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
Pasal itu juga menjabarkan berbagai jenis tindakan kekerasan seksual yang dilakukan "tanpa persetujuan korban". Frasa ini lah yang ditolak oleh MUI.
"Kata tersebut bermakna bahwa transaksi atau aktivitas seksual di luar nikah selama dilakukan suka sama suka (sexual consent) menjadi tidak diatur, dan dunia pendidikan tidak menghukuminya," kata Wido kepada BBC Indonesia.
Baca juga:
- Dugaan pelecehan seksual di universitas: Peraturan Menteri soal pencegahan kekerasan seksual 'rawan digembosi'
- Korban dugaan pemerkosaan Kapolsek Parigi 'sering menangis histeris', mampukah sanksi tegas Kapolri ditegakkan?
- Kasus dugaan pelecehan di KPI disebut bagian dari 'fenomena gunung es' di lembaga negara
MUI juga meminta agar frasa "kekerasan seksual" diganti menggunakan "kejahatan seksual" karena dianggap "lebih komprehensif dibanding kekerasan seksual".
"Hakikat sebuah kejahatan seksual adalah transaksi atau aktifitas seksual baik 'dengan persetujuan' ataupun 'tanpa persetujuan'.
"Jika frasa 'tanpa persetujuan' dihapuskan, maka seluruh transaksi dan aktifitas seksual, menjadi sebuah kejahatan seksual," ujar Wido.
Sementara itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim menolak Permendikbud tersebut ditafsirkan sebagai dukungan atas pelegalan seks bebas.
"Kemendikbud tidak pernah mendukung seks bebas atau zina. Ini terjadi karena adanya klausul yang diambil di luar konteks," kata Nadiem.
Apa itu consent dalam kerangka kekerasan seksual?
Aktivis perempuan dari Forum Pengada Layanan, Veni Siregar mengatakan 'sexual consent' berarti persetujuan atas tindakan seksual yang diterima seseorang.
Dalam konteks kekerasan seksual, consent menunjukkan persetujuan korban atas tindakan seksual yang terjadi padanya.
Tanpa consent atau izin atau ketidaksetujuan itu lah, kata dia, yang kemudian menjadi penentu bahwa korban telah mengalami kekerasan seksual.
Consent juga harus diberikan oleh seseorang secara sadar dan sukarela, tanpa ada tekanan dari pihak lain.
Selain itu, consent juga bisa ditarik kembali. Menyetujui salah satu tindakan seksual, bukan berarti menyetujui seluruh jenis tindakan.
"Consent itu dimaknai untuk melihat ketidakberdayaan korban dari ketidaksetujuannya atas kekerasan yang terjadi. Ini yang menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan," kata Veni kepada BBC Indonesia.
Di dalam Permendikbud 30/2021, ketentuan mengenai consent diatur dalam pasal 5, yang mengatur apabila korban tidak memberi persetujuan, maka tindakan itu dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual.
Persetujuan itu juga dianggap tidak sah apabila usia korban belum dewasa, mendapat ancaman karena pelaku menyalahgunakan kedudukan, korban berada di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, atau narkoba, serta ketika korban sakit, tidak sadar, atau tertidur.
Apa dampaknya jika consent dihilangkan dari Permendikbud 30/2021?
Menurut Veni, prinsip consent justru menjadi jantung dari Permendikbud tersebut dan apabila frasa "tanpa persetujuan korban" dihilangkan, maka aturan tersebut menjadi tidak berguna.
Menghilangkan frasa tersebut justru bisa membuat posisi korban semakin rentan karena tidak ada lagi penegas yang membatasi bahwa dia adalah korban kekerasan seksual. Begitu juga dengan mengubah frasa "kekerasan seksual" menjadi "kejahatan seksual" seperti yang yang diusulkan oleh MUI.
"Itu berarti MUI tidak pro kepada korban," kata Veni.
"Kejahatan seksual itu hanya fokus pada pelaku, kekerasan seksual itu fokus pada pencegahan dan pendampingan korban, juga supaya menimbulkan efek jera pada pelaku," kata dia.
Realitanya, kata Veni, banyak korban sulit mendapatkan keadilan karena ketidaksetujuannya akan tindakan kekerasan seksual sering kali dikesampingkan dalam proses hukum.
"Sering kali dalam kasus kekerasan seksual yang kami dampingi, polisi dan pihak kampus mengatakan peristiwa itu suka sama suka karena sudah sama-sama dewasa," kata Veni.
Lalu, apakah persetujuan atas tindakan seksual kemudian dapat dipandang sebagai upaya melegalkan perzinaan?
Baca juga:
- Dugaan pelecehan seksual di universitas: Peraturan Menteri soal pencegahan kekerasan seksual 'rawan digembosi'
- Korban dugaan pemerkosaan Kapolsek Parigi 'sering menangis histeris', mampukah sanksi tegas Kapolri ditegakkan?
- Kasus dugaan pelecehan di KPI disebut bagian dari 'fenomena gunung es' di lembaga negara
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan konsep consent yang tercantum pada Permendikbud tidak serta merta bisa diartikan sebagai upaya melegalkan perzinaan.
"Tidak semua yang tidak diatur [di dalam Permendikbud] itu menjadi boleh. Judulnya saja pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, bukan mengatur tindakan kesusilaan," kata Bivitri.
"Kita kan tidak hidup hanya dalam norma hukum, kita hidup dalam norma kesusilaan dan lain-lain. Tidak semua harus diangkat dalam peraturan Menteri," lanjut dia.
Menurut Bivitri, Permendikbud 30/2021 justru hadir untuk mengisi kekosongan hukum atas maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang tidak bisa dijangkau oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Pasalnya, mahasiswa yang rata-rata berusia mulai dari 18 tahun sudah bukan lagi tergolong sebagai anak untuk bisa dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Mayoritas juga belum menikah untuk bisa mengacu pada UU PKDRT.
Permendikbud ini, kata dia, menjadi jawaban atas kekosongan tersebut untuk menciptakan ruang yang lebih aman bagi seluruh pihak di perguruan tinggi.