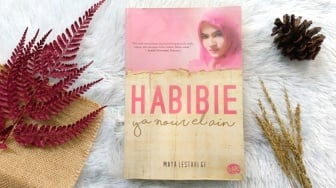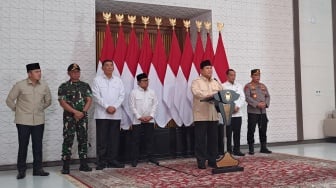Suara.com - Amar Alfikar, 30 tahun, terlahir sebagai perempuan dari keluarga pesantren. Sang ayah adalah kiai, penceramah ulung yang dihormati.
Tapi, ketika dewasa, pikiran Amar buncah, merasa dirinya bukan lelaki melainkan perempuan. Hanya tubuhnya saja yang perempuan.
Setelah bertahun-tahun hidup dalam kegelisahan, Amar memutuskan untuk bertransisi menjadi laki-laki.
"Ibu, saya bukan perempuan dan saya tidak bisa suka dengan laki-laki," kata Amar ketika melela pada ibunya.
Baca Juga: Fakta Baru Terungkap! Ada Pertemuan Diduga Untuk Akali Pencairan Dana Hibah Ponpes
Amar menceritakan pergulatan batinnya dalam transisi, dan bagaimana dia melibatkan keluarga dan komunitasnya dalam perubahannya, dari yang tadinya berjilbab menjadi bersarung.
Juga, bagaimana dia mencari tempatnya sebagai transpria dalam agamanya, Islam.
Wartawan BBC Indonesia Famega Syavira Putri dan Dwiki Marta menemui Amar di rumah dan pesantren keluarganya di Kendal, Jawa Tengah, Agustus lalu.
Inilah penuturan Amar.
Nama saya Amar Alfikar dan saya adalah transpria
Sejak kecil saya merasa berbeda, berada di kotak yang tidak sesuai dengan apa yang saya rasakan. Waktu kecil, saya merasa kenapa saya dianggap sebagai anak perempuan, tapi saya tidak merasa perempuan.
Baca Juga: Peneliti Malaysia: Taliban Bisa Belajar dari Indonesia soal Sekolah untuk Perempuan
Saya tidak tahu ini apa, karena masih kecil. Orang bilang tomboy saja, seiring berjalannya waktu akan berubah. Tapi nyatanya tidak. Perasaan ketidakperempuanan saya terus muncul dan semakin menyiksa ketika diharuskan memakai jilbab di sekolah.
Saya beberapa kali ke psikolog, dan didiagnosis punya gender dysphoria. Ini adalah kondisi di mana kesadaran gender saya laki-laki meskipun secara biologis betina.
Saya juga tidak ingin seperti ini. Siapa yang ingin hidup susah, bergulat dengan dirinya sendiri, itu hal yang sangat berat. Kalau ditanya apakah saya ingin menjadi transpria, saya bisa jawab, saya tidak ingin hidup seperti ini.
Menjadi transpria itu bukan soal keinginan menjadi laki-laki, menjadi transpuan itu bukan ingin menjadi perempuan. Ini soal memilih kemerdekaan diri sendiri, memilih hidup merdeka dari kebencian terhadap diri sendiri.
Saya percaya Allah memberikan akal, fitrah manusia untuk berpikir, merenung dan melihat ke dalam diri kita sendiri.
Allah memberikan kita fitrah tubuh agar kita memperlakukannya dengan baik. Dan tubuh itu tidak sekadar yang terlihat secara fisik, tapi takdir fitrah juga wujud yang tidak terlihat, seperti pengalaman, pemikiran, kesadaran.
Sebagai trans, saya meyakini penuh bahwa apa yang saya jalani adalah bagian dari takdir yang Allah berikan. Kalau saya menyerah, tidak memperjuangkannya, maka justru saya yang melanggar takdir Allah itu, artinya saya tidak memperjuangkan kemerdekaan dan ketenangan batin saya sendiri.
Saya percaya bahwa takdir itu apa yang kita upayakan sendiri.
Saya telah mencoba menjalani hidup belasan tahun sebagai perempuan. Tapi jiwa ini tidak bisa dibohongi. Saya laki-laki. Saya tidak bisa merasa bahwa tubuh ini adalah tubuh perempuan. Tubuh saya, kesadaran saya, jiwa saya, adalah laki-laki.
Ada momen-momen di mana saya melakukan tindakan menyakiti diri sendiri, melukai diri dengan silet.
Karena stigma masyarakat kita dari dulu mengatakan bahwa orang yang berbeda kesadaran gender dan seksualitas adalah orang yang berpenyakit, maka mau tidak mau itu terinternalisasi dalam diri saya.
Itu juga yang mungkin membuat saya menyakiti diri sendiri, membenci diri sendiri, dan merasa saya tidak layak dihargai karena saya berpenyakit.
Saya benci diri saya dan hidup saya.
Pada tahun 2012 saya berangkat haji dengan ibu saya. Saya hanya membatin, sepanjang haji itu doa saya adalah, "Ya Allah, tunjukkan siapa diri saya sebenarnya karena saya tidak mengenal diri saya dan itu menyakitkan".
Saya tidak bisa mencintai diri saya, karena saya tidak tahu diri saya siapa. Setelah saya pulang haji, kegelisahan ditempatkan sebagai perempuan itu justru semakin kuat.
Momennya adalah dorongan itu, bahwa saya tidak bisa terus menerus membohongi diri sendiri, saya tidak bisa terus menerus bertahan karena ini menyakitkan.
Mau tidak mau saya harus memilih kebahagiaan dan kemerdekaan sendiri. Harus sembunyi dan menjadi orang lain itu sangat menyiksa. Ini yang membuat saya merasa harus bercerita pada keluarga.
Awalnya saya mengira saya akan diusir, karena merasa keluarga besar tidak mungkin menerima saya.
Kakek saya mendirikan pesantren pada tahun 1973 dan diteruskan oleh orang tua saya. Sejak lahir saya tinggal di pesantren, meskipun tidak ikut nyantri di sini, tapi ikut mengaji pada orang tua saya. Kemudian saya menjalani pendidikan di MI, MTS, dan pesantren tahfizul Quran.
Jadi bisa dikatakan saya menghabiskan sebagian besar waktu hidup saya untuk belajar di lingkungan pesantren yang setiap hari mengaji Quran, mengaji kitab, berjamaah bersama dan ritual-ritual ibadah yang lain.
Di luar sana, berita yang muncul adalah para trans diusir ketika mereka mengaku pada keluarganya. Berita dan realitas itu yang membuat saya menduga bahwa saya juga pasti akan diusir.
Saya menduga bahwa orang tua saya akan menjadi pihak dalam keluarga yang akan paling membenci.
Tapi ketika saya bercerita kepada Ibu, beliau justru menjadi orang pertama dalam keluarga yang menerima. Kami mengobrol selama tiga jam. Itu obrolan terpanjang saya dan Ibu karena dulu kami begitu jauh.
"Ibu, saya bukan perempuan dan saya tidak bisa suka dengan laki-laki, saya tidak nyaman dengan pakaian perempuan dan saya tidak nyaman ditempatkan sebagai perempuan," kata saya waktu itu.
Ibu saya tentu bingung. "Maksudnya apa, kamu kan perempuan?" Saya menjawab, "Tapi saya tidak merasa perempuan".
Selama tiga jam percakapan kami, saya melihat Ibu mencoba memahami, mendengarkan. Meskipun ada kegelisahan, Ibu bertanya, dan mendengarkan lebih banyak jawaban.
Di tengah kebingungannya, Ibu menerima. Bagi saya, momen itu adalah titik balik. Saya yang tadinya sudah mengepak barang dan siap keluar dari rumah, jadi menahan diri karena Ibu juga mengatakan, "Jangan pernah tinggalkan keluarga ini, kamu tetap anak Ibu dan Bapak".
Ibu memeluk saya dan mengatakan, "Ibu semakin sayang sama kamu".
Proses perubahan saya berlangsung pelan-pelan, saya tidak pernah pergi dari rumah ini untuk tiba-tiba datang dengan diri yang berbeda. Saya membiasakan keluarga dan orang-orang melihat transisi saya, dari yang tadinya berjilbab jadi bersarung.
Mereka melihat momen-momen itu, detik detik, hari demi hari saya bertransisi, dan melihat saya sebagai manusia. Saya bagian dari keluarga ini dan bukan orang yang berbeda dari sebelumnya.
Tentu ada debat, penolakan, orang bertanya-tanya, orang nyinyir dan memaki, dan memperlakukan tidak baik. Saya terima itu sebagai bagian dari proses mereka. Saya percaya bahwa transisi bukan hanya tentang saya, tapi orang lain belajar bertransisi juga untuk menerima.
Awalnya itu beban berat. Sebelum melela atau cerita kepada orang tua, saya juga mempertanyakan ketuhanan dan keislaman saya, yang saya pikir tidak bisa menerima. Karena dari yang saya baca dan saya lihat pada waktu itu, stigmanya dan stereotipnya transgender itu bukan bagian dari Islam.
Sebelum transisi, saya melihat dan meyakini narasi agama yang selalu mengatakan bahwa Islam menolak transgender, bahwa transgender adalah ahli neraka, tidak berhak mendapatkan kasih Allah, bahkan tidak layak diperlakukan adil. Tansgender adalah mahkluk barat yang asing dan begitu najis.
Dulu, meskipun dibesarkan di pesantren, saya sering meragukan kehadiran Tuhan dan rahmat Allah karena saya tidak pernah merasa hangat dengan diri saya sendiri, orang tua, dan keluarga.
Dulu saya sangat marah kepada Allah, setiap salat saya merasa, salat saya ini untuk apa? Saya tidak menemukan ketenangan. Saya tidak merasa ada makna-makna di balik Islam saya.
Namun, saya merasa Tuhan sedemikian dekat ketika saya bertransisi. Penerimaan orang tua menuntun saya menyadari kebesaran Tuhan dalam kehidupan. Dari penerimaan Bapak dan Ibu, saya belajar lebih jauh tentang keislaman saya sendiri, ketuhanan saya sendiri.
Orang tua saya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang intelektual untuk menerima saya. Mereka tidak tahu gender itu apa, seksualitas itu apa, beliau cukup menggunakan, "Inilah takdir anak saya. Seperti inilah fitrah anak saya".
Itu yang saya pelajari dan membuat saya yakin. Tumbuh kepercayaan diri saya untuk tetap menyatakan diri sebagai muslim, sebagai trans, dan meneruskan hidup.
Setelah transisi, saya tidak pernah lagi menyakiti diri. Justru saya malah sangat hati-hati dengan tubuh saya.
Memang banyak yang menghujat, mengatakan "Kamu melanggar takdir Allah, kamu ahli neraka".
Kakak saya, Mas Muis, dulu paling menolak saya, orang yang paling tidak terima dengan kondisi yang saya alami sebagai seorang trans. Dia selalu mengatakan yang saya lakukan adalah salah dan dosa, "Ingat, kamu anak kyai, kita punya pesantren, jaga nama baik".
Tetapi saya menyadari itu adalah prosesnya menerima saya. Sebuah usaha panjang dan terbantu banyak oleh orang tua yang seringkali menasehati kakak saya. Ketika kakak saya berproses, saya juga berproses untuk berjuang juga.
'Saya marahin sampai dua tahun'
Abdul Muis, kakak Amar yang kini memimpin pesantren setelah ayah dan ibu mereka meninggal, semula mengaku marah dan menentang transformasi Amar.
"Amar itu berani lepas jilbab saya marahin. 'Kamu ini nggak sesuai ajaran agama'. Saya marahin terus sampai dua tahun," kata Abdul Muis.
"Saya ingin mengubah dia. Saya doakan, saya ajak ke psikolog dan sebagainya. Ikhtiar itu kami lakukan semuanya, di awal. Saya selalu bilang, kamu harus berubah, kamu harus berubah," kata dia.
Penerimaan adalah proses panjang dan menguras emosi, demikian Muis menjelaskan. Setelah bertahun-tahun berupaya mengubah namun tidak berhasil, dia dan keluarga pun berserah diri kepada Tuhan, bertawakal.
"Kalau memang yang terbaik menurut Allah seperti ini, bagaimana? Kadang kala kita berdoa minta uang tapi yang terbaik bukan uang, kesehatan misalnya. Dikasih uang, tetap sakit juga. Akhirnya saya banyak belajar, berdoa dengan meminta yang terbaik, termasuk buat adik saya," kata anak pertama dari tiga bersaudara ini.
"Amar paling dekat sama Ibu, saya malah dikasih pesan, karena dianggap paling keras waktu itu. Justru Ibu yang meminta saya support Amar. Orang tua kami sangat mengerti meskipun kami dari basis pesantren, agama Islam, di mana kami tahu bahwa itu tantangannya luar biasa," kata dia.
Dalam ketidaksetujuannya, Abdul Muis juga berusaha belajar dan memahami apa itu transgender. "Saya juga banyak belajar, jadi tahu. Sekarang saya mengerti bahwa memang secara psikis dan batiniah, ada orang yang seperti itu," kata dia.
Setelah proses bertahun-tahun itu, Muis pun akhirnya menerima keadaan adiknya. Meski awalnya canggung karena perubahan nama, dia dan keluarga pun telah terbiasa memanggil nama "Amar".
Muis pun mengenang bahwa Amar memang sejak kecil "tomboy".
"Amar itu sejak kecil kalau pakai baju selalu celana pendek. Dibelikan rok, tapi tidak pernah mau dipakai. Bapak kami membelikan boneka tapi tidak pernah mau dipakai. Waktu kecil pilihan dia pasti mobil-mobilan, robot, pistol," kata Muis.
"Karena saya tahu kecilnya, saya tahu ini tidak mungkin dibentuk dari lingkungan. Saya jadi yakin ada kodrat ilahi, yang punya hati itu Allah, yang bisa membalikkan hati itu Allah, jadi tugas manusia hanya untuk ikhtiar dan berdoa," katanya.
"Awalnya sanget stres sekali, saya kepikiran betul. Tapi saya bangga sekarang," kata Muis. Dia bersyukur berada dalam komunitas muslim yang sangat heterogen dan toleran, dengan tradisi pesantren yang saling menguatkan.
"Sering kali orang menyarankan agar saya meminta Amar berubah. Saya katakan, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi pada akhirnya tetep begitu, itu kekuasaan Allah. Saya tidak bisa melakukan banyak di luar kemampuan saya.
"Tugas saya dan kemampuan saya adalah support, karena dia adik saya. Saya bahkan memberi pesan balik, tugas kita sebagai manusia adalah memanusiakan manusia," kata dia.
Kini Muis berharap adik laki-lakinya terus berkarya dalam bidang keilmuan agama, dan dapat membantu mengelola pesantren keluarga.
Saat BBC News Indonesia menemui Amar di rumah sekaligus pesantren keluarganya di Kendal, Jawa Tengah, sedang ada acara syukuran untuk melepas kepergian Amar melanjutkan sekolah ke Universitas Birmingham, Inggris.
Teman-teman Amar dari sekitar pesantren dan dari organisasi pemuda turut hadir, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian dari mereka adalah teman-teman yang menyaksikan transisi Amar dari perempuan menjadi laki-laki.
"Saya tidak kaget juga, dulu waktu dia masih cewek sudah kerasa. Soul-nya terasa kalau cowok. Secara sikap juga menunjukkan, tapi yang paling besar terasa jiwanya, memang kayak cowok," kata Aldila Akbar, teman Amar.
Aldila mengaku tidak peduli dengan komentar negatif beberapa orang ketika mengetahui dia berteman akrab dengan Amar. "Ada sebagian orang yang mengatakan takut saya ketularan menjadi trans. Tapi saya tidak ambil pusing sih," kata Aldila.
Latifah, teman yang telah mengenal Amar sejak kecil, tidak setuju dengan perubahan Amar menjadi transpria.
"Saya tahu betul itu dilarang agama. Tapi akhirnya saya melihat dia sebagai manusia dan harus dimanusiakan. Urusan saya dengan dia, kami baik. Urusan dia dengan Tuhannya, biarkan dia sendiri," kata Latifah.
Dia mengaku sudah sering menasihati dan menegur Amar.
"Saya tidak pernah membenarkan, saya tidak pernah mengiyakan, saya hanya, ya sudahlah mau gimana lagi. Memanusiakan manusia saja. Saya menganggapnya dia lagi sakit dan suatu saat akan sembuh," kata Latifah.
Meski demikian, Latifah mengaku tetap akan terus berteman dan mendampingi jika Amar menghadapi kesulitan atau diskriminasi.
"Teman-teman militannya Amar ya kita-kita ini. Semuanya kompak tidak akan pernah sedikit pun meninggalkan. Kami tidak pernah merasa dia adalah orang yang berbeda," kata Latifah.
Kembali pada penuturan Amar:
Yang paling berat adalah menyaksikan keluarga juga dihujat
Bagi saya, pilihan untuk transisi sudah menjadi risiko perjuangan, dihujat dan dicaci.
Tapi momen yang paling berat adalah ketika melihat Ibu saya, Bapak saya, mereka juga harus berhadapan dengan cemoohan orang lain. Orang bilang, "Kyai dan Bu Nyai tidak bisa mendidik anaknya".
Saya belajar dari Ibu saya yang selalu menghadapi orang lain dengan cara yang sederhana dan legowo menghadapi orang lain. Ibu tidak menanggapi orang lain dengan emosi atau marah.
Ada momen-momen di mana ibu menghadapi pertanyaan orang lain dengan cara jenaka. Misalnya, ada momen ketika di depan saya, Ibu ditanya, "Mana anak perempuannya?" Ibu menunjuk saya dan menjawab, "Ini suaminya", seolah-olah saya adalah suami diri saya sendiri.
Ada momen ketika saya transisi, Bapak selalu minta saya antar beliau. Ketika pengajian, ceramah, bertemu santri di daerah, beliau percaya diri dan tidak malu membawa saya yang sudah transisi.
Bapak pernah mengatakan kepada santri-santri, "Dia sekarang begini, tapi jangan dihina, ini adalah bagian dari takdir Allah untuk saya dan juga untuk anak saya. Kalau saya menolak anak saya, maka saya menolak takdir Allah untuk saya dan keluarga saya".
Santri di pesantren keluarga pun pada awalnya kaget. Semua orang pasti kaget, saya bohong kalau mereka nggak kaget.
Dan orang menerima pun pasti berproses, tidak mungkin orang menerima orang lain yang berbeda dalam sekali duduk. Ada proses perjumpaan, ada dialog.
Dari pengalaman saya, banyak orang hanya penasaran. Kalau sudah ngobrol, mau tak mau sering bersosialisasi, akhirnya akan biasa saja.
Berkali-kali orang datang mendoakan saya, teman bapak saya ibu saya, mereka Kyai dan Bu Nyai mendoakan saya. Saya mengamini karena doa mereka adalah wujud kasih sayang, wujud bahwa mereka peduli.
Bapak Ibu saya selalu tegar menghadapi hujatan, dan dari mereka juga saya belajar untuk cuek. Orang yang menghujat sebenarnya gelisah dengan kebenciannya sendiri, itu sebenarnya masalah dia dengan dirinya.
Semua orang punya kesempurnaannya masing-masing dan kita tidak bisa menyamakan versi sempurna menurut kita harus sama dengan orang lain.
Apa yang terjadi pada diri saya ini sudah ciptaan-Nya yang sempurna. Allah tidak salah menjadikan saya sebagai diri saya yang seperti ini karena Allah tidak mungkin keliru.
Yang mungkin tidak sempurna adalah cara kita melihat diri dan cara kita melihat orang lain, terutama melihat keragaman.
Bagi saya yang terpenting adalah apa yang bisa saya lakukan untuk perjuangan kehidupan saya ke depan, dan juga untuk komunitas trans secara keseluruhan. Saya bekerja dalam bidang aktivisme yang melibatkan ragam kelompok, terutama minoritas. Kemudian saya diterima beasiswa untuk program MA Theology and Religion di University of Birmingham di Inggris.
Saya ingin belajar banyak dan lebih punya dasar dan pengetahuan yang lebih luas lagi untuk agama dan teologi, untuk memperkuat aktivisme
Saya ingin sekali melihat ada lebih banyak ruang-ruang agama di mana agama diajarkan dan dipraktekkan dengan cara yang humanis.
Ketika kuliah S1, saya hampir di-DO karena identitas gender saya. Waktu itu saya sudah transisi tapi belum sidang ganti nama. Kampus mensyaratkan kalau ganti harus sidang, dan ternyata prosesnya bertahun-tahun.
Birokrasi ganti nama sangat sulit. Ganti nama adalah hak warga negara, tapi perspektifnya masih phobia terhadap trans, jadi dipersulit dalam berbagai hal. Meskipun akhirnya bisa, tapi perspektif hukum birokrasi dan administrasinya tidak inklusif maka sulit untuk orang seperti saya.Saya juga banyak mengalami diskriminasi, misalnya ketika saya mau salat di masjid dan orang tahu saya trans, mereka akan menghindar atau mengusir karena menganggap saya perempuan dan tidak boleh salat di shaf laki laki.
Meski demikian, saya tidak bisa tutup mata bahwa yang terjadi pada saya adalah privilese besar bagi orang trans, karena mayoritas trans diusir dari rumah.
Kalau diusir mereka tidak punya akses lagi atau berpengaruh pada akses mereka pada pendidikan, atau hak-hak dasar. Misalnya ketika mereka dicabut dari KK, dapat bantuan pun tidak bisa karena masalah identitas dan KTP.
Itu hal yang membuat saya sedih, kenapa keluarga dan orang tua tidak dapat menerima anaknya yang trans? Kadang mereka tidak cuma diusir tapi juga dilecehkan dan menerima kekerasan.
Setelah saya transisi dan menyadari identitas gender saya sebagai laki-laki, justru saya melihat bahwa penyakit yang sebenarnya adalah ketidaktahuan orang dan kebencian.
Ketidakterimaan dan pengucilan membuat banyak orang menderita, terutama bagi orang seperti saya di luar sana yang tidak diterima oleh keluarganya.
Saya selalu percaya bahwa keluarga adalah pondasi utama untuk hal apa pun. Ketika keluarga menjadi ruang aman untuk trans, itu bisa mendorong mereka untuk kuat dan tegar mencapai impiannya.
Saya berharap ada lebih banyak orang tua yang menerima anaknya yang trans sehingga mereka tidak harus diusir atau kehilangan hak hidupnya.
Orang selalu mengatakan trans hidup di jalanan, mengamen, tapi mereka begitu karena sistem. Kawan-kawan saya begitu karena mereka ditolak keluarga, mereka begitu karena harus. Mereka terpaksa hidup seperti itu karena masyarakat kita belum menerima.
Impian saya adalah melihat agama dijadikan alasan orang untuk berlaku adil kepada orang lain.
Agama tidak pernah punya tafsir tunggal. Tafsir dalam agama itu pasti beragam dan tidak bisa disamaratakan. Kalaupun dari sisi agama orang punya pendapat berbeda bahwa transgender adalah haram, misalnya, tapi sepanjang mereka bisa memberikan penghormatan, mendukung hak hidup trans, tidak masalah buat saya.
Salah satu alasan kenapa saya terjun ke aktivisme, dan juga kenapa saya membagikan kisahku adalah karena saya berharap agama tidak lagi digunakan untuk membenci dan menindas orang lain.
Orang selalu bilang Tuhan maha baik dan agama adalah jalan kedamaian, tapi faktanya agama sering menjadi jalan kebencian, agama menjadi alasan orang untuk menindas menghukumi bahkan membunuh orang lain.
Saya ingin membagi kisah ini karena ingin lebih banyak lagi orang melihat bahwa keluarga saya dari kalangan agama tapi bisa menghadirkan agama dengan cara pandang yang menghormati manusia, apapun perbedaan tafsirnya.
Saya ingin lebih banyak orang percaya bahwa agamanya bisa menjadi jalan untuk memerdekakan diri dan memerdekakan orang lain.
'Dialog antara teks dan realitas'
Marzuki Wahid adalah Rektor di Institut Islam Fahmina, lembaga pendidikan Islam yang berfokus pada kajian gender dan hal asasi manusia. Dia juga menjadi pimpinan (mudir) Ma'had Aly Kebon Jambu Al-Islamy, perguruan tinggi pesantren dengan kurikulum kesetaraan dan keadilan gender.
Dr KH Marzuki Wahid yang dikenal sebagai kyai berpandangan progresif ini juga menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia PBNU (Lakpesdam PBNU).
Saat ditemui oleh BBC, Marzuki menjelaskan pandangannya mengenai transgender dalam Islam.
Bagaimana pandangan Islam tentang transgender?
Islam sebetulnya bukan semata-mata teks, tapi juga realitas. Dan dialog antara teks dengan realitas, itulah sebetulnya Islam.
Islam itu dinamis, sejak zaman nabi sampai sekarang selalu terjadi dinamika dan perubahan, dan perubahan itu mengikuti perubahan realitas.
Karena itu ketika ada suatu masalah baru, kontemporer, tentu pertama yang kita dekati adalah realitas itu sendiri.
Misalnya soal isu transgender atau transeksual. Kita tanyakan kepada yang bersangkutan, bagaimana sebetulnya duduk masalahnya?
Seperti apa perasaannya, prosesnya, dampaknya, dan seterusnya. Baru kemudian kita melihat, gimana teksnya. Nah dialog antara teks dan realitas itulah yang kemudian kita menemukan dan menentukan status pandangan keislaman.
Bagaimana pandangan keislamannya?
Saya kira transgender itu juga tidak tunggal. Para ulama melihat realitasnya, apakah seorang trans itu amdan, sengaja menjadi trans, ataukah ghoiro amdin, artinya dia tidak menghendaki tapi itu di luar kuasa dia. Dalam konteks ini saya melihat kasus per kasus.
Ini adalah dua hal yang berbeda hukumnya dalam Islam, kalau orang yang amdan, sengaja, artinya dia menyalahi kebiasaan. Berbeda dengan orang yang mengatakan "Saya tidak menghendaki ini tapi apa yang saya jalani adalah bagian dari perjalanan ketentuan Tuhan". Saya melihat ini sebagai dua hal yang berbeda.
Karena itu di luar kuasa dia, pertanyaannya, siapa yang menghendaki dia berbuat seperti itu?
Maka menurut saya orang seperti ini harus diberi ruang, bahwa Tuhan menciptakan sesuatu yang lain, yang berbeda dengan mainstream. Islam itu kan pesan-pesan Tuhan. Kalau ini kehendak Tuhan, masa kita mau menolaknya?
Sama dengan perempuan menstruasi, itu kehendak siapa? Bukan kehendak perempuan, tapi kehendak Tuhan. Maka perempuan menstruasi itu tidak berkurang sedikitpun agamanya. Karena dia tidak salat karena taat dengan aturan Tuhan dan yang menghendaki menstruasi kan tuhan, bukan dia. Kira-kira seperti itu.
Bagaimana dengan tuduhan bahwa trans membawa bencana atau dosa untuk orang lain di sekitarnya?
Cara pandang ini harus ditinggalkan dan dihapus karena nyatanya tidak terbukti. Saya kira tidak ada satu teks yang menjelaskan secara shorif tentang ini. Ini mitos yang dibangun oleh mereka untuk membenci komunitas tertentu.
Karena kenyataannya, teman-teman trans tidak merusak dan memicu bencana apa-apa. Saya bisa bergaul dengan mereka dan bahkan saling menolong, saling membantu, saling melengkapi dan mereka bermanfaat buat kita.
Tidak hanya trans, tapi manusia secara umum ada yang baik ada yang buruk. Kita juga ada yang membawa berkat, ada yang membawa bencana.
Jangan dikira orang hetero tidak membawa bencana. Banyak juga yang membawa bencana, kalau kita melanggar hukum, tidak taat aturan perilaku kita tidak sesuai dengan susila dan norma, bisa membawa bencana.
Bagaimana dengan ibadah atau fikih kaum trans?
Ini yang jadi masalah karena dalam Islam belum memberikan ruang ini.
Menurut saya, ruang untuk mereka di dalam ajaran Islam harus ditemukan dan diciptakan, perlu ada fikih waria.
Contohnya, salatnya bagaimana? Laki-laki perempuan kan berbeda, jadi salatnya ikut kelaminnya atau penampilannya? Ikut kelamin yang lama atau yang baru? Itu menjadi perdebatan.
Ini yang saya pikir belum tuntas hingga sekarang, atau setidaknya belum ada satu kesepahaman. Kalau sepaham sekali tentu tidak akan ada, tapi setidaknya sesuatu yang bisa dijadikan pegangan agar mereka bisa beribadah dan merasa nyaman berjalan menuju Tuhannya.
Karena ini soal syariah aja, soal fikih. Kalau soal hakekat, urusan manusia dengan Tuhan, itu urusan hati, pikiran, nurani dan tidak ada bedanya laki-laki atau perempuan. Manusia di hadapan Tuhan itu sama apapun jenis kelamin, warna kulit dan bentuknya. Yang beda di hadapan Tuhan adalah ketakwaannya.
Bagaimana hukumnya persekusi terhadap transgender?
Dalam pendekatan HAM, kita harus menghargai apapun pilihan orang. Setiap orang punya pertanggungjawabannya sendiri baik secara personal moral, spiritual dan sosial kepada alamat-alamat tertentu, kalau agama kepada Tuhan, kalau sosial kepada masyarakat.
Menurut saya, hargailah pilihan orang selagi tidak merugikan, mengancam, merusak orang lain dan diri sendiri. Di dalam Islam, kita tidak boleh merusak diri kita sendiri dan orang lain.
Karena itu persekusi dalam bentuk apapun kalau bisa dilarang karena itu bertentangan dengan prinsip Islam yang menjaga martabat kemanusiaan. Salah satu martabat kemanusiaan adalah menghargai pilihan.
Yang paling penting, agama ingin mewujudkan keselamatan, keamanan, kemaslahatan kenyamanan untuk semuanya. Itu yang disebut rahmatan lil alamin, damai untuk semuanya.