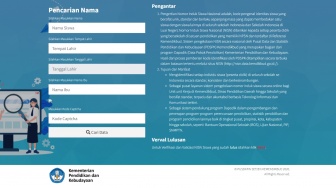Suara.com - Malam kelam pada 30 September 1965 menjelang dini hari menjadi saksi bisu pembunuhan enam jenderal dan satu perwira Angkatan Darat di Jakarta oleh apa yang disebut sebagai Gerakan 30 September (G30S).
Tubuh para korban yang terbunuh di sumur Lubang Buaya ditemukan tiga hari kemudian.
Autopsi yang dilakukan di rumah sakit tentara pada 4 Oktober — dan ditandatangani oleh Jenderal Soeharto dan Presiden Soekarno — merinci bahwa penyebab kematian mereka karena tembakan senjata api dan trauma yang mungkin disebabkan pukulan dari senjata.
Autopsi juga mencatat kerusakan pada tubuh sejumlah jenderal terjadi karena jenazah mereka terbaring selama sekian lama di dasar sumur yang lembab. Menurut dokter forensik, inilah yang menyebabkan kondisi mata salah satu korban sangat buruk.
Baca juga:
- Peristiwa G30S 1965, penumpasan PKI, dan hari-hari sesudahnya
- Peristiwa 65 dan PKI: wajah para korban dan pelaku
- Film G30S/PKI ditayangkan kembali, keluarga penyintas peristiwa 1965: 'Seperti menghidupkan hantu-hantu zaman dulu'
Namun, temuan ini tidak dipublikasikan. Hasil autopsi ini baru muncul di arena publik setelah dipublikasikan oleh sosiolog Ben Anderson lewat tulisannya How Did The Generals Die pada 1987.
Alih-alih hasil autopsi, pemerintah pada saat itu menyebarkan cerita yang sangat berbeda ke dunia luar.
Harian Angkatan Bersendjata, yang menjadi corong pemerintah, menerbitkan foto-foto jenazah dan memberitakan kematian mereka sebagai "perbuatan biadab berupa penganiayaan yang dilakukan di luar batas perikemanusian".
Sementara, Berita Yudha, koran tentara yang juga menjadi menjadi corong pemerintah, mencatat bahwa "bekas-bekas luka di sekujur tubuh akibat siksaan sebelum ditembak" masih membalut tubuh-tubuh para korban.
Baca Juga: Ingin Nonton Filmnya? Berikut Link Film G30S PKI
Pemberitaan koran-koran tentara ini segera diikuti oleh media massa lain, yang menggambarkan para perempuan menggoda jenderal dengan melakukan tarian telanjang yang erotis, disertai nyanyian lagu Genjer-Genjer. Setelah itu, mereka mulai mengebiri para jenderal dan mencungkil mata mereka.
Laporan-laporan yang tidak terverifikasi ini menyebar ke media massa lainnya, yang memberitakan cerita-cerita bohong tentang penyiksaan seksual dan pengebirian yang dilakukan oleh anggota Gerwani, berakibat pada kekerasan yang disasar pada perempuan.
'Dituduh nyilet kemaluan jenderal'
Mudjiati adalah salah satu dari perempuan korban propaganda Orde Baru.
Pada tahun 1965, ia masih muda belia dan aktif dalam organisasi Pemuda Rakyat, yang berafiliasi dengan PKI.
Hanya dalam hitungan pekan setelah Peristiwa 65 berkecamuk, ia langsung ditahan tanpa proses pengadilan. Usianya kala itu masih 17 tahun.
Mudjiati baru merasakan udara bebas pada Desember 1979.
Walau bukan anggota Gerwani, ia dituduh melakukan apa yang ditudingkan dalam kampanye fitnah penguasa terhadap Gerwani.
"Anak-anak muda itu pasti dituduhnya nyilet-nyilet kemaluan jenderal, tari telanjang. Itu tuduhan itu semua begitu, pada perempuan," tutur perempuan berusia 73 tahun itu kepada BBC News Indonesia.
Beberapa pekan sebelum penangkapannya, pada Oktober 1965, rumahnya digeledah oleh sejumlah tentara yang mencari alat pencungkil mata. Saat itu juga, ayahnya yang merupakan anggota Front Nasional ditangkap.
Oleh tentara yang menjemputnya, Mudjiati diberitahu hanya "dimintai keterangan" terkait penangkapan ayahnya dan dijanjikan pemeriksaan dilakukan "paling lama dua jam".
"Penyiksaan itu pasti kalau kita bilang tidak pada apa yang dituduhkan pada saya, sebagai yang ikut tari Genjer-Genjer, tari telanjang," aku Mudjiati ketika ditanya apakah dirinya mengalami penyiksaan selama proses pemeriksaan.
"Saat kita tidak mengakui, kita dipaksa harus mengakui. Itu kita pasti dipukuli di situ. Tapi saya bertahan karena saya tidak merasa [melakukan]. Apapun yang terjadi, saya alami saja," tutur Mudjiati.
Alih-alih dua jam, Mudjiati menghabiskan 14 tahun masa mudanya di dalam kungkungan terali besi lantaran menolak mengakui tuduhan itu.
Ia dipindahkan dari tempat penahanan satu ke yang lain, dari tahanan KORAMIL, KODIM, Rumah Tahanan Chusus Wanita (RTCW) Bukit Duri, hingga dipindahkan ke Inrehab Plantungan, kamp khusus tapol perempuan di Kendal, Jawa Tengah.
Yosephina Endang Lestari juga mengalami hal serupa.
Kala itu, anggota organisasi mahasiswa Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) — organisasi underbow PKI — itu baru menjalani tahun kedua kuliah di IKIP Yogyakarta demi meraih cita-citanya menjadi seorang guru.
Ketika pemeriksaan, para tentara mencari cap Gerwani di tubuhnya. Ia disuruh menanggalkan pakaian, namun tak ada yang menemukan cap tersebut.
"Di situ cuma ditanya,'Kamu Gerwani ya?'. Mau diperiksa ada capnya nggak di dalam, 'Nggak ada, saya bukan Gerwani', saya bilang gitu. Tapi dipaksa [untuk menanggalkan pakaian]," aku Endang.
"Pendirian saya, kalau saya sampai disentuh lebih baik saya mati daripada nanti kalau ada apa-apa."
Sama seperti Mudjiati, ia dipindahkan dari satu tahanan ke tahanan lain. Ia sempat ditahan di Penjara Wirogunan di Yogyakarta selama dua pekan. Di sana, ia berbagi satu kamar kecil bersama sekitar 30 tahanan lain.
"Pokoknya tidurnya seperti dijejer-jejer pindang. Kalau mau miring, 'Aku arep miring ngiwo' [aku mau miring ke kiri], bareng-bareng miringnya."
Pada April 1966, ia dipindahkan ke Benteng Pendhem Ambarawa di Jawa Tengah, dulunya bernama benteng Fort Willem I pada masa kolonial Belanda, yang dialih fungsi menjadi tempat penahanan tapol dan tahanan militer.
Endang menceritakan, ketika ada membesuk, mereka dipisahkan sawah dan kawat berduri dengan jarak sekitar 30 meter; komunikasi antara para tahanan dan keluarga yang menjenguk pun harus berlangsung dengan berteriak-teriak.
Magdalena Kastinah justru mengalami kekerasan bertubi-tubi di tahanan satu dan yang lain. Mulai dari pelecehan seksual hingga kekerasan fisik.
Salah satu kekerasan yang ia alami adalah ketika pemeriksaan, penjaga menusuk dadanya berulang kali dengan besi untuk membersihkan senjata.
"Kadang-kadang masih terasa sakit," katanya lirih.
'Kejahatan terhadap kemanusiaan'
Apa yang dialami oleh Mudjiati, Endang Lestari dan Kastinah, juga dialami oleh para perempuan lain yang dituding terlibat dalam tragedi 65, ungkap Saskia Wieringa, antropolog Universitas Amsterdam di Belanda, yang bertahun-tahun meneliti tentang Peristiwa 65.
"Di mana-mana di Indonesia, perempuan yang pernah ikut dengan Gerwani dipenjarakan dan mereka diperiksa, ditelanjangi seolah-olah mereka mencari cap Gerwani," kata Saskia dalam wawancara yang dilakukan secara daring.
Tak hanya itu, perempuan dari organisasi lain yang berhaluan kiri kadang juga "di-Gerwani-kan", kata Saskia, bahkan "diperkosa".
"Mereka disiksa, mereka kadang-kadang ditelanjangi, dan difoto, yang diambil beberapa minggu setelah [Peristiwa 65] terjadi. Itu direpresentasikan sebagai bukti di koran-koran bahwa mereka menggoda jenderal-jenderal itu."
"Mereka diperkosa, orang tidak membayangkan apa yang terjadi pada mereka, tapi tidak ada seorang pun yang dibawa ke pengadilan," jelas Saskia kemudian.
Kekerasan berbasis gender yang dialami oleh para tapol perempuan disebut sebagai sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" oleh Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi.
Hal itu merujuk pada hasil pemantauan yang dilakukan Komnas Perempuan terhadap 122 perempuan penyintas 65 yang memberikan kesaksian.
"Dari 122 perempuan yang berikan kesaksian, bahwa betul perempuan-perempuan itu mengalami pemerkosaan dan kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, juga mengalami perbudakan seksual, juga kemudian ada bentuk-bentuk stigma setelah mereka menjalani tahanan," jelas Ami.
Propaganda yang berujung 'pembantaian'
Hasil wawancara dengan para perempuan yang diterbitkan di surat kabar, yang menggambarkan bahwa mereka "menggoda jenderal, mengkrastasi dan membunuhnya", kata Saskia, menjadi propaganda yang "membakar api benci" kelompok kanan.
"Terutama di kelompok-kelompok agama, dan mulai pembantaian besar [terhadap] PKI," ujar Saskia Wieringa.
Apa yang terjadi setelahnya, adalah perburuan dan pembantaian anggota PKI dan afiliasinya — termasuk Gerwani — oleh kelompok anti-komunis.
"Pelan-pelan suasana diciptakan di mana PKI dan Gerwani dihancurkan, pembunuhan massal yang terjadi, mungkin satu juta orang dibunuh. Kita dengan IPT, hakim-hakim kita sudah memutuskan bahwa itu memang termasuk genosida terbesar setelah Perang Dunia II," katanya.
Kendati belum ada angka pasti berkaitan jumlah korban pembantaian tersebut, sebagian besar sejarawan sepakat bahwa setidaknya setengah juta orang menjadi korban keganasan propaganda tersebut.
Secara keseluruhan, tragedi 65 membuat belasan ribu orang dipenjara, dibuang, disiksa, tanpa proses pengadilan, atau diberi kesempatan pembelaan diri.
Sementara, hasil penyelidikan Komnas HAM, sekitar 32.774 orang diketahui telah hilang dan beberapa tempat diketahui menjadi lokasi pembantaian para korban.
Penghancuran gerakan perempuan
Lebih lanjut Saskia mengatakan, propaganda yang berpusat pada "penyimpangan seksual anggota Gerwani", serta penggambaran PKI sebagai ateis dan anti-nasionalis tak hanya memicu pada pembunuhan massal orang-orang berhaluan kiri, tapi juga penghancuran gerakan perempuan progresif.
"Saya rasa sesudah propaganda [Joseph] Goebbels [Menteri Penerangan Publik dan Propaganda Nazi Jerman] dalam Perang Dunia II tentang orang Yahudi, propaganda terhadap Gerwani adalah yang mungkin lebih efektif lagi, karena mungkin 50 tahun sesudah itu terjadi orang masih percaya. Sampai sekarang pun Gerwani punya nama jelek," kata Saskia.
Menilik sejarah, Gerakan Wanita Sedar (Gerwis) yang dibentuk pada 1950 merupakan gabungan organisasi perempuan dari sejumlah daerah yang menjadi cikal bakal Gerwani.
Menurut Saskia, kebanyakan dari mereka yang tergabung di dalamnya adalah perempuan "nasionalis dan membantu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia". Salah satunya, S.K. Trimurti, seorang jurnalis perempuan pejuang kemerdekaan.
"Situasinya waktu itu adalah seluruh gerakan perempuan terarah kepada kemerdekaan, nasionalis, dan Gerwani juga ikut dalam itu, dan Gerwani yang terbesar dalam periode itu".
Gerwis — yang pada 1954 berganti nama menjadi Gerwani — mencurahkan perhatian pada masalah pemberantasan buta huruf dan pendirian sekolah.
"Banyak perempuan yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis apa-apa dan orang Gerwani membantu. Anggota Gerwani juga selalu aktif di dalam perjuangan di dalam rumah tangga.
Organisasi itu juga menuntut perlunya hak-hak perempuan, termasuk tentang poligami.
"Malah di dalam organisasi sendiri, kalau ada pimpinan PKI yang ambil istri kedua mereka berdemo, sampai orang itu keluar," kata dia.
Tak hanya berfokus pada isu perempuan, Gerwani juga menjadi organisasi paling aktif dalam politik nasional juga isu internasional.
Pada perayaan Hari Wanita Internasional pada Maret 1955, Gerwani memprotes percobaan senjata nuklir dan pendudukan Belanda di Irian Barat.
Kemudian, para perempuan yang disebut sebagai "ibu-ibu militan" oleh Saskia ini juga melakukan kampanye besar-besaran atas nama kaum tani miskin dan menuntut penurunan harga yang melambung tinggi.
Pada 21 April 1961, Gerwani menegaskan bahwa gerakan perempuan harus menjadi "gerakan revolusioner sejati" dan "imperialisme harus dikaitkan dengan perjuangan melawan imperialisme".
Dalam perkembangannya, Gerwani tumbuh subur dengan jumlah anggota lebih dari satu juta orang.
"Gerwani waktu itu di tahun 65 termasuk gerakan perempuan di dunia yang terbesar, nomor tiga [di dunia] sebenarnya, dengan jumlah anggotanya 1,5 juta," jelas Saskia.
Baca juga:
- Penari asal Kupang yang dituding PKI: Diperkosa, katong diperlakukan seperti anjing, 'Biar Tuhan yang mengadili'
- Pendiri TAPOL Carmel Budiardjo, yang berperan besar dalam perjuangan kemanusiaan di Indonesia, tutup usia
- Siti Rukiah Kertapati, sastrawati era kemerdekaan yang terlupakan
Pada 1964, pemerintah Indonesia menginstruksikan organisasi massa agar mengikatkan diri pada partai politik.
Gerwani — yang berideologi feminis dan sosialis — menyatakan diri berada dalam kubu komunis, yang akan diresmikan dalam kongres yang digelar Desember 1965.
Namun, kongres itu urung digelar, Peristiwa 65 meletus dan sejak saat itu Gerwani "dihancurkan".
"Itu betul-betul penghancuran gerakan sosial yang terjadi di Indonesia dan di bawahnya selalu ada fitnah seksual."
Stigma dan trauma anak Gerwani dan PKI
Apa yang diakibatkan oleh fitnah seksual itu adalah stigma dan trauma yang dirasakan tak hanya para perempuan korban propaganda Orde Baru, namun juga generasi penerusnya, seperti yang dialami Uchikowati Fauzia.
"Ada stigma, ada label yang diberikan ke saya sebagai anak PKI dan Gerwani," aku perempuan yang akrab dipanggil Uchi tersebut.
"Pandangan mereka terhadap saya sebagai anak dari seorang ibu [anggota] Gerwani, itu moralnya lebih rendah dan kalau dalam bahasa anak-anak, 'Halah itu anaknya orang Gerwani kan lebih rendah daripada seorang pelacur'."
Ibunya, Hartati — seorang anggota Gerwani — ditahan tanpa diadili selama delapan tahun di Penjara Bulu, Semarang.
Sedangkan ayahnya, Djauhar Arifin Santosa — anggota PKI yang menjabat sebagai Bupati Cilacap hingga 1965 — divonis 20 tahun penjara pada 1967 karena dituduh terlibat G30S.
Stigma yang diberikan masyarakat kepadanya dan anak-anak tapol yang lain, kata Uchi, membuatnya "takut" dan "menjadi berbeda" dari teman-teman yang lain.
"Untuk bergaul, kami tidak sepenuhnya ada kebebasan, kemerdekaan."
"Stigma yang dialami akibat Peristiwa 65 itu sampai sekarang sebenarnya belum hilang, sekalipun mereka sudah tidak memberikan label lagi," katanya.
Trauma dan stigma terus Uchi tanggung hingga kini, di usia senjanya.
"Saya tidak bisa mengatakan apakah saya sudah sembuh dari trauma itu belum, tapi yang pasti itu selalu muncul ketika saya bertemu atau mendengar ada orang yang berasal dari satu daerah dengan saya."
Perempuan sebagai 'konco wingking'
Stigma itu kian langgeng meski Peristiwa 65 sudah berlalu, ketika pada era 1980-an, pemerintah Indonesia menugaskan sutradara Arifin C Noer membuat film yang mengisahkan Peristiwa 65 dari kacamata pemerintah.
Film berjudul Pengkhianatan G30S/PKI itu menjadi tontonan wajib semua penduduk Indonesia hingga akhirnya Soeharto lengser pada 1998 dan disusul dengan Reformasi. Bahkan, hingga kini film tersebut masih sering diputar tiap akhir September.
Menurut Saskia Wieringa, "fitnah seksual" terhadap kelompok perempuan progresif sekaligus mengontrol perempuan dengan propaganda tersebut "demi menjaga stabilitas negara".
Baca juga:
- 'Saya dituduh anggota Gerwani yang mencukil mata jenderal'
- Kisah anak algojo PKI di Blitar selatan yang mendampingi penyintas kasus 1965: 'Saya minta maaf'
- 'Dosa turunan' dicap PKI, keluarga penyintas 65 masih mengalami diskriminasi: 'Jangan bedakan kami'
Padahal, metode yang dilakukan Gerwani dalam membela hak-hak perempuan — seperti menentang kekerasan seksual dan domestik, serta kawin paksa atau perkawinan anak — "sangat penting", kata Saksia, bahkan untuk konteks masa sekarang.
"Semua hal yang diperjuangkan oleh perempuan Gerwani masih tetap ada. Kita bisa belajar dari pengalaman mereka karena mereka punya banyak sukses. Sekarang gerakan perempuan di Indonesia aku pikir cukup lemah," aku Saskia.
Imbasnya, di era Orde Baru peran perempuan kembali mengurusi urusan domestik, ketimbang urusan sosial-politik.
Hal sama dikemukakan oleh Amurwani Dwi Lestariningsih dari Masyarakat Sejarawan Indonesia, yang juga meneliti tentang perempuan penyintas 65.
"Di dalam budaya patriarki di masyarakat kita yang begitu kuat dominasi laki-lakinya, aneh melihat Gerwani memasuki pentas ranahnya laki-laki," ujar Amurwani.
"Jadi, kalau perempuan itu harus yang lemah lembut, menjadi konco wingking kaum laki-laki, jadi jangan mengambil ranahnya laki-laki. Peranannya domestik, jangan ke ranah publik."
Propaganda terhadap Gerwani yang langgeng selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, lanjut Amurwani, membuat "sesuatu yang menjengkelkan, yang dianggap jahat, dikonotasikan dengan Gerwani".
"Pengalaman dan pengetahuan yang terbangun menjadikan masyarakat memberikan legitimasi, menjustifikasi, menstigma kepada mantan tapol perempuan itu. Gerwani yang dicitrakan sebagaimana yang mereka baca, mereka lihat, mereka dengar dari pemberitaan masa itu, dan itu kan terus diinternalisasikan ke generasi-generasi selanjutnya," jelas Amurwani.
'Pertarungan' narasi
Namun, tak bisa dipungkiri, gelombang protes yang memicu lengsernya Orde Baru dan melahirkan Reformasi telah membawa angin segar pada pelurusan sejarah tentang Peristiwa 65.
Namun, apakah perspektif generasi muda saat ini terhadap Gerwani telah mengalami perubahan?
Giovano Melvernus Hendrawan, yang lahir menjelang lengsernya Orde Baru, menyebut, sepengetahuannya, Gerwani adalah organisasi selain PKI yang terlibat G30S. Lain dari itu, ia tidak mengetahui tentang seluk-beluk Gerwani.
"Gerwani singkatannya Gerakan Wanita Indonesia, bener? Ya mereka mungkin seperti organisasi wanita yang memperjuangkan emansipasi wanita. Itu sepengetahuan saya," jelas pemuda berusia 26 tahun itu.
"Kalau sepanjang pengetahuan yang saya dapatkan, Peristiwa G30S andil terbesar tetap ada di PKI sih, itu sepanjang pengetahuan saya," tambah Giovano yang mengaku mendapat pengetahuan tentang Peristiwa 65 dari pelajaran sejarah dan dari internet.
Ia mengatakan, dalam buku-buku sejarah yang ia pelajari ketika sekolah, "PKI berencana mengkudeta dengan menyandera para tokoh yang sangat vital saat itu, jenderal-jenderal TNI. Dengan tujuan mereka ingin mendirikan negara berideologi komunis di Indonesia".
Sementara, Hesti Melinda, perempuan berusia 20 tahun yang lahir setelah era Orde Baru berakhir, mengaku tak tahu-menahu tentang Gerwani, PKI dan G30S.
"Peristiwa 65? Saya nggak tahu," akunya.
Jawaban sama ia utarakan ketika BBC News Indonesia menanyakannya tentang "pahlawan revolusi".
Sedangkan Loni Velianda, mengaku kerap mencari referensi di dunia maya dan film dokumenter berkaitan dengan tragedi 1965 "karena penasaran" dengan sejarah peristiwa tersebut.
"Pengen tahu jelasnya sih, kronologinya gimana, fakta-faktanya gimana," aku perempuan berusia 21 tahun itu.
Ia mengaku pernah mendengar tentang Gerwani, namun ketika ditanya lebih lanjut apa yang ia ketahui tentang organisasi perempuan tersebut, ia mengaku "lupa".
Apa yang terjadi saat ini, kata sejarawan Bonnie Triyana, adalah "pertarungan" narasi sejarah 65.
Baca juga:
- Pemutaran film Senyap dihentikan di Yogya
- Pembunuh massal yang memerankan kembali kejahatannya
- Tragedi 1965 dalam film dan kampanye HAM
"Pada akhirnya pertarungan ini terjadi di wilayah masyarakat. Tapi itu jauh lebih baik, daripada perdebatan ini disudahi dengan versinya pemerintah lagi."
Kendati begitu, diakui Bonnie, perspektif generasi muda tentang Peristiwa 65 telah mengalami perubahan secara perlahan.
Menurutnya, konotasi negatif yang disematkan kepada para penyintas dan keturunan mereka selama setengah abad terakhir perlahan luntur.
"Sementara stigmanya masih kuat, tapi saya optimis mungkin 10 tahun lagi orang sudah mulai berubah, anak muda sekarang sudah mulai berubah, sudah mulai bisa lebih memaknai masa lalunya dan mencari tahu kebenaran yang sudah berserak."
Sementara, Saskia memperingatkan bahwa propaganda anti-komunis hingga kini masih tetap ada.
Menurutnya, Indonesia perlu "belajar dari sejarah" supaya stigma dan trauma akibat propaganda anti-komunis tak terulang kembali.
"Hanya negara yang bisa belajar dari sejarahnya sendiri yang bisa menjadi dewasa dan Indonesia sampai sekarang belum bisa maju, belum bisa menjadi negara yang punya keadilan sosial untuk semua warga Indonesia, kata Saskia.
"Selama orang Indonesia tetap pikir bahwa Gerwani salah, gerakan perempuan juga tidak bisa tumbuh, karena setiap aktivis perempuan sekarang kalau terlalu aktif dan mereka menuntut hak-hak mereka yang sebenarnya ada di konstitusi Indonesia, langsung dicap Gerwani baru, sampai sekarang pun."
Tulisan ini merupakan bagian dari liputan khusus Peristiwa 1965 - Kisah para perempuan dan minoritasdi situs BBC News Indonesia. Anda juga bisa menyimak kisah ini di Siaran Radio Dunia Pagi Ini BBC Indonesia dan siniar kami di Spotify.
Produksi visual oleh Anindita Pradana dan Dwiki Marta. Grafis oleh tim jurnalis visual East Asia BBC News.