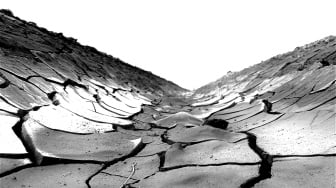Suara.com - Jika rakyat pergi
Ketika penguasa pidato
Kita harus hati-hati
Barangkali mereka putus asa
Kalau rakyat bersembunyi
Dan berbisik-bisik
Ketika membicarakan masalahnya sendiri
Penguasa harus waspada dan belajar mendengar
Bila rakyat berani mengeluh
Itu artinya sudah gawat
Dan bila omongan penguasa
Tidak boleh dibantah, Kebenaran pasti terancam
Apabila usul ditolak tanpa ditimbang
Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan
Dituduh subversif dan mengganggu keamanan
Maka hanya ada satu kata: lawan!
Puisi penyair cum aktivis Wiji Thukul berjudul Peringatan yang dibuat tahun 1986, saat Soeharto masih kuat-kuatnya, kini kembali bergema ketika banyak bentuk seni protes warga dihapus aparat.
Beberapa pekan terakhir, aparat sibuk menghapus sejumlah mural yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Padahal, grafiti tersebut berada di ruang publik, yang seharusnya bebas dari intervensi pemerintah.
Sejak revolusi kemerdekaan Indonesia, mural atau grafiti adalah satu dari sekian banyak cara rakyat untuk melakukan protes maupun perlawanan.
Pakar sosiologi politik dan pengamat kebebasan berekspresi menyebut penghapusan terhadap sejumlah mural berisi kritik sosial sebagai bagian karakter pemerintah yang "paranoid terhadap kritik".
Baca Juga: Telak! dr Tirta ke Faldo Maldini: Jangan Pernah Takut sama Gambar Kawan, Mari Ngopi
Karya seni itu disebut sebagai simbol protes yang tidak membahayakan, dan menurut kedua pakar, ekspresi melalui mural itu menunjukkan kebuntuan atau sumbatan pada saluran aspirasi di ruang lain.
Alih-alih mendengarkan dan mengoreksi kebijakan, respons yang kini diambil pemerintah dianggap tidak tepat, kata mereka.
Namun Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi, Faldo Maldini mengatakan pemerintah bukannya antikritik, tapi ia beralasan kebebasan berekspresi yang disampaikan juga harus berdasarkan koridor hukum.
Mural pada dinding terowongan inspeksi Tol Kunciran-Bandara Soekarno Hatta di Batuceper, Kota Tangerang, Banten itu kini tak jelas lagi bentuknya.
Ada bulatan hitam pada bagian tengah lukisan yang, kentara sekali hasil dipoles ulang dengan cat hitam.
Tapi sebagian masyarakat kemungkinan mengetahui — melalui media sosial — bahwa mural itu semula adalah wajah yang diduga Presiden Joko Widodo dengan mata tertutup tanda merah bertulis "404: Not Found".
Karena ditimpa cat hitam, sejak Jumat (13/08), orang-orang yang melewati lorong itu tidak akan lagi melihat gambar yang sama.
Kejadian serupa juga terjadi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mural yang semula bergambar dua karakter kartun dengan tulisan "Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit" pun tak lagi tampak, berganti dengan sebidang tembok polos bercat kuning.
Serangkaian penghapusan mural-murak itu pun ramai di media sosial. Salah satu pengguna Twitter melalui akun @milikandi membandingkan antara mural sebelum dihapus dengan yang sudah dihapus atau cat ulang.
Cuitan itu mengundang respons warganet lain @boim_blackpearl yang berkomentar dengan mengutip salah satu lirik lagu musisi Iwan Fals berjudul Coretan di Dinding.
Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan Bakti Jati Permana beralasan, penghapusan mural di wilayahnya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Sementara itu bulan lalu di Kabupaten Tangerang, Banten, kejadian yang sama dialami mural bertuliskan "Tuhan Aku Lapar!".
Kalimat yang ditulis dengan cat putih dan berlatar hitam itu kemudian jadi diblok dengan warna hitam, sehingga tulisan itu tak lagi terbaca.
Pakar sosiologi politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menyebut respons pemerintah, melalui tindakan aparatnya, dengan menghapus mural serta mencari siapa yang membuatnya, adalah tindakan yang berlebihan.
"Aparat berlebihan atau paranoid terhadap kritik. Apalagi kritiknya hanya sekadar lukisan, kata-kata, melalui mural.
"Itu menunjukkan ada semacam ketakutan dari rezim, dari pemerintahan, terhadap ekspresi yang ada dalam mural itu," tutur Ubedilah kepada kepada wartawan Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (15/08).
"Karena pembuat mural itu bukan penjahat, yang penjahat itu koruptor, yang penjahat itu kekuasaan yang melanggar HAM, atau pelaku kriminal lain," lanjut dia lagi.
Bentuk kebuntuan saluran aspirasi warga
Padahal bila ditelisik, ekspresi kritik melalui mural justru memperlihatkan mampatnya saluran aspirasi warga ke para pengambil kebijakan.
"Jadi misalnya aspirasi rakyat tentang pentingnya kebutuhan pokok masyarakat di tengah pandemi itu kan banyak yang tidak didengar baik oleh elite kekuasaan," ungkap Ubedilah.
"Lalu mereka mengekspresikan lewat media sosial, mereka takut. Mereka mau mengekspresikan dengan aksi damai di jalanan, juga enggak bisa kan, karena PPKM," lanjut dia.
"Maka mereka menyampaikan melalui mural, yang dalam terminologi demokrasi sah-sah saja sebagai aspirasi," Ubedilah menambahkan.
Senada diungkapkan Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto.
Ruang berpendapat yang kian sempit kemudian membuat warga memilih mural sebagai medium untuk menyampaikan protes, ujarnya.
Alih-alih mendengarkan dan mengoreksi kebijakan, pemerintah disebut Damar secara konsisten merespons semua narasi yang berbau protes dengan 'pendekatan keamanan'.
"Kalau saya melihatnya ini sebagai bagian dari antikritik, jadi alergi kritik, karena itu kan protes kemudian dibalas dengan seperti itu [penghapusan mural]," jelas Damar yang fokus bergelut di isu kebebasan berekspresi.
"Karena ini bukan soal estetika, bukan soal tertib hukum, tetapi kita harus melihatnya sebagai ruang ekspresi warga kemudian semakin mengecil dan terbatas kalau modelnya kayak gini," terang Damar kepada BBC News Indonesia.
Kondisi tersebut, menurutnya, sejalan dengan analisis sejumlah intelektual yang ia sebut melihat semakin terbatasnya ruang-ruang berpendapat bagi warga.
Penghapusan mural ini, demikian Damar, hanya satu kejadian kecil yang menghubungkan banyak kejadian yang tengah terjadi di masyarakat terkait ancaman kebebasan berekspresi dan berpendapat.
"Ketika warga menyampaikan protes dengan berbagai medium, pun akan mengalami ancaman yang sama, ada yang dihapuskan, dicat ulang, ada yang harus berhadapan dengan hukum," beber Damar.
"Banyak juga yang harus kehilangan entah barang entah nyawa. Yang terakhir ini, yang menjadi sorotan kan apa yang terjadi di daerah konflik, di Papua, ketika banyak protes, dihadapinya dengan kekuatan senjata," imbuh dia lagi mencontohkan.
Stafsus Mensesneg: pemerintah tidak antikritik
Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, petugas Polresta Tangerang sampai menelusuri siapa pembuat mural 'Tuhan Aku Lapar'.
Hal ini juga dialami seniman mural dengan gambar wajah diduga Jokowi bertuliskan "404: Not Found".
Dikutip dari Tempo.co, Kabid Humas Polres Metropolitan Tangerang Abdul Rachim menyebut mural itu tak hanya mengganggu ketertiban umum melainkan juga berindikasi pelecehan dan penghinaan simbol negara.
"Kami masih melakukan penyelidikan, pemural masih dalam penelusuran," kata Rachim.
BBC News Indonesia mencoba menghubungi Kepolisian Indonesia atas penindakan di sejumlah daerah, tapi Kepala Divisi Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono tak menjawab panggilan telepon maupun pesan yang dikirim redaksi hingga berita ini diturunkan.
Akan tetapi perwakilan pemerintahan, Faldo Maldini selaku Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi mengklaim 'pada prinsipnya pemerintah tidak pernah antikritik'. Ia mengatakan, ruang dialog selalu terbuka.
Bahkan mural itu sendiri menurut dia menjadi salah satu bukti keterbukaan ruang berpendapat bagi publik.
"Tidak ada tendensi kami untuk membatasi kritik, apapun kritik diperbolehkan, kalau saya pribadi me-list serangan ke Pak Jokowi itu sudah macam-macam," kata Faldo saat dihubungi BBC News Indonesia.
"Yang terakhir paling ramai The King of Lip Service itu, PKI lah, Cina lah, antek asing lah, dan tidak ada marah Pak Presiden. Asal, tidak sewenang-wenang, tidak melawan hukum," lanjut dia.
Faldo berkeras dan meyakini apa yang terjadi pada kontroversi mural berujung penghapusan itu terjadi karena menyalahi peraturan yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Ia mengklaim pemerintah tak pernah mempermasalahkan konten mural.
"Karena mural, apapun isinya, yang gambarnya memuji pemerintah, tokoh politik, atau mengkritik pemerintah, kalau tidak ada izinnya ya bisa berujung ke tindakan melawan hukum, mencederai hak orang lain karena kan memang ada di KUHP," kata dia.
Kendati ia tidak menjelaskan lebih lanjut pasal yang dimaksud dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP).
"Sesulit apapun situasi kita hari ini, banyak orang yang lagi sulit, bukan jadi alasan bagi kita untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang, bertindak melawan hukum, karena bisa mencederai hak orang lain," tutur Faldo.
"Jadi kalau kita benarkan, di situ kita sedang pecah-belah bangsa ini, politik belah bambu, pakai kebencian, apalagi kita sedang menghadapi pandemi karena kerja kita trennya sedang positif dan itu yang menjadi fokus utama," imbuh dia.
Amnesty International: '132 kasus pelanggaran kebebasan bereskpresi'
Sepanjang 2020, laporan terbaru Amnesty International yang diterbitkan April 2021 mencatat setidaknya 132 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi dengan total korban 157 orang — dengan dugaan kriminalisasi baik menggunakan pasal dalam UU ITE maupun KUHP.
Baca juga:
- Kapolri Listyo Sigit Prabowo akan bentuk polisi virtual, peneliti khawatir orang kritis 'dikriminalisasi'
- Pemerintah bentuk tim kajian reformasi UU ITE, diharapkan dua bulan ke depan ada solusi soal pasal karet
- Revisi UU ITE membatasi kebebasan berekspresi?
Menurut Ubedilah Badrun, sebagaimana juga diungkapkan oleh Damar Jurniarto, kritik melalui mural sesungguhnya tak membahayakan. Karena itu tidak tepat jika protes melalui mural berbuntut pada proses hukum.
Berdasarkan analisisnya, aparat akan menindak sebuah peristiwa biasanya didasarkan setidaknya pada tiga hal yakni jika itu melanggar aturan, atau jika hal itu membahayakan warga di sekitar, atau yang ketiga adalah jika ada perintah dari atasan.
Ia menduga alasan terakhirlah yang menjadi faktor kejadian belakangan. "Mural kritik sosial itu tidak menyakiti atau melukai hak asasi manusia. Dan mural itu juga tidak dalam bentuk kekerasan fisik kan," urai Ubedilah.
"Karena [penghapusan mural] ini situasinya nasional, dan umum terjadi di mana-mana, itu berarti ada semacam perintah terhadap aparat di mana-mana untuk menghapus mural yang bernuansa kritik sosial dan kritik pada kekuasaan," kata dia curiga.
'Apa yang melatari? Kenapa kita tidak boleh protes?'
Pengamat kebebasan berekspresi Damar Juniarto punya pendapat sama. Penghapusan mural tersebut tak berdiri sendiri, melainkan harus dikaitkan dengan rangkaian respons terhadap pelbagai kritik lain--termasuk di ranah digital.
"Saya tidak melihat ini sebagai sebuah bentuk yang insidental, karena ini kan terjadi di banyak tempat, artinya ruang-ruang protes itu makin lama ditanggapinya dengan cara demikian," lanjut dia.
Setiap kali muncul protes, cara penanganan pemerintah acapkali seragam melalui pendekatan keamanan yang disebut Damar 'memperlihatkan karakter merespons warga itu yang lebih dikedepankan adalah upaya menutupi dan tidak mendengarkan'.
"Nah, apa yang melatari? Kenapa kita tidak boleh protes, ya?" kata Damar.
"Apakah kebijakan ini memang kebijakan yang tidak boleh dikritik dan dianggap sudah benar. Ataukah ini hanya sentimen 'ABS' Asal Bapak Senang," lanjut dia mengurai dua kemungkinan yang melatari mengapa pemerintah alergi terhadap protes.
Berdasarkan pengamatannya sejauh ini, respons pemerintah menunjukkan kecenderungan yang lebih mengarah ke karakter otoritarianisme. "Meskipun tidak langsung melompat kita menuduh bahwa pemerintahan ini otoriter."
"Tapi karakternya itu, protes-protes warga lebih diarahkan ke tidak ada dialog dan dialog macet. Komunikasi politik yang macet itu kan sebenarnya karakter otoritarianisme," terang dia lagi.
"Karena kalau ABS, [penghapusan mural] itu kan terjadinya bukan hanya di Tangerang, tapi di tempat lain ada," imbuh Damar.
Ia menyaksikan 'konsistensi' perlakuan sepanjang periode kepemimpinan Jokowi. Menurut Damar, 'karakter antikritik' itu muncul pertama-tama pada tahun 2014, meski tak begitu kentara dan mulai menguat belakangan.
"Semua narasi yang berbau protes ditangani dengan pendekatan keamanan, pendekatan cipta kondisi bahwa semua baik-baik saja. Saya rasa itu yang lebih mengkhawatirkan," pungkas Damar.
Pengamatan itu juga disampaikan pakar sosiologi politik Ubedilah Badrun. Sepanjang setelah reformasi, belum pernah ada insiden penghapusan mural yang mengandung kritik sosial. Terakhir yang ia saksikan hal seperti ini terjadi ketika era Orde Baru.
Dia lantas menambahkan, penghapusan mural juga merupakan bentuk pembungkaman kritik dan menunjukkan ketakutan pemerintah. Itu artinya menurut dia, boleh jadi apa yang disuarakan warga adalah fakta yang berusaha ditutupi pemerintah.
"Jadi kalau kemudian, mural-mural itu begitu cepat dihapus, itu menunjukkan bahwa apa yang disuarakan oleh rakyat itu adalah suatu kebenaran.
"Dan upaya menghapus itu adalah agar aspirasi rakyat itu tidak meluas. Tapi justru sekarang makin meluas kan?" kata Ubedilah.
"Itu artinya apa, artinya rakyat meyakini ekspresi mereka benar. Bahwa aspirasi di dalam mural itu menunjukkan hal empirik yang sesungguhnya terjadi di masyarakat.
"Artinya penguasa sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Bayangkan, sama mural saja takut," ucap dia lagi.