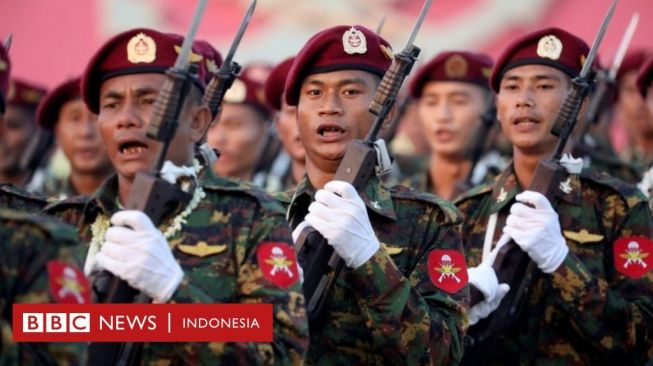Suara.com - Kudeta yang dilakukan angkatan bersenjata Myanmar berlangsung, Selasa (2/2/2021). Lewat kudeta itu, militer menahan pemimpin de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Namun ini bukan kudeta militer pertama di negara yang juga dikenal dengan nama Burma itu. Bagi banyak warga Myanmar, kudeta awal pekan ini mengingatkan mereka pada peristiwa yang terjadi pada akhir dekade 1980-an.
"Seperti deja vu, kami seperti kembali ke masa lalu," kata seorang warga Myanmar berusia 25 tahun.
Lantas seperti apa kehidupan masyarakat di bawah pemerintahan junta militer?
- Warga Myanmar memukul panci dan wajan, serta bunyikan klakson sebagai protes kudeta militer
- Diiringi lagu 'Ampun Bang Jago', instruktur kebugaran tidak sengaja rekam video kudeta militer di Myanmar
- Siapa Min Aung Hlaing, jenderal di balik kudeta militer Myanmar?
'Saya tumbuh dengan rasa takut'
Wai Wai Nu berumur lima tahun ketika melihat ayahnya ditangkap. Saat itu ayahnya adalah aktivis politik yang berafiliasi dengan Aung San Suu Kyi.
Wai Wai melihat bagaimana ayahnya dinaikkan ke atas truk lalu dibawa tentara.
Ayahnya memang dilepaskan satu bulan setelah setelah penangkapan itu. Namun sampai sekarang Wai Wai tidak bisa melupakan bagaimana perasaannya hari itu.
"Saya tumbuh dengan rasa takut yang terus-menerus mengintai saya," ujarnya.
"Sebagai seorang anak, saya selalu merasa takut. Di mana-mana selalu ada tentara dan saya masih bisa membayangkan mereka mengambil ayah dari saya.
Baca Juga: 6 Negara yang Pernah Kudeta Militer Selain Myanmar
"Saya ingat, pada kejadian itu kami memakai penyuara telinga dan mendengarkan siaran radio dengan tenang."
Wai Wai, yang berlatar belakang Rohingya, salah satu etnis minoritas yang paling teraniaya di negara itu, menyebut ayahnya selalu dikejar-kejar aparat.
Ketika Wai Wai berusia 10 tahun, keluarganya memutuskan pindah ke ibu kota Myanmar saat itu, Yangon.
"Saya memang melihat lebih banyak kebebasan di Yangon," katanya.
"Di Rakhine, mayoritas penduduk beretnis Rohingya, sedangkan masyarakat di Yangon lebih multikultural dengan bahasa yang berbeda.
"Akan tetapi banyak orang di Yangon tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang terjadi dengan orang-orang beretnis minoritas," tuturnya.
Ketika itu, kehidupan Wai Wai terlihat cukup normal.
"Kami berangkat ke sekolah lalu pulang. Di sekolah, saya ingat kami pernah diharuskan menyambut dan memberi penghormatan kepada beberapa jenderal militer," ujarnya.
"Sistem pendidikan kami sederhana, basisnya propaganda militer," kata Wai Wai.
Namun kemudian, saat dia berusia 18 tahun, ayahnya kembali menjadi sasaran aparat. Seluruh anggota keluarganya dipenjarakan. Mereka berada di balik jeruji besi selama tujuh tahun.
- Kudeta Myanmar: Mengapa dilakukan sekarang dan apa keuntungan yang didapat militer?
- Barat kecam kudeta di Myanmar, ASEAN tak satu suara
- Benarkah Myanmar tujuan jihad baru kelompok ekstrem Indonesia?
Tapi apa yang membuat Wai Wai dipenjara? Statusnya sebagai anak seorang aktivis politik.
Setelah dibebaskan, Wai Wai melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Sekarang dia bekerja sebagai aktivis hak asasi manusia. Dia menggaungkan persamaan hak bagi perempuan dan orang-orang Rohingya.
"Saat saya tumbuh dewasa, negara bagian Rakhine adalah kawasan miskin tapi kondisinya tidak sedemikian buruk. Banyak orang masih bisa menjalankan bisnis," kata Wai Wai.
"Dulu kondisinya tidak seperti sekarang," ujarnya.
Penyadap di balik telepon
Warga Myanmar lainnya, Phyo (bukan nama sebenarnya), memiliki pengalaman yang sangat berbeda saat tumbuh dewasa.
Laki-laki berumur 25 tahun yang lahir dan besar di Yangon ini berasal dari keluarga yang lebih kaya dibandingkan Wai Wai. Dia mengaku terlindungi dari hiruk-pikuk yang terjadi di Myanmar.
Namun Phyo mengingat beberapa hal menonjol yang terjadi saat dia masih anak-anak.
"Ketika Anda berbicara di telepon, Anda dapat mendengar suara lain, misalnya seseorang yang menonton televisi atau suara orang yang sedang berbicara. Mereka adalah aparat militer yang mengawasi Anda," ujarnya.
"Itu tidak menakutkan, karena ketika Anda lahir dalam situasi itu, Anda tidak mengetahui kondisi yang berbeda dengan keseharian Anda.
"Tapi orang tua kami memberitahu agar kami tidak menggunakan telepon," tuturnya.
Phyo lahir tahun 1995 atau tiga tahun setelah diktator militer Than Shwe berkuasa. Phyo menyebut tahun kelahirannya sebagai "puncak kekuasaan militer setelah revolusi tahun 1988".
Di sekolah, kata Phyo, kurikulum sekolah disusun dengan sangat selektif terkait hal-hal yang akan diajarkan kepada murid.
"Para guru tidak mengajarkan hal-hal sensitif. Jika di Amerika Serikat pendidikan mungkin membuat Anda mengkritik situasi politik, kami malah diminta membaca dongeng-dongeng Buddha," ucapnya.
"Atau Anda akan belajar bahwa raja-raja Myanmar benar-benar hebat sampai semua jengkal tanah mereka diambil Inggris."
Inggris menduduki Myanmar dari tahun 1824 hingga 1948.
Bagaimanapun, Phyo mengaku terlindungi dari pergolakan politik negaranya sampai usia 12 tahun.
"Saya masih ingat saat itu adalah ulang tahun saya yang ke-12 ketika Revolusi Saffron terjadi. Saat itulah saya tersadar bahwa kami hidup di bawah kediktatoran," kata Phyo.
Revolusi Saffron adalah serangkaian unjuk rasa jalanan di Myanmar pada tahun 2007. Kala itu ribuan biksu di Myanmar bersatu melawan rezim militer.
Biksu sangat dihormati oleh kebanyakan orang di Myanmar, negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Tapi banyak biksu dipenjara pada revolusi itu. Sebuah laporan menyebut setidaknya tiga biksu dibunuh militer kala itu.
"Saya melihat banyak pengunjuk rasa di luar rumah say. Ada ketegangan dan ketakutan. Tentara ada di mana-mana," kata Phyo.
- Aung San Suu Kyi dan mantan pemimpin sipil Myanmar didakwa 'miliki walkie-talkie'
- Mengapa China halangi PBB kutuk kudeta militer di Myanmar?
- Kesaksian warga Myanmar setelah kudeta militer: 'Dunia kami benar-benar terbalik dalam satu malam'
Saat tumbuh menjadi seorang remaja, Phyo melihat bahwa ponsel hanya digunakan oleh orang-orang mampu di Myanmar.
"Pemerintah membuat harga ponsel sangat mahal, jadi tidak ada yang mampu membelinya.
"Dulu masyarakat hanya memiliki sambungan telepon rumah tapi kadang-kadang terjadi pemadaman listrik sehingga Anda tidak bisa menghubungi siapa pun," ujarnya.
Phyo melanjutkan pendidikan ke universitas di luar negeri. Saat itulah dia menyadari banyak hal di Myanmar sangat berbeda dengan apa yang terjadi di negara Barat.
"Saya ingat, jika melihat polisi kawan-kawan saya akan berkata, 'mereka menakutkan!' Tapi bagi saya, melihat tentara berkeliaran di mana-mana adalah hal normal," ujarnya.
Pagi hari pada 1 Februari lalu, Phyo bangun jam 6 pagi karena puluhan notifikasi muncul di ponsel pintarnya.
"Anda baru saja bangun dan tiba-tiba seluruh pejabat pemerintahan Anda ditangkap," katanya.
"Ketika masih anak-anak, saya terbangun dengan berita-berita seperti ini, bahwa orang tiba-tiba masuk penjara atau menghilang.
"Rasanya seperti deja vu, kami seperti kembali ke titik awal seperti keadaan yang dulu. Upaya yang telah kami lakukan, segala legitimasi yang semua kami berikan kepada pemerintah hilang," ujar Phyo.
Hidup dalam keheningan
Kyaw Than Win, 67 tahun, masih ingat di mana dia berada saat kudeta militer terjadi tahun 1988.
Kyaw tinggal di Min Bu, sebuah kota di kawasan tengah Myanmar. Dia berkata, waktu itu penembakan dan kekerasan terjadi di kota lain. Tapi Min Bu relatif tenang dan tenang.
Setelah kudeta itu, kata Kyaw, kebanyakan orang meneruskan keseharian seperti biasa. Meski begitu, dia menyebut orang-orang tidak membicarakan kudeta secara terbuka.
"Kami kembali bekerja. Beberapa pegawai negeri yang terlibat unjuk rasa diberhentikan dan sebagian lagi dipindahkan atau mendapat penurunan pangkat, dan ada juga yang ditahan," kata Kyaw.
"Tapi untuk pegawai negeri seperti saya, kami kembali bekerja seperti biasa. Kami harus memaksa diri untuk menjalani hidup dalam keheningan karena ketakutan."
Sebagian besar kehidupan Masyarakat Myanmar berlanjut seperti itu hingga pemilu tahun 2015, saat pemilu digelar di negara itu untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi menang telak dalam pemilu itu. Mereka mengakhiri pemerintahan militer yang berlangsung hampir selama 50 tahun.
"Saya sangat senang bahwa seseorang seperti Suu Kyi memimpin negara ini. Pemerintahannya menjalankan tugas dengan baik. Infrastruktur umum dasar diperbaiki dan kehidupan pegawai negeri juga meningkat," kata Kyaw.
"Hidup menjadi jauh lebih baik," klaimnya.
Namun, ternyata masa-masa itu berumur pendek. Menurut Kyaw, keputusan militer melakukan kudeta awal pekan ini mengkhianati "harapan jutaan orang".
Menurut Profesor Simon Tay, ketua Singapore Institute of International Affairs, angkatan bersenjata Myanmar masih yakin bahwa hanya mereka yang dapat menjaga persatuan negara itu.
"Meskipun NLD menyapu dua pemilihan umum, mereka tidak menerima bahwa mereka harus mundur dari politik nasional," kata Tay.
Namun Tay menilai "hanya sedikit kelompok, bahkan di kalangan militer, yang ingin kembali ke masa ketika Myanmar terperosok oleh otokrasi, sanksi ekonomi dan kemiskinan massal".
"Tapi transisi dan upaya Myanmar membuka diri masih jauh dari selesai dan militer akan melakukan apa yang mereka anggap harus mereka lakukan," ujar Tay.
---
Yip Wai Yee turut berkontribusi untuk artikel ini.