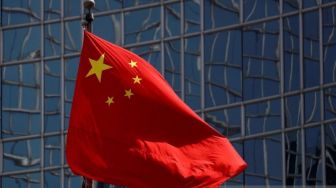Suara.com - Para pejabat Partai Komunis China sudah sejak lama penasaran, tapi juga terganggu dengan pemilihan presiden Amerika Serikat.
Bisa dipahami juga pilpres di AS selalu dipantau secara saksama oleh para pejabat di Beijing.
Namun hajatan demokrasi di AS digelar dalam situasi yang berbeda: pandemi Covid-19 masih terus menyebar, lanskap ekonomi yang hancur, dan polarisasi politik yang sangat tajam.
China merasakan ada sesuatu yang telah berubah.
Baca Juga: Sudah Mundur, Meghan Markle Lagi-lagi Dituduh Langgar Aturan Kerajaan
Yang terancam bukan otoriterisme China, melainkan demokrasi Barat, yang tiba-tiba seperti menghadapi krisis legitimasi.
Ekonomi paling bebas dan terkaya di dunia, yang pernah dianggap berada dalam posisi yang jauh lebih baik untuk melawan virus -- melalui alat transparansi dan akuntabilitasnya -- telah dianggap gagal.
- Siapa capres AS yang diinginkan menang oleh China, Iran, dan Rusia?
- Apakah perlu Yesus untuk memenangkan Pilpres AS?
- Pilpres AS: Apa yang dimaksud dengan electoral college?
Sementara China, yang awalnya dituduh menutup-nutupi skala pandemi, dengan aneka sumber daya dan konsenstrasi kekuasaan, memaksa orang mengikuti karantina secara massal. Dampaknya sungguh terasa.
Pabrik, toko, restoran, sekolah, dan universitas semuanya buka, jumlah penumpang angkutan umum hanya sedikit di bawah rata-rata sebelum pandemi.
Perekonomian China diharapkan bisa tumbuh, ketika banyak semua negara lain diperkirakan menyusut.
Baca Juga: Dilanda Pandemi, Gedung Putih Pastikan Pilpres AS Pada 3 November 2020
Ada ongkos yang harus dibayar.
Sensor ketat bisa membuat apa yang sebenarnya terjadi tak bisa diberitakan.
Tak seorang pun diizinkan memberikan suara yang berarti untuk atau menentang pembuat keputusan mana pun, di tingkat pemerintahan mana pun.
Namun, para petinggi mengklaim pendekatan mereka membawa hasil.
"Pencapaian strategis utama yang diperoleh dari upaya China melawan Covid-19 sepenuhnya menunjukkan keunggulan luar biasa dari kepemimpinan Partai Komunis China," kata Presiden Xi Jinping bulan lalu di sebuah acara untuk merayakan para pekerja kesehatan dan "pahlawan" dari kemenangan ini.
Di berita-berita yang disiarkan TV pemerintah, dipampang statistik suram yang memetakan bencana kesehatan Amerika yang sedang berlangsung, di samping gambar demonstrasi, perbedaan pendapat dan kekacauan kampanye pemilihan presiden.
Tidak peduli siapa yang menang, pesan yang ingin disampaikan adalah, ketika politik Amerika sakit, terbongkar apa yang dikatakan sebagai kelemahan demokrasi dan memudarnya prestise demokrasi AS di mata dunia.
Tidak banyak metafora visual yang lebih baik untuk menggambarkan kepercayaan China terhadap sistem yang mereka bangun. Pameran Mobil Beijing bulan ini adalah salah satunya.
Ajang konsumerisme ini juga bisa dibaca bahwa kerja sama ekonomi mestinya menggantikan konfrontasi ideologis dengan Amerika.
Acara yang digelar di kompleks pameran yang luas itu adalah pertunjukan industri otomotif besar pertama di dunia sejak pandemi dimulai, sekaligus bukti kemenangan negara ini atas virus corona.
Terlepas dari masker-masker medis yang dikenakan, peristiwa itu seperti pemandangan dari era sebelum virus corona melanda.
Masyarakat yang membawa merchandise di sekitar stan perdagangan, berpose untuk foto dengan model dengan gaun ketat yang berdiri di samping mobil.
Tetapi jika pameran itu adalah tanda kemampuan China untuk membendung gelombang pandemi, itu juga bukti dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan memiliki dampak jangka panjang: kemampuan China meraup keuntungan dari perdagangan global.
Salah satu mobil termahal yang dipamerkan adalah SUV listrik berwarna hijau cerah dengan label harga 550.000 Yuan China (Rp1,2 miliar) yang dibuat oleh Hongqi, pabrikan China yang pernah terkenal dengan limusin bergaya Soviet yang membosankan.
"Kita harus mendukung merek buatan negara kita sendiri," kata seorang pria, sambil memeriksa lis kulit kursi penumpang depan.
Ini adalah simbolisme yang tidak akan terlewati oleh Richard Nixon, presiden AS yang meluncurkan pemulihan hubungan Amerika dengan China.
Dalam kunjungan bersejarahnya ke Beijing pada tahun 1972, ia dibawa dengan mobil tradisional Hongqi di sepanjang jalan tanpa kemacetan - awal dari perjalanan hubungan antara kedua negara yang akan berlanjut selama lebih dari 40 tahun.
Hampir setiap presiden AS sejak itu mempercayai gagasan bahwa itu tidak hanya menguntungkan China dan perusahaan multinasional yang menghasilkan keuntungan di sana, tetapi juga untuk Amerika dan dunia yang lebih luas.
Itu tidak hanya meningkatkan kemakmuran global secara keseluruhan, itu dikatakan, tetapi itu akan membawa China ke tatanan global liberal dan bahkan mendorongnya untuk merangkul kemungkinan reformasi politik di dalam negeri.
Pada kenyataannya, China melihatnya dengan sangat berbeda, didorong oleh tujuan tunggal untuk merebut kembali tempat yang selayaknya di panggung global dan dengan caranya sendiri.
Pada saat pemilihan AS 2016, China adalah ekonomi terbesar kedua di dunia dan negara pengekspor terbesar ke AS.
Namun China juga dituduh melakukan pencurian rahasia industri terbesar dalam sejarah dan menahan secara massal satu kelompok etnis, yang digambarkan sebagai penahanan terbesar sejak Perang Dunia Kedua.
Di kampanye tahun 2016 itulah, konsensus yang sudah tidak jelas tentang kebijaksanaan perdagangan dan keterlibatan yang terus meningkat dengan China akhirnya pecah.
Mencalonkan diri untuk masa jabatan pertamanya, pesan Donald Trump ke basis kerah birunya adalah bahwa China yang sangat proteksionis telah lama menipu komitmen perdagangan bebas untuk mengubah dirinya menjadi negara adidaya ekonomi.
Dalam hal kehilangan pekerjaan, menurutnya, hal itu membuat pekerja AS lebih buruk, bukan lebih baik.
Dia membawa pesan itu sampai ke Gedung Putih dan semuanya berubah sejak itu.
Perang dagang tit-for-tat oleh presiden, pada puncaknya, menyebabkan barang dengan nilai total US$362 miliar (Rp5,3 kuadriliun) dikenai tarif hukuman.
Tahun ini, pemerintahannya telah menambah tekanan ekonomi dengan rentetan sanksi politik atas pelanggaran hak asasi manusia di China.
Di stan Hongqi, saya bertanya kepada salah satu dari mereka siapa yang dia inginkan untuk memenangkan pemilu AS.
"Mungkin Biden," katanya, menambahkan, "Saya benci Trump."
"Karena dia begitu keras terhadap China?" Saya bertanya.
"Sedikit," jawabnya, "dan menurutku dia gila."
Para pemimpin China mungkin memiliki perasaan yang semakin kuat bahwa demokrasi AS tidak lagi relevan, tetapi jika mereka harus mengungkapkan pilihan, mungkinkah mereka juga senang melihat Donald Trump terlempar dari Gedung Putih?
Itu menjadi penilaian komunitas intelijen AS yang telah menyimpulkan bahwa ketidakpastian Trump, dan kritik kerasnya terhadap Beijing, berarti kepemimpinan Partai Komunis akan lebih suka jika dia kalah.
Tetapi Profesor Yan Xuetong, Dekan Institut Hubungan Internasional di Universitas Tsinghua Beijing tidak setuju.
"Jika Anda bertanya kepada saya tentang di mana letak kepentingan China," katanya, "preferensi akan ke Trump daripada Biden".
"Bukan karena Trump akan melakukan lebih sedikit kerusakan pada kepentingan China daripada Biden, tetapi karena dia pasti akan lebih merusak [reputasi dan kepentingan] AS daripada Biden."
Ini adalah tanda seberapa jauh hal-hal telah memburuk dari gagasan tentang ikatan ekonomi yang lebih erat untuk keuntungan bersama.
Pengamat China yang terkemuka sekarang siap untuk menyatakan secara terbuka bahwa kemunduran AS, baik secara ekonomi maupun politik, adalah keuntungan bagi China.
Sementara beberapa pengamat berpendapat bahwa kepercayaan China pada akhir dominasi global AS sudah ada sebelum virus mewabah dan ketika Presiden Trump menang pilpres, yang berubah adalah kesiapan untuk mengutarakannya.
Dari perspektif ini, Donald Trump adalah pilihan yang lebih baik, bukan karena dukungannya terhadap cita-cita demokrasi, tetapi justru karena ia sering terlihat menolak atau meremehkan demokrasi.
Serangan Trump terhadap kebebasan pers, misalnya, tentu akan disambut dengan hangat oleh Beijing, yang menolak pengawasan independen dan berniat mengontrol internet.
Memang pemerintahan Trump semakin kritis terhadap catatan atas hak asasi manusia di China, namun sejatinya, motivasinya jauh lebih dangkal dan sempit, yaitu keuntungan perdagangan dan ekonomi.
Menurut mantan Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, Trump pernah memberi tahu Xi Jinping bahwa Trump menyetujui tindakan keras Xi Jinping terhadap warga Muslim Uighur, meskipun Trump membantah klaim tersebut.
Ia juga mengolok-olok dukungan Joe Biden bagi hubungan ekonomi yang lebih dekat dengan China.
Namun, sebagai perbandingan, Beijing akan lebih khawatir dengan Biden karena komitmen Biden terhadap HAM jauh lebih besar dan ini membuat Beijing khawatir.
Juga, Trump cenderung mundur dari kerja sama internasional, sementara Biden dinilai punya kelebihan membangun jaringan internasional, kemampuan yang diperlukan untuk menekan China terkait perlakuan mereka terhadap warga mereka sendiri.
Christian Ji adalah salah satu korban dari apa yang dilihat beberapa akademisi AS sebagai perubahan xenofobia dalam pendekatan Washington; menargetkan siswa China.
Seorang siswa pertukaran belajar ilmu komputer di Arizona, bulan lalu visa Ji dicabut sebagai bagian dari larangan masuk yang diberlakukan oleh Washington pada ratusan peneliti China dari universitas yang memiliki hubungan dengan militer.
Visanya kemudian dipulihkan karena peraturan, yang dirancang untuk mengecualikan mahasiswa, salah diterapkan kepadanya.
Tetapi meskipun pengalaman itu membuatnya marah pada Presiden Trump, itu tidak mengubah pandangannya tentang Amerika.
"Saya sangat menyukai lingkungan di AS," katanya saat kami bertemu di kedai teh di Beijing.
"Polusi lebih sedikit daripada di China, dan pendidikan lebih didasarkan pada pemikiran. Di China, lebih fokus pada benar atau salah."
Ini adalah pengingat bahwa meskipun China semakin yakin bahwa demokrasi barat sedang dalam krisis, nilai-nilai Amerika masih dihormati oleh banyak orang di sini.
Jika suar demokrasi benar-benar kehilangan kilau, mengapa, Anda mungkin bertanya-tanya, ada 360.000 siswa China di AS pada tahun 2018, 30 kali lebih banyak dari jumlah siswa AS di China?
Upaya propaganda China untuk menggambarkan penaklukan virus sebagai bukti keunggulan sistemnya tidak boleh dianggap remeh.
Para pemimpin negara itu tahu betul bahwa sejumlah negara demokrasi juga berhasil mengendalikan virus; Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan, hanyalah beberapa di antaranya.
Bahkan bagi mereka yang berjuang dengan serius, beberapa pengamat percaya masih ada alasan untuk optimisme tentang kemampuan masyarakat terbuka untuk akhirnya belajar, beradaptasi, dan mengoreksi.
Dan sementara perlindungan hak individu dapat membuat pengendalian epidemi menjadi jauh lebih sulit, sistem di mana orang dapat "diborgol ke rumah mereka" tidak mungkin menjadi utopia kesehatan masyarakat.
Jadi, keyakinan China bahwa virus itu membantu mempercepat kedatangan dunia 'multi-kutub' - di mana norma otoriternya diberi bobot yang sama dengan yang demokratis - mungkin lebih merupakan angan-angan daripada prediksi sejarah.
Ironisnya, seorang presiden AS yang menegaskan kembali keyakinannya pada tatanan dunia liberal dan kembali ke panggung dunia mungkin jauh lebih baik bagi China dalam jangka pendek.
Joe Biden mungkin menjanjikan untuk menekan China terkait isu hak asasi manusia dan - sebagai tanda seberapa jauh konsensus sekarang telah bergeser di Washington - menyebut Xi Jinping "seorang preman".
Tetapi dia mungkin mengambil garis yang lebih lunak tentang tarif dan dia akan jauh lebih bersedia untuk mencari kerja sama dalam masalah-masalah seperti perubahan iklim, yang berpotensi dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh China untuk keuntungannya.
Penguasa China meskipun tidak berpikir dalam hal siklus pemilihan, mereka merenungkan akhir suatu zaman.
Dan Amerika yang menegaskan kembali dirinya sebagai negara terdepan dalam penegakan nilai-nilai universal adalah hal yang paling mereka takuti.