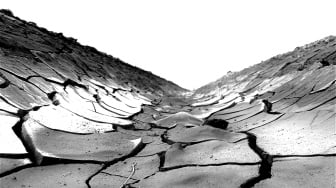Suara.com - Seorang pria kulit hitam tampak kesakitan ketika tubuhnya ditindih oleh polisi. Pria bernama George Floyd itu berusaha mengambil napas namun semakin ia melawan, semakin besar juga tekanan yang dirasakan.
Tak lama setelah diselamatkan, George justru menghembuskan napas terakhir. BBC melaporkan nyawanya tak tertolong meskipun ia sudah dilarikan ke rumah sakit. Kemarahan publik memuncak atas kejadian ini.
Sekali lagi Minneapolis menjadi saksi bagaimana rasisme terus menggerus Amerika.
Unjuk rasa atas kematian George Floyd tak bisa dibendung, massa berkerumun di depan gedung putih dan mulai mengunci kantor pemerintahan, tempat Presiden Trump memimpin negaranya. Mereka menuntut keadilan atas kematian Floyd.
Kasus ini tak sesederhana kasus pembunuhan lainnya. Nafas Floyd yang tersekat adalah potret nyata bagaimana ras kulit hitam berdiri dalam bayangan ketakutan.
Keisha N. Blain, seorang profesor madya bidang sejarah di Universitas Pittsburgh menulis di Washington Post bahwa kekerasan terhadap Floyd hanya berselang dua bulan setelah kematian wanita kulit hitam bernama Breonna Taylor.
Keisha mengungkapkan bahwa ancaman orang kulit hitam di Minneapolis bukanlah virus yang menjadi pandemi, tapi kekerasan polisi.
![Seorang demonstran memainkan drum di depan gedung yang terbakar saat demonstrasi di Minneapolis, Minnesota, Jumat (29/5). [Chandan Khanna/ AFP]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/05/30/34173-rusuh-kematian-george-floyd.jpg)
Berdasarkan sejarah, kekerasan seperti ini sudah terjadi berabad-abad lamanya di Amerika. Sejak dulu, orang kulit hitam hanya dianggap budak dan hak-hak mereka dibatasi oleh orang kulit putih yang merasa yakin, kedudukannya lebih tinggi dari kulit hitam.
Jauh sebelum George Floyd dilahirkan, sekitar abad ke-20, hukuman mati tanpa pengadilan muncul sebagai taktik baru untuk mengendalikan kehidupan orang kulit hitam.
Baca Juga: Aksi Solidaritas untuk George Floyd Menjalar hingga ke Inggris
Pejuang anti-hukuman mati tanpa pengadilan, Ida B. Wells-Barnett mengungkapkan dalam 'The Red Record' bahwa hukuman mati tanpa pengadilan terhadap orang kulit hitam Amerika tidak hanya direncanakan sebelumnya tapi juga didukung penuh oleh polisi setempat.
Selama musim panas 1919, kekerasan ras besar-besaran meletus di Amerika. Di Chicago, Eugene Williams, seorang remaja kulit hitam dibunuh pada 27 Juli 1919 karena berenang di bagian khusus 'kulit putih' Danau Michigan.
Persis seperti amarah pasca kematian Floyd, massa juga geram ketika William dibunuh.

Unjuk rasa ini berlanjut sekitar sebulan dan berakhir pada Agustus 1919 dengan kematian 15 orang kulit putih, 23 orang kulit hitam dan sedikitnya 500 orang terluka. Jumlah ini belum termasuk ribuan keluarga kulit hitam yang kehilangan rumah.
Melanjutkan tulisan Keisha, penyerangan polisi pada aktivis kulit hitam selama kampanye Birmingham 1963 dan pawai Selma-to-Montgomery 1965 adalah akar rasis polisi Amerika. Kekerasan itu menargetkan pria, wanita dan anak kulit hitam.
Melesat jauh pada tahun 2009, untuk pertama kalinya Amerika memiliki presiden kulit hitam. Ia adalah Barrack Hussein Obama yang dilantik pada 20 Januari. Tentu saja ini menjadi angin segar bagi warga kulit hitam.
Sayangnya, meskipun Obama memiliki banyak prestasi di bidang pemerintahan, ia tetap disebut sebagai akar meningkatnya permasalahan rasial yang terjadi sepanjang pemerintahannya.
Kembali pada pembunuhan George Floyd, jika Marthin Luther King Jr masih hidup, mungkin ia akan menatap kosong pada kertas pidatonya yang fenomenal 'I Have Dream'. Akankah keadilan bagi orang kulit hitam selamanya menjadi mimpi?