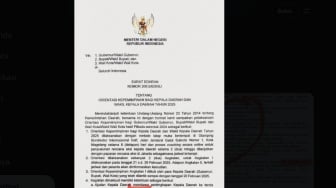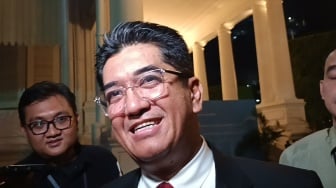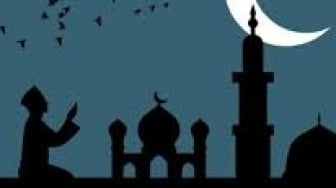Namun, Dandhy pulang sebagai orang yang tak sepenuhnya bebas. Dia pulang dengan membawa serta status tersangka penyebar ujaran kebencian berbasis SARA.
Pada pagi yang sama setelah Dandhy dibolehkan pulang, persisnya pukul 04.28 WIB, aparat Polda Metro Jaya menangkap jurnalis Ananda Badudu di sebuah gedung, kawasan Tebet.
Empat penyidik dari Polda menggedor-gedor pintu kamar eks vokalis band Banda Neira itu. Pintu dibukakan teman Ananda.
Tim polisi yang dipimpin penyidik bernama Eko menunjukan kartu identitas dan lencana Polisi. Dia mengatakan membawa surat penangkapan Ananda, karena diduga terlibat membiayai aksi mahasiswa penolak beragam RUU bermasalah yang berujung ricuh.
Mereka lalu membawa Ananda ke kantor Resmob Polda Metro Jaya memakai mobil Toyota Avanza berwarna putih. Penangkapan disaksikan oleh seorang satpam gedung dan dua tetangga.
Wakil Koordinator Kontras Feri Kusuma mengatakan, penangkapan terkait uang yang dihimpun Ananda melalui media sosial dan disalurkan untuk demonstrasi mahasiswa.
Ananda menginisasi penggalangan dana publik untuk mendukung gerakan mahasiswa melalui laman daring crowdfunding, kitabisa.com.
Dia telah menggalang dana untuk aksi mahasiswa di depan gedung DPR sejumlah Rp 131 juta. Jumlah ini melebihi target awal yaitu Rp 50 juta.
Baca Juga: CEK FAKTA: Jadi Tersangka, Benarkah Dandhy Memprovokasi Konflik Papua?
Ananda memperpanjang penggalangan dana itu. Alasannya, rapat paripurna pembahasan RUU KUHP masih akan diperpanjang sampai 30 September.
Dalam deskripsi di laman Kita Bisa, Ananda menyebut donasi ini merupakan bentuk dukungan kepada mahasiswa yang memperjuangkan hak-hak rakyat.
Uang donasi rencananya dibelanjakan keperluan logistik, penyewaan mobil komando, alat kesehatan, dan transportasi para mahasiswa menuju Gedung DPR.
Rentetan represi
SEBELUM DANDHY dan Ananda, pengacara sekaligus aktivis HAM Veronica Koman lebih dulu terbelit pidana karena gencar menyebar informasi tentang kondisi Papua.
Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan Veronica sebagai tersangka pada Rabu, 4 September 2019.
Pengacara HAM dan pendamping mahasiswa Papua di Surabaya itu dianggap melakukan provokasi dan menyebarkan berita bohong di media sosial.
Veronica dituduh menyebarkan provokasi melalui media sosial terkait persekusi rasis di asrama mahasiswa asal Papua, Surabaya, 16 Agustus lalu. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis, yakni Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.
Tak berhenti di situ, Polisi bahkan melacak rekening Veronica. Polisi mempersoalkan beasiswa S2 yang bersangkutan dari pemerintah. Veronica mendapatkan beasiswa pada 2017 untuk studi pascasarajana (S2) bidang hukum pada sebuah universitas di Australia.
Sebelumnya, polisi lebih dulu menangkap Surya Anta Ginting, Ketua Front Rakyat Indonesia untuk West Papua. Ia ditahan dan dijadikan tersangka kasus makar.
Jauh sebelum rentetan penangkapan serta proses hukum terhadap para aktivis, beragam represi terhadap masyarakat yang memperjuangkan haknya sudah lama terjadi.
Misalnya, warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) mengalami intimidasi saat melakukan aksi penolakan pabrik semen PT Semen Indonesia.
Tenda-tenda dan musala yang menjadi posko penolakan pabrik PT Semen Indonesia di kawasan Pegunungan Kendeng pada Februari 2017 lalu dirusak dan dibakar. Namun, polisi hingga kekinian belum juga menangkap pelaku dan dalangnya.
Posko penolakan pabrik PT Semen Indonesia itu didirikan warga pada 16 Juni 2014. Namun, pada 10 Februari 2017, sekitar pukul 19.30 WIB, posko itu dirusak dan dibakar sekelompok orang tak dikenal.
Aksi perusakan disertai pembakaran itu dilakukan di depan warga yang menolak pembangunan pabrik semen. Tapi, warga tak berani berbuat apa-apa karena massa perusak datang dengan jumlah besar dan menujukkan perilaku kasar.
Kejadian itu telah dilaporkan warga penolak pabrik semen kepada Polda Jateng dan Polres Rembang. Bahkan, pihak kepolisian kala itu telah menerbitkan surat laporan polisi (LP) dengan nomor: LP/A/17/II/2019/Jtg/Res/Rbg. Namun hingga kini belum ada kelanjutannya.
Sementara di Banyuwangi, warga Tumpang Pitu mengalami tindakan kekerasan dan kriminalisasi karena menolak kehadiran pertambangan.
Berdasarkan catatan investigasi KontraS, sebanyak 15 orang di Tumpang Pitu mengalami kriminalisasi dalam 5 kasus berbeda sepanjang kurun waktu 2015-2017.
Pertama, pertengahan November 2015, 1 orang warga dituduh merusak pesawat nirawak milik perusahaan. Atas tuduhan itu, warga tersebut menjadi tersangka.
Kedua, akhir November 2015, sebanyak 8 orang warga dituduh merusak fasilitas perusahaan. Kekinian, 4 orang di antaranya divonis bebas murni, sedangkan sisanya masih berproses hukum di tingkat kasasi.
Ketiga, awal April 2017, sebanyak 22 orang warga dituduh membawa spanduk aksi yang diduga mirip logo palu arit.
Atas tuduhan tersebut, 4 orang warga Sumberagung ditetapkan menjadi tersangka, dan salah satu diantaranya, Heri Budiawan ditahan.
Kasus itu bermula dari aksi pemasangan spanduk “tolak tambang” yang dilakukan pada tanggal 4 April 2017.
Aksi pemasangan spanduk penolakan ini dilakukan di sepanjang pantai Pulau Merah, Dusun Pancer-Sumberagung hingga kantor Kecamatan Pesanggaran.
Keempat, akhir April 2017, seorang warga dituduh melakukan pengadangan terhadap pekerja PT DSI. Atas tuduhan tersebut, warga itu ditetapkan sebagai tersangka.
Kelima, Mei 2017, seorang pengacara warga dituduh melakukan pencemaran nama baik perusahaan. Kasus ini bermula saat pengacara warga itu mengatakan kepada media, bahwa aktivitas kegiatan pertambangan di Tumpang Pitu diduga telah mencemari lingkungan. Atas kasus ini, pengacara warga tersebut ditetapkan menjadi tersangka.
Di Urutsewu, persisnya Desa Brencong, Kecamatan Bulupesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Selasa 10 September, sejumlah anggota TNI memukuli warga. Pemukulan petani oleh tentara itu buntut dari konflik agraria.
Peristiwa itu terjadi saat prajurit TNI melakukan pemagaran di sebuah lahan yang hingga kini masih menjadi sengketa antara warga dan TNI.
TNI mengklaim lahan warga itu adalah milik institusi militer, sedangkan dari pihak warga memiliki sertifikat hak milik atas lahan tersebut.
Warga yang melihat aksi tersebut langsung berbondong-bondong ke lokasi menghalau pemagaran itu. Sesampainya di lokasi, warga disuruh bubar dan dihadang oleh TNI bersenjata lengkap. Tak hanya menyuruh bubar, tetapi TNI juga memukuli warga.
Atas konflik tersebut, sedikitnya 16 warga terkena pukulan. Mereka di antaranya Wiwit Herwanto (30) terkena luka pukul di kaki dan dinjak-injak; Imam Suryadi (25) terkena pentungan di punggung; Haryanto (38) terkena luka tembak di pantat akibat peluru karet; Edi Afandi (32) dipukul di kepala; Supriyadi (40) dipukul di kepala, punggung dan kaki.
Selain itu, Wawan (26) terkena luka pukul di kepala; Manto (34) luka pelipis kanan; Partunah (42) ditendang-tendang kakinya dan diseret; Saikin (53) dipukul di kepala; Sartijo (52) luka paha di belakang; Sartono (45) luka pukul di kepala; Wadi (27) ditendang kakinya; Tolibin (30) luka pukul di kaki; Sumarjo (70) luka pukul di punggung; Martimin (35) luka pukul kepala; Saryono (34) luka pukul di kepala.
Kaum oligarkis
ARIZAL MUTAHIR, Dosen Sosiologi Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, mengatakan, kekerasan negara terhadap rakyatnya kekinian menjadi sesuatu yang banal alias dianggap sudah biasa dan bisa dimaklumi.
Para aktivis yang kontra, bak berada dalam rumah kaca, yakni terus diawasi dan suatu saat bisa saja terbelit masalah hukum seperti kasus Dandhy maupun Ananda.
”Kalau kekerasan dilakukan secara struktural, itu untuk melegitimasi dominasi mereka. Karena untuk melindungi sebuah kepentingan, kekuasaan mereka juga. Intinya karena melindungi kepentingan ekonomi politik. Ada kepentingan ekonomi politik yang lebih besar yang disebut oligarki itu,” kata Mutahir, Senin (7/10/2019).
Ia menuturkan, secara teoritik, penguasa biasanya menjalankan dua aparatusnya sekaligus, yakni aparatus ideologis dan aparatus represif.
Perangkat aparatus ideologis diterapkan untuk mendapatkan konsensus atau persetujuan publik atas kekuasaan melalui cara-cara lunak alias non-represif. Sementara aparatus represif bekerja sebaliknya.
Menurutnya, terdapat kecenderungan negara menerapkan secara masif aparatus represif kalau terdapat krisis hegemoni.
”Iya, kemungkinannya pemerintah sekarang krisis itu, lebih ke arah sana. Pemerintahan, eksekutifnya sekarang defisit kekuasaan,” ungkapnya.
Halili, Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta menilai, represifitas negara terutama dikaitkan dengan penangkapan para aktivis harus dilihat dari beragam arah.
Pertama, konsep aktualisasi negara, bahkan dalam sistem demokrasi, harus ditempatkan seagai satu-satunya yang diberikan otoritas untuk menggunakan alat-alat kekerasan.
“Jadi, suka tidak suka, sengaja atau tidak, dengan atau tanpa kontrol sekali pun, negara sebenarnya punya, dan dibolehkan menggunakan alat represif,” kata Halili.
Menghadapi situasi seperti itu, menurut Halili, yang diperlukan adalah kontrol demokratik guna memastikan penggunaan kekerasan oleh alat-alat negara tersebut betul-betul sejalan dalam kerangka dan nilai-nilai demokrasi.
Kedua, ada faktor-faktor terang benderang yang bisa dijadikan alasan oleh negara untuk menggerakkan aparatus represifnya.
“Tapi di lain sisi, jangan lupa, ada faktor-faktor tak terlihat yang juga bisa memanfaatkan negara dalam rangka memelihara kepentingan politik mereka, semisal swasta atau yang lain: oligarki,” ungkapnya.
Tak kalah penting, menurut Halili, terdapat kecenderungan menguatnya kapasitas warga untuk menggunakan instrumen kekerasan dalam satu dekade terakhir.
Kalau biasanya instrumen kekerasan itu dimonopoli negara, kekinian warga juga turut berperan dalam hal tersebut.
“Cek data kebebasan beragama dan berkeyakinan, 5 tahun terakhir bisa pastikan, pelanggaran oleh aktor non-negara, artinya oleh warga dan individu, angkanya lebih tinggi dibandingkan pelanggaran yang dilakukan negara,” ungkapnya.
Kenapa Dimaklumi?
PADA ERA ORDE BARU, warga lama kelamaan satu suara untuk menentang beragam represifitas pemerintah. Namun, pada zaman kiwari, kondisinya berbeda, justru terdapat warga yang mendukung represifitas tersebut.
Halili menjelaskan, fenomena itu benar-benar tampak semisal di media-media sosial. Warganet terbelah ketika merespons represifitas aparat terhadap demonstran maupun aktivis.
“Artinya paling tidak menunjukkan dua hal. Satu sisi, terdapat fenomena menguatnya peran negara dalam konteks kehidupan, berbangsa dan berdemokrasi hari ini,” tuturnya.
Situasi ini terbilang unik. Halili mengungkapkan, di banyak negara, demokratisasi melahirkan penguatan pada masyarakat sipil. Tapi di Indonesia, yang dikuatkan justru negaranya.
Ia mengakui, kecenderungan menguatnya negara ketimbang masyarakat sipil tampak dari gerakan publik yang melemah dan berpeluang terkooptasi oleh kepentingan lain.
Selain itu, di lain sisi, terdapat pula persoalan dalam kebudayaan masyarakat yang bercirikan feodal serta melodramatik.
Kebudayaan feodal dan melodramatik tersebut melahirkan kecenderungan politik patron klien. Artinya, masyarakat hanya melihat seseorang yang dianggap baik, kuat, sehingga memunculkan ”loyalis-loyalis buta.”
”Loyal secara membabi buta, kira-kira begitu. Tetapi secara umum fenomenanya memang demikian, kultur kita yang patronis, kemudian feodal, cenderung memberikan ruang bagi warga untuk tunduk buta sedemikian rupa terhadap apa yang menjadi kelindan dari aparat atau negara,” kata dia.
Namun, Halili tak setuju kalau represifitas negara kekinian bisa diartikan sebagai pemerintah yang krisis hegemonik.
”Saya kira sebelum krisis hegemonik, penting untuk membaca fenomena itu sebagai kekhawatiran yang lebih besar dari negara soal penurunan legitimasi mereka. Legitimasi itu penting. Praktik sosial dan politik, tertib hukum itu hanya bisa dibangun oleh kelembagaan yang ligitimatif secara demokrasi,” kata dia.
Satu hal yang perlu dipahami, kata Halili, represifitas negara yang justru didukung oleh sebagian warga, adalah fenomena tergerusnya ruang-ruang publik.
Halili menyebutkan, media sosial adalah ruang publik paling mutakhir, yakni tempat warga mengekspresikan banyak hal termasuk pandangan politik.
Pemerintah, kata Halili, seharusnya bisa memberikan jaminan keadilan bagi warga dalam ruang-ruang publik semisal media sosial.
Keadilan dalam ruang publik itu penting menurut Halili. Sebab, jangan sampai karena faktor suka atau tidak, persoalan dukungan dan tantangan, membuat negara memperlakukan satu kelompok dengan lain berbeda.
“Nah yang terjadi hari ini kan, kelompok aktivis yang kontra pemerintah bisa diproses secara hukum, ditangkap, dijadikan tersangka. Tetapi yang pro pemerintah bisa dengan mudah mencaci-maki para aktivis di media sosial.”