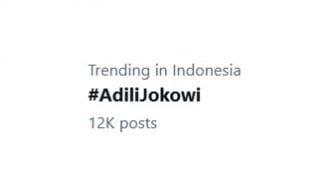Suara.com - Satu komunitas kecil di pedalaman hutan belantara Sumatera, Indonesia, menjadi jantung pertempuran untuk mempertahankan lahan garapan. Pertempuran yang bisa mengganti sistem hukum kepemilikan lahan yang kacau dan eksploitatif, sebuah "revolusi agraria".
Cuaca dingin bergelayut di antara kegelapan malam di belantera Pulau Sumatera. Namun, sekelompok tetua tetap meringkuk melingkari selembar peta, merencanakan strategi pertempuran mereka.
Tahun lalu, mereka menorehkan sejarah dalam tonggak kemenangan kecil mempertahankan hak mereka atas tanah garapan. Tahun 2016, mereka dijanjikan mendapat hak atas tanah yang sebenarnya sudah dikuasai komunitas mereka sejak beberapa generasi lampau.
Baca Juga: Sindikat Saracen, Asma Dewi Adik dari Anggota Mabes Polri
Tapi kekinian, mereka mendapat kabar buruk. Seorang inspektur lokal meminta sejumlah lahan itu untuk diberikan kepada perusahaan besar bubur kertas. Padahal, lahan itu tempat mereka biasa memanen benzoin—zat seperti kemenyan. Mereka menilai permintaan itu sebagai pengkhianatan.
Sembari menyeruput teh, para tetua berdebat dalam bahasa campuran antara Batak dan bahasa Indonesia. Mereka tengah merencanakan aksi perlawanan untuk keesokan hari. Selama setahun terakhir, setiap hari mereka selalu membuat rencana perlawanan.
"Kami meneruskan perjuangan. Ini adalah satu-satunya pilihan bagi kami," tutur Arnold Lumban Batu yang ikut pertemuan yang diorganisasikan komunitas adatnya.
"Sejujurnya, semua dari kami lebih memilih mati daripada kalah," tegasnya kepada dua jurnalis The Guardian yang datang, Vincent Bevins dan Humbang Hasundutan.

Baca Juga: Pernyataan Henry Ungkap Agenda Tersembunyi Pansus KPK
Mereka yang bersamuh adalah anggota komunitas pribumi "Pandumaan-Sipituhuta". Mereka mungkin bisa mengubah peraturan kapitalisme di Indonesia, yang mendominasi puluhan juta orang.