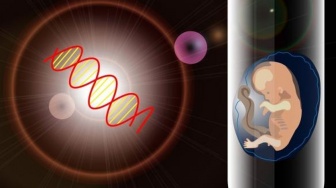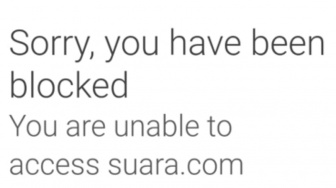Vedi Hadiz: Islam Radikal Bukan Pemenang Pilkada Jakarta

"Sebenarnya pihak pemenang dalam pilkada itu adalah sebuah faksi oligarki politik di Indonesia."
Suara.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 telah selesai, tapi ”gema” dari perhelatan tersebut masih kental terasa hingga kekinian. Lantas, apa yang tersisa dari politik kontestasi tersebut?
Ahok—Basuki Tjahaja Purnama—calon gubernur petahana kalah. Ia lalu divonis bersalah dalam kasus penodaan agama, dan kekinian tengah mendekam di bilik tahanan Rutan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Ketika masa kampanye, Ahok digempur oleh serial aksi yang mengatasnamakan Islam.
Sementara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, sang penantang, secara mengejutkan menang. Kemenangan itu dinilai banyak pihak sebagai kemenangan kaum radikalis Muslim. Penilaian tersebut tak hanya diyakini oleh banyak orang di Indonesia, melainkan dalam pemberitaan media-media internasional.
Namun, Vedi R Hadiz—ilmuwan sosial Indonesia yang menjadi Professor of Asian Studies di Asia Institute, University of Melbourne, Australia—memunyai penilaian berbeda yang dijelaskannya dalam diskusi bertajuk “Identity Politics in Indonesian Electoral Democracy” yang digelar di Melbourne University, Australia, Rabu (17/5/2017) malam.
Baca Juga: Rute Baru AirAsia yang Dinanti Wisatawan: Adelaide ke Bali Kini Tanpa Transit
Menurutnya, Pilkada DKI yang dianggap sebagai miniatur pertarungan Pilpres 2019 bukanlah palagan yang dimenangkan oleh kaum radikalis Islam ataupun populisme Islam. Pemenang dalam politik kontestasi itu justru suatu klik oligarkis.
"Sebenarnya pihak pemenang dalam pilkada itu adalah sebuah faksi oligarki politik di Indonesia yang telah memobilisasi sentimen populisme Islam," ujar Profesor Vedi, seperti dilansir ABC Australia Plus.
Penulis buku “Islamic Populism in Indonesia and the Middle East” (2016) ini mengatakan, identitas politik Islam yang secara tradisi selalu berada di tengah pentas politik Indonesia selalu terfragmentasi atau terbelah-belah.
Karenanya, tidak pernah ada satu organisasi politik yang tunggal sebagai representasi keinginan ”umat”. Kata ”umat” sendiri diartikan Vedi sebagai terminologi pengganti ”rakyat” (the people) dalam skema pemikiran populisme.
Ketika kekuatan Islam politik tersebut terserak, massa pendukungnya menjadi sasaran empuk bagi kelompok atau elite untuk dimobilisasi demi kepentingan mereka sendiri.
Baca Juga: Salah Embrio, Salah Anak: Kisah Ibu Australia yang Melahirkan Bayi Milik Pasien Lain
Vedi menuturkan, mobilisasi politik identitas Islam yang terfragmentasi tersebut, mensyaratkan adanya kontroversi yang konstan sehingga upaya itu efektif serta berhasil.