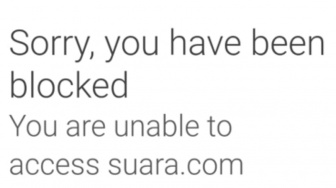Setahun Diberlakukan di Aceh, Qanun Jinayat Diskriminasi

Penerapan Qanun Jinayat berpotensi mengakibatkan kekerasan berlapis terhadap perempuan.
Suara.com - Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qanun Jinayat mengkritik pemberlakuan Qanun Jinayat atau Peraturan Daerah Hukum Pidana di Aceh. Sebab, sejak pemberlakuannya 23 Oktober 2015, Qanun Jinayat dianggap sebagai peraturan daerah yang diskrimintatif.
"Sejak proses pembentukannya terkesan dipaksakan dengan pembahasan yang terburu-buru, serta tidak melibatkan dan mempertimbangkan masukan masyarakat. Apalagi, sebanyak 97 persen perempuan tidak mendapatkan informasi mengenai pembentukan Qanun Jinayat. Padahal, perempuan justru sangat rentan menjadi korban yang terdiskriminasi dalam Qanun ini," kata Koordinator Program Solidaritas Nisa Yura dalam konfrensi pers di Kantor YLBHI, Jakarta, Minggu (23/10/2016).
Menurutnya, penerapan Qanun Jinayat berpotensi mengakibatkan kekerasan berlapis terhadap perempuan. Dalam pasal 48 Qanun ini, sambungnya, korban perkosaan justru dibebankan dengan menyediakan alat bukti permulaan.
Padahal, sulit mencari saksi dalam kasus seperti ini. Korban perkosaan akhirnya mendapatkan dampak psikologis dan trauma yang diakibatkan karena sulitnya penyediaan alat bukti.
Baca Juga: All Girls All Around: Ketika Lari Menyatukan dan Menguatkan Perempuan
"Implementasi Qanut Jinayat juga berdampak pada kekerasan lebih lanjut, terutama bagi perempuan. Eksekusi di hadap publik akan menimbulkan trauma dan pelabelan negatif yang berdampak pada pengucilan dan peminggiran perempuan. Apalagi hukuman cambuk ini menghasilkan budaya kekerasan di Aceh. Karena eksekusinya dipertontonkan di Hadapan masyarakat termasuk anak-anak," kata dia.
Sebagai contoh, Nisa berkata, ada seorang remaja yang akhirnya bunuh diri karena dituduh sebagai perempuan tidak baik-baik oleh polisi syariah Aceh atau Waliyatul Hisbah. Padahal, Qanun Jinayat masih dalam proses rancangan.
"Padahal dia Anak SMA dan baru pulang dari Konser. Karena diberitakan sedemikian rupa akhirnya berujung pada bunuh diri," tuturnya.
Selain itu, tambah Nisa, Proses persidangan dalam pemberlakuan Qanun Jinayat ini juga terkesan tertutup. Dia mengatakan, para terdakwa tidak diketahui apakah didampingi oleh pendamping hukum atau tidak. Selain itu, proses persidangannya juga tidak diketahui secara jelas.
"Secara logika ada 180 kasus yang sudah dieksekusi padahal untuk kejahatan pencurian saja, di sidang nasional, itu sangat panjang. Ada pembuktian dan lain-lain sebelum dieksekusi, termasuk adanya Kasasi dan Banding," ujarnya.
Baca Juga: Demi Capai Kesetaraan Gender, Perempuan Didorong Jadi Pilar Masa Depan Indonesia
Lebih jauh, menurut Nisa, Qanun Jinayat ini dianggap sebagai pengalihan isu. Sebab, isu kesejahteraan dan eksploitasi sumber daya alam di Aceh jadi tidak tersentuh dengan adanya Qanun Jinayat ini.
"Orang jadi lebih konsen dengan Qanun Jinayat. Akhirnya masyarakat lebih memperhatikan terhadap itu daripada berbicara bagaimana menurunkan angka kemiskinan di Aceh, dan menurunkan angka kematian ibu melahirkan," tuturnya.
Apalagi, sambungnya, buntut Qanun Jinayat ini memunculkan perda yang diskriminatif di daerah lain. Salah satunya Perda Penertiban Umum di Tangerang. Nisa bercerita, ada seorang perempuan yang memilih bunuh diri karena mendapatkan tekanan dan diskriminasi akibat penerapan Perda tersebut.
"Di Tangerang juga ada korbannya, perempuan buruh yang ditangkap karena sedang shift malam, tapi dituduh sebagai pekerja seks. Dan itu berakhir bunuh diri. Karena dia dan suaminya mendapatkan diskriminatif dan pengucilan yang luar biasa akibat ditangkap," kata dia.
Qanun Jinayat ini pernah digugat ke Mahkamah Agung untuk uji materi. Namun, MA memutuskan Niet Ontvankelijke verklaard (NO) karena salah satu batu uji materi yang diajukan, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-perundang tengah diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi. Padahal, masih ada lima batu uji lainnya yang seharusnya bisa menjadi pertimbangan MA.
"Padahal batu ujinya banyak ada lebih dari lima. Salah satunya diuji di MK. Tapi (batu uji) itu yang menjadikan dasar di MA," kata Koordinator Bidang Sipil Politik YLBHI Mochamad Ainul Yaqin.