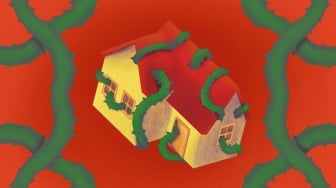Suara.com - Isu agama dan etnis hampir selalu muncul menjelang pilkada di era reformasi. Bahkan di Ibu Kota Jakarta yang notabene dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari lintas suku, agama, ras dan golongan.
Padahal, menurut hasil survei, isu semacam itu sebenarnya sudah tak laku lagi untuk menurunkan elektabilitas lawan politik. Jakarta pernah membuktikan di pilkada tahun 2012, isu agama dan etnis tak sanggup menjegal langkah pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menang. Publik sekarang sudah cerdas. Mereka tak menjadikan latar belakang agama sebagai tolak ukur memilih calon pemimpin.
Tetapi kenapa isu tak laku masih tetap didengungkan? Bagaimana sejarahnya?
Pengajar filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Antonius Benny Susetyo menceritakan sejarah politik di Indonesia modern hampir tak pernah lepas dari isu SARA. Isu tersebut, kata Benny, biasanya muncul ketika partai peserta pemilu tidak lagi mengedepankan ideologi. Isu agama dan etnis muncul ketika para kandidat dan pendukung lebih mementingkan kemenangan dibandingkan hal dasar yang harus mereka perjuangkan.
"Sekarang ini kan, partai yang sifatnya masih kekanak-kanakan, karena partai sekarang ini lebih pada figurkan, bukan pada agenda dan ideologi yang menjadi hal yang diperjuangkan. Kalau dulu, partai-partai punya ideologi, dan berpihak kepada masyarakat, ada yang perjuangkan nasib petani, buruh, sosialis, orang kecil. Mereka waktu itu dalam konteks untuk merebut hati rakyat dengan memperjuangkan ideologi rakyatnya. maka semua partai punya ideologi," kata Benny kepada Suara.com, Senin (10/10/2016).
Menurut Benny penyebab pendekatan isu SARA masih dipakai jelang pemilu adalah karena Indonesia masih berkiblat pada demokrasi Amerika Serikat. Sosok kandidat yang menjadi perhatian, sementara ideologi dihilangkan.
Padahal, kata Benny, seharusnya setiap partai tetap konsisten berjuang dengan dasar ideologi masing-masing. Dengan demikian, akan terpenuhi keinginan masyarakat karena yang diperjuangkan adalah kepentingan rakyat.
"Sekarang berbeda, karena ini zamannya demokrasi kita itu sama seperti model Amerika, maka figur yang dipentingkan, maka pendekatan lebih pada pemasaran. Nah, kalau pemasaran politik pakai figur, nah problemnya lawan politik selalu menggunakan agama untuk menjadikan jargon politiknya. ini yang sebenarnya tidak sehat, karena di sini sebenarnya mereka tidak bisa membaca keinginan rakyat," katanya.
Benny kemudian membandingkan dengan situasi pemilu pertama di Indonesia yang diselenggarakan tahun 1955. Ketika itu, katanya, tidak ada isu SARA yang dipakai untuk menyerang lawan. Mereka bicara tentang program kerja. Menurut pastor dan aktivis ini, politik pada masa itu penuh etika.
"Partai dulu dengan yang sekarang perbedaannya sangat mendasar. Pada waktu itu partai agama itu tidak berbicara agama. Partai Katolik, partai Masyumi, semua berbicara tentang program, kalau kita lihat pemilu 1955, itu pemilu yang paling demokratis, karena kita lihat di situ perdebatan, orang adu program, adu perencanaan, mereka memiliki namanya etika berpolitik, meskipun mereka menggunakan partai agama, tetapi mereka mengedepankan yang disebut politik akal sehat itu," kata Benny.