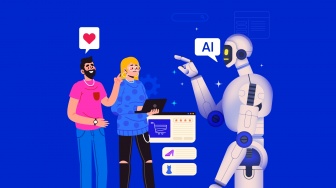Suara.com - Waktu di layar monitor laptop Ara telah menunjukkan pukul 22.00. Lelaki yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi itu masih belum beranjak dari depan laptopnya. Dari pukul 09.00 Ara masih terus berkutat merespons keluhan dan menjawab deretan pertanyaan dari pengguna layanan teknologi tempatnya bekerja.
“Kalau aplikasi ada problem kita mesti tangani saat saat itu juga, enggak peduli walau itu sudah malam. Enggak peduli juga malam sebelumnya ada masalah,” kata Ara
Kerja di industri teknologi yang dijalani Ara sejak lima tahun lalu memang terkenal tidak punya waktu. Karakter teknologi yang serba cepat menuntut Ara mesti adu maraton dengan deretan keluhan yang datang beruntun tak berkesudahan.
“ Enggak peduli dengan kondisi kita sebagai individualnya,” ujar Ara.
Sejak pemerintah menyatakan status pandemi Covid-19 di Indonesia, tempat Ara bekerja meminta seluruh karyawan untuk bekerja dari rumah. Ara yang tinggal di sebuah kamar kost berukuran 3 x 3 meter terpaksa hanya bisa menghabiskan hari-harinya di depan laptop. Tidak ada lagi istilah jam kerja. Batasan antara istirahat dan waktu bekerja juga jadi kabur. Semua waktu ia habiskan untuk bekerja dan bekerja. Tanpa bersosialisasi.
“Kondisi itu bikin saya sudah lupa sama diri sendiri. Pekerjaan itu membuat saya tidak mengenal diri saya sendiri,” kata Ara.
Pada hari-hari tertentu tidak jarang ia hanya bisa meringkuk di pojok kamar kostnya. Air matanya tumpah. Ia menangis.
“Saya sudah mencoba suicide (bunuh diri) berkali-kali,”

Bahkan, ia sampai menyimpan sebilah pisau lipat di balik bantalnya. Deretan peristiwa itu membawanya untuk terapi ke psikiater. Selama proses terapi berlangsung, psikiater memberi dua jenis obat yang mesti ia habiskan selama dua minggu. Kondis Ara tak banyak berubah. Sehingga psikiater menyarankan untuk mengambil cuti dan pergi liburan.
Baca Juga: Survei: Pandemi COVID-19 Bikin Resiko Kesehatan Tubuh Lebih Kompleks
Ara kemudian memutuskan terbang ke Pulau Dewata dan meninggalkan seluruh pekerjaannya di Tangerang Selatan. Di sana ia menghabiskan waktu pergi ke pantai melihat deburan ombak dan hembusan angin sepoi-sepoi. Kondisinya sempat membaik usai liburan.