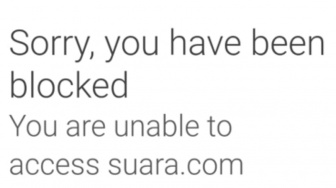Studi Baru: Parasit Malaria di Afrika Mulai Resisten terhadap Obat ACT yang Disetujui WHO

Temuan soal parasit malaria ini membuat para ilmuwan khawatir.
Suara.com - Para ilmuwan mengumumkan bahwa parasit malaria, Plasmodium falciparum, di Afrika mulai resisten terhadap obat yang disetujui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni Artemisinin Combination Therapy (ACT), Senin (27/9/2021).
WHO menyetujui regimen kombinasi obat ACT yang terdiri atas artemether dan lumefantrine, artesunate dan amodiaquine, dihydroartemisinin dan piperaquine, dan artesunate, sulfadoxine, dan pyrimethamine.
Sebuah studi baru yang terbit dalam New Egland Journal of Medicine menunjukkan penurunan obat dalam merawat penderita malaria, lapor The Guardian Nigeria.
Penelitian yang dilakukan di Uganda dari 2017 hingga 2019 ini menunjukkan perlu lebih dari lima jam untuk menghilangkan setengah Plasmodium falciparum yang menginfeksi 14 pasien malaria. Padahal, umumnya pengobatan artesunate hanya perlu beberapa jam untuk menghilangkan setengah parasit.
Baca Juga: Dokter Penemu Terapi Sel Punca Pengobatan Covid-19 Naik Pangkat Luar Biasa
Penurunan kemampuan yang memenuhi definisi resistensi WHO itulah yang membuat ilmuwan berpikir parasit telah kebal terhadap pengobatan ACT.

Sebenarnya, tanda resistensi sudah lama terlihat di benua tersebut. Misalnya, di Rwanda pada 2012 hingga 2015, para ilmuwan mendeteksi adanya mutasi gen terkait resistensi parasit malaria.
Gejala resistensi terhadap artemisinin dan obat lainnya juga muncul di Kamboja pada awal 2000-an. Beberapa tahun kemudian, parasit malaria di Asia Tenggara mulai kebal terhadap beberapa obat ACT.
Hal itu membuat beberapa kombinasi obat paling efektif tidak berguna lagi di wilayah tersebut dan membuat pemerintah kesehatan setempat mencari obat kombinasi yang manjur.
"Kita semua sudah memperkirakannya dan menjadi takut akan hal itu selama beberapa waktu," jelas ahli biokimia Leann Tilley dari University of Melbourne, Australia.
Baca Juga: Stigma Negatif Bisa Berdampak Buruk dalam Pengobatan Pasien Epilepsi
Tilley juga menyatakan keprihatinannya atas perkembangan baru di Afrika, menggambarkan kondisi itu sebagai hal mengerikan. Sebab, lebih dari 90 persen kasus malaria dan kematian di seluruh dunia terjadi di benua tersebut.
Para ilmuwan khawatir skenario di Asia Tenggara juga akan terjadi di Afrika. Terlebih kurangnya akses ke fasilitas kesehatan memadai di banyak bagian Afrika Sub-Sahara. Masalah ini dapat menimbulkan banyak korban.