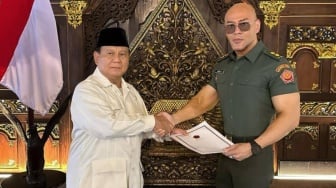Suara.com - Belakangan ini, kasus kekerasan seksual menjadi salah satu berita hangat di berbagai media sosial, media digital, hingga televisi.
Mulai dari kasus glorifikasi yang dilakukan pada seorang artis yang baru saja keluar dari penjara, pelecehan seksual di salah satu lembaga penyiaran milik pemerintah, hingga meninggalnya seorang perawat karena dilecehkan oleh sekelompok anggota masyarakat.
Kasus pelecehan seksual bukanlah barang baru. Hal ini sudah terjadi sejak lama dan selalu menjadi salah satu tugas besar pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat.
Alih-alih melapor, kebanyakan penyintas memilih diam. Di beberapa kondisi, penyintas kekerasan seksual yang berhasil melapor malah menjadi korban pernikahan dengan pelaku. Tidak sedikit bahkan yang setelah melapor justru mendapat stigma negatif dari publik.
Baca Juga: Dipanggil Komnas HAM Soal Dugaan Pelecehan Pegawai KPI, Kapolres: Masih Penyelidikan

Menurut Falah Farras, Psikolog Klinis yang juga Co-Founder Social Connect, pelecehan seksual sulit dilaporkan karena kurangnya bukti. Sehingga ketika ingin melapor, penyintas merasa ragu. Belum lagi anggapan orang lain ketika penyintas melaporkan kejadian tidak senonoh yang mereka terima.
"Ketika pelecehan seksual terjadi, penyintas atau korban merasa kesulitan untuk mengumpulkan bukti. Jarang ada yang memiliki bukti foto atau rekaman."
"Penyintas juga mengalami kesulitan karena yang menjadi saksi hanyalah pelaku dan korban itu sendiri. Itu biasanya yang jadi alasan mengapa penyintas kekerasa seksual lebih sulit untuk bercerita atau melapor," tuturnya dikutip dari siaran pers, Rabu (22/9/2021).
Apalagi bila korban atau penyintas tersebut berasal dari kalangan laki-laki. Ada stigma maskulin yang melekat di masyarakat. Laki-laki tidak boleh lemah, tidak boleh cengeng, dan tidak boleh takut. Hal ini juga menjadi alasan yang menghambat korban melaporkan tindak kekerasan seksual yang mereka terima.
Belum lagi munculnya Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) di diri penyintas tersebut. Efeknya bisa dalam bentuk hyperarrousal atau kesulitan mengingat kejadian yang terjadi hingga tubuh tidak bisa bergerak (freeze) ketika pelecehan terjadi.
Lantas, apa yang bisa dilakukan penyintas kekerasan seksual agar bisa pulih dari trauma?
Baca Juga: Cara Cek KTP Lewat WhatsApp, SMS, Media Sosial dan Situs Pemerintah
![Ilustrasi kekerasan seksual pada anak di bawah umur. [SuaraJogja.com / Ema Rohimah]](https://media.suara.com/pictures/original/2020/12/10/61229-ilustrasi-kekerasan-seksual-pada-anak.jpg)
1. Stabilisasi Emosi
Ketika berada di masa trauma atau PTSD, penyintas biasanya akan merasakan emosi lebih intens dibanding biasanya. Emosi negatif seperti sedih, marah, hingga menyalahkan diri sendiri jadi muncul lebih sering. Penyintas juga jadi mudah terpicu karena beberapa hal tertentu.
Untuk mengatasi hal ini, Farras menyarankan penyintas untuk melakukan stabilisasi emosi, terutama ketika emosi tersebut sedang meluap. Misalnya dengan mencari metode coping yang paling sesuai seperti menangis, meditasi, atau melakukan hal-hal positif, atau mencari bantuan dari profesional.
2. Memproses Ingatan Kembali
Karena kekerasan seksual merupakan hal yang traumatis, biasanya ingatan akan hal tersebut akan sangat melekat dan sulit diterima oleh tubuh.
Sehingga dapat mengganggu kehidupan penyintas. Dengan memproses ingatan kembali, penyintas akan ‘diajak’untuk menoleransi pengalaman tersebut atau tidak terlalu reaktif terhadap ingatan itu.
"Kita coba memperbaiki emosi yang terjadi dalam ingatan itu. ‘Oke, itu memang bagian dari hidupku, bagian dari pengalaman yang sudah aku lalui."
"Pada saat itu aku marah, tapi saat sekarang, aku dengan diriku yang sekarang.’ Proses itu kita menarik diri kita ke masa saat ini, dan yang masa lalu itu kita terima sebagai pengalaman hidup. Lebih ke mengubah toleransi emosinya," ujar pria tersebut.
Bagaimana dengan penyintas yang mengalami hyperarrousal? Farras menuturkan bahwa orang-orang yang mengalami freeze akibat stres atau trauma bukan berarti mereka baik-baik saja. Mereka juga membutuhkan bantuan untuk menoleransi trauma yang terjadi, baik di tubuh maupun pikirannya.
3. Membangun Koneksi Kembali
Biasanya orang-orang yang mengalami momen traumatis akan mengalami krisis kepercayaan atau trust issue. Misalnya mudah terpicu terhadap orang yang memiliki ciri spesifik dengan pelaku atau lingkungan yang mirip dengan kejadian masa lalu.

Dalam tahap ini, dibantu oleh bantuan profesional, penyintas akan diajak untuk membangun koneksi kembali bahwa setiap tempat atau manusia yang memiliki ciri tertentu tidak selamanya akan melakukan kejahatan seksual. Dengan cara tersebut, emosi penyintas akan jadi lebih netral.
Di masa ini, penyintas juga akan diajak untuk mengenal dirinya sendiri secara lebih mendalam. Penyintas akan diajak untuk membangun koneksi dengan dirinya sendiri, mengenal kelebihan, dan potensi yang ia miliki.
Menurut Farras, yang menjadi kesulitan bagi penyintas adalah ketika mereka mesti menghadapi kenyataan bahwa pelaku mendapatkan glorifikasi. Terutama ketika pelaku malah diagung-agungkan sebagai pahlawan dan justru mendapat lebih banyak perhatian. Hal ini akan berdampak pada proses healing atau penyembuhan pentintas. Penyintas akan merasa kesulitan untuk menolerir perasaannya.
"Pertentangan-pertentangan di dalam diri dia itu akan mengganggu proses healing penyintas. Dan di tahap manapun itu akan selalu mengganggu korban ketika itu blm sempurna dan dia harus berhadapan dengan glorifikasi itu," tutup Farras.