"Ya sudah disampaikan ke Menteri Pendidikan bahwa saya mendorong bagaimana kalau di pendidikan ini kurikulum tentang pendidikan kesehatan reproduksi itu masuk ke sekolah. Ini penting sekali karena banyak orang yang tidak mengerti tentang risiko nikah usia dini. Kanker rahim itu juga ada hubungannya dengan nikah terlalu dini," pungkas Hasto.
Namun kajian Global Early Adolescent Study (GEAS) dan Youth Voices Research yang dilakukan di Indonesia antara bulan Juli 2018 dan Juli 2019 menunjukkan pendidikan reproduksi saja tidak cukup. Diperlukan pendidikan reproduksi berperspektif gender untuk mendorong perubahan pola pikir.
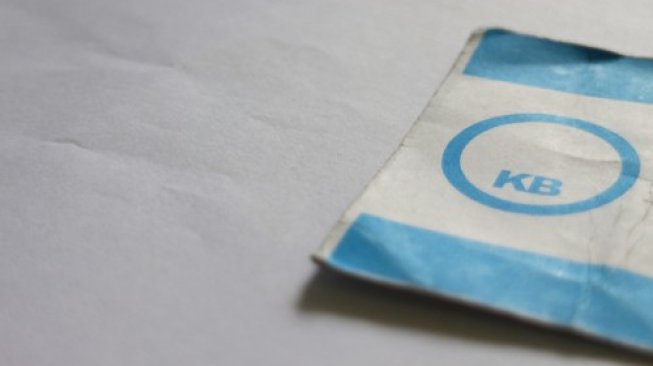
GEAS melakukan survei atas 4.684 remaja yang duduk di kelas 7 SMP (usia 12-13 tahun) di tiga lokasi: Semarang (Jawa), Bandar Lampung (Sumatera), dan Denpasar (Bali). Kajian juga dilakukan lewat 24 diskusi kelompok terarah (focus group discussions, FGD) dan 86 wawancara mendalam dengan responden muda berusia 18-24 tahun; 18 diskusi di ruang kelas dan 18 FGD dengan murid sekolah yang berusia 12- 13 tahun; sembilan FGD dengan orang tua; serta sembilan FGD dengan guru.
Hasilnya mencengangkan. Bahwa remaja – khususnya perempuan – mempunyai pengetahuan yang rendah tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Perempuan juga memiliki rasa tidak nyaman yang tinggi terhadap perkembangan tubuhnya sendiri. Perempuan mudah cemas dan merasa bersalah terhadap mulai munculnya perasaan seksual. Hal ini tidak ditemukan pada laki-laki. Ini erat kaitannya dengan masih kuatnya pemahaman bahwa membahas masalah seksualitas, dalam keluarga sekali pun, merupakan hal yang tabu.
Baca Juga: Sedang Program KB? Ini 5 Tips Mendapatkan Alat Konstrasepsi Saat Pandemi
Namun kajian GEAS – yang merupakan hasil kerjasama banyak institusi, antara lain Rutgers, WPF Indonesia, PKBI, GEAS dan Bill & Melinda Gates Foundation – menunjukkan bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki keinginan untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi (terutama anak perempuan) dan untuk menunda menikah sampai paling sedikit usia 21 tahun.
Dua pertiga di antaranya ingin menunda memiliki anak sampai paling sedikit usia 25 tahun, serta tiga perempat ingin memiliki anak dua orang saja atau kurang dari itu. Anak perempuan menunjukkan skor yang lebih tinggi daripada anak laki-laki dalam hal bersuara, mengambil keputusan, dan “perencanaan”.
Temuan-temuan ini menarik karena tampak jelas bagaimana norma gender ikut mempengaruhi pengambilan keputusan, termasuk dalam hal Keluarga Berencana.






























