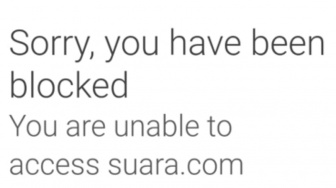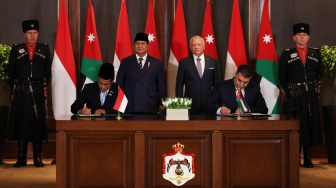Prediksi Arah Kebijakan Industri Hasil Tembakau di Era New Normal

industri padat karya seperti Industri Hasil Tembakau (IHT) perlu menyikapi kebijakan di era new normal dengan penuh kehati-hatian.
“Hendaknya pemerintah tidak melihat isu kesehatan secara sempit. Justru yang harus dikuatkan adalah peningkatan pengawasan dan penegakan disiplin atas distribusi dan akses masyarakat terhadap produknya. Perbanyak edukasi, sosialisasi ke tingkat akar rumput agar konsumen paham bahwa produk tembakau hanya bisa dikonsumsi orang dewasa. Saya kira pemerintah sudah jelas mengatur di PP 109 Tahun 2012 untuk produk tembakau dan aturan ini sudah lebih dari cukup, tugas selanjutnya adalah memastikan implementasi di lapangan berjalan tertib, jangan terus merevisi poin saja tapi praktiknya nihil,” tegasnya.
Dalam paparannya, Maharani Hapsari Co Chair-holder UGM-WTO Chair Program menuturkan, sektor IHT kerap menjadi entitas yang harus menerima aturan-aturan restriktif dengan peluang yang sangat minim untuk dapat mengajukan keringanan.
Hal ini terjadi karena dalam proses pembuatan kebijakan untuk IHT, ada banyak prosedur yang tidak transparan sehingga berpotensi pada praktik pelanggaran, antara lain kurangnya transparansi informasi kepada seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan, ketiadaan proses partisipatif.
“Argumen tentang adanya tendensi prinsip keterbukaan yang diabaikan salah satunya berangkat dari studi kasus kami yakni perumusan rencana revisi PP 109 Tahun 2012. Dalam hal ini, para pelaku IHT tidak mendapat transparasi ketika membahas poin-poin restriksi. Faktanya, sampai saat ini, belum benar-benar ada kata mufakat di antara stakeholders yang berkepentingan, seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, komunitas rantai pasok IHT, dan Kementerian Perindustrian,” tutur Maharani.
Baca Juga: 241 Pekerja SKT Sampoerna Dapat BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
“Bahkan, diskusi kerap berjalan secara sendiri-sendiri antar pemangku kepentingan, dan ujung-ujungnya menciptakan klaim yang saling berseberangan. Hal ini tentu bukanlah praktik yang sehat, terlebih saat ini kita semua sedang berada di fase transisi untuk menerima kenormalan baru. Tidak terkecuali pelaku industri,” tambahnya.
Posisi dan klaim yang saling berseberangan antara pemangku kepentingan dinilai sangat menghambat terbentunya kebijakan yang inklusif bagi kelangsungan industri. Dampaknya, hasil kebijakan bisa sangat bias dan menimbulkan favoritsm terhadap kelompok tertentu.
“Seringnya, argumen dasar kebijakan kontrol IHT bersumber dari adopsi norma internasional tanpa konteks lokal. Padahal, jika mengacu pada standar prosedur perumusan kebijakan publik, harus ada tiga dimensi yang dipenuhi yakni transparansi, partisipasi dan dukungan bukti. Ketiga dimensi ini mewakili prinsip keterbukaan yang harapannya bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak ketika aturan tersebut disahkan. Jika ada satu dimensi yang diabaikan, konsekuensinya adalah masyarakat bisa tidak patuh pada aturan,” jelas Maharani.
Maharani juga menyampaikan, di tengah berbagai himpitan yang menimpa IHT, pemerintah harus mulai proaktif dalam mendengarkan banyak suara dari berbagai pihak. Terlebih di momen kenormalan baru pemerintah perlu mempercepat proses pemulihan industri untuk menopang ekonomi nasional.
“Salah satunya tentu dengan mendorong dialog multi-stakeholder yang berbasis demokrasi deliberatif untuk mencapai kebijakan yang inklusif. Namun, perlu ditekankan lagi untuk mencapai kebijakan publik yang betul-betul dapat dipatuhi publik, regulator tidak bisa abai pada aspek transparansi dan partisipasi lintas pelaku industri. Akan lebih adil rasanya jika suara-suara dari pelaku yang terdampak langsung bisa didengarkan agar mencapai kebijakan yang rasional dan implementatif, tidak hanya reaktif,” tutupnya.
Baca Juga: Pentingnya Edukasi Penggunaan Produk Tembakau Alternatif